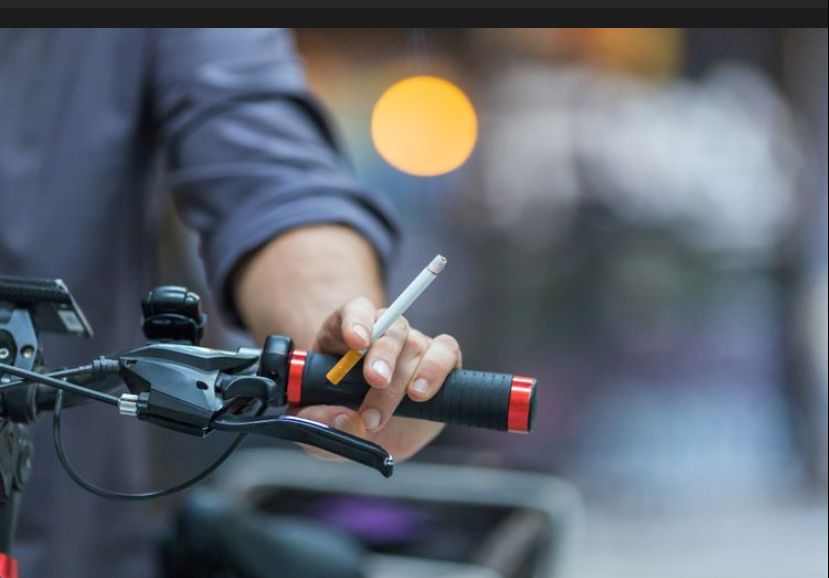Saya percaya, bahwa saya bukan satu-satunya anak muda Indonesia yang berasal dari keluarga tidak mampu, berlatar masyarakat kelas bawah serta tumbuh sejak kecil di daerah pedalaman, yang punya keinginan kuat untuk terus sekolah dan memupuk pengharapan akan hidup yang lebih berkemanusiaan, beradab, setara dengan siapapun di negeri ini, lahir maupun batin.
Nasib baik memperkenankan saya melanjutkan pendidikan dengan beasiswa. Nasib baik pula yang memperbolehkan saya mengenyam bangku kuliah hingga magister di satu kota besar, beratus-ratus kilometer jauhnya dari kampung halaman. Nasib baik itulah yang mempertemukan saya dengan kenyataan atas perjuangan teman-teman saya, orang-orang yang tidak dikenal, atau sosok tanpa nama yang saya jumpai di jalanan, pasar rakyat, kampung kumuh pinggir kali, berjejalan di halte ataupun stasiun, hingga gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Saya tidak tahu kebanyakan nama mereka. Tapi, saya tahu hidup seperti apa yang mereka jalani. Hidup yang keras, kerja yang keras, di mana nasib baik belum tentu mau berpihak pada suatu hari, suatu waktu.
Saya tahu juga, apa impian yang setiap malam mewujud sebagai doa, dipanjatkan pada Tuhan yang diyakini berdiam mendampingi, dan menjadi pegangan berkerja esok hari: cukup makan, cukup sandang, bagi ia dan keluarganya. Teringat saya pada sebuah petang: seorang gelandangan, tukang ojek, penjual buah keliling, sujud sembahyang bilamana mahgrib datang. Warga sebuah kampung di Pamulang, Tangerang Selatan, yang terusir dari tanah leluhurnya di Betawi karena arus pembangunan yang tak menunjukan tanda-tanda berhenti—ataupun bersikap lebih manusiawi—membagikan makanannya yang tidak seberapa kepada saya, berkali-kali, bilamana saya melakukan tugas wawancara di sana. Rumah mereka berdiri di sepetak tanah, tanpa halaman apalagi kebun-kebun penuh bunga. Selokan kecil di dekatnya mengalirkan sedikit air, yang tentu tidak akan mempan mencegah banjir. Saya paham, hidup mereka susah, tapi mereka membagikannya ikhlas sekali. Ikhlas, kata yang makin jarang saya temui belakangan ini.
Teringat saya pada suatu siang: memasuki pusat perbelanjaan mewah di Thamrin-Sudirman, seorang pelayan membukakan saya pintu dan tersenyum hangat sekali. Ujung bawah celananya basah, tanda-tanda kehujanan. Tangannya gelap, bekas tebakar matahari. Berkali gelisah berdiri, tidak tahan berjam-jam, berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun diam di sana sebagai pelayan pintu. Saya melewatinya. Orang-orang melewatinya. Orang-orang dengan jas paling necis seharga lima hingga sepuluh juta. Dengan tas keluaran mode terbaru yang dibeli dari Singapura, Paris, atau Amerika. Dengan celana dan sepatu limited edition, yang dipakai untuk tampil gaya, elegan, berkelas.
Syukur tiada akhir acap saya panjatkan atas segala nasib baik yang saya alami. Namun, saya jauh lebih malu, kepada orang-orang kecil itu, yang diam-diam masih bisa merasakan syukur dan terimakasih dalam suka maupun dukanya. Saya hanya bersyukur untuk hal-hal yang membahagiakan. Saya tidak pernah bersyukur atas cobaan demi cobaan yang dihadapi; yang sebagaimana kata orang lazim, ujian diberikan Tuhan karena ia tahu kita dapat melampauinya.
Akan tetapi, apa arti syukur, apa arti terimakasih, bilamana setiap hari kita menemukan, melihat dan merasai ketidakadilan? Saya bukan satu-satunya anak muda Indonesia yang melihat segala rupa ketidakadilan hidup. Saat berjuta-juta anak di negeri ini bermimpi sangat untuk sekolah, mendapat kerja dan upah layak, masa depan yang menjanjikan (meskipun belum tentu mewujud indah sebagaimana dibayangkan), ada segelintir putra-putri pejabat, keturunan para konglomerat, keluarga politisi maupun birokrat, bisa lanjut pendidikan hingga ke luar negeri, kemudian kembali mewarisi kekayaan keluarga yang mereka punya. Kekayaan dan kesejahteraan yang entah dari mana datangnya. Keuntungan demi keuntungan mengalir ke saku mereka, sementara sopir bis tua jurusan Ciledug-Senen yang sering saya tumpangi mencari makan serupiah demi serupiah. Sementara salah satu teman saya, penerima beasiswa di sebuah universitas negeri, rela tinggal di laboratorium kampus yang tidak lagi terpakai sebab tidak punya biaya kos. Atau kawan saya yang lain, yang harus berjalan berkilometer menembus kabut asap di pagi buta hanya supaya bisa masuk kelas tanpa terlambat.
Saat para ibu berjuang melahirkan di kampung pedalaman dengan minimnya segala fasilitas, para orang kaya yang saya temui di pusat perbelanjaan Jakarta sibuk berencana operasi plastik hingga ke Korea. Saat kita mendambakan pemimpin jujur dan amanah—mungkin ini satu-satunya harapan yang tersisa di tengah persoalan korupsi yang memuakkan dan sikap apatis atas kepentingan rakyat—yang muncul di hadapan kita justru sosok manusia tanpa hati, tanpa nurani, yang tiada malu memperjuangkan kekuasaan bagi dirinya, dan mempertontonkannya secara gamblang seolah laku macam itu sudah lumrah adanya.
Hanya ada segelintir para elite, yang jumlahnya tidak sampai ratusan atau ribuan, namun ternyata menguasai hak hidup ratusan juta rakyat kita.
Tidak pernah ada kata ‘cukup’ bagi mereka. Mungkin juga dengan ‘syukur’ dan ‘terimakasih’ yang ikhlas. Kata-kata itu, saya percaya, pasti telah lebur lama sekali, sejalan dengan keinginan untuk lebih, lebih, dan lebih berkuasa lagi.
Saya gelisah. Sangat gelisah. Saya merasa nasib baik yang saya alami selama ini tiada artinya sedikitpun dibandingkan ketidakadilan yang dialami banyak orang. Saya merasa harus berbuat sesuatu, untuk membuktikan bahwa kebaikan, kehangatan kemanusiaan, dan kekuatan nurani, masih ada di dunia ini, di negeri ini. Dan saya percaya, saya bukanlah satu-satunya anak muda Indonesia yang merasai kegelisahan ini.
Mari Bergerak! Dalam Kata, dalam Kerja. Memperjuangkan hidup dan mewujudkan harapan itu!
Arsip Foto: Tempo.co.
Ikuti tulisan menarik Ni Made Purnama Sari lainnya di sini.