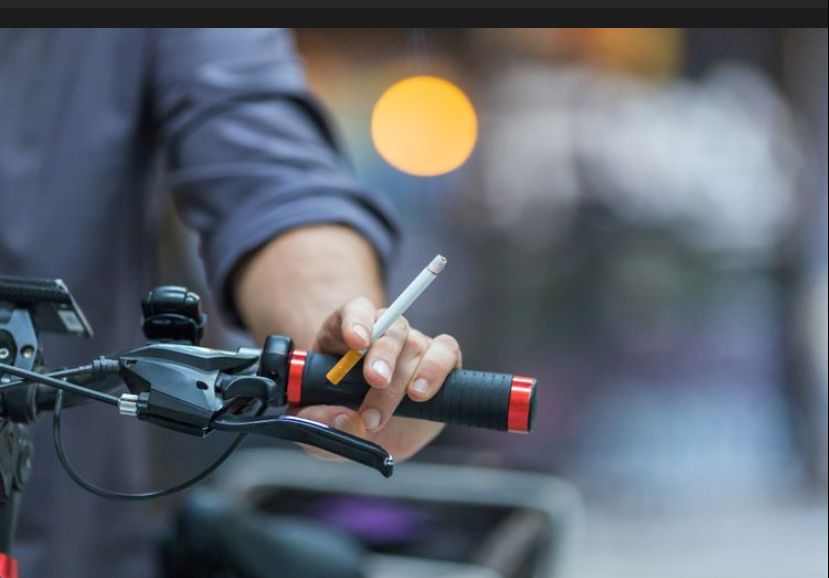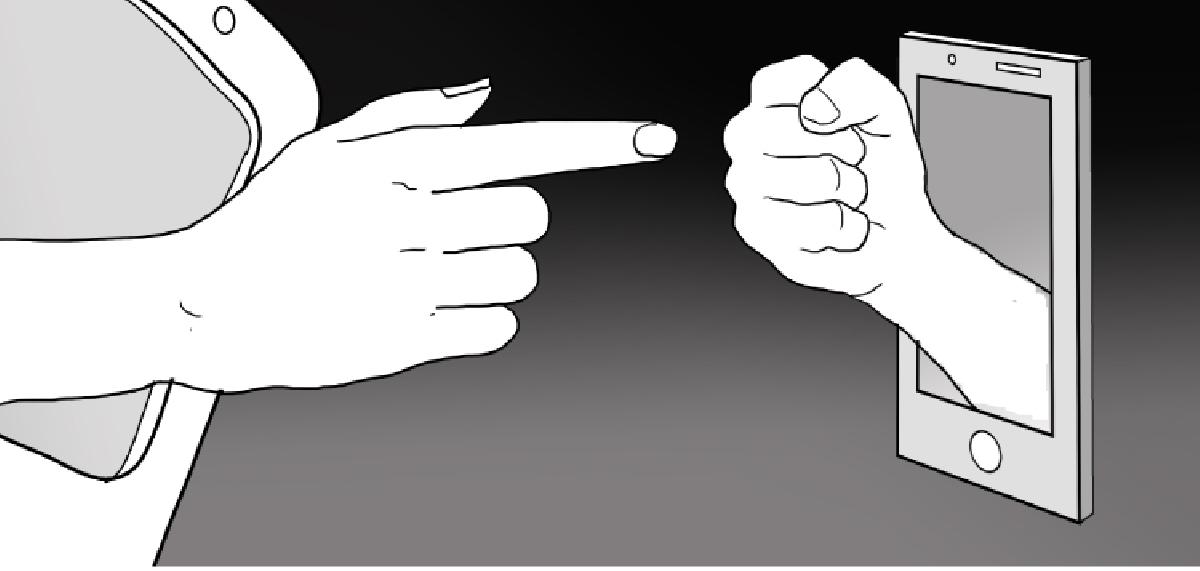Dengan menerima dana cukup besar dari negara, seharusnya PGRI mampu meningkatkan kompetensi dan profesionalitas anggotanya. Namun fakta berbicara lain. Masih banyak guru yang tidak kompeten, bahkan terlibat politik praktis.
Perubahan sistem politik yang meruntuhkan rezim Orde Baru pada 1998 turut berpengaruh dalam dinamika organisasi termasuk pada organisasi guru. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) tak lagi menjadi satu-satunya organisasi tunggal para pendidik. Berbeda dengan dulu ketika PGRI dijadikan alat untuk kepentingan penguasa. Semasa Orde Baru, amat biasa pengurus PGRI yang merangkap jadi pengurus parpol penyokong pemerintah, Golkar. Organisasi guru itu pun lebih condong jadi corong kekuasaan ketimbang tempat memperjuangkan aspirasi guru.
Setelah reformasi, organisasi profesi guru tumbuh bak cendawan di musim hujan. Ada Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Ikatan Guru Indonesia (IGI), dan Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Kini, guru bebas memilih untuk bergabung dengan salah satu dari organisasi profesi yang ada.
Dari sisi jaringan, PGRI memang yang terbesar. Ini wajar, mengingat umur organisasinya hampir sama dengan usia republik ini. PGRI lahir pada 25 November 1945 atau 100 hari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Hari lahirnya itu kemudian dijadikan dasar oleh pemerintah untuk menetapkan Hari Guru Nasional.
Awalnya ada tiga tujuan dari terbentuknya PGRI, yaitu mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia; mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan; dan membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya.
Lalu, bagaimana peran PGRI kini? Dari struktural, belum banyak perubahan yang terjadi sejak masa Orba. Pucuk pimpinannya bukan seorang guru, tetapi seorang senator (Dewan Perwakilan Daerah). Ini cukup berbeda dengan organisasi profesi guru yang lahir belakangan dimana ketua umumnya adalah seorang guru. Dengan latar belakang yang sama dengan anggota, pemimpin dapat lebih mudah menyuarakan kepentingan anggotanya.
Di level daerah, banyak pimpinan PGRI yang juga bukan guru melainkan kepala dinas pendidikan setempat. Sehingga tudingan bahwa PGRI masih bersifat politis untuk meraih jabatan tertentu sulit dielakkan. Dengan jaringan struktur hingga tingkat desa, PGRI memang cukup “seksi” untuk menaikkan daya tawar pengurusnya. Apalagi jumlah anggotanya diklaim sekitar 1,6 juta orang dari total guru di seluruh Indonesia sebanyak 3,015 juta orang guru.
Meski organisasinya “gemuk” dan sudah mengakar, namun cita-cita awal pendirian organisasi ini tampaknya masih jauh panggang dari api. Misalkan, tujuan untuk membela nasib para guru. Jangankan melakukan pembelaan, di banyak tempat justru malah membebani guru. Ambil contoh pemberitaan pada Koran Tempo.co.id, 2 Desember 2013 berjudul “Guru Daerah Keluhkan Pungutan PGRI”. Sejumlah guru di daerah mengeluhkan pungutan gaji ke-13 sebesar Rp 50-400 ribu per orang yang dikenakan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia. "Pungutan juga ditarik dari para guru yang bukan anggota PGRI untuk kegiatan rutin organisasi dan pembangunan sarana organisasi," kata Fahmi Hatib, guru SMP Negeri 1 Monta, Kabupaten Bima, yang juga mantan Bendahara PGRI Bima. Misalnya, menurut Surat Edaran PGRI Kabupaten Bima, yang salinannya diperoleh Tempo, seluruh kepala sekolah di kabupaten itu wajib menarik pungutan dari para guru untuk pekan olahraga seni dan kongres pengurus besar PGRI pada 1-5 Juli 2013.
Sementara Hariyantoni, guru di Kabupaten Banteng, Bengkulu, juga mengeluhkan tindakan PGRI mengenakan pungutan terhadap gaji ke-13 pada Juli 2013 untuk membangun gedung sekretariat PGRI provinsi. Besarannya Rp 150 ribu per orang. "Padahal mereka (PGRI) pernah ditawari Rp 1 miliar oleh pengurus provinsi untuk membangun gedung, tapi ditolak," ujarnya.
Masih dari sumber yang sama, sejumlah guru di daerah, mengeluh banyak pungutan yang dikenakan PGRI daerah di luar ketentuan yang telah diatur PGRI pusat. Pungutan itu biasanya dikenakan ketika guru mendapat gaji ke-13. Adapun besaran potongannya disesuaikan dengan jabatan dan golongan. Besaran pungutannya berkisar Rp 50-400 ribu.
Padahal menurut BPK, PGRI mendapat berbagai fasilitas dari negara, baik di APBD maupun APBN. Pada APBN 2013 saja pemerintah pusat memberikan dana sebesar Rp 10 miliar untuk PGRI. Sementara, dalam APBD DKI Jakarta 2013 melalui anggaran dinas pendidikan memberikan Rp 750 juta.
Meski datanya 2 tahun lalu, namun dari pemberitaan media nasional itu membuktikan bahwa ada masalah struktural dan transparansi di tubuh organisasi profesi guru tertua itu. Ini adalah pekerjaan rumah yang perlu diprioritaskan. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kata kunci untuk menjaga harga diri PGRI ke depan.
Dengan dana sebesar itu, seharusnya PGRI dapat lebih memberdayakan anggotanya. Jika klaim bahwa 80 persen guru yang tergabung dalam PGRI benar, maka seharusnya kompetensi, profesionalisme, dan kinerja guru sudah sangat baik. Namun, fakta berbicara lain. Dari 3 juta orang guru, sebanyak 27,5% guru di 288 kab/kota belum S1/D4. Belum lagi jika melihat hasil Ujian Kompetensi Guru (UKG) tahun 2002-2014. Hanya 192 orang guru (dari TK sampai SMK) yang memperoleh nilai di atas 90. Sedangkan sebagian besar (495 ribu guru) mendapat nilai antara 40-50. ***
---
Data itu menunjukkan bahwa masih banyak guru yang tidak kompeten. Karena itu, jika PGRI serius memperjuangkan nasib guru, maka seharusnya mereka bekerja sama dengan pemerintah. Urusan kompetensi sejatinya juga menjadi tanggung jawab organisasi profesi seperti PGRI.
Selain urusan kompetensi, dengan banyaknya pengurus PGRI yang juga politisi, organisasi ini rawan untuk dipolitisasi. Temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), mendekati pilkada calon kepala daerah biasanya memanfaatkan guru sebagai alat kampanye. Maklum, guru adalah jumlah profesi paling banyak di Indonesia. Mereka paling strategis untuk dijadikan alat kampanye di musim pilkada.
Para guru biasanya dijanjikan kesejahteraannya sehingga didorong untuk memenangkan calon kepala daerah tertentu. Dengan keterlibatan guru dalam kegiatan politik sudah barang pasti dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar. Hal ini menjerumuskan guru dalam ketidakprofesionalan dalam mendidik muridnya.
Pada titik ini, PGRI dituntut komitmennya dalam meningkatkan mutu pendidikan di Tanah Air. Langkah awal membuktikan komitmen itu adalah menjauhkan anggotanya dari politik praktis. Bisakah? ***
Ikuti tulisan menarik Ronggo Warsito lainnya di sini.