Banteng Gondrong
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Iklan
Gondrong atau Mohawk, spike atau cepak, tak penting bagi politisi partai. Dan lagi-lagi pahami saja. Itu kuncinya.
Jika Golkar pasca pilpres terlihat sempoyongan tak karuan, bergerak linglung seperti mobil parkir yang ditumpangi pasangan mesum, maka wajari saja. Pohon ini sangat besar, punya sejarah politik yang belum tertandingi, bahkan oleh PDIP sekalipun. Sejarah berkuasa partai ini cukup lama, jadi saat sebagian petinggi baru mencondongkan pohon beringin ke luar halaman istana, maka akan banyak yang tak terima. Sekali lagi, wajari saja, tak ada masalah. Rakyat pemilih pun saya kira akan mahfum belaka.
Nah, jika hari ini kita menyaksikan Golkar dengan berat hati harus mengatakan “goodbye” kepada sekondannya di dalam Koalisi Merah putih, dengan kacamata diatas tadi, maka itupun biasa saja. Tak perlu ada “farewell party” yang berlebihan. Bahkan tokoh sekaliber Prabowo 08 pun sangat maklum hal ini dengan menyematkan sedikit kata permakluman bahwa Gerindra memahami kondisi politik yang ada dan memahami keputusan “on the record dan off the record” yang diambil oleh pohon beringin jika ternyata harus merapat kembali ke istana.
Karena memahami itulah Gerindra akhirnya sangat ikhlas menjadi oposisi sendiri. Ini layaknya keputusan menjomblo, jomlo itu pilihan, bukan nasib. Kadang-kadang orang jomlo memang suka membela diri, karena realitasnya memang sendiri, tak ada pasangan dan kawan, maka defenisinya sudah seharusnya menjomlo, apapun latar belakanng yang menyebabkan mengapa seseorang sampai harus menjomlo. La wong tuhan pun sudah mewanti-wanti, hidup itu diciptkaan dalam kondisi yang berpasang-pasangan, kalau ada yang mengatakan tanpa pasangan adalah sebuah keputusan, maka tuhan yang mana yang telah menakdirkan kondisi itu? Nampaknya tak salah jika itu kita pertanyakan pada mereka yang jomlo, bukan.
Tentu ini bukan perkara bahwa di dalam politik itu tidak ada kawan abadi, yang ada adalah kepentingan abadi, tapi ini perkara saling memahami. Koalisi Merah Putih yang semula kelihatan begitu tambun dengan anggota-anggota koalisi yang memang sudah berumur diatas 50 tahun (artinya obesitas adalah hal yang biasa), akhirnya kalang kabut juga setelah Golkar, partai terbesar di dalam koalisi, terombang ambing ombak besar antara Ancol dan Bali. Kenyataan ini harus dipahami oleh semua pihak, terutama oleh pihak-pihak yang semula telah membesarkan KMP.
Mengapa? Karena berpolitik adalah bersikap realistis. Jika tak butuh berteriak melebihi kenyataan, mengapa harus berteriak berlebihan. Jika memang ‘bubar” adalah pilihan terbaik, ya semua pihak harus terima. Ini kan ibarat orang berpisah, tapi tak bercarai. Yang satu harus mengais rejeki di dalam Istana, yang lain harus mencari makan diluar istana, ya sama saja, sama-sama cari makan. Itulah yang disebut realistis.
Ibarat pasangan lama yang sudah saling memahami, yang satu harus merelakan diri menjadi tante-tante genit yang cubit sana cubit sini, yang satu berfilsafat tentang kesetiaan dan murninya sebuah perasaan, sehingga dikhianatipun terasa sangat manis. Jika ada yang menyebut itu masokisme politik, ya itu cuma perkara terminology saja, kebetulan yang memberi gelar itu memahami ilmu psikologi, misalnya. Toh orang partai jarang yang belajar psikologi, tak penting bagi mereka istilah ini dan itu yang diproduksi di kampus atau dilaboraturium, sungguh tak penting, percaya deh sama saya.
Bukankah sudah biasa para politisi menganut ajaran “anjing menggong kafilah berlalu”. Mau dikata apa, mereka tetap berasaskan “terserah”. Maksudnya, “terserah” siapa yang anjing dan siapa yang kafilah, yang penting asasnya ya begitu itu, “terserah”. Bahkan jika H. Rhoma Irama pun ikut terenyeuh melihat kondisi yang ada saking semerautnya, lalu berujar “terlalu” dan tanpa sadar tertular, kemudian ikut-ikutan mendirikan partai dan asas itu akhirnya berubah menjadi “terlalu terserah”, konsepnya tetap sama, yakni “terserah”, “terserah orang-orang pada bicara apa, sakit ya sakit saya, partai ya partai saya, untung ya untung saya, kalau rugi ya nanti dulu”, begitulah kira-kira prinsipnya.
Disisi yang lain, jika Istana terkesan mengobok-obok partai berwarna kuning (jangan ngeres dengan warna kuning) sejak pilpres berakhir, maka itupun wajari saja. Ini politik bro, apapun akan menjadi sah-sah saja jika semua pihak bisa diajak untuk menyepakatinya. Istana, yang kekuasaannya tak perlu lagi dipertanyakan, mampu kok menlakukan itu. Nah topiknya akan kembali lagi ke urusan realistis tadi. Jika istana mampu, maka wajar istana melakukan itu. Obok sana obok sini, siapa berani larang. Ini adalah realisme politik, jika mampu, ya lakukan saja, urusan ada aturan main, itu pastinya urusan belakangan. Aturan dibuat untuk dirubah, jika perlu. Jika tak perlu, ya mari sama-sama kita berteriak “tegakan hukum meskipun langit runtuh”.
Dengan logika seperti ini, terlihat begitu sederhananya urusan politik itu, bukan? Rakyat tak perlu pusing dengan mengatakan bahwa urusan politik itu urusan orang gedean, urusan yang memusingkan, toh hari ini terlihat semuanya sederhana saja. Mereka berteman, mereka terkadang saling menggunjingkan layaknya anda menggunjingkan tetangga atau mantan sahabat yang sudah jarang bertegur sapa. Itu biasa saja, itulah hidup. Dan itulah politik sevulgar-vulgarnya politik.
Kuncinya, pahami saja layaknya mereka saling memahami. Bukan kah keharmonisan itu bermula dari kesalingpahaman, lalu saling memberi dan menerima, saling menghormati dan memberi respon positif. Ini nilai-nilai ketimuran yang sudah membesarkan kita. Dan mereka sedang menerapkan itu, lalu mengapa harus dipersoalkan. Mereka memainkan kartu yang seharusnya dimainkan. Itulah mengapa harus dipahami dengan seluruh jiwa dan raga kita sebagai rakyat.
Jadi tak perlu dibawa-bawa urusan Lapindo. Urusan Lapindo sudah lewat, sudah menyedot begitu banyak anggaran APBN alias sudah biasa dan sudah diwajari oleh publik. Bukan pula urusan konstelasi politik istana yang belum permanen. Konstelasi istana dari dulu memang tak pernah permanen, sudah biasa pasang surut dan jatuh bangun, terutama sejak reformasi bermula. Jadi ini hanya urusan saling memahami, istana paham, Golkar pun paham, sehingga mau tak mau Gerindra pun harus pula paham. Itu saja.
Nah, dengan asas terserah tadi, jika Istana yang secara konstelatif disokong oleh PDIP tertimpa Golkar, lalu mendadak bertampang gondrong karena kepala banteng harus ditiban pohon beringin yang rindang, itupun tak perlu dipandang lucu. Itu biasa saja, tak perlu memakai teori-teori dari sekolah penata rambut bahwa itu penampakan yang buruk, mereka tak akan paham. Besar kemungkinan tidak ada yang lulusan sekolah peñata rambut di partai, jadi tak akan ada yang mengamini bahwa itu adalah penampilan yang buruk. Gondrong atau Mohawk, spike atau cepak, tak penting bagi politisi partai. Dan lagi-lagi pahami saja. Itu kuncinya.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Kalkulasi Politik Kang Emil
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Banteng Gondrong
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
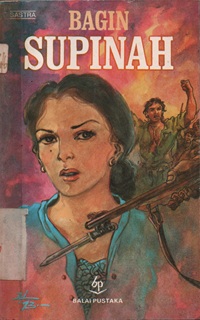






 99
99 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan












