Ledhek dan Subordinasi Gender
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Gaung emansipasi adalah senjata yang dapat melunturkan ibuisme
Representasi kaum hawa yang terbatas di mata publik merupakan warisan rezim Orde Baru (1966-19898) yang secara apik mampu memposisikan wanita ke dalam subordinasi kekuasaan pria. Politik gender yang dimainkan mampu menjadikan wanita terkungkung pada wilayah kodratinya. Akan tetapi, ledhek, penari ritual di Jawa, mampu membingkai semangat emansipasi yang mungkin tak disadari oleh rezim karena bertubi-tubinya stigmatisasi buruk terhadap peran sosial yang dimainkannya.
Idealnya, selama Orde Baru, seorang wanita berperan sebagai isteri dan ibu bagi buah hatinya. Dalam istilah Jawa, secara hierarkis, wanita adalah kanca wingking (teman belakang) yang peranannya terbatas pada macak, masak, dan manak (berdandan, memasak, dan melahirkan). Kehadiran wanita tak lebih hanya sebagai pelengkap sebuah rumah tangga dengan fungsi seksual yang dimilikinya. Pandangan ideal wanita kembali kepada periode kolonial, 1930an.
Produksi kultural Orde Baru, yang secara masif diperankan oleh media, merepresentasikan keterbungkaman wanita dan subordinasi posisinya terhadap kaum pria. Film Janur Kuning mempertontonkan representasi wanita sebagai seorang isteri yang patuh kebijakan negara. Potret perkosaan wanita dalam banyak sinema Indonesia, kala itu, membingkai keterbatasan seksualitas wanita yang berada dalam genggaman pria. Wanita adalah korban yang berbicara dan melihat dari kaca mata pria.
Ledhek, sebenarnya, hadir sebagai sebuah antitesis kebijakan pemerintah. Peran sosial yang dimainkannya, setidaknya, mampu merepresentasikan wanita tak harus melulu seperti prototipe yang dicanangkan oleh negara. Secara kultural, memang, ledhek hadir di tengah masyarakat sebagai seorang penyanyi bayaran yang menampilkan atraksinya pada ritual atau acara tayuban, pesta pasca panen. Lekuk tubuh dan lincah gerak tariannya adalah ucapan syukur atas keberkahan serta hiburan tahunan dan menjadi identitas masyarakat di perkampungan. Akan tetapi, ledhek tak ubahnya simbol keberanian wanita yang tampil di muka umum dengan keahlian tradisoinal yang dimilikinya. Resiko berat yang mengiringi profesinya, seperti godaan, kecupan para lelaki yang bukan suaminya, bahkan perkosaan adalah tantangan kehidupan yang harus ia arungi. Dengan segala keterbatasan yang dimilikinya, ia mencoba eksis dalam kebudayaan Indonesia di tengah gempuran kebudayaan yang dianggap lebih bernilai tinggi dan populer.
Kebijakan rezim Orde Baru dalam kaitannya dengan feminiitas, dalam budaya tarian, diwujudkan melalui sesuatu yang tinggi dan mulia seperti laiknya kultur istana Jawa. Sisi estetis ditampilkan tanpa menguak seksualitas yang mewujud kesederhanaan, berkebalikan punggung dengan ledhek. Ledhek merupakan simbol erotisme yang mengeksploitasi seksualisme dan terlepas dari pakem perempuaan buatan pemerintah.
Antitesis yang coba ditawarkan oleh para ledhek dapat diredam secara lihai oleh kuasa rezim. Produksi film Nji Ronggeng, 1969, serta Ronggeng Dukuh Paruk, 1980an yang diangkat dari novel Ahmad Tohari memosisikan wanita sebagai korban yang hanya dapat ditolong oleh seorang pria. Subordinasi wanita di bawah kaum pria sangat kentara dan menjadi wacana utama. Bahkan, dalam film Ronggeng Dukuh Paruk, sang penari, Srintil, dipenjarakan karena menari pada kampanye partai komunis. Tayubam diasosiasikan dengan komunisme karena menjadi bagian dari LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) yang dianggap sayap kebudayaan partai komunis.
Satu fakta menarik mencuat ketika seorang ledhek menggunakan selendang merah saat tampil. Sekonyong-konyong, ia kena marah sang boss, yang seorang bupati, karena tak menggunakan selendang berwarna kuning. Sang ledhek berargumen hal itu hanya, estetis tanpa muatan politis. Ketika tampil ia menggunakan blus berwarna kuning dan mengkontraskannya dengan selendang berwarna merah. Ternyata warna kuning adalah representasi dari partai penguasa, Golkar (Golongan Karya), sementara merah adalah simbol partai Megawati, PDI-P (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), yang menjadi oposisinya. Tanpa disadari, sebuah pertunjukan telah menjadi agen politik dan melewati batas-batas kewajaran.
Pasca reformasi yang berhasil merubuhkan tembok tirani di negeri ini, isu gender masih mengemuka. Warisan Orde Baru yang menjadikan wanita sebagai subordinasi tentu layak untuk dikritisi. Momentum hari ibu, yang tepat jatuh hari ini, menuntut untuk dilakukannya reinterpretasi posisi sosiologis wanita dalam kehidupan sehari-hari. Kita patut mengapresiasi usaha pemerintah Jokowi yang mencoba memberikan ruang bagi kaum hawa untuk turut berpartisipasi dalam lingkup birokrasi dengan memangku jabatan sebagai menteri. Meski masih kentara dominasi kaum pria, setidaknya hal itu mampu mencuatkan semangat emansipasi dan mengikis adanya subordinasi. Hanya dengan gaung emansiasi, stereotip wanita sebagai kanca wingking akan ditransformasi menjadi kanca ngarsa (teman depan) yang sama-sama berjuang menggapai masa depan yang lebih baik.
PRIMA DWIANTO
Alumni Jurusan Ilmu Sejarah, FIB, UGM
(Sumber Foto: Felicia Hughes-Freeland, Gender, Representation, Experience: The Case of Village Performers in Java)
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Romantisme Sukarno-Hatta dan Wajah Semu Demokrasi Kini
Minggu, 1 September 2019 13:23 WIB
Mitos dan Kuasa Pasar: Dewi Sri sebagai Penguat Subsistensi
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0






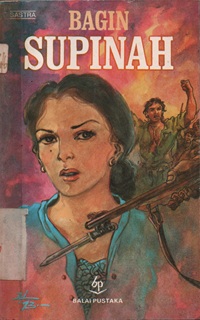

 97
97 0
0






 Berita Pilihan
Berita Pilihan






