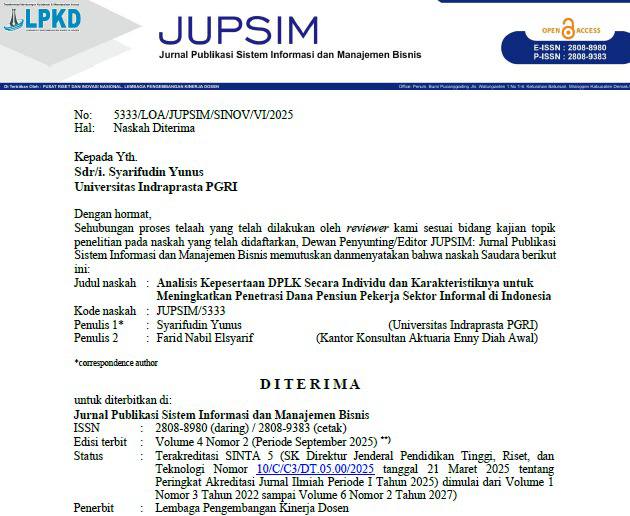Sampai Kapan Akademisi Tiarap?
Minggu, 2 Mei 2021 06:57 WIB
Bagaimana para akademisi kampus mau mengajarkan dengan baik dan benar kepada para mahasiswanya untuk menemukan dan menegakkan kebenaran ilmiah, jika mereka sendiri tidak berani menegakkan kehormatan sebagai akademisi. Bagaimana para akademisi akan merasa terhormat bila membiarkan kemerdekaan berpikir dan kebenaran ilmiah disubordinasikan oleh kekuasaan?
Lama tidak terdengar suaranya dan tidak terbaca tulisannya, akhirnya muncul juga suara dari lingkungan kampus akademik yang berbicara tentang lingkungan sendiri: lingkungan kampus perguruan tinggi, lingkungan akademik. Dalam wawancara dengan channel Youtube Bravos Radio Indonesia beberapa hari lalu, Prof. Dr. Sulistyowati Irianto, SH. MA., guru besar antropologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, melontarkan kritik tajam terhadap lingkungan akademik.
Secara khusus, Prof. Sulistyowati mengritik akademisi masa sekarang sangat mengabdi kepada birokrasi, sehingga bersikap sangat formalis dan berlebihan dalam mengikuti arahan kementerian. Padahal, kata guru besar ini, universitas merupakan institusi yang otonom dan berada di tengah jantung masyarakat. Para akademisi, masih kata Prof. Sulistyowati, mestinya memahami bahwa ilmu harus berpihak kepada kemanusiaan dan lingkungan, termasuk lingkungan hidup.
Jika kita mengikuti logika Prof. Sulistyowati, maka para akademisi mestinya berbicara ihwal kebenaran, keadilan, dan hal-hal lain terkait kemanusiaan yang tidak steril dari kejadian di dalam masyarakatnya; bukan membenarkan apa saja yang dilakukan birokrasi dan pemerintahan. Sayangnya, kata guru besar ini, banyak akademisi yang kehilangan daya kritis dan tidak berani speak out. Ia mencontohkan, ada ahli perburuhan tidak pernah berbicara tentang perburuhan, ada ahli korupsi tidak pernah menyoroti persoalan korupsi. Di dalam lingkungannya sendiri saja, bahkan mereka tidak peduli pada praktik plagiarisme dan praktik kecurangan lainnya.
Otokritik Prof. Sulistyowati ini sangat relevan dengan situasi sekarang ketika para akademisi dan intelektual umumnya terlihat sedang tiarap di hadapan kekuasaan. Suara mereka mengenai isu-isu kemanusiaan, kemasyarakatan, dan pemerintahan terbilang sepi. Kritik terpenting Prof. Sulistyowati ialah hilangnya daya kritikal akademisi sehingga terkesan menutup mata terhadap apa yang terjadi di tengah masyarakatnya. Padahal, sebagai akademisi, mereka dituntut untuk mempraktikan kemampuan berpikir kritis yang mereka ajarkan kepada anak didik mereka di kampus. Mengapa para akademisi tiarap dan bungkam?
Meskipun menyaksikan keadaan yang menuntut perhatian kaum cerdik cendika, para akademisi justru cenderung memilih untuk berdiam diri dan menyimpan ilmu mereka rapat-rapat ketimbang memakainya sebagai pisau analisis untuk menjelaskan berbagai persoalan kepada masyarakat luas. Integritas mereka sebagai akademisi—dan sebagai intelektual dan ilmuwan yang memburu dan menegakkan kebenaran—tampak bengkok tatkala dihadapkan pada kekuasaaan. Banyak akademisi yang terlihat senang menjadi pejabat tinggi negara, bahkan seorang guru besar perguruan tinggi negeri terang-terangan menawarkan diri menjadi menteri.
Bagi mereka, mengembangkan ilmu, mendidik mahasiswa, serta memperkuat ekosistem perguruan tinggi barangkali dianggap kalah bermartabat. Menjadi pejabat publik, yang karena itu juga berpolitik praktis, memang bukan hal yang buruk seandainya para akademisi ini tetap mampu menjaga integritas dan kredibilitasnya sebagai akademisi dan intelektual. Namun kenyataannya, godaan terhadap jabatan publik jauh lebih menggiurkan—baik yang berkaitan dengan akses terhadap pusat sumber daya ekonomi, pusat kekuasaan dan pengambilan keputusan, maupun kehormatan karena jabatan.
Kita menyaksikan banyak akademisi, sekelas guru besar sekalipun, yang kemudian membenarkan apapun kebijakan yang diambil pemerintah dan mengabaikan prinsip-prinsip akademis yang seharusnya ia tetap pertahankan: mendukung bila benar dan mengritik bila salah. Dalam perdebatan di televisi, kita pernah disuguhi tontonan akademisi yang membela habis-habisan kebijakan yang dikritik luas oleh masyarakat. Ia, meminjam istilah Prof. Sulistyowati, kehilangan daya kritis—barangkali jabatan sebagai staf ahli telah menumpulkan daya kritisnya.
Sikap para akademisi ini sungguh berbeda dengan para akademisi yang aktif pada masa Orde Baru. Sekalipun orde ini dikenal sebagai rezim yang galak terhadap perbedaan pandangan, namun para akademisi tetap setia kepada integritasnya sebagai ilmuwan dan intelektual. Bahkan pada masa pergolakan kampus pada tahun-tahun 1970an, para rektor bersama akademisi berbagai perguruan tinggi tetap berusaha menjaga kehormatan akademik dengan tidak menyerah begitu saja kepada kemauan pemerintah. Saat menjalani masa-masa sulit perguruan tinggi berhadapan dengan kekuasaan Orde Baru, mereka tidak mudah menyerah.
Bagaimana para akademisi kampus mau mengajarkan dengan baik dan benar kepada para mahasiswanya untuk menemukan dan menegakkan kebenaran ilmiah, jika mereka sendiri tidak berani menegakkan kehormatan sebagai akademisi. Bagaimana para akademisi akan merasa terhormat bila membiarkan kemerdekaan berpikir dan kebenaran ilmiah disubordinasikan oleh kekuasaan? Sampai kapan para akademisi umumnya menutup mata terhadap perkembangan masyarakatnya? >>
Penulis Indonesiana
2 Pengikut

Di Balik Dugaan Manipulasi Angka Statistik ala Rezim Prabowo
Rabu, 27 Agustus 2025 18:54 WIB
Di Balik Amnesti Hasto: Prabowo dan Megawati Sepakat Mengubah Permainan
Sabtu, 2 Agustus 2025 08:59 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0




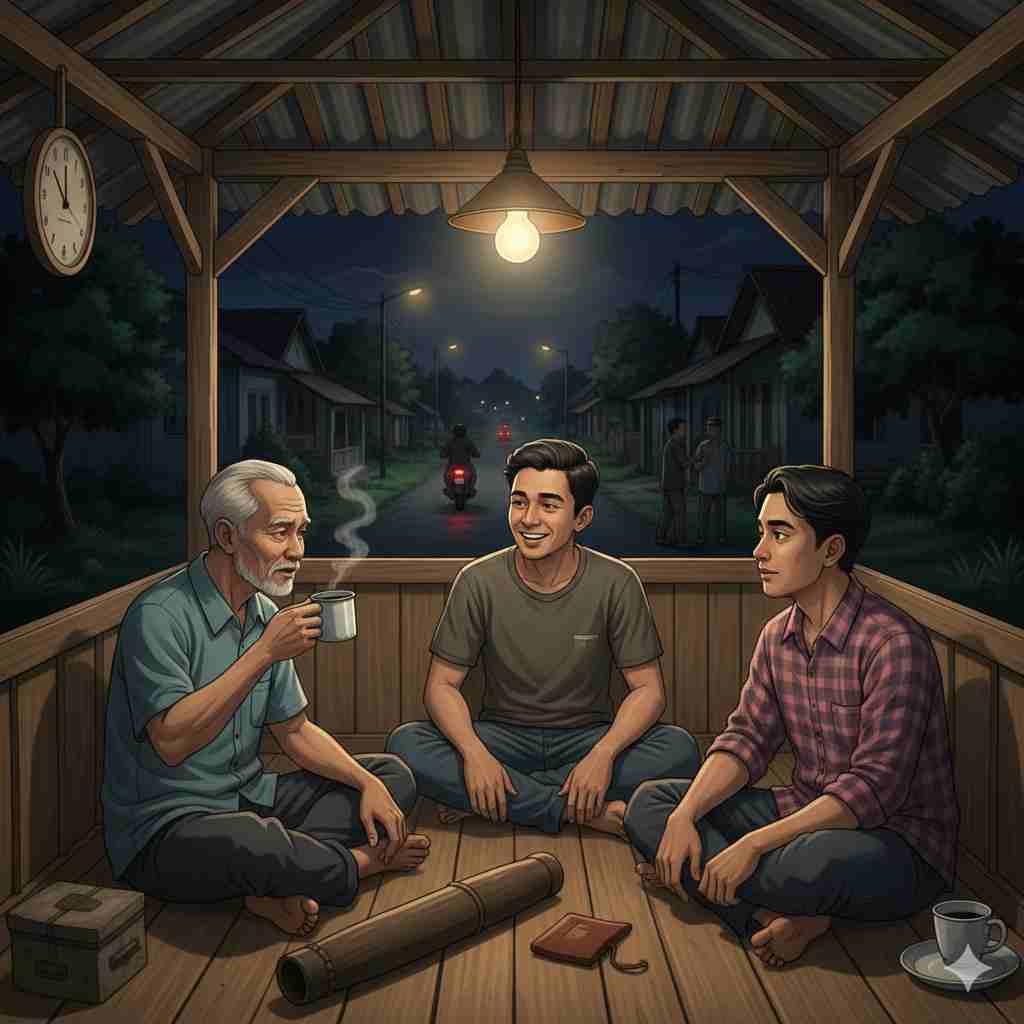

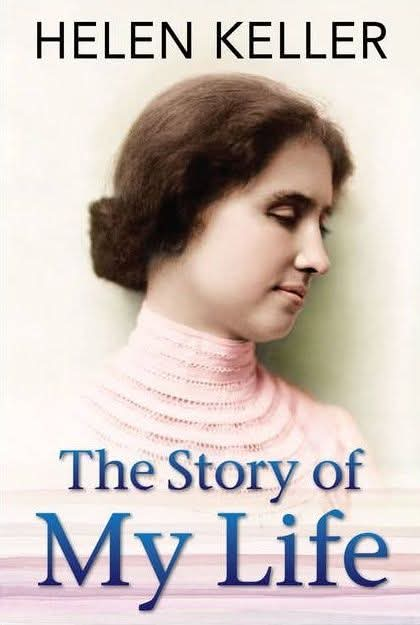
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 96
96 0
0