Rasa Yang Tak Pernah Ingin Kurasakan
Rabu, 8 Desember 2021 21:11 WIB
Kenangan pahit itu masih terekam dengan begitu jelas di dalam kepalaku, terus berputar bak sebuah kaset rusak yang dipaksa untuk berbunyi. Rasa hari itu masih terasa hingga saat ini, tipe rasa yang tak pernah ingin ku rasakan lagi di dalam hidupku yang singkat ini.
Saat itu, saat matahari masih berada di atas kepala, aku mendapati ponselku berdering, menggemakan lantunan lagu favoritku dari penyanyi kekinian, Selena Gomez. Dengan gerakan cepat, salah satu tanganku terulur untuk meraih ponselku yang terselip di balik bantal kapuk.
Deg. Deg. Deg.
Jantungku berpacu dengan begitu hebatanya, kedua netra hitamku membelalak dengan begitu sempurna saat aku mendapati nama si pemilik panggilan.
Wali Kelas.
Dua kata yang berhasil membuatku bertanya, apakah aku telah melakukan sebuah kesalahan? Dengan naluriah, aku kembali mengingat – ingat apa yang telah ku lakukan dan yang telah ku katakan kepada wali kelasku yang sangat pemilih itu. Namun, tiba – tiba, terlintas di dalam benakku sebuah alasan yang mungkin menjadi dasar wali kelasku menghubungiku disaat luar jam pelajaran sekolah seperti ini.
Lomba.
Ya. Setelah berpikir begitu keras, akhirnya aku mendapatkan kemungkinan jawaban dari pertanyaan yang memenuhi otakku. Tanpa bisa dicegah, rasa bahagia dan semangat langsung membumbung tinggi di dalam relung hatiku.
Saat itu, aku memang sedang mengikuti lomba bertaraf nasional dan aku telah berhasil melewati tahap penyisihan pertama, tinggal tiga tahap lagi, aku dapat mengikuti tahap final dari lomba bertaraf nasional tersebut. Ah ya, sebelumnya, aku memang telah menginformasikan kepada sekolahku bahwa aku ingin mengikuti lomba ini, namun sayang, mereka tak mengirimkan satu sosok guru untuk mendampingi langkahku selama mengikuti lomba.
Dengan jantung yang masih berdegub dengan begitu kerasnya, jari telunjukku terulur untuk mengangkat panggilan itu.
“Selamat siang pak. Ada apa pak?” tanyaku dengan begitu formal saat panggilan suara itu terhubung
“Selamat siang Bintang. Bapak ingin bertanya, darimana kau mendapatkan surat izin mengikuti lomba?”
Deg.
Tubuhku membeku dengan begitu sempurna.
Ada apa ini?
Tanpa bisa dicegah, aku menggigit bibir bawahku dengan begitu cemas. Rasa panik berhasil melahap habis seluruh rasa bahagia yang tadi sempat memenuhi diriku.
“Oh itu, pak. Saya mendapatkannya dari kantor tata usaha, pak,” ucapku dengan jujur, walau hatiku diliputi rasa cemas.
Aku masih ingat, ketika aku meminta surat izin mengikuti lomba dari sekolah, wali kelasku tersebut berada di tempat yang sama denganku. Bahkan, beliau sempat mendatangiku dan menanyakkan alasanku berada di kantor tata usaha sekolah.
Namun sekarang, kenapa beliau menanyakan sebuah pertanyaan yang seharusnya sudah bisa didapatinya sendiri jawabannya? Apa karena aku tak termasuk dalam jajaran siswa penjilat yang berhasil menarik perhatiannya?
“Iya, nak. Atas izin siapa kamu mengambilnya?”
“Dari wakil kepala sekolah, pak,” ucapku sembari berusaha untuk tak menunjukkan getar ketakutan dalam setiap kata yang terucap dari bibirku.
“Oh. Tunggu sebentar, wakil kepala sekolah mau berbicara denganmu,”
Apalagi ini sekarang?!
Jiwaku berteriak dengan begitu nyaring. Setelah lebih dari dua minggu aku meminta surat izin dari sekolah, namun kenapa… kenapa harus sekarang mereka mempermasalahkannya?
“Kenapa kamu buat nama saya di surat izinmu?!”
Pertanyaan itu tak terdengar seperti sebuah pertanyaan yang seharusnya dilontarkan seorang guru kepada siswanya. Pertanyaan itu terdengar seperti sebuah pertanyaan penuh amarah yang dilontarkan seorang majikan kepada budaknya.
“T—tapi, saya ‘kan sudah izin dengan bapak. Bapak juga yang menyuruh saya untuk mengambil di kantor tata usaha atas nama bapak,” ucapku dengan kedua netra yang terlihat begitu berkaca – kaca.
Saat itu, rasanya aku ingin langsung meneteskan air mata yang telah tertampung di kedua pelupuk mataku, namun aku tak bisa. Aku harus tetap kuat, karena aku sedang membicarakan kebenaran, tak seharusnya aku menangis seperti seorang pengecut.
“Tapi lomba itu bukan bidang bapak! Bapak guru fisika, itu lomba ekonomi! Seharusnya kamu tanya dulu sama bapak, supaya bapak carikan kamu guru ekonomi!”
Bum!
Seperti terdengar suara lonceng dari menara Big Ben di dalam kepalaku, menggema lalu melumpuhkan kinerja otakku. Untaian kalimat penuh amarah yang diucapkan oleh beliau benar – benar membuatku mempertanyakan kewarasanku sendiri. Rasanya, sebelum aku mengikuti lomba, aku telah menanyakkan hal ini kepada beliau dan ia hanya memberitahuku untuk mengambil surat izin di ruang tata usaha.
“Kemarin bapak hanya bilang kalau saya bisa langsung mengambil surat iz—
“Tapi bapak tidak ada menyebut kalau kamu bisa memakai nama bapak di surat izin itu!”
Skak mat.
Lidahku terasa begitu kelu ketika aku mendengarkan rangkaian kata itu dari loudspeaker ponselku. Tak pernah terbesit di dalam hatiku bahwa akan tiba hari ini, hari dimana guru yang ku anggap ‘dekat’ dengan diriku akan mengucapkan kalimat penuh amarah kepadaku hanya karena sebuah masalah sepele.
Saat itu, aku tak tau ingin mengatakan apa lagi kepada beliau. Hatiku bertanya – tanya, apa yang salah jika namanya tertera di dalam surat izin itu? Aku meminta izin padanya dan ia adalah seorang wakil kepala sekolah, apa yang salah?!
Setelah itu, beliau kembali berbicara, mengucapkan berbagai kalimat penuh amarah yang tak lagi kudengar. Saat itu, hanya ada satu pertanyaan yang bersarang di dalam kepalaku, kenapa beliau tak memberikanku kesempatan untuk membela diri? Apa karena aku dan beliau dipisahkan oleh jarak usia yang begitu jauh? Atau apa karena aku dan beliau dipisahkan oleh jabatan yang begitu tinggi?
Aku tak tau dan aku tak mau tau. Saat itu, aku hanya berupaya untuk tidak menangis, aku tak ingin membuat keluargaku yang berada di rumah mempertanyakan kedua mataku yang akan terlihat sembab nantinya.
“Surat izin itu harus diganti!”
Kerutan yang begitu dalam menghiasi keningku saat aku mendengar kalimat yang penuh akan keotoriteran itu terucap dari bibir wakil kepala sekolahku. Bagaimana bisa dia dengan begitu mudahnya memintaku untuk mengganti surat izin, disaat aku bahkan telah lulus di tahap satu?!
“Tapi pak, saya sudah mengirim berkasnya ke pihak penyelenggara lomba. Saya juga sudah lulus tahap satu pak, jika ada perubahan data, mungkin saja saya akan didiskualifikasi, pak,” ucapkan di sela – sela kesesakan yang mulai menghimpit dadaku.
“Bisa! Namanya diganti dengan nama guru ek---
“Enggak. Enggak perlu!”
Suara wakil kepala sekolah terputus, tergantikan oleh suara seorang wanita. Sepertinya, saat ini tak hanya ada wali kelasku saja yang bersama dengan wakil kepala sekolah, namun juga seorang guru wanita yang kuyakini merupakan guru mata pelajaran ekonomi di kelasku.
Kedua netra hitamku tampak begitu kosong. Aku mendengar wakil kepala sekolah serta guru ekonomi itu saling berbicara dengan amarahnya masing – masing terhadap diriku, terdengar samar memang, namun kalimat – kalimat mereka berhasil memupuk rasa benci di dalam hatiku.
“Nak, lain kali, jangan diulangi ya,”
Itu suara wali kelasku, namun entah kenapa, aku tak merasakan sedikitpun rasa tenang ketika mendengar kalimat lembutnya. Saat aku mengambil surat izin, dia ada disana, melihat dan mempertanyakan surat izinku, namun saat itu, ia hanya diam dan tak mengatakan apapun kepadaku saat ia melihat nama wakil kepala sekolah tertera di atas kertas putih itu.
Dia wali kelasku, ayahku saat aku berada di sekolah, namun kenapa ia tak membelaku? Kenapa ia tak membela putrinya sendiri?
Pip.
Panggilan itu diputus secara sepihak dan disaat itu pula, aku merasakan setengah jiwaku melayang di udara. Pikiranku kosong.
Bayang – bayang amarah wakil kepala sekolah selalu menghantui kepalaku. Nasi padang yang seharusnya terasa begitu lezat di dalam mulutku, kini terasa begitu hambar. Aku sangat ingin menangis, namun aku tak bisa, mereka, kedua orang tuaku, selalu ada di sisiku dan aku tak ingin mengecewakan mereka dengan tangisanku.
Aku berusaha untuk menguatkan hatiku, aku selalu mengatakan kepada diriku bahwa semuanya akan baik – baik saja. Sekarang, aku hanya perlu fokus belajar dan membuktikan kalau aku dapat masuk ke tahap selanjutnya. Ya, seharusnya, aku melakukan itu, setidaknya, sebelum panggilan dari guru yang berbeda kembali menghiasi layar ponselku.
Aku sangat ingin untuk menolak panggilan itu, namun disaat yang bersamaan, aku ingin semuanya berakhir. Saat itu, di ruang tamu, aku mengangkat panggilan tersebut dengan berat hati.
“Halo, Bintang,” ucap guru wanita yang kuyakini mengajar mata pelajaran ekonomi di sekolahku.
“Halo, bu. Ada apa, bu?” tanyaku dengan sesopan dan seformal mugkin, walau hatiku telah mengetahui apa yang akan dibicarakannya.
“Seperti ini Bintang, ibu ingin membicarakan soal lombamu,”
Aku menarik nafas dalam – dalam ketika aku mendengar kalimat itu keluar dari mulut beliau. Aku telah mempersiapkan hatiku untuk menghadapi amarah lainnya.
“Jujur, waktu wali kelasmu membagikan surat kalau kamu berhasil lolos tahap 1, ibu terkejut. Kenapa ada nama wakil kepala sekolah disana? Seharusnya, disana itu nama guru ekonomi karena itu lomba ekonomi. Tentu saja lah ibu protes,”
Lalu, kau ingin aku melakukan apa?!?
Aku sudah begitu frustasi, aku merasakan kehidupan sekolahku telah hancur berantakan. Rasanya aku ingin berteriak kepada semua guru – guru itu, kenapa mereka tak bisa menutup mata akan hal ini dan membiarkanku mengikuti lomba dengan tenang?!?
“Itu ekonomi syariah dan kamu tidak mempelajarinya di sekolah, pasti sulit untuk bisa lol—
“Tidak, bu. Saya sudah belajar dan saya berhasil lolos tahap satu, saya sudah mengalahkan 400 lebih pelajar dari tahap satu,” ucapku dengan hati yang terasa begitu panas. Aku tak bermaksud untuk melawan, namun kalimatnya terdengar begitu meremehkanku.
Jangan singgung rasa hormat terhadap guru lagi padaku, karena rasa itu telah hilang saat mereka mempermasalahkan nama yang tertera di dalam surat izin lombaku.
“Oh, baguslah,”
Itu tak terdengar seperti sebuah pujian yang tulus, orang bodoh pun dapat mengetahuinya dengan mudah.
“Yasudah, ibu cuma mau meluruskan hal itu saja. Sekolah kita punya guru ekonomi, tak perlu repot – repot mencantumkan nama guru fisika kalau mau mengikuti lomba ekonomi,”
“Baik, bu. Maafkan saya kalau saya ada salah,” ucapku dengan nada yang terdengar begitu datar dan tak terselip sedikitpun keinginan meminta maaf dari hatiku. Aku mengatakan hal itu hanya untuk formalitas semata saja, agar panggilan sial ini dapat terputus dan aku dapat menangis di dalam kamarku.
“Oke. Ibu tutup panggilannya,”
Pip.
Kali ini, aku yang menutup panggilannya. Aku meremas ponselku dengan gerakan begitu kasar dan disaat itulah aku sadar bahwa sedari tadi Ibuku berada di ruang tamu, mendengarkan panggilan itu dan memperhatikan ekspresiku.
Aku terkejut, aku tak menyangka jika Ibuku akan berada disini. Tatapan kami bertemu dan terkunci untuk beberapa detik, namun entah kenapa, aku melihat sorot kesedihan di kedua netra hitam milik ibuku. Sorot kesedihan yang mengundangku untuk meneteskan air mata.
Tes.
Kristal – kristal bening yang sedari tadi sudah kutahan dengan mati – matian, kini meluruh jatuh dari kedua netra hitamku. Ibuku melihatku menangis tak berdaya dengan rintihan yang terdengar memilukan, ia lantas mendekatiku dan menarikku ke dalam pelukan hangatnya.
Di dalam pelukan hangatnya, aku menumpahkan segala kesedihanku. Ibu tak mengatakan apapun dan aku pun tak mengharapkan Ibu akan mengerti masalahku karena aku sendiri pun tak mengerti apa inti dari masalah ini. Elusan lembut yang diberikan oleh ibu di atas punggung kecilku tak membuahkan hasil apapun, aku tetap menangis dan terus menangis.
Sisa hari itu, seharusnya aku menghabiskannya dengan kegiatan belajar untuk mempersiapkan tahap dua lombaku, namun selembar buku pun tak ada ku buka pada hari itu. Saat matahari telah digantikan oleh bulan, aku sudah membaringkan tubuhku di atas tempat tidur.
Kedua netraku menatap kosong atap seng yang menutupi rumah kecil keluargaku. Aku lelah, aku ingin berhenti menangis dan aku ingin tidur, namun aku tak bisa. Isakan memang tak lagi keluar dari bibirku, namun kristal – kristal bening itu tetap meluruh jatuh dari sudut netra hitamku. Setiap tetesannya selalu menyiksaku.
Aku tak tau ingin melakukan apapun, hingga netraku tanpa sengaja menatap seonggok obat paracetamol yang berada di atas meja belajarku. Tanpa pikir panjang aku bangkit dari tempat tidurku dan meminum dua tablet obat paracetamol itu. Aku tak memperdulikan anjuran yang tertera di bungkus obat paracetamol itu, aku hanya membutuhkan sesuatu yang dapat meringankan kepalaku dan dapat memaksaku masuk ke dalam dunia mimpi yang terasa jauh lebih indah dibandingkan dunia nyata ini.
Malam itu, dengan bantuan dua obat paracetamol, akhirnya aku berhasil memejamkan kedua netra hitamku dan tidur dengan tenang. Akhirnya, aku menemukan ketenangan fana dari seluruh kemelut masalah hidup yang tengah menghantam diriku, menghantam seorang gadis yang masih berusia 16 tahun.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Rasa Yang Tak Pernah Ingin Kurasakan
Rabu, 8 Desember 2021 21:11 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0






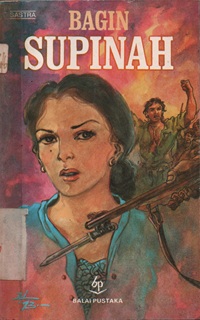

 97
97 0
0






 Berita Pilihan
Berita Pilihan










