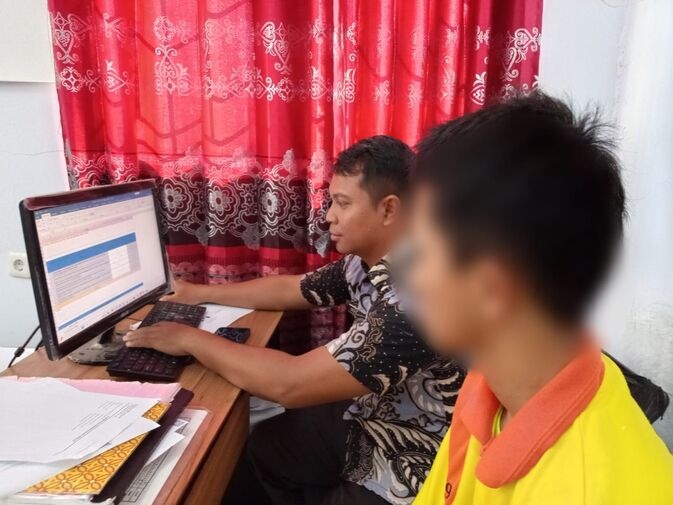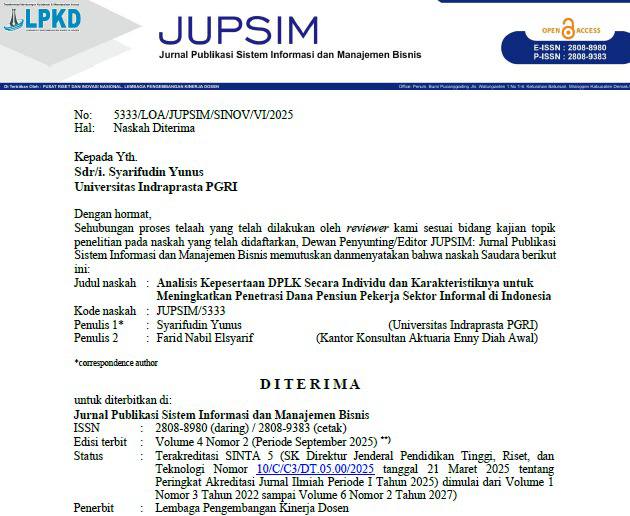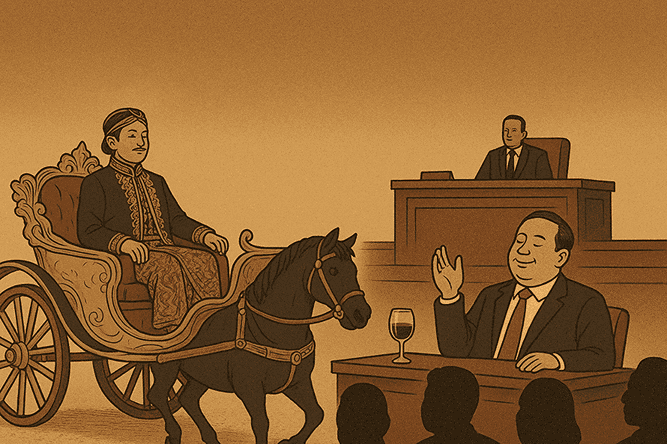Pemilu Presiden 2019: Polarisasi Politik dan Komodifikasi Identitas Agama di Media Sosial
Sabtu, 30 April 2022 05:59 WIB
Polarisasi politik pada satu sisi menjadi persoalan krusial bagi negara-negara di dunia, namun secara keseluruhan memperlihatkan krisis demokrasi global. Ancaman konflik politik, pemerintahan yang jatuh bangun, dan perang sipil selama puluhan tahun membuat persoalan polarisasi politik mulai mendapat perhatian internasional melalui inisitiatif-inisiatif counter- polarization yang dilakukan para pemangku kepentingan (termasuk organisasi masyarakat sipil). Namun di Indonesia pengetahuan tentang polarisasi politik masih minim, terutama terkait implikasi polarisasi politik yang memperburuk praktik intolerasi dan diskriminasi bagi kelompok-kelompok minoritas, serta meningkatkan kekerasan dalam masyarakat (Carothers dan Andrew, 2019). Setelah mati suri sejak 1950-an, polarisasi politik di Indonesia muncul kembali sejak Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, kemudian mengalami peningkatan tajam pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, dan hingga menjadi semakin dalam (deepen polarization) pada Pemilu 2019 (Warburton, 2020).
Pemilu 2019 merupakan peristiwa politik mutakhir yang penting untuk diamati dalam konteks polarisasi politik di Indonesia. Olle Törnquist (2019) mengklaim Pemilu 2019 merupakan pemilihan umum terbesar di dunia yang diselenggarakan dalam satu hari. Dalam peristiwa ini terlibat 185 juta pemilih dan 800 ribu tempat pencoblosan suara, dua pasang kandidat calon presiden, 300 ribu kandidat anggota parlemen memperebutkan 20 ribu kursi parlemen di tingkat nasional, provinsi, dan kota/kabupaten.
Ironisinya, Pemilu 2019 menjadi salah satu potret kemunduran demokrasi di Indonesia karena politik identitas menjadi strategi yang masif digunakan oleh kontestan politik untuk merebut suara pemilih (Sebastian dan Arifianto, 2021). Politik identitas juga memengaruhi perilaku politik pemilih yang lebih mementingkan kesamaan identitas primordial ketimbang kemampuan untuk mengelola dan mengawasi jalannya pemerintahan. Thomas Pepinsky (2019) dalam konteks agama dan politik pada Pemilu Presiden 2019 menemukan kecenderungan tentang melebarnya pembelahan elektoral (electoral cleavage) berbasis identitas agama ketimbang ideologi politik.
Pemilu presiden (Pilpres) merupakan salah satu bagian dari Pemilu 2019 yang menunjukkan secara jelas penggunaan politik identitas sebagai strategi untuk memenangkan persaingan politik. Islam menjadi identitas politik yang penting bagi dua calon presiden yang bersaing, Joko Widodo dan Prabowo Subianto untuk merebut suara pemilih di tengah menguatnya konservatisme agama di Indonesia.
Edward Aspinall (2019) menyebut Pilpres 2019 sebagai pertarungan ideologis antara kekuatan politik Islam yang saling bersaing, yaitu tradisional, modernis, dan fundamentalis. Joko Widodo mendapat dukungan dari kelompok Islam tradisional—termasuk golongan non-Islam, sementara Prabowo Subianto mendapat dukungan dari kelompok Islam modernis dan fundamentalis (Aspinal, 2019). Persaingan antar kedua kandidat presiden ini secara terang-terangan menggunakan narasi-narasi Islam sehingga digambarkan sebagai pertarungan antara “santri tradisional melawan santri millennial”, “Islam Nusantara melawan Islam Trans-nasional”, “calon presiden yang memilih ulama sebagai calon wakil presiden melawan presiden yang didukung oleh ijtima (konsensus) ulama” (Temby, Burhani, dan Irawanto, 2019).
Kedua calon presiden yang saling bersaing ini memilih calon wakil presiden dengan identitas keislaman yang kuat. Sebastian dan Nubowo (2019) menyebut keputusan pemilihan calon wakil presiden ini disebabkan karena Joko Widodo dan Prabowo Subianto tidak memiliki identitas keislaman yang cukup di tengah menguatnya populisme dan konservatisme Islam di Indonesia. Oleh sebab itu, Joko Widodo memilih Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pimpinan Nahdatul Ulama (NU), Ma’ruf Amin terlepas dari perannya dalam menerbitkan fatwa penistaan agama terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama, fatwa menentang paham sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, serta sikap koservatismenya yang menentang kelompok minoritas Ahmadiyah, kaum lesbian, gay, transgender, dan biseksual (LGBT), serta dukungan terhadap UU Pronografi (Simandjuntak, 2019).
Sementara Prabowo Subianto memilih Sandiaga Uno, pengusaha dan politisi berpendidikan Katolik dan Barat diberi label santri di era pos-Islamisme oleh presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Pasangan ini mendapat dukungan dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI (Sebastian dan Nubowo, 2019 ; IPAC, 2019).
Kampanye-kampanye dalam Pilpres 2019 juga memperlihatkan praktik politik identitas, terutama penggunaan narasi-narasi agama. Kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden menggunakan narasi-narasi keislaman untuk memperlihatkan keberpihakan pada Islam dan menyerang kubu lawan yang dicap anti-Islam. Kampanye-kampanye dari pihak Joko Widodo menyerang dan memberikan label ekstrem, intoleran, dan radikal kepada organisasi-organisasi Islam yang mendukung Prabowo Subianto (IPAC, 2019 ; Törnquist, 2019). Para pendukung Joko Widodo juga mengklaim jika Prabowo Subianto memenangkan Pilpres 2019 maka akan terjadi islamisasi besar-besaran di Indonesia (Sebastian dan Nubowo, 2019).
Sebaliknya, pihak Prabowo Subianto menuding pemerintah yang berkuasa korup dan anti-Islam karena melakukan kriminalisasi kepada ulama-ulama, menangkap aktivis-aktivis Islam, dan memberangus organisasi Islam, seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) (Sebastian dan Arifianto, 2021). Beberapa isu lama juga diangkat kembali untuk menyerang kebijakan Presiden Joko Widodo, seperti keberpihakan pada tenaga kerja China dalam proyek-proyek infrastruktur, bersimpati kepada komunisme yang merupakan musuh Islam, menghapus pelajaran agama di sekolah-sekolah, mengancam agama-agama yang diakui negara, pelarangan azan, hingga legalisasi perkawinan sesama jenis (Simandjuntak, 2019 ; Temby, Burhani, dan Irawanto, 2019). Sementara status anak Prabowo Subianto yang dituding sebagai gay dan mendukung perkawinan sesama jenis yang bertentangan dengan ajaran Islam juga menjadi isu lama yang dimunculkan kembali (IPAC, 2019).
Penerapan strategi politik identitas, terutama narasi-narasi keislamanan untuk menarik suara pemilih membuat polarisasi politik dalam masyarakat pada Pilpres 2019 menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Temby, Burhani, dan Irawanto (2019) menyebut penggunaan politik identitas dan Islam dan Pemilu 2019 meningkatkan risiko polarisasi politik dalam masyarakat, terutama perbedaan tentang peran yang dimainkan Islam kepada negara. Polarisasi politik ini juga membuat kelompok Islam, nasionalis, dan sekuler yang mapan kini berada dalam tekanan. Kelompok Islam, misalnya, mengalami polarisasi karena perbedaan tentang proses Islamisasi yang masih terus berjalan atau sudah selesai hingga persaingan antara mazab dalam tradisi Islam di Indonesia yang beragam (Sebastian dan Nubowo, 2019). Mengikuti perbedaan dukungan terhadap calon presiden dan wakil presiden, polarisasi baru terjadi antara dua organisasi Islam besar di Indonesia, Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, begitu pula dengan kelompok-kelompok Islam yang pluralis (moderat) dan konservatif.
Media Sosial dan Polarisasi Politik
Media sosial menjadi medium yang memperlihatkan polarisasi politik selama Pilpres 2019. Secara umum media sosial menjadi media politik baru yang strategis[1] dan digunakan sebagai medium untuk berkampanye. Selain karena berbiaya murah dan menjangkau khalayak yang luas, Survei AIPJI 2017 memperlihatkan sebanyak 41,55 % pengguna menggunakan internet untuk mengonsumsi informasi keagamaan dan 50,26 % pengguna menggunakan internet untuk mengkases informasi politik. Kombinasi antara efektivitas media sosial dan perilaku pengguna internet (warganet) membuat kedua pasang calon presiden memiliki tim khusus yang bekerja di media sosial untuk berkampanye. Namun penggunaan praktik politik identitas sebagai materi kampanye kedua calon presiden membuat polarisasi politik juga terjadi di media sosial. Riset Salahudin dkk. (2020) memperlihatkan polarisasi politik Islam dalam Pilpres 2019 sebenarnya merupakan polarisasi politik yang terjadi di media sosial. Polarisasi politik di media sosial juga lebih tajam terjadi ketimbang di dalam kehidupan sehari-hari dan membuat terbentukknya tiga kelompok Islam, yaitu kelompok Islam tradisional, modernis, dan fundamentalis yang mendukung calon presiden yang berbeda (Salahudin dkk., 2020).
Polarisasi politik di media sosial terjadi karena kedua calon presiden menggunakan narasi-narasi keagamaan. Untuk menarik dukungan warganet kedua calon presiden menggunakan narasi-narasi Islam untuk membentuk citra diri saleh dan taat pada pemimpin agama. Joko Widodo memperlihatkan kedekatannya dengan Habib Luthfi Yahya dan KH Maimoen Zubair, melakukan umrah di Mekah—termasuk mempublikasikan fotonya ketika sedang memasuki Ka’bah, menampilkan diri sebagai pemimpin shalat ketika berkunjung ke pesantren NU di Jombang, hingga berniat membebaskan tokoh yang terafiliasi pada terorisme, Abu Bakar Ba’asyir (Haq, 2021).
Hal serupa juga dilakukan oleh calon wakil presiden Ma’aruf Amin yang mempublikasikan kegiatan kesehariannya yang tak lepas dari kegiatan keagamaan. Dengan menggunakan sarung dan peci, foto-foto di media sosial menggambarkan Ma’aruf Amin sedang memberikan tausiah dan mendapat sambutan dari pimpinan-pimpinan organisasi masyarakat dan selebritis yang mendukung dirinya sebagai calon wakil presiden Melalui foto-foto ini Ma’aruf Amin ingin menampilkan dirinya sebagai ulama senior, dihormati, dan memiliki banyak aktivitas meskipun telah berusia 75 tahun (Irawanto, 2019). Prabowo Subianto juga berupaya menampilkan sosok pribadinya sebagai seorang muslim yang taat dengan mengadakan pengajian di kediaman pribadinya (Salahudin dkk., 2020).
Seperti Joko Widodo, Prabowo Subianto juga menghormati para pemimpin agama. Ia mengadakan pertemuan dengan ulama-ulama populer, seperti KH Abdullah Gymnastiar, Abdul Somad, dan Adi Hidayat. Sementara calon wakil presiden Sandiaga Uno berupaya mencitrakan dirinya sebagai seorang muslim yang saleh. Melalui foto dan video yang disebarkan di media sosial, Sandiaga Uno memperlihatkan dirinya yang sedang menunaikan ibadah, berziarah ke makam pendiri organisasi Nahdatul Ulama (NU), dan berpuasa sunnah (IPAC, 2019).
Penyebarluasan narasi-narasi keagamaan juga dilepaskan dari peran tokoh-tokoh yang populer (influencer) di media sosial. Untuk memperkuat penggunaan narasi-narasi keislaman di media sosial, para influencer juga terafiliasi ke organisasi-organisasi Islam, seperti Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Haq (2021) menyebutkan Candra Malik yang mendukung calon presiden Joko Widodo, memperkenalkan dirinya sebagai murid dari kyai kharismatis Habib Luthfi. Dengan begitu, Candra Malik ingin memperlihatkan bahwa Nahdatul Ulama (NU) merupakan organisasi Islam yang mendukung calon presiden Joko Widodo. Candra Malik, juga membagikan video Habib Luthfi yang menyambut kedatangan calon presiden Joko Widodo dalam kampanye akbar di stadion Gelora Bung Karno. Video yang diunggah pada 14 April 2019 ini, disaksikan sebanyak 7.400 kali (Haq, 2021).
Sementara, Dahnil Azar Simanjuntak yang menjabat sebagai Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah menggunakan sosok sosok kyai populer Abdullah Gymanstiar yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto (IPAC, 2019). Pada 13 April 2019, Dahnil Azar Simanjuntak menunggah foto kunjungan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uni ke kediaman penceramah KH Abdullah Gymnastiar yang mendapat 2.600 likes dari warganet (Haq, 2021).
Polarisasi politik di media sosial juga terjadi karena masing-masing pasangan calon presiden mengkaryakan tim bawah tanah—yang berada di luar tim kampanye resmi—bertugas memantau percakapan di media sosial dan mengambil langkah-langkah strategis untuk mempopulerkan calon presiden yang didukung dan menghalau serangan dari lawan-lawan politik. Calon presiden Joko Widodo memiliki tim bawah tanah bernama Awan yang dipimpin oleh politisi Andi Widjajanto. Sementara Prabowo Subianto memiliki tim bawah tanah bernama Pride (Prabowo-Sandi Digital Team) yang dipimpin oleh praktisi pemasaran digital, Anthony Leong (Temby, Burhani, dan Irawanto, 2019). Salah satu peran tim bawah tanah inilah adalah untuk mendeteksi pertarungan antara kedua calon presiden dan para pendukungnya di media sosial yang tampak dalam perang tagar.
Perang tagar[2] (hashtag war) merupakan salah satu bentuk polarisasi politik khas media sosial yang terjadi sepanjang Pilpres 2019. Salah satu perang tagar yang terjadi adalah pertarungan antar tagar #2019GantiPresiden melawan #Jokowi2Periode. Perang tagar ini dimulai pada Maret 2018, ketika tagar #2019GantiPresiden muncul di Twitter dan diinisiasi oleh politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Tagar ini merupakan serangan terhadap calon presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh pendukung calon presiden Prabowo Subianto.
Tagar #2019GantiPresiden[3] yang merupakan ajakan untuk memilih sosok presiden yang baru menjadi populer disirkulasikan di media sosial dan mempersatukan seluruh kekuatan politik pendukung sekaligus mempopulerkan calon presiden Prabowo Subianto (Irawanto, 2019). Sebagai respon atas tagar #2019GantiPresiden, muncul tagar tandingan #Jokowi2Periode. Tagar ini dimunculkan oleh pendukung calon presiden Joko Widodo yang berisi pesan dukung agar calon petahana menjadi presiden kembali untuk periode ke-2. Mengikut strategi yang sama dilakukan oleh tagar #2019GantiPresiden menjadi populer di media sosial dan bertransformasi menjadi gerakan sosial di sejumlah kota. Perang tagar ini menjadi menarik ketika presiden Joko Widodo menyebut proses penggantian presiden tidak dapat dilakukan melalui tagar atau kaos-kaos bertulis #2019GantiPresiden, tetapi hak untuk mengganti presiden dimiliki oleh masyarakat dan Allah (Suraya dan Kadju, 2019).
Peran tokoh-tokoh agama yang berafiliasi kepada calon presiden yang bersaing dalam Pilpres 2019 memiliki kontribusi bagi polarisasi politik di media sosial. Yuka Kayane (2020) menyebut peran penceramah-penceramah agama adalah menjembatani jarak antara pemilih dan calon presiden. Artinya, penceramah agama yang aktif di media sosial memiliki peran untuk menghubungkan dan menjangkau warganet yang memiliki hak pilih, serta meyakinkan mereka untuk memilih calon presiden tertentu.
Dalam konteks Pilpres, untuk mengimbangi sosok Ma’aruf Amin yang berada di kubu Joko Widodo, pihak Prabowo Subianto mendapat dukungan dari sejumlah tokoh agama dan penceramah, seperti Habib Rizieq, Bachtiar Nasir, Abdullah Gymnastiar (Aa Gym), Adi Hidayat, dan Abdul Somad (Adi dan Setyowati, 2019). Ustad Abdul SOmad (UAS) merupakan salah satu penceramah agama yang mendukung calon presiden Prabowo Subianto dan memiliki jutaan pengikut di media sosial. UAS mencitrakan dirinya sebagai seorang penceramah agama yang berani dan mendukung klaim kubu Prabowo Subianto bahwa pemerintah yang berkuasa saat itu anti-Islam. Dengan memanfaatkan ketidakpuasan sebagian umat muslim pada pemerintahan Jokowi, UAS memiliki kemampuan untuk menjadikan calon presiden Prabowo Subianto sebagai representasi umat Islam di mata para pemilih muslim (Kayane, 2020). UAS aktif membantu kampanye dan memobilisasi massa di pulau Sumatera.
Hasilnya, UAS berhasil memengaruhi pengikutnya untuk memilih Prabowo Subianto dalam Pilpres dan membantu kemenangan Prabowo Subianto di tiga provinsi, yaitu Sumatera Barat (85,95 %), Sumatera Barat (85,54 %), dan Riau (61,21 %). Hal ini memperlihatkan identitas agama menjadi faktor penting yang memengaruhi warganet untuk menentukan calon presiden yang dipilih[4].
Implikasi Polarisasi Politik
Implikasi praktik politik identitas dalam Pilpres 2019 masih terlihat dalam kehidupan politik sehari-hari sampai saat ini.[5] Namun persoalan ini masih menjadi objek perdebatan para peneliti ilmu sosial, terutama tentang implikasi politik identitas ini apakah berdampak jangka panjang atau jangka pendek. Sebastian dan Arifianto (2021) masih mempertanyakan implikasi dari politik identitas dalam Pemilu 2019, apakah menjadi sebuah peristiwa penting dalam politik Indonesia yang ditandai dengan politik identitas yang menyebabkan perpecahan dalam masyarakat atau hanya sekadar kelanjutan dari politik elektoral yang pragmatisme dan patronase politik.
Meskipun begitu, praktik politik identitas di Indonesia dalam satu dasawarsa terakhir merupakan sesuatu yang bersifat kontiniu. Praktik politik identitas dalam Pemilu 2019 merupakan kelanjutan dari peristiwa politik sejenis, seperti Pemilu 2014 dan Pilkada DKI Jakarta 2017. Sandra Hamid (2018) telah melihat polarisasi politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 yang berimplikasi pada normalisasi intoleransi dalam kehidupan sehari-hari. Kecenderungan ini terus berlanjut dalam Pemilu 2019 yang disebut Warburton (2020) polarisasi politik menjadi semakin dalam. Jika dalam Pilkada DKI 2017, garis demarkasi polarisasi politik ini adalah yang Islam dan non-Islam, maka dalam Pemilu 2019 polarisasi politik semakin dalam karena melibatkan Islam tradisional dan non-Islam melawan Islam moderen dan konservatif.
Polarisasi politik yang semakin mendalam pada Pilpres 2019 ini menyebabkan dukungan para pemilih di media sosial didasarkan pada identitas keislaman hingga ke tingkat kesalehan personal dalam kehidupan sehari-hari. Foto-foto di media sosial yang memperlihatkan kesalehan personal kedua calon presiden juga menjadi objek perbincangan warganet. Ketika Joko Widodo mempublikasikan foto sedang menuju Ka’bah, warganet mengkritiknya karena dianggap mempermainkan tempat suci umat Islam.
Hal yang sama juga terjadi ketika Prabowo Subianto mempublikasikan foto pengajian, warganet yang kontra menganggap publikasi foto ini, seperti anak kecil karena ingin memperlihatkan keislaman Prabowo Subianto yang diragukan (Haq, 2021). Selain itu, beberapa hari setelah Joko Widodo melakukan kunjungan ke pesantren NU di Jombang, Jawa Timur, pada 25 Desember 2018, para pendukung calon petahana membahas tentang Prabowo Subianto turut merayakan Natal keluarga—sesuatu yang diharamkan oleh pengikut Islam modernis dan konservatif. Pendukung calon presiden Joko Widodo mempopulerkan Tagar #JelasIslamnya sembari menyerang Prabowo Subianto melalui tagar #JogetNatalPrabowo dan mempertanyakan kesalehan Prabowo Subianto melalui kalimat Prabowo sholat Jumat dimana?
Sebaliknya serangan ke pihak Joko Widodo oleh pendukung Prabowo Subianto ditujukan kepada calon wakil presiden Ma’aruf Amin. Ketua MUI itu dalam narasi-narasi di media sosial digambarkan sebagai ulama suu (jahat), yaitu ulama yang melayani kepentingan penguasa ketimbang umat Islam (Haq, 2021). Hal ini memperlihatkan warganet mengamati secara detail identitas keislaman dan menjadikannya referensi yang memengaruhi perilaku pemilih dalam menentukan calon presiden yang dipilih. Perbedaan dukungan terhadap calon presiden yang diekspresikan di media sosial menjadi pintu masuk bagi normalisasi intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap warganet
Referensi
Aspinall, Edward (2019, 22 April). ‘Indonesia’s Election and the Return of Ideological Competition’. https://www.newmandala.org/indonesias-election-and-the-return-of-ideological-competition/
Adi, A., Sari, M., & Setyowati, R. (2019, November). Radicalism and Political Indentity in Indonesia President Election 2019. In International Conference on Social Science 2019 (ICSS 2019) (pp. 411-416). Atlantis Press.
Carothers, T., & O'Donohue, A. (Eds.). (2019). Democracies divided: The global challenge of political polarization. Brookings Institution Press.
Hamid, S. (2018). Normalising intolerance: elections, religion and everyday life in Indonesia.
Haq, M. N. (2021). Patronizing the Mass: How Middle-Agents Deepened Populism and Post-Truth in Indonesia 2019 Presidential Election. Jurnal Politik, 7(1), 75-104.
IPAC (2019, 15 Maret). "Anti-Ahok to Anti-Jokowi : Islamist Influence on Indonesia's 2019 Election Campaign, IPAC Report No 55.
Irawanto, B. (2019). Making it personal: The campaign battle on social media in Indonesia’s 2019 Presidential election. ISEAS Yusof Ishak Institute, 28, 1-11.
Kayane, Y. (2020). The Populism of Islamist Preachers in Indonesia’s 2019 Presidential Election. The Muslim World, 110(4), 605-624.
Pepinsky, T. (2019). Islam and Indonesia's 2019 Presidential Election. Asia Policy, 26(4), 54-62.
Salahudin, Nurmandi, A., Jubba, H., Qodir, Z., Jainuri, & Paryanto. (2020). Islamic Political Polarisation on Social Media During The 2019 Presidential Election in Indonesia. Asian Affairs, 51(3), 656-671.
Sebastian, L. C., & Arifianto, A. R. (2020). Introduction: The 2018 and 2019 Indonesian elections–identity politics and regional perspectives. Dalam The 2018 and 2019 Indonesian Elections (. Routledge.Sebastian, L.C., & A. Nubowo. 2019. The Conservative Turn in Indonesian Islam: Implications for the 2019 Presidential Elections, Asie Visions, 106, Paris: Ifri. www.ifri.org/en/publications/notes-de-lifri/asie-visions/conservativeturn- indonesian-islam-implications-2019."
Simandjuntak, Deasy (2019, 6 Juni). ""Jokowi’s Triumph in the 2019 Presidential Election and the Future of Binary Politics"". https://th.boell.org/en/2019/06/06/jokowis-triumph-2019-presidential-election-and-future-binary-politics"
Suraya, S., & Kadju, F. E. D. (2019). Jokowi versus Prabowo Presidential Race for 2019 General Election on Twitter. Saudi Journal of Humanities and Social Sciences, 4(3), 198-212.
Temby, Quinton , Ahmad Najib Burhani dan Budi Irawanto, ‘Indonesia’s 2019 Elections: the Key Issues’. ISEAS Perspective 2019-30, 15 April 2019
Törnquist, O. (2019). Many Votes, Little Voice: Indonesia's 2019 Presidential and Parliamentary Elections. Pacific Affairs, 92(3), 459-474.
Warburton, E. (2019). Polarization and democratic decline in Indonesia. Dalam Carothers, T., & O'Donohue, A. (Eds.). Democracies divided: The global challenge of political polarization. Brookings Institution Press.
Catatan Kaki
[1] Meskipun layanan internet di Indonesia belum merata dengan tingkat penetrasi mencapai 54,6 %, namun terdapat lebih dari 350 juta pengguna internet mobile (We Are Social 2019) dan sebagian besar menghabiskan waktu rata-rata 3 jam 23 menit per hari untuk mengakses media sosial[1]. Menurut The 2018 Global Digital Report, terdapat 130 juta pengguna Facebook (36 % pengguna di Asia Tenggara), dan 38 % dan 27 % pengguna Instagram dan Twitter—dua platform media sosial yang semakin populer di Indonesia.
[2] Perang tagar muncul karena inisiasi pendukung calon presiden dan bertujuan untuk menyerang calon presiden pesaing melalui isu tertentu di media sosial. Serangan ini kemudian dibalas dengan memunculkan isu tandingan yang membela calon presiden yang mendapat serangan di media sosial. Perang tagar ini biasanya tak hanya melibatkan elit-elit politik atau tokoh-tokoh yang populer di media sosial, tetapi juga warganet yang terbelah dukungannya dalam mendukung dua tagar yang sedang “berperang”.
[3] Tagar ini bertransformasi menjadi gerakan sosial di kota-kota besar, seperti Jakarta, Solo, Lampung, dan Makasar pada Mei 2019. Ketika turun ke jalan, gerakan dikenal melalui kaos dan pernak-pernik #2019GantiPresiden dan diklaim bersifat organik dalam mengorganisasi massa, seperti halnya Aksi 212 (Report_55).
[4] Riset Pepinsky (2019) juga menyebutkan lebih dari 80 % pemilih muslim Jawa, bermukim di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang merupakan penganut Islam tradisonal memilih Joko Widodo dalam Pilpres 2019 karena sosok Ma’aruf Amin dan organisasi Nahdatul Ulama (NU).
[5] Polarisasi politik yang melabelkan cebong (pendukung pemerintah) melawan kampret, kadrun, dan taliban (oposisi pemerintah).
*) Tulisan ini adalah opini pribadi penulis.
Sejarah bukan masa lalu, tetapi seperti foto yang merepresentasikan masa lalu
0 Pengikut

Politik Listrik Kolonial Mengorbankan Kepentingan Kaum Bumiputera
Sabtu, 25 Juni 2022 18:34 WIB
Pemilu Presiden 2019: Polarisasi Politik dan Komodifikasi Identitas Agama di Media Sosial
Sabtu, 30 April 2022 05:59 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0




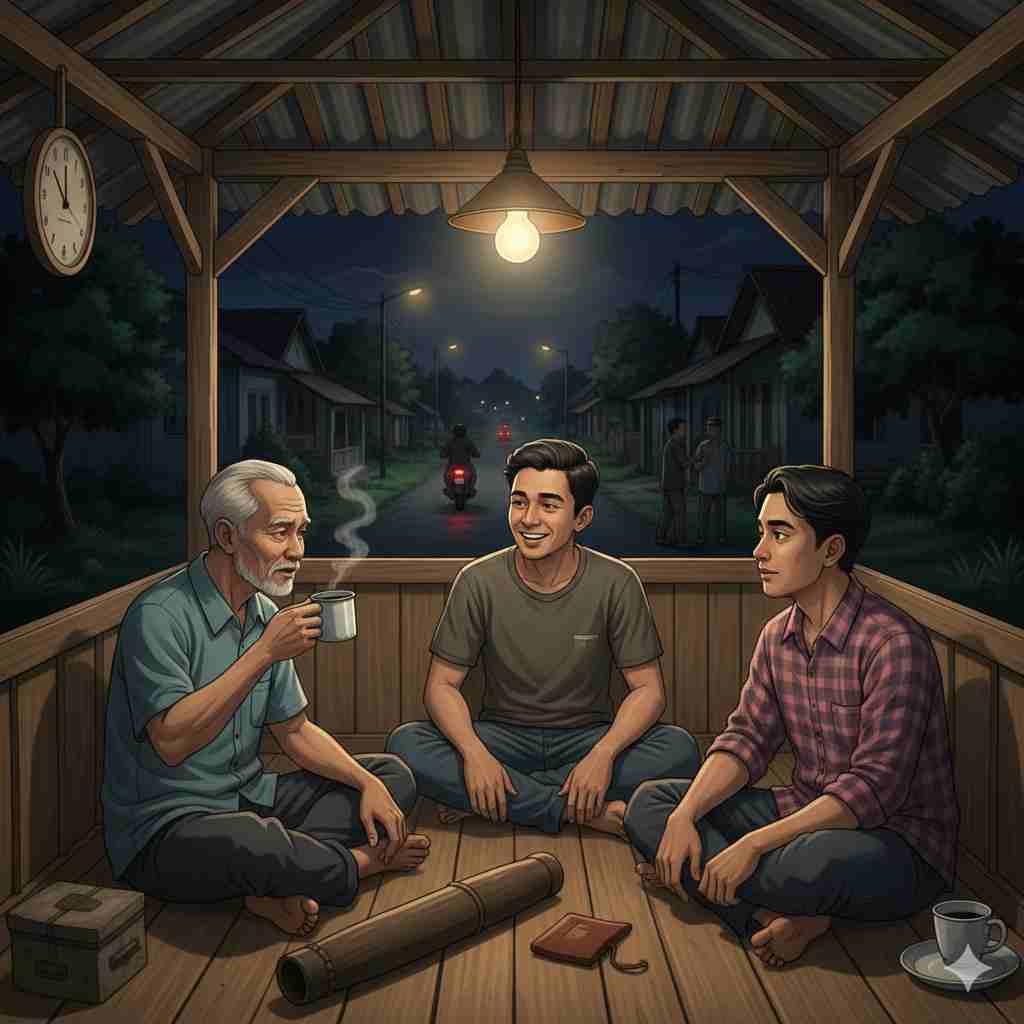

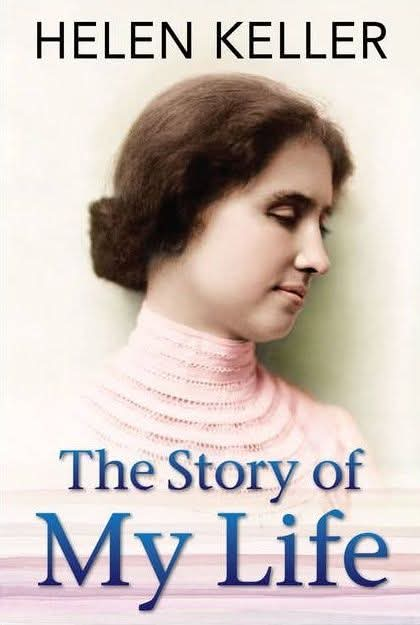
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 97
97 0
0