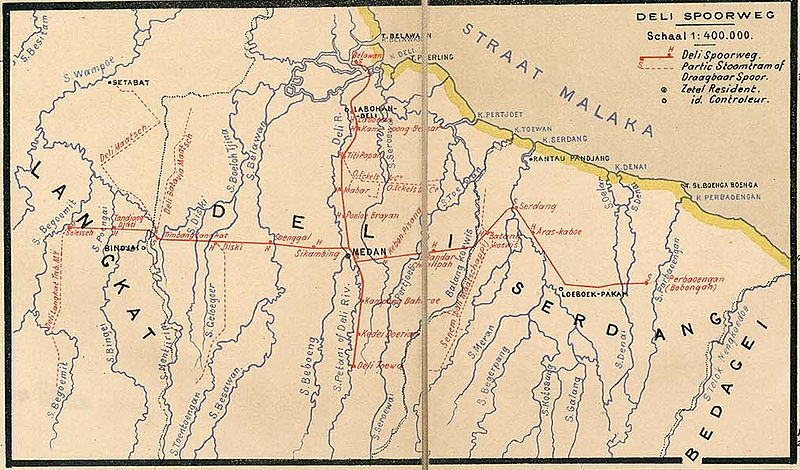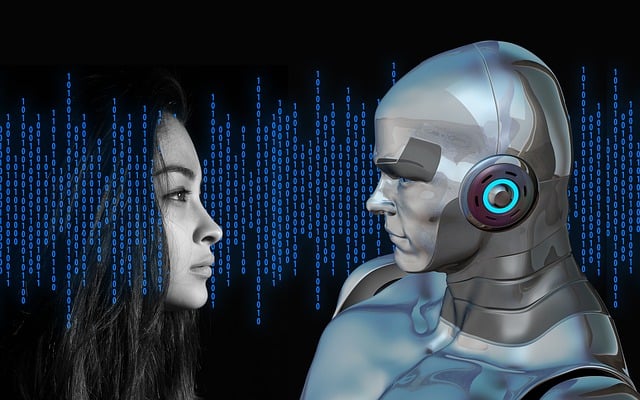Provinsi adalah hal yang ajaib. Ia merupakan tatanan administratif yang memungkinkan negara merasuk lebih dalam ke pedalaman. Birokrasi provinsi hampir tidak merupakan urusan yang menggairahkan, kecuali barangkali untuk kaum birokrat. Tetapi, provinsi bisa juga menjadi wahana sebuah identitas. Maka ia pun jadi bermuatan sentimen perkasa, walau kabur, yaitu rasa menjadi bagian dari bangsa yang lebih besar, namun terpisah darinya.
Kontras antara dua sisi fenomena kedaerahan ini berjalan sejajar dengan kontras negara-bangsa. Banyak provinsi baru dibentuk di Indonesia akhir tahun 1950-an, antara lain Kalimantan Tengah. Ini merupakan bagian dari ketegangan dramatis yang menyelimuti daerah-daerah di luar Jakarta. Hal ini terjadi di masa masih panas- panasnya nasionalisme. Semua yang ikut membantu terbentuknya Kalimantan Tengah tahun 1957 membicarakannya dengan istilah ’bangsa’—artinya sebagai isu identitas.
Tentu saja penglihatan dari Jakarta berlainan dengan penglihatan di Kalimantan. Media metropolitan menggambarkan pembentukan provinsi Kalimantan Tengah itu sebagai hasil proses menghimpun berbagai bagian bangsa menjadi satu bangsa. Wacana Indonesia mengenai identitas kedaerahan akhir tahun 1950-an menekankan sifat kesukarelaan dan kerakyatan komunitas kedaerahan ini.
Namun, wacana ini hanyalah semacam tabir asap. Di balik tabir itu, berlangsung permainan kekuasaan yang melibatkan pemain yang jumlahnya jauh lebih sedikit. Karangan ini menjelaskan bahwa pembentukan Kalimantan Tengah bukan tindak nation-building (pembentukan bangsa), melainkan state-building (pembentukan negara). Itu adalah pemecahan atas masalah negara, yaitu lemahnya negara di daerah-daerah kepulauan yang jauh sesudah berkecamuknya perang dan revolusi. Pembentukan negara dalam kondisi lemahnya pemerintah pusat menjadi masalah umum bagi ilmu politik di seluruh dunia. Hal itu berulang kali terjadi dalam sejarah Indonesia abad ke-20.
Klimaks kisah berorientasi bangsa ini terjadi pada hari Rabu 17 Juli 1957. Pada hari itu, Presiden Soekarno memudiki Sungai Kahayan yang besar di Borneo Tengah diiringi sejumlah perahu untuk meletakkan batu pertama Palangkaraya, ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah yang baru. Sampai waktu itu, daerah pedalaman yang diliputi hutan rimba itu merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan yang diperintah dari ibu kota Banjarmasin yang terletak di kuala.
Selama 36 jam memudiki sungai itu, menurut laporan serial sebuah harian Jakarta yang besar, orang-orang kampung keluar dengan biduk masing-masing untuk menyambut presiden dan memekik ’Merdeka!’ Mereka hanya pernah melihat potretnya dijual di perahu-perahu sungai. Ketika ia mendekati pintu gerbang pedalaman Dayak di Kuala Kapuas pada hari sebelumnya, bunyi genderang telah sampai di telinga rombongan sebelum rombongan selesai melingkari belokan terakhir. Prajurit-prajurit Dayak berpakaian menakjubkan melingkarkan biduk mereka di depan kapal presiden.
Ketika presiden menjejakkan kakinya di pantai, orang-orang mempersilakannya naik joli yang indah. Ia menolak, sebaliknya ia letakkan bendera merah putih di atas joli, dan bergabung dengan orang banyak mengibarkan bendera itu. Soekarno mengatakan pada orang banyak itu bahwa semangat Proklamasi ’45 masih hidup di Kalimantan, dan bahwa ’orang-orang asing’ yang mengatakan Kalimantan ingin memisahkan diri terbukti salah. Adegan serupa dimainkan hari berikutnya di Palangkaraya yang sampai waktu itu merupakan sebuah kampung kecil berpenduduk 900 jiwa, bernama Pahandut.
Pembangunan negara di Indonesia selamanya melalui salah satu dari dua cara yaitu cara sentralisasi atau cara desentralisasi. Tahun-tahun yang dibicarakan di sini—khususnya akhir tahun 1940-an dan akhir tahun 1950- an—ditandai oleh berlakunya cara desentralisasi. Bab ini merupakan bagian dari minat akademis yang semakin tumbuh dalam mempelajari kontur cara desentralisasi dalam pembangunan negara di Indonesia di daerah luar Jawa. Kebutuhan Jakarta untuk menjalin hubungan dengan banyak kelompok elite lokal di daerah untuk menjamin agar mereka tidak berkomplot melawan pusat, cenderung mempersempit idiom negosiasi pada etnisitas tempat asal, dan menyempitkan pilihannya pada para mitra lokal yang sanggup memaksakan kehendak pada tingkat lokal.
Oleh karena itu, pembangunan negara dengan cara desentralisasi selalu diwarnai wacana tentang tradisi, etnisitas, dan hierarki—kalau perlu, tradisi yang dibuat-buat alias direkayasa. Cara sentralisasi, sebaliknya, diwarnai wacana modernitas dan nasionalisme. Ini tidak berarti bahwa nasionalisme modern di tingkat lokal tidak ada, begitu pula minat terhadap tradisi di pusat. Tetapi elemen-elemen ini kurang menentukan proses pembangunan negara pada saat- saat yang kritis di tahun 1950-an.
Kedua cara ini, sentralisasi dan desentralisasi, tetap merupakan ciri yang bertahan dalam lanskap politik di Indonesia sampai dewasa ini. Kadang-kadang cara desentralisasi yang lebih menonjol (abad ke-19, wilayah-wilayah federal tahun 1946-49, 1956-58, 1999-2001), kadang-kadang cara sentralisasi yang unggul (dari 1900 sampai 1927, 1959-98).
Federalisme dan Dewan Dayak (1946-1949)
Dayak adalah istilah generik yang untuk pertama kalinya dirumuskan oleh para antropolog Barat mencakup beberapa macam penduduk asli Borneo non-Muslim. Umumnya mereka tinggal di pedalaman, sementara kota-kota pantai yang pokok didominasi oleh orang-orang Muslim pribumi (yang kadang- kadang secara generik disebut orang Melayu) dan oleh kelompok-kelompok migran (King 1993). Pulau besar ini, dewasa ini, dibagi di antara tiga negara yang berdaulat, dan di bagian Indonesianya terdapat empat provinsi.
Gerakan Dayak etnis berwarna politik memiliki sejarah sendiri di hampir seluruh wilayah Borneo, tetapi gerakan itu cenderung beredar di dalam perbatasan politik masing-masing provinsi. Jadi gerakan di Kalimantan Barat dan apa yang kemudian dinamakan Kalimantan Tengah praktis tidak ada hubungan.
Pedalaman yang didominasi orang Dayak sebelum Perang Dunia II itu adalah bagian dari ’pemerintah’ Borneo Tenggara yang luas, dengan ibu kotanya di Banjarmasin. Orang Dayak di situ tidak pernah sebelumnya memiliki sendiri wilayah yang jelas gambarannya. Mereka mulai bergerak untuk pertama kali menuju identitas teritorial ketika Gubernur B. J. Haga mulai menunjukkan beberapa wilayah sebagai reservasi khusus untuk suku Dayak di rawa-rawa Buntok dan Pegunungan Meratus di timur laut Banjarmasin tepat sebelum perang.
Reservasi-reservasi untuk menampung suku asli dibentuk juga di negeri-negeri lain sekitar waktu ini—termasuk di Afrika Selatan tahun 1913 dan 1936 dan di Amerika Serikat tahun 1934 (Indian New Deal).5 Di luar otonomi resmi terbatas yang dinikmati oleh orang-orang Dayak suku sebagai komunitas asli (rechtsgemeenschap), otonomi teritorial yang lebih substansial agaknya secara administratif tidak mungkin. Alasannya yang pernah disebutkan ialah bahwa masyarakat Dayak itu ’betul-betul primitif’.
Alasan lain ada hubungannya dengan undang-undang kolonial. Otonomi teritorial adalah bagian dari sistem pemerintahan tak langsung, yang satuan-satuan prakolonial mempertahankan sebagian hidupnya sendiri. Dasarnya ada dalam beratus-ratus kerajaan ’berpemerintahan sendiri’ di seluruh Hindia Belanda. Namun Kesultanan Banjarmasin telah dihancurkan tahun 1859-1860, dan sejak itu Belanda memerintah Borneo tenggara dan tengah secara langsung (Cribb 2000: 124).
Pembentukan Provinsi Kalimantan Tengah bukan bagian penting dalam sejarah Indonesia, bukan juga kisah yang begitu gemilang. Tetapi pembentukan provinsi ini menarik karena menggambarkan sebuah dinamika yang pernah penting. Sesudah berakhirnya Orde Baru tahun 1998, Jakarta yang lemah telah membentuk sejumlah besar distrik dan provinsi baru, banyak di antaranya mengikuti garis etnis. Dinamika politik lokal berwarna etnis sering disalahtafsirkan.
Dalam cerita di atas, dinamika tersebut tidak ditentukan oleh gerakan pemberontakan, melainkan merupakan bagian dari gerakan loyalis di kalangan pegawai negeri bawahan. Pejuang gerilya ’liar’ yang terlibat dalam perjuangan bagi pembentukan sebuah provinsi terpisah hanyalah alat bagi pemain yang lebih penting.
Pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah boleh dikatakan adalah mata pisau sebuah negara birokratis yang sedang meluaskan diri, dan sekaligus ditarik memasuki wilayah terpinggir kepulauan ini. Citra-citra identitas kesukuan yang digunakannya tidaklah ’alamiah’, yaitu citra- citra yang kuno, melainkan penemuan yang sangat baru. Di tangan mereka yang mempolitikkannya, citra-citra ini tak banyak dikaitkan dengan otonomi melainkan dengan penyesuaian, dan tak banyak dengan keinginan menentukan nasib sendiri dan demokrasi, melainkan dengan perluasan mesin pemerintahan yang menguntungkan bagi mereka.
Ketika berkunjung ke Palangkaraya bulan Juli 1957 untuk meletakkan batu pertama, Presiden Soekarno tanpa disadari telah memberikan restu pada satu bentuk etnis kenegaraan di tingkat provinsi yang sangat bertentangan dengan peringatannya sendiri untuk menolak ’sukuisme dan separatisme’ (Merdeka 23-04-1957). Etnisitas pribumi yang liar tapi loyal, yang dengan tangkas dimanfaatkan baik oleh kaum birokrat provinsi yang berjuang untuk provinsi, maupun oleh A. H. Nasution dan letnan-letnannya di Jakarta yang memberikannya, tidak begitu merupakan satu bentuk perlawanan rakyat, melainkan satu elemen dalam politik persekongkolan yang dipraktikkan di antara Banjarmasin dan Jakarta.
Bagaimana kiranya wujud perlawanan yang sungguh-sungguh berasal dari rakyat setempat terhadap penindasan—dan apakah perlawanan demikian akan mengambil idiom etnis itu juga—kita tidak bisa tahu dari cerita ini. Seandainya Simbar tidak dikooptasi, ia mungkin mengembangkan hubungannya dengan KRJT dari Ibnu Hadjar, dan siapa tahu berjuang bukan untuk sebuah provinsi, atau untuk Pancasila, ataupun untuk Islam, melainkan untuk keadilan sosial.
Episode yang dibahas di sini merupakan contoh pembangunan negara atau state-building berdasarkan desentralisasi yang pernah dialami Indonesia. Hasilnya adalah sebuah provinsi baru yang oleh para aktivis Dayak sudah lama dilukiskan sebagai ’sebuah Rumah Dayak’ (Usop 1996: 82). Politik identitas etnis telah diizinkan keberadaannya di Republik Indonesia, bukan karena para pemberontak etnis yang menginginkan separatisme telah memaksakannya, melainkan karena Jakarta sendiri telah memilih merekrut para loyalis provinsi yang telah menampilkan diri sebagai ’minoritas terbelakang yang mencari perlindungan’.
Sikap mereka mirip sekali dengan sikap orang Dayak pada waktu Konferensi Malino tahun 1946 sebagaimana dilukiskan oleh orang Belanda. Politik sejenis muncul kembali pada tahun 2001 dalam wujud penyingkiran orang non-Dayak. Sebuah organisasi militan Dayak dihidupkan kembali, termasuk milisi yang mempunyai koneksi dengan elite yang mengingatkan kita pada gerombolan Ch. Simbar. Melalui tindakan-tindakannya organisasi ini berusaha mengarahkan politik kedaerahan pada zaman pasca-Suharto dengan mengusir semua pendatang dari Madura (Van Klinken 2002).
Ikuti tulisan menarik Dedeh nurhasanah lainnya di sini.