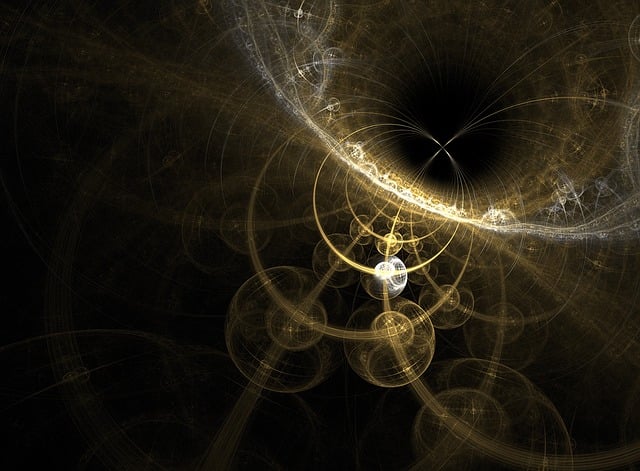Deru kendaraan bermotor yang lalu lalang tidak menghentikan Thamrin, 35 tahun, dari aktivitasnya. Tangannya lincah merakit pelepah daun kelapa yang berserakan di hadapannya. Satu demi satu helai daun itu ia rekatkan dengan straples menjadi satu bagian dari janur yang memikat. Bagian itu adalah bagian terpenting dari janur, berupa bulatan melengkung dengan bonggol pisang di dalamnya. Di sisi-sisi bonggol pisang itulah daun kelapa direkatkan sebagai pembungkus. Setelah jadi, hiasan itu ia bungkus dengan plastik, lalu digantung di bagian muka hingga dalam kiosnya yang sempit, kira-kira 2x3 meter, di Jalan Palmerah Barat.
Keringat menetes di dahinya siang itu, Sabtu, 22 Agustus 2015. Thamrin segera mengusapnya dengan kaos cokelat yang ia kenakan. Sesekali ia beristirahat sambil mendengarkan lagu jaipongan yang diputar di radio portabel milik teman sebelah kiosnya. Alunan musik itu cukup mengobati rindunya pada anak dan istri yang terpaksa ia tinggalkan di kampung halaman.
“Ya, habisnya kan kita perlu makan. Saya bisanya cuma ini,” ujarnya lirih. Sejak tujuh tahun lalu Thamrin merantau ke Jakarta dari Kecamatan Petir, Serang, Banten. Kosongnya lapangan pekerjaan di kampung serta didorong tanggung jawab mencari nafkah untuk keluarga, ia terdampar di Kebayoran. Mula-mula Thamrin ikut kakaknya berdagang, lalu ia belajar membuat janur dan ketupat yang akhirnya menjadi mata pencahariannya hingga kini. Rasa persaudaraan yang kuat karena seluruh pedagang ketupat dan janur di tempat itu berasal dari Serang cukup mengobati kesepiannya.
Thamrin tak punya rumah di Jakarta. Kala malam tiba, ia mengandalkan tikar lusuh yang digelarnya di dalam kios untuk tidur. Tentu saja itu sangat tidak nyaman, terutama karena tanah yang menjadi alasnya tidak begitu rata. Tapi Thamrin tak punya pilihan lain. Untuk mandi saja ia menumpang di Pasar Pisang yang terletak di seberang kiosnya. Sebagai hiburan, kadang-kadang ia menonton tayangan dari televisi kotak 14 inci milik bersama.
Untuk menebus rasa kangen terhadap keluarga, seminggu sekali Thamrin pulang ke Serang naik mobil bak terbuka. Tak lupa ia membawa oleh-oleh uang hasil untung berdagang. Setiap hari ia mengaku bisa menjual 25 janur yang masing-masing dihargai Rp 30 ribu. Sedangkan ketupat dijualnya Rp 4 ribu per sepuluh buah atau satu karung 200 ketupat Rp 80 ribu. Sebagian hasil keuntungannya ia jadikan modal lagi untuk membeli daun kelapa di Serang. “Soalnya lebih murah cari bahan di kampung, Mbak,” ujarnya.
Di deretan kios-kios itu, paling ujung sebelah kanan, seorang bapak tua sedang menyerut lidi. Jika pedagang yang lain memiliki kios, Dodong, 52 tahun, hanya menumpang di depan lahan usaha tambal ban. Satu karung ketupat teronggok di sisi kirinya, sementara di belakang lidi-lidi yang sudah ia jadikan sapu tampak tergantung. Dodong lahir di Pemalang dan datang ke Jakarta pada 1972. Lalu pada 1973 ia menikahi Asmanah, 47 tahun, perempuan Betawi asal Petamburan. Dodong sudah kenyang merasakan pahit getirnya hidup di Jakarta. Ia pernah bekerja menjadi kenek bus Mayasari jurusan Tanah Abang. Seiring dengan meredupnya pamor bus kota dan usia tua, Dodong kini berjualan ketupat dan menyerut lidi pelepah kelapa.
Akibat beratnya beban hidup, wajahnya tampak lebih tua dari usia Dodong yang sebenarnya. Ia kini masih harus berjuang mencari makan karena anak-anaknya sudah meninggalkan dirinya. “Saya enggak mau ngerepotin anak,” ujarnya membuka cerita. Anak pertama, Herawati, 35 tahun, sudah menikah dan mempunyai lima orang anak. Anak keduanya, Yunita, 34 tahun, juga sudah menikah dan memberinya tiga orang cucu. Malang, anak laki-laki satu-satunya, M. Riki, 27 tahun, baru saja meninggal akibat kanker getah bening. Riki sudah berputra. Istrinya terpaksa pulang ke kampung halamannya di Tegal sambil memboyong putranya karena tak ada sandaran hidup di Jakarta.
Dodong mengaku pekerjaan yang ia lakukan sekarang sebenarnya tak menguntungkan. Cekaknya modal dan kurangnya keahlian membuat ia tak bisa bersaing dengan rekan-rekannya yang lebih muda. Ia tak bisa membuat janur. “Ya, kalau tidak ada kerjaan paling saya menyerut lidi begini,” tuturnya.
Pendapatannya dalam satu hari pun tak menentu. Pernah dalam seminggu tak sebiji pun dagangannya laku. “Kalau sudah begitu saya terpaksa ngutang buat ongkos pulang,” ujarnya. Dodong berutang pada siapa saja yang mau meminjamkan. Bahkan pada hari itu saat saya berjumpa dengannya, ia belum memperoleh uang sepeser pun. Namun Dodong mengaku tetap optimistis. Ia yakin rejeki sudah diatur dan tak akan tertukar. Karena itu, Dodong terus menyerut dan menyerut, membersihkan sisa-sisa daun yang menempel, lalu mengikatnya jadi satu dalam bulatan yang kokoh. Ia, seperti Thamrin, abai pada deru kendaraan yang lalu lalang di hadapannya. Ia memasrahkan nasibnya di antara lipatan ketupat dan lengkungan janur.
Fadjriah Nurdiarsih
Ikuti tulisan menarik Fadjriah Nurdiarsih lainnya di sini.