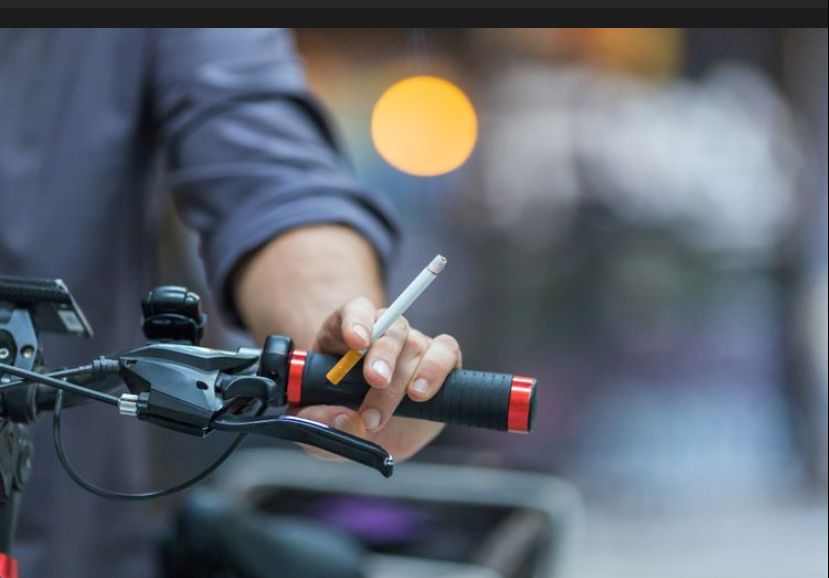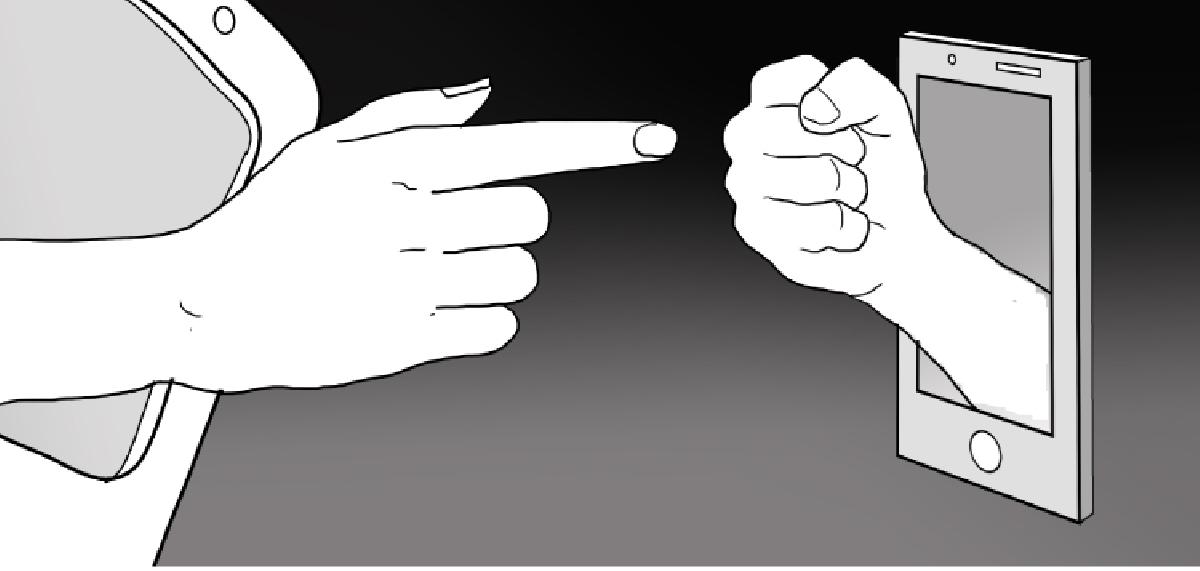Beberapa saat lalu tersebar gambar Kiai Maimun Zubair, ulama Nahdlatul Ulama sekaligus tokoh politik sedang makan bertadah nampan bersama Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy dan Pengasuh Pondok Pesantren Al-Itqan Bugen Semarang, Kiai Haris Shodaqoh. Gambar itu diambil netizen pada saat acara Khataman Al-Ibriz, di Semarang pada akhir pekan lalu, 15 Januari 2017.
Gambar itu kemudian tersebar sporadis di lini media sosial. Tak banyak komentar dari netizen. Karena mungkin makan di atas nampan adalah hal yang biasa. Terlalu biasa bagi para santri, ketika makan bersama di atas daun pisang sudah menjadi keseharian mereka.
Dalam foto itu, Mbah Maimun, begitu ia akrab disapa, sedang muluk (makan dengan tangan). Menunya nasi, telur, mie, dan beberapa lauk lain. Bagi saya itu suatu hal lumrah untuk kebudayaan orang Jawa, khususnya di lingkungan masyarakat Nahdlatul Ulama. Mbah Maimun selalu sahaja seolah mewakili falsafah hidup umatnya.
Gambar itu juga seperti mencitrakan kehangatan orang-orang di kampung saya. Itu mengingatkan saya pada Tuban, kota kecil di Timur Pondok Pesantren Al-Anwar, asuhan Mbah Maimun di Sarang, Rembang. Setiap Jumat Wage, tetangga saya memiliki kebiasaan mendoakan para pendahulunya. Biasanya, mereka mengundang masing-masing tetangga, memotong tumpeng, membagikan makananan, dan guyup rukun bersama-sama.
Dalam semalam saya bisa bertandang ke sedikitnya 6 sampai 10 tetangga. Mereka saling mendoakan dan berbagi rejeki. Tetangga yang memasak tempe, suatu ketika dapat mengecap soto daging. Bagi tetangga yang mampu memasak empal dan membagi goody bag, itu adalah kesempatan bersedekah.
Selepas berdoa, kami sesama tetangga berbagi kisah tentang keluh-kesah hidup yang kami jalani selama sebulan. Sebagian besar mereka menceritakan was-was mereka bercocok tanam. Yang menanam padi khawatir diserang hama tikus, petani jagung khawatir diserang hama bajing, atau peternak sapi yang kesulitan mencari hijaunya rumput.
Praktis yang kami lakukan hanya sebatas merapal doa, berbagi, dan saling mengerti antar sesama. Itulah kesederhanaan yang bisa kami lakukan. Saya melihat hal itu juga dilakukan dan diajarkan oleh Mbah Maimun dan para pendahulu kiai di Nahdlatul Ulama. Masih banyak ulama lain juga mengajarkan banyak tentang kesederhanaan. Usia saya terlalu sempit untuk mengenang keluasan keserdehanaan mereka.
Kenapa harus sederhana, jika bisa berbuat lebih? Pertanyaan ini sering melintas di pikiran saya. Nyatanya, sederhana itu hanyalah kata yang remeh dilafalkan, tapi terlalu berat untuk kita maknai. Suatu kali Kiai Mustofa Bisri mengatakan bahwa sederhana itu adalah kemanusiaan di antara manusia.
Saya renungkan, banyak orang yang tergila-gila pada hidup atau matinya. Ada orang yang gila pada hartanya, sampai lupa tak membayar keringat tetangga. Ada yang gila pada Tuhannya, Sampai lupa umatnya tak masuk surga. Ada yang gila pada pekerjaannya, sampai ia lupa keluarganya. Ada yang gila pada perempuan, sampai tak habis-habisnya menyakiti ibunya. Saya sendiri, mungkin sedang tergila-gila satu di antaranya.
Apakah kita perlu kembali merenung untuk mencari wujud kesederhanaan itu? Atau kita lupakan saja? Kita teruskan perjuangkan kita membela Tuhan, kita teruskan takbir kita, dan kita teruskan maki-maki antar sesama manusia.*
Ikuti tulisan menarik Avit Hidayat lainnya di sini.