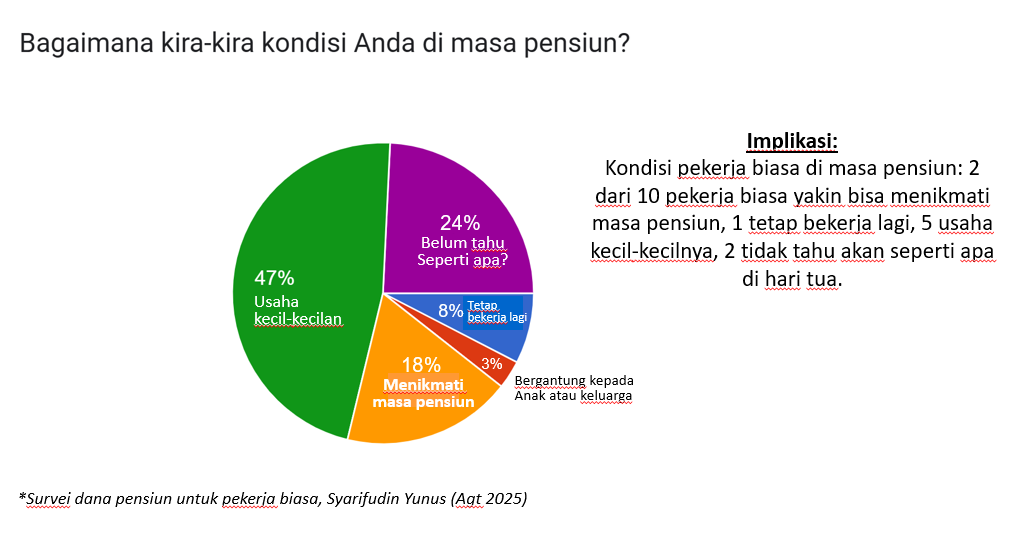Sembilan Kelemahan RUU Masyarakat Hukum Adat
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
UU ini tidak saja penting bagi masyarakat adat karena hasilnya akan menentukan masa depan mereka tapi juga bagi pemerintah sekarang,
R. Yando Zakaria
antropolog, pendiri dan peneliti pada Pusat Kajian Etnografi Hak Komunitas Adat (PUSTAKA), Yogyakarta
Kamis, 19 Juli 2018 lalu, Badan Legislatif (Baleg) DPR melakukan rapat kerja dengan sejumlah Menteri, atau yang mewakili, dari sejumlah K/L.
Pada intinya, sebagaimana yang dilaporkan berbagai media, pihak DPR RI dan Pemerintah sepakat akan menyelesaikan (baca: menetapkan) Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) menjadi UU dalam 3 kali persidangan, yang akan dimulai pada tanggal 16 Agustus mendatang. Satu masa persidangan di antaranya akan digunakan untuk kunjungan lapangan.
Waktu yang relatif pendek untuk urusan yang cukup pelik sebenarnya. Buktinya, UU yang diamanatkan konstitusi itu telah absen hampir 70 tahun! Apalagi sudah masuk pada tahun politik.
Bisa membunuh
Meski begitu, kesepakatan itu merupakan perkembangan penting yang perlu dikawal realisasinya. Jangan sampai terjadi seperti DPR RI periode lalu.
Sebab, UU ini tidak saja penting bagi masyarakat adat karena hasilnya akan menentukan masa depan mereka. Namun juga penting bagi Pemerintah sekarang, mengingat hal ini masuk dalam janji Nawacita.
Komitmen waktu adalah satu hal dan komitmen substansi adalah hal yang lain lagi. Untuk itu, apa yang terkandung dalam RUU yang akan dibahas itu harus dipastikan akan memenangkan masyarakat adat dan bukan justru untuk membunuhnya (kembali).
Masalahnya, jika dicermati, ada 9 permasalahan yang diduga akan menghalangi pencapaian tujuan ditetapkannya UU. Dalam bahasa perumusan UU, kesembilan permasalah itu menyangkut aspek formil, aspek substansi, dan aspek dampak pemberlakukan regulasi.
Dari aspek formil, masalah pertama, judul yang kemudian digunakan DPR RI tidak sesuai dengan agenda prolegnas yang menyebutkan ‘RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat’. Penyebutan judul RUU yang demikian itu tentu tidak sembarangan dan punya alasan tertentu.
Maka, pihak DPR perlu menjelaskan perubahan itu. Judul yang digunakan sekarang secara substansi tidak menjawab amanat konstitusi (Pasal 18B ayat 2, dan Pasal 28i ayat 3).
Masalah substansi
Dari aspek substansi, ada 7 hal yang perlu dipikirkan ulang. Pertama, RUU masih menggunakan terma MHA padahal hasil amandemen konstitusi mengandung dua terma setara. Yakni MHA dan masyarakat tradisional (MT). Untuk mengurus dua mandat konstitusi ini para perumus kebijakan harus berani melakukan terobosan untuk melahitkan nomenkaltur baru, yakni masyarakat adat (MA).
Toh, hal itu dimungkinkan. Dalam konstitusi MHA dan MT disebut dalam huruf kecil yang berarti sekedar nama fungsi. Dengan begitu penyusun undang-undang bisa membentuk nomenklaur baru yang pengertiannya mencakup pengertian teknis MHA dan MT. Seperti halnya ‘bank sentral’ yang kemudian disebut sebagai Bank Indonesia.
Kedua, RUU MHA terperangkap pandangan romantik tentang MHA yang seolah-olah tidak boleh/tidak bisa berubah. Jika berubah, sudah tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam UU, maka hak MHA akan hapus. Tanah adat menjadi tanah negara. Padahal, UUPA saja membuka ruang perubahan status tanah adat menjadi tanah privat cq. tanah perorangan yang disebut sebagai tanah ex-tanah adat.
Ketiga, pendekatan RUU ini berorientasi pada pengakuan subyek. Dalam konteks ini penggagas terperangkap pada pandangan MHA/MA sebagai entitas politik semata (yang sudah diakomodasi dalam UU Desa), dan tidak memperhatikan dimensi keperdataan yang kompleks terhadap ha-hak masyarakat adat, di mana masing-masing jenis hak (tanah, politik, dll.) bisa merujuk pada subyek yang beragam.
Mengasumsikan pengakuan hak-hak masyarakat adat akan paripurna dengan sekali pengakuan terhadap suatu subyek tertentu tidak selalu sesuai dengan realitas sosio-antropologi. Kemampuan pengelolaan kehidupan bersama MA secara otonom faktanya terus memudar dari masa ke masa. Kalaupun ada, hanya tersisa pada sedikit masyarakat adat. Saat ini, penguasaan tanah secara adat berpusat pada kesatuan-kesatuan kekerabatan saja. Seperti kaum dan suku di Minangkabau; marga raja di masyarakat Batak Toba; dan soa atau mata rumah di Maluku.
Nyatanya, meski UU Desa memberi ruang pada desa adat, atau disebut dengan nama lain dalam berbagai konteks kebudayaan, hampir tidak ada desa adat yang telah memanfaatkannya. Di Bali, Minangkabau, dan Maluku misalnya, di mana entitas MHA masih begitu bertahan, realitas dualisme desa dinas dan desa adat, dengan derajat yang berbeda-beda, tetap berlangsung.
Dalam situasi itu, pendekatan pengakuan obyek hak jauh lebih realistis. Jika selama ini ada pandangan yang beranggapan bahwa pengakuan yang bersifat sektoral ini menjadi salah satu penyebab ketidaklancaran pengakuan hak masyarakat adat, hal itu terjadi bukan karena pendekatan sektoral itu sendiri, melainkan karena belum ada defenisi kerja yang menaungi seluruh pengakuan hak masy adat yang memang beragam itu.
Keempat, implikasi dari pendekatan yang berorientasi subyek adalah pengakuan atas hak kemudian menjadi sekedar deklaratif. Sebagaimana yang telah terjadi selama ini, pada akhirnya proses pengakuan hak masyarakat adat menjadi mengantung. Masih perlu pengaturan lebih lanjut. Hal ini tentunya sangat riskan. Belajar pada pengalaman selama ini, ada kebutuhan agar arahan pengakuan yang bersifat operasional ini sudah dicantumkan dalam UU.
Kelima, akibatnya, beberapa pengaturan yang keliru dalam berbagai UU sektoral yang ada saat ini kehilangan kesempatan untuk diluruskan. Padahal, inilah kesempatan untuk meluruskan sesat pikir yang terkandung dalam UU, bahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (Zakaria, 2017).
Masalah substantif keenam, mekansime pengakuan yang dianut oleh RUU ini sangat teknokratik dan birokratik. Proses identifikasi, verifikasi, validasi, dan penetapan dimulai dari tingkat komunitas hingga tingat kementerian. Di samping prosesnya yang begitu panjang, peran yang berwenang untuk menentukan ada-tidaknya suatu masyarakat adat adalah negara (bersama beberapa pihak yang berad dari luar masyarakat adat itu sendiri). Padahal, keberadaan masyarakat adat itu adalah realitas sosiologis yang kasat mata. Untuk mengakui dan melindungi mereka, Pemerintah hanya perlukan pengetuhan etnografis tentang relitas masyarakat adat di daerah yang bersangkutan. Dalam konteks ini seharusnya negara hanya bertugas mendaftarkan/mencatat keberadaan dan/atau pengakuan atas hak yang dimiliki oleh MA.
Ketujuh, oleh sebab itu, untuk mengimplementasikan amanat konstitusi ini, menurut RUU versi DPR RI 2018 ini diperlukan kelembagaan khusus di luar kelembagaan pemerintahan reguler yang telah tersedia. Kelembagaan khusus itu disebut Panitia MAsyarakat Hukum Adat, yang dibentuk mulai dari tingkat Kabupaten hingga Pusat. Panitia ini terdiri dari pewakilan dari berbagai pihak dari unsur Pemerintah, organisasi masyarakat sispil dan organisasi masyarakat adat, dan perguruan tinggi. Apa jaminannya lembaga baru ini tidak mengalami stagnasi sebagaimana yang dialami oleh kelembagaan regular yang mengurus masyarakat adat selama ini?
Padahal stagnasi yang terjadi saat ini bisa diatasi dengan penetapan kewenangan yang lebih pasti pada tataran kementerian, apakah itu dengan adanya kementerian khusus urusan masyarakat adat atau dengan menetapkannya sebagai kewenangan dari salah satu kementerian koordinator.
Perlu perombakan
Akhirnya, aspek dampak pelaksanaan regulasi. Dengan mekanisme dan kelembagaan yang diusulkan, beban pada anggaran negara akan membengkak.
Hal ini pernah dikeluhkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan menjadikannya sebagai alasan untuk menolak membahas RUU dimaksud. Namun, karena desakan berbagai pihak, pandangan Kementerian Dalam Negeri yang demikian berubah ke arah sebaliknya.
Demikinlah, jika kesimbilan hal di atas tidak diluruskan, dikuatirkan, alih-alih akan memenangkan masyarakat adat, UU itu justru akan membunuhnya!
Oleh sebab itu, logika hukum dan norma pengaturan yang terkandung dalam RUU Masyarakat Hukum Adat yang diusulkan DPR RI tahun 2018 ini perlu dirombak total!
Bagaimana wujudnya? Mari kita rembug bersama.***
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Kematian Juliana, Sulit bagi Pemerintah Brasil Menuntut Indonesia Secara Hukum
Sabtu, 5 Juli 2025 19:42 WIB
Paska Tragedi Juliana, Gunung Rinjani Terlarang bagi Pendaki Pemula
Rabu, 2 Juli 2025 18:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan
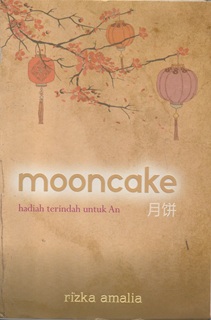







 92
92 0
0