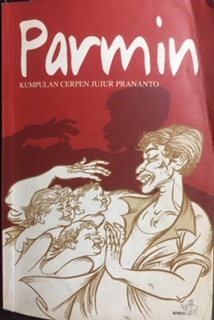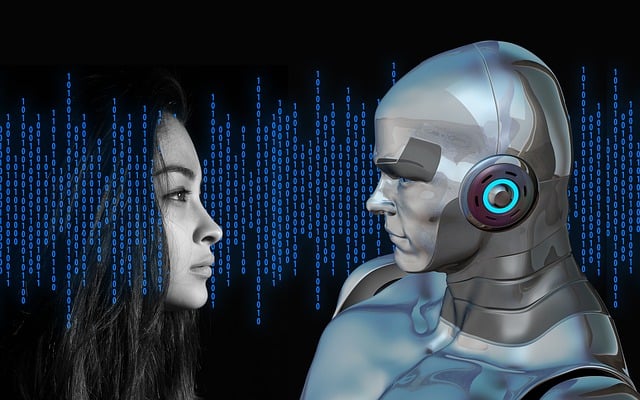Sambil menunggu novel Jujur Prananto yang konon masih dalam proses penulisan, saya membaca beberapa cerpennya yang dimuat dalam kumpulan cerpen Parmin. Kumpulan berisi 16 cerpen ini diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas tahun 2002.
Pada umumnya cerpen-cerpen Jujur enak dibaca karena ditulis dalam bahasa yang jelas. Penokohan atau perwatakan tokoh dan setting ceritanya juga jelas. Di bagian akhir, hampir semua cerpennya selalu ada kejutan (semacam twist) yang bisa menimbulkan efek lucu, gembira, atau bahkan tragis.
Saya mulai dengan cerpen Jujur Prananto yang “agak berbeda” atau – setidaknya menurut saya-- yang paling “serius” di antara lima belas cerpen lain yang saya baca, yakni Dua Pemerkosa. Begini ringkasan ceritanya:
Pada suatu senja, dua orang pemerkosa (Monod dan Dayat) sadis berhasil melarikan diri dari penjara. Mereka yang masih mengenakan seragam penjara itu masuk ke dalam hutan pinus yang lebat. Ketika beristirahat, mereka saling bertukar pengalaman tentang pemerkosaan yang mereka lakukan selama ini. Dayat, meskipun bertubuh kecil, termasuk pemerkosa yang yang sadis. Kepada Monod yang berbadan besar dan berwajah kasar itu Dayat berkata: “.... Saya ingin korban saya menjerit karena benar-benar takut atau sakit. Saya ingin korban saya sepenuhnya tak berdaya, karena ketidakberdayaan seperti itu bakal menjadikan kita merasa sangat berdaya dan berkuasa...”
“Lalu bagaimana akhirnya kau tertangkap?” tanya Monod.
“Tidak pernah ada kasus yang terbongkar kecuali pada korban terakhir. Waktu itu saya mabuk berat. Melihat seorang bocah perempuan umur sembilan tahun tidur telentang di atas ranjang, saya tidak bisa menahan diri. Saya sergap dia habis-habisan. Belakangan barulah saya sadar bahwa anak itu pingsan dan mengeluarkan banyak darah,” jawab Dayat.
“Lalu matikah dia?”
“Tidak. Saya cepat-cepat membawanya ke rumah sakit.”
“Kau sendiri membawanya ke rumah sakit?”
“Ya. Kenapa?”
“Ternyata kau masih punya perasaan.”
“Apa boleh buat. Bocah perempuan itu anak saya sendiri.”
Alangkah kejamnya. Dia memperkosa anaknya sendiri. Dan itu bukan korban pertamanya. Sebelumnya dia pernah memperkosa wanita lain. Kini gilaran Dayat yang bertanya kepada Monod: “Bagaimana dengan kamu sendiri?” Monod tak menjawab. “Terlalu buruk untuk kamu ceritakan?” Monod tetap membisu.
Tiba-tiba Monod mencabut sebilah belati dari balik bajunya. Dayat terlonjak berdiri. Monod tertawa pendek. “Jangan panik,” katanya.
“Dari mana kau peroleh belati itu?
“Itu tidak penting. Yang perlu kau ketahui ialah apa yang telah dialami oleh senjata ini.”
“Apa maksudmu?
Monod berjalan mendekati Dayat yang masih berdiri membeku, membimbingnya duduk kembali di tempat semula.
“Aku selalu menggunakan belati ini untuk memaksakan kehendakku pada para korban.”
“Kau melukainya?”
“Ya, sedikit demi sedikit. Pertama-tama kutempelkan belati ini pada leher korbanku sambil berbisik, ‘jangan coba-coba melawan’. Dia buru-buru mengeluarkan dompet berikut seluruh isi tasnya dan melemparkan ke tanah. Aku bilang aku tidak butuh duit dan tidak ingin merampok. Dia bingung. Lalu kuperintahkan agar dia menanggalkan seluruh pakaiannya. Dia semakin bingung.”
“Saya rasa bukan bingung, tapi takut.”
“Bukan. Dia mengira aku mengada-ada.”
“Dia pasti berpikir kau akan memperkosanya.”
Tiba-tiba Monod bergerak cepat menempelkan belatinmya ke leher Dayat. “Apa yang kau rasakan sekarang?”
“He, jangan bercanda! Ini bukan saat yang tepat untuk bercanda.”
“Aku tidak bercanda! Aku tanya, apa yang kau rasakan sekarang???”
Dayat tergagap-gagap. “Kita berdua lelah. Tapi kamu tidak perlu menambahnya dengan ketegangan-ketegangan yang bisa membuat kita makin merasa lelah.”
“Apakah kau berpikir aku akan memperkosamu?!”
“Sudahlah, jangan mengada-ada.”
“Nah!” Monod berseru keras sambil segera menarik belatinya dari leher Dayat. “Kamu sendiri mengatakan aku mengada-ada.”
Dayat menghembuskan napasnya keras-keras. “Teruskan sajalah cerita tentang korban-korbanmu itu.”
Monod kemudian melanjutkan ceritanya. “Aku tusuk-tusuk bagian tubuhnya dengan belati ini hingga dia berteriak-teriak kesakitan dan meronta tak berdaya.”
Beberapa saat Dayat terpana. “Lalu bagaimana kau memperkosanya?
“Aku tetap memperkosanya seperti kau memperkosa korban-korbanmu.”
“Dengan merusaknya terlebih dulu?”
“Ya. Aku rusak seluruh permukaan kulitnya, perutnya, dadanya... “
“Dadanya?”
“Kalau terpaksa kubungkam mulutnya dengan sabetan belati ini pula agar dia membisu selamanya.”
“Kenapa untuk kepuasannmu harus kau rusak kecantikannya?
“Persetan dengan kecantikannya! Korban-korbanku adalah para lelaki busuk seperti kamu!!!”
Sekonyong-konyong, bagaikan harimau lapar Monod meloncat menerkam Dayat, kembali menekan leher calon korbannya ini dengan belati. Dayat memberontak. Namun belati Monod lebih cepat menyambar kakinya, pahanya, dan ke hampir seluruh bagian tubuhnya, menusuk-nusuk, menghajar. Sampai akhirnya tubuh Dayat terkapar, menggelepar. Lalu dengan mudah Monod membalikkan tubuh Dayat sekaligus merenggut pakaiannya.
“Kau ingin mendengar jeritan tertahan seseorang yang menahan kesakitan dan ketakutan? Supaya kau merasa paling berdaya dan berkuasa? Bukankah sudah lama kau tidak mendengarnya? Dan tak bisa melupakannya? Nah, kalau sekarang kau ingin menikmati suara-suara itu, dengarkanlah suaramu sendiri!”
Maka segera setelah itu Dayat benar-benar memperdengarkan jeritan menyayat, namun tidak tertahan-tahan. Suaranya nyaring melengking, mengalahkan nyanyian jutaan serangga malam yang riuh bersahut-sahutan.
“Angkat tangan!!!”
Monod berdiri dan menoleh ke belakang. Sekian banyak lampu senter menyala, lurus-lurus terarah kepadanya, begitu pula belasan laras senjata para petugas keamanan yang tiba-tiba muncul mengepungnya.
“Yang satu lagi, berdiri!!”
Namun tubuh Dayat tampak bergeming. Seorang petugas mendekatinya dan menyodok-nyodok tubuh pelarian itu dengan ujung laras senjata.
“Dia sudah mati.”
Si komandan mendekati Monod. “Kau yang membunuhnya?”
Monod mengangguk mantap. “Ya, Dia pernah memperkosa istri saya.”
***
Ada kemarahan dan kebencian pada Jujur terhadap para pemerkosa itu. Bagi Anda yang senang dengan kajian ekstrinsik sebuah karya sastra, maka Anda bisa melacak peristiwa maraknya pemerkosaan dan pemberitaannya yang terjadi pada pertengahan tahun 1993. Jadi teks dihubungkan – antara lain-- dengan realitas sosial yang terjadi pada saat seorang sastrawan menulis. Silakan saja, Jujur Prananto menulis cerpen ini pada Juli 1993.
Sementara saya sendiri – yang bukan kritikus sastra alias sekadar pembaca sastra-- langsung teringat pada Arthur Schopenhauer. Jangan-jangan, apa yang pernah dikatakan si pesimistis kelahiran Danzig (Jerman Timur) itu benar, bahwa realitas kita ini sakit, tidak beres, dan jahat. Di dunia manusia ini terdapat egoisme, kemiskinan, kesengsaraan, penyakit, dendam, ketidakpercayaan, dan pembunuhan. Yang tidak baik dalam dunia ini jauh lebih besar jumlahnya daripada yang baik.
Lalu tindakan dan keputusan-keputusan manusia tidak pertama-tama berasal dari kesadarannya, tetapi muncul atas dorongan kehendak (wille) yang tidak rasional. Adapun kesadaran kita cuma sebagian kecil dari hakekat manusia. Ia hanyalah "permukaan" dari sebuah "lautan" yang dalam. Keputusan-keputusan kita muncul dari dalam lautan itu. Pendeknya, dunia batin serta akal budi kita dikuasai oleh kehendak yang buta ini. Hidup manusia, menurutnya, selalu berarti mengalami penderitaan, meskipun hal itu bisa diatasi melalui kesenian atau secara radikal memadamkan segala hawa nafsu dan melepaskan diri dari segala keinginan. Sejak muda Schopenhauer memang orang yang tidak gampang diajak bergaul dan sering bersikap murung.
Tetapi, jika pandangan Schopenhauer itu benar, maka tidak perlu heran apabila kita sering menyaksikan kekejaman di sekitar kita. Perkosaan, pembunuhan, pengeroyokan, penjarahan, tipu-menipu, berlangsung dahsyat dan terus menerus di depan kita.
Absurd, memang. Kita --setelah turun menurun-- seakan tak pernah menjadi dewasa. Anak-anak muda seakan tak pernah belajar apa-apa dari bapaknya. Sang bapak seolah tak pernah mengajar apa-apa kepada anaknya. Sejarah seakan tidak berjalan ke depan, tapi berputar-putar. Dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, tiap individu seolah-olah harus mulai dari titik nol. Padahal, pada setiap zaman telah diumumkan begitu banyak hikmat kehidupan oleh orang-orang alim dan cerdik pandai, tetapi kita seakan tak pernah belajar apa-apa dari semua itu. Selalu saja terjadi kebodohan yang sama berulang-ulang. Dari generasi ke generasi.
Padahal, kata Gottfried Leibniz, juga filosof asal Jerman, dunia kita adalah yang terbaik di antara semua dunia yang mungkin. Leibniz memang pemikir yang relijius, beriman, dan percaya pada kebaikan Tuhan. Katanya, Tuhan telah menciptakan dunia yang paling baik bagi kita. Dunia yang kita tempati ini sudah merupakan hasil maksimal. Dan manusia adalah makhluk yang memiliki tingkat kesadaran sangat tinggi --dibanding tumbuhan dan hewan. Lalu, mengapa ada kejahatan dan penderitaan di dunia ini? Jawab Lebiniz, karena ciptaan tidak sesmpurna Penciptanya. Manusia diberi kehendak bebas, tetapi dalam kehendak bebas ini manusia memilih yang jahat, maka dia menkjadi korban dari yang jahat. Meski demikian, dunia ini tetap berada dalam kekuasaan dan kebaikan Tuhan.
Tidak bisakah kesadaran kita itu digunakan untuk menjaga ketertiban dunia? Apa susahnya kita saling menyintai dan menghargai sesama? Bukankah sudah amat jelas, bahwa dalam pluralitas terdapat disparitas. Maka kebenaran tidak selalu harus tunggal. Lalu kenapa pendapat saya – atau Anda, misalnya-- merasa harus lebih dihargai, dimanja, atau mendapat privilege lebih tinggi dari yang lain? Sungguh mengherankan, kenapa kebodohan terus berulang-ulang, kekejaman selalu berulang-ulang.
Sebagai catatan, ada dua filosof lain yang “bertentangan” dalam melihat manusia dan dunia, yakni Thomas Hobbes dan Jean-Jacques Rousseau. Thomas Hobbes, misalnya, mengatakan bahwa kekerasan merupakan keadaan alamiah manusia. Karena itu, suatu pemerintahan yang keras, terpusat, dan kuatlah yang dapat mengatasi keadaan ini. Hobbes memang beranggapan bahwa manusia adalah makhluk yang dikuasai dorongan-dorongan irasional, egoistis, anarkistis, dan mekanis, yang saling curiga, saling iri dan membenci. Itu sebabnya manusia menjadi kasar, jahat, buas, dan tak panjang pikir. Pendeknya, manusia adalah serigala bagi yang lain (homo homini lupus).
Lain lagi dengan pendapat Jean-Jacques Rousseau. Katanya, manusia dalam keadaan alamiahnya (etat naturel) adalah ciptaan yang otonom, polos, bahagia, tidak egois, tetapi juga tidak altruis. Kebudayaanlah yang telah membentuk manusia menjadi binatang yang memiliki sifat menyerang seperti keadaan saat ini. Lebih jauh tentang kedua filosof ini lebih baik kita perbincangkan di lain kesempatan.
***
Sekarang kita lihat sekilas satu-dua cerpen Jujur Prananto yang lain, sekaligus proses kreatifnya. Kita ambil contoh cerpen berjudul Parmin. Cerpen ini berkisah tentang seorang tukang kebun yang dicurigai mencuri, padahal ternyata ia Cuma “mencuri” sisa-sisa es krim untuk dibawanya pulang sebagai oleh-oleh buat anak-anaknya di rumah. Kepada anak-anaknya pun Parmin mengatakan bahwa es krim itu pemberian dari tante Oche, tante Ucis, dan Om Himan – anggota keluarga di mana Parmin bekerja sebagau tukang kebun.
Cerpen ini kemudian dikembangkan menjadi skenario, lalu dibuat menjadi film televisi (FTV) yang disutradarai oleh Enison Sinaro. Dalam Festival Sinetron Indonesia (FSI) 1994, Parmin menggaet beberapa piala Vidia di antaranya Sutradara Tebarik, Editor Terbaik, Teleplay Terbaik dan Film Televisi Terbaik.
Cerpen Parmin ini mendapat “inspirasi” dari tiga hal yang berbeda. Pertama, ketika Jujur pindah ke Jakarta dan tinggal di rumah tantenya di Kebayoran Baru, beberapa kali dalam sebulan selalu datang seorang tukang kebun yang hanya ia ketahui namanya. Kedua, ada seorang pembantu yang dicurigai mencuri, tapi kecurigaan itu “hanya berhenti pada wacana” karena tak ada satu pun yang berani melontarkan tuduhan secara langsung pada pembantu ini. Ketiga, soal es krim, minuman kegemaran Jujur sejak kecil. Penggalan-penggalan kejadian yang berlangsung di rumah sang tante itulah kemudian melahirkan cerpen Parmin. Padahal, dalam cerpen itu hanya ada satu orang Parmin dan kisahnya benar-benar berbeda dengan kenyataan yang terjadi di rumah itu. Dalam cerpen, salah seorang anggota keluarga itu bahkan sampai membuntuti Parmin ke rumahnya.
Lalu kita tengok cerpen berjudul Bahasa Inggris. Cerpen ini mendapat inspirasi dari seorang kenalan Jujur yang ia ketahui menjadi sarjana yang skripsinya dihasilkan dengan membayar orang lain untuk menuliskannya. Kenalan tersebut berhasil menjadi PNS lewat koneksi seorang pejabat tinggi di sebuah kementerian. Setelah sekian lama bekerja, dalam rangka meningkatkan pangkat kepegawaian, ia diminta mengikuti kursus bahasa Inggris. Konon ia kesulitan mengikuti kursus ini.
Muncul kejahilan Jujur Prananto untuk meledek. Bagaimana seandainya orang seperti itu kariernya melesat sampai menjadi pejabat? Bagaimana seandainya pejabat seperti itu kemudian ditugaskan menghadiri sebuah forum internasional yang mengharuskan dia berpidato dalam bahasa Inggris, padahal kursus Inggrisnya mentok di kelas basic? Kejahilan Jujur itulah yang menghasilkan cerpen Bahasa Inggris yang isinya seperti yang ia “andaikan” itu. Dalam beberapa cerpen lainnya, sebut misalnya Ibu Senang Duduk Depan Warung; Peran-Peran Semu; dan beberapa cerpen lainnya, muncul dari dorongan “seandainya-seandainya” itu. Jadi, menurut versi Jujur sendiri, beberapa cerpennya lahir dari proses berandai-andai: “Seandainya saya mengalami kejadian seperti itu... Seandainya bukan seperti itu yang terjadi... Seandainya yang terjadi adalah kebalikannya,,,”
Tidak ada yang salah dengan semua itu. Setiap penulis punya cara atau metode sendiri dalam melahirkan karya kreatifnya. Yang salah, menurut saya, adalah jika ada orang --termasuk penulisanya sendiri—yang menganggap orang lain (pembaca) pasti keliru dalam memberi “arti” atau makna dari cerpen yang sudah dipublikasikan. Kita tahu, dalam proses menulis, seorang penulis bisa mendapat ide-ide spontan yang tadinya tidak dia pikirkan sebelumnya. Apakah itu berupa dialog baru, munculnya tokoh baru, atau kejadian baru yang memperkaya tulisannya. Juga adanya koreksi-koreksi sesudahnya, termasuk keinginan penulis sendiri untuk mengubah tulisannya sehingga pikirannya yang ‘asal”, yakni sesuatu yang ingin dikatakan sebelumnya, kemudian berubah. Intinya, hasil akhir sebuah cerpen atau novel, misalnya, tidak selalu sama persis dengan yang dia ingin tuliskan sebelumnya.
Masih ingatkah Anda bahwa sajak Chairil Anwar pun pernah diubahnya sendiri? Sajak “Aku”-nya Chairil Anwar yang terkenal itu pada mulanya begini:
Kalau sampai waktuku
Kutahu tahu tak seorang ‘kan merayu
Tak juga kau
Tapi kemudian diubah menjadi:
Kalau sampai waktuku
Kumau tak seorang ‘kan merayu
Tak juga kau
Perubahan kata “tahu” menjadi kata “mau” tentunya terjadi perubahan makna pula. Nah, jika puisi yang umumnya tidak terlalu panjang saja bisa berubah atau diubah, apalagi cerpen atau novel yang mestinya lebih panjang dari puisi. Jadi, dalam “membaca” sebuah teks sastra, silakan saja memberi makna atau arti baru, asal bisa menjelaskan secara logis. Tidak perlu –bukan berarti tidak boleh--- selalu harus bertanya kepada penulisnya tentang arti tulisannya dan menganggap itulah satu-satunya kebenaran. Tetapi, pembaca sastra yang baik (apalagi kritikus) memang dituntut memiliki pengetahuan yang luas, kritis, dan mengenal berbagai metode serta aliran kritik sastra. Tapi itu tugas Anda. Bukan tugas saya, yang hanya sekadar pembaca sastra pada umumnya. Buat Jujur Prananto, selamat berkarya. Saya tunggu novelnya..
- Atmojo adalah penulis yang meminati bidang filsafat, hukum, dan seni.
###
Ikuti tulisan menarik atmojo lainnya di sini.