Menjelang Lenyapnya Kajang
Rabu, 24 Mei 2023 21:08 WIB
Setahun yang lalu, saya menuntaskan pengabdian Kuliah Kerja Nyata yang umum kita singkat dengan sebutan KKN. Jujur saja, orang-orang benar kalau KKN adalah salah satu masa paling indah di kampus, terbebas sejenak dari tugas dan healing di tengah-tengah pedesaan, sembari bercengkerama langsung dengan masyarakat. Namun, di balik kesenangan 45 hari itu, saya juga menyadari satu hal, bahwa krisis iklim berada pada titik nadir dan masyarakat adat adalah mangsa yang binasa secara perlahan, dan tentu saja industri adalah musabab utama yang harus bertanggungjawab atas bencana itu.
Menjelang Lenyapnya Kajang
Penghujung Oktober 2021, lokasi KKN telah diumumkan. Aku beruntung, dari pengumuman website kampus, namaku berada di daftar mahasiswa yang akan mengabdi di Kabupaten Bulukumba, sebuah daerah di ujung selatan Pulau Sulawesi yang didiami salah satu masyarakat adat yang mahsyur, masyarakat adat Kajang.
Jujur, ada sukacita yang teramat bagiku tentang Bulukumba, pantai yang indah, budaya yang berbeda, dan tentu saja yang paling menarik, kehidupan tradisional Suku Kajang. Sejauh yang kutahu orang-orang kajang menolak dunia modern, semuanya serba tradisional. Pakaian hitam-hitam senada, tanpa alas kaki, tanpa listrik dan segala bentuk alat elektronik hingga hukum adat yang dijunjung tinggi melebihi fatwa agama dan peraturan negara.
Keberangkatan
Sepekan kemudian, rombongan bis tua yang mengangkut para anak KKN meluncur ke berbagai daerah setelah dilepas oleh Prof. Hamdan Juhannis Rektor UIN Alauddin Makassar. Aku bersama dengan teman posko berada di bus uzur milik kampus yang saban kali menyalip mobil di hadapan yang sontak saja membuat kami merapal syahadat dan doa-doa keselamatan. Setelah 4 jam perjalanan, bus tiba di pintu gerbang Kabupaten Bulukumba. Beberapa kawan di kursi belakang bilang, untuk sampai ke tanah Kajang masih butuh waktu satu jam menuju belantara pedalaman.
“Kalau sudah banyak pohon karet, berarti sudah dekat,” ujar kawan poskoku saat kutanyakan perihal berapa lama lagi kita akan tiba, katanya ia beberapa kali telah menginjakkan kaki disana.
Benar saja, tak berselang lama, pepohonan karet menyambut kami. Aku mendongakkan kepalaku keluar jendela, dan juga ini kali pertama aku melihat pohon karet, terlebih yang sebanyak dan seluas ini. Aku bahkan tidak yakin, kalau pandanganku bisa menemukan ujung perkebunan, sejauh mata memandang hanya lahan kosong nan gersang yang siap ditanami pohon yang menjulang dengan karut-marut di batangnya, bekas carikan celurit untuk menyadap getah. Di pinggiran jalan tak jarang, nampak bapak-bapak dengan gergaji mesin duduk melingkar sembari menyeruput kopi, sepertinya mereka baru saja membalak kayu di hutan-hutan. Di baju mereka terpampang tulisan PT Lonsum yang aku duga nama perusahaan milik perkebunan karet ini.
Bus merapat pelan di parkiran. Dari balik cermin depan nampak supir mengusap peluh di dahinya, tugasnya telah usai.
Kami tiba, setelah 5 jam perjalanan dari kota Makassar dan segera berhamburan meninggalkan bus yang sebentar lagi sakratul maut itu. Dengan koper dan barang bawaan di tangan kupandangi kantor kecamatan di depanku. Kantor camatnya sama seperti kantor pemerintah di pedalaman pada umumnya, lahan parkir yang luas, orang-orang tua berbaju dinas, dan plang besar di gerbang depan. Plang tersebut bertuliskan “Kantor Camat Kajang”, di bagian bawah tertera tulisan Kabupaten Bulukumba, agak kecil dengan tegel berwarna hitam gelap yang nampak megah.
Banyak orang disana, kebanyakan berbaju ceki dengan lambang perahu phinisi di lengan, beberapa dengan setelan kaus oblong dan celana jeans yang mulai luntur, beberapa lagi memakai baju hitam kebesaran dengan sarung yang dililit rapi di kepala, mereka juga bertelanjang kaki tanpa sehelai alas, konon merekalah yang dikenal sebagai tu kajang (orang kajang). Mereka semua datang menyambut sekaligus bersiap memboyong kami ke desa-desa mereka di pedalaman.
Bambanna Alloa
Keesokan hari pukul 9 pagi, kami bersiap untuk tamasya ke dusun-dusun. Sebagaimana anak KKN yang baru saja tiba di kampung orang, mereka tak mau terlampau cepat ketahuan sebagai pemalas, maka pagi-pagi buta seragam tempur dan segala hiasannya telah melekat; almamater hijau kebesaran, topi longgar mengarah ke belakang, senyum polos meminta rasa akrab, dan satu lagi tambahan hiasan yang sejak kemarin memenuhi tubuh, keringat yang mengucur tiada henti. Pagi itu, panas telah menyerang sejak pukul 7, ketika tanah Kajang masih terang-terang tanah.
Barulah satu dusun kami kunjungi, dahaga sudah mencekik kerongkongan dan toko kelontong satu-satunya penolong di terik siang itu. Alhasil, kami mengunjungi ibu-ibu penjual lebih sering ketimbang rumah kepala dusun.
Salah seorang kawan dari Kabupaten Jeneponto yang mahsyur panasnya mendengus kesal. “Omalee, bambanna alloa, panas sekali aih,” . Lima teman perempuan yang juga tengah mengibas-ibaskan jilbabnya mengangguk mengiyakan.
Aku mulai memikirkan dalam-dalam penyebab panas jahannam yang menyerang sejak kami menginjakkan kaki di desa ini.
Dugaan pertama, desa ini terlampau gersang. Namun, sejauh mata memandang, rimbunan pohon randu dan jambu nampak subur di hutan-hutan, pohon kelapa juga bermekaran di tiap-tiap kebun. Paling tidak, tak ada gurun pasir disini.
Dugaan kedua, desa ini mungkin terlampau dekat dengan pesisir yang panas tak kira-kira. Hanya saja, saat kutanyakan ke ibu posko, ia mengaku setidaknya masih ada tiga desa untuk tiba ke bibir pantai, 6 km tidak kurang jauhnya. Lagipun, tak ada pasar ikan tempat para nelayan beradu rayu dengan penadah.
Dugaan terakhir dan sekaligus yang paling logis. Kajang saat ini masih dilanda kemarau, namun apa betul selalu sepanas ini, inikan bulan November, seharusnya hujan lagi deras-derasnya, iyakan? Andai betul sepanas ini setiap tahun, orang-orang kajang pasti salah satu golongan umat Muhammad yang kebal panas di Padang Mahsyar, yang katanya ubun-ubun manusia hanya sejengkal saja dari matahari.
Demi memenuhi jawaban atas dugaan-dugaan itu, aku tanyakan ke bapak posko yang sejak kami menumpang di rumahnya, saban siang berlindung di pohon mangga dengan baju yang bertengger melingkar di bahunya yang lebar.
“Baru 2 tahun belakangan ini panas sekali do, tidak pernah ma saya tidur siang itu di kamar,”
Benar, perayaan tidur siang tidak berlaku bagi tubuh-tubuh yang penat disini, hawa jahannam ini merenggut kenikmatan itu.
Mujahir Ibu Jari
Di hari-hari selanjutnya, seorang lelaki paruh baya mengundang kami ke empang untuk ikut menangkap ikan piaraan. Lelaki itu sudah tua, Pung Ishak namanya, umurnya tak kurang 50-an, kulitnya legam gelap mengkilap, jalannya cepat-cepat, kumisnya tebal demi menyaring tuak saat ditenggak.
Dengan jala yang terkembang, kami mulai menangkap ikan, ia sibuk melempar jala sedang aku menonton di balik pematang. Telah 2-3 kali ia melempar, namun hanya siput-siput parasit yang tersangkut di jaringnya. Ia berpindah-pindah, menduga sarang ikan-ikan kesayangannya. Seekor ikan yang kukira kodok akhirnya tersangkut disana. Ia tersenyum lepas, mujahir sebesar ibu jari kaki akan masuk ke penggorengan siang nanti.
Ia berkisah, kalau Mujahir kesayangan itu rupanya untuk makan sehari-hari saja atau sekadar hiasan di balik tudung saji, ikan-ikan itu tidak dijual sama sekali. Saat aku ajukan pertanyaan perihal panas yang menyengat, ia juga membenarkan.
“Karena panas begini yang bikin kurang sekali air empang, makanya kecil-kecil ikan ka,”
Ketimbang hanya membakar kulit, panas ini berdampak lebih buruk bagi pemilik empang, mereka harus memakan ikan sebesar ibu jari, Mujahir pula.
Keramahan orang-orang Kajang, adalah hal yang patut kami syukuri. Selain ajakan menangkap ikan di empang, kelapa dan tuak manis selalu jadi ajang bagi kami untuk menikmati indahnya KKN. Pak dusun, yang akrab kami panggilkan Pung Amri selalu semangat mengajak kami ke kebun miliknya, entah untuk sekedar mencicip kelapa hibrida yang selalu ia banggakan, katanya air dan nira di kebun miliknya adalah yang paling manis di desa. Sementara, anak sulungnya tengah asyik memasak air kelapa di tepi gubuk beratapkan ilalang. Disini, gula merah berbahan kelapa adalah sumber penghidupan utama warga kajang. Selain karena memang menjadi komoditas penting masyarakat Kajang, tak ada tanaman yang bisa panjang umur di kebun mereka selain kelapa dan pohon aren.
“Sebenarnya, saya mau ajak kalian makan jagung, sudah jauh hari saya niatkan kalau anak KKN nanti datang akan saya bawa makan jagung di kebun, tapi yah lihatlah sekarang. Nda tau beberapa tahun ini jagung nda bisa tumbuh, mungkin mapassemi tanahnya,” pak dusun menyebut mapasse sebagai dugaan kalau tanah kebun tak lagi subur. Matanya tampak nanar memandang kejauhan, mata yang sama kala kakekku meratapi gabah yang habis diterjang banjir, tatapan kecewa milik petani.
Jejak bahwa kebun ini adalah lahan jagung juga masih terlihat tengah-tengah kebun, yang kini lebih mirip semak kering dan jadi santapan lezat kambing kerontang yang berlalu lalang di sana.
Ritual
Di malam hari, sebuah ritual menggelikan dimulai. Entah kerasukan dewi cinta macam apa, para anak KKN sibuk bertelpon ria hingga larut malam, mengumbar sayang dan bohong secara bersamaan. Ritual itu dimulai sejak pak imam usai membaca doa selamat dunia akhirat di waktu isya hingga radio mesjid dini hari kembali berkumandang. Aku yang tak punya siapa-siapa untuk diajak membunuh waktu, memutuskan menelpon kawan senasib yang juga sibuk mengabdi di daerah lain. Tujuanku sama seperti sebelumnya, menanyakan hawa panas apakah menyiksa mereka juga? Sontak semua mengiyakan. Jeneponto usah ditanya panasnya seperti apa, gersang ditambah daerah pesisir tempat ia mengabdi kata seorang kawan. Sinjai juga sama, Majene apalagi, bahkan Enrekang yang mahsyur dinginnya karena cuma selemparan batu dari Gunung Lattimojong, juga tak sesuai harapan, panas jahannam sewaktu-waktu. Di ujung panggilan video, salah seorang menimpali perihal penyebab panas yang kuajukan.
“Ini pasti krisis iklim sodara, bukan panas biasa,”
Bukan main, Ia bawa-bawa krisis iklim pula, tapi ah masa iya?. Krisis iklim. Dugaan itu bergeming di kepalaku, tak mau pergi semalaman. Pertanyaan tentang panas masih terus membebani, bersamaan dengan keringat karenanya dan sayup-sayup dari kamar para anak muda yang kerasukan dewi cinta itu berbisik-bisik mengumbar kasih, cih bikin iri saja.
Hutan Keramat
Di lain malam, pesan singkat berisi undangan yang lebih mirip perintah dialamatkan ke seluruh posko KKN di Kecamatan Kajang. Dosen pembimbing akan berkunjung, bukan kunjungan biasa sepertinya, sebab mereka turut membawa petinggi kampus, entah siapa, sebab terlalu banyak petinggi di kampus. Di pesan tersebut juga turut tertera nama tokoh adat masyarakat Kajang, Abdul Kahar Muslim.Pung Kahar sebagaimana ia dipanggilkan, telah tiga kali jadi Kepala Desa di kawasan adat Tanah Toa, tiga kali jadi wakil rakyat, dan dua kali jadi calon penguasa Bulukumba. Yang terakhir Ia hanya mampu menjadi calon.
Siang itu di aula kecamatan, Ia terduduk penuh wibawa dengan jas tutup gelap mengkilap, peci dan celana dengan warna senada, kumisnya melintang lebat dan mata tajam khas manusia Kajang. Ia didapuk menjadi pembicara, menyoal eksistensi kearifan lokal masyarakat Kajang.
Dialog dimulai dengan Pung Kahar berkisah tentang masyarakat Kajang dan sistem kepercayaan yang dianutnya. Katanya, sebelum mengenal Islam dan Tuhannya Yang Esa, orang-orang Kajang juga percaya dengan penguasa semesta yang esa pula, serupa dengan apa yang didakwahkan oleh Islam. Bedanya, mereka menyebut sesembahannya sebagai Tu Ria Ra’na yang berarti Maha Kuasa dan Maha Tinggi.
Di dalam keberlanjutan sistem masyarakat Kajang kata Pung Kahar, Amma Toa selaku kepala pemerintahan dan tetua adat tertinggi berfungsi untuk menjaga sistem, dan salah satu yang paling utama yakni hubungan manusia dengan alam di sekitar. Perwakilan tiap posko dan tamu undangan yang sejak tadi diserang kantuk membenarkan posisi duduknya, di tengah kuliahnya yang berapi-api Pung Kahar merapalkan petuah serupa mantra.
“Punna nitabangi kajua ri boronga angngurangi bosi appatanre’ tumbusu injo raunna ngonta,”
“Jikalau pohon-pohon ditebang di hutan, hujan berkurang dan mata air lenyap,” pungkasnya, sembari menyebarkan pandangan ke penjuru aula kecamatan.
Pung Kahar meraih segelas air kemasan, menenggaknya perlahan, peserta dan tamu undangan memandanginya lamat-lamat. Pung Kahar kembali berkisah, kali ini tentang Borong Karrasa, katanya di kawasan adat Kajang terdapat rimba, sebuah hutan larangan yang mahsyur, tempat segala mistis dan hukum adat berlaku, dimana tak ada suatupun alasan dapat dibenarkan untuk membunuh sebatang pohon disana. Adat dan hutan yang lestari hingga kiwari.
Aku terkagum beberapa saat. Mereka yang tak beralas kaki sebagai bentuk perlawanan terhadap kemajuan pengetahuan dan modernisasi justru memahami siklus alam dengan hutan sebagai penopangnya. Tanpa penelitian dan embel-embel metodologi, tanpa alat-alat canggih pengukur segala kondisi, orang-orang Kajang paham dan tetap melestarikan petuah itu sebagaimana hutan yang masih terjaga.
Sejak petuah tentang hutan itu meluap dari bibir lelaki paruh baya itu. Aku menemukan jawaban yang hampir tidak masuk akal perihal panas, seperti sebuah paradoks. Aku menyusun dan mengurainya secara seksama dan dalam tempo yang tidak sesingkat-singkatnya, maka kutariklah sebuah kesimpulan.
Di saat Masyarakat Kajang berpegang teguh pada petuah pelestarian hutan seperti yang dikatakan Pung Kahar, justru panas jahannam menyerang masyarakatnya tanpa ampun. Lalu, apakah berarti petuah hutan itu tidak diindahkan oleh masyarakat? Jelas tidak kataku, mereka masyarakat yang patuh terhadap adat. Borong Karrasa adalah bukti bahwa hutan tetap terjaga dikawasan adat. Yang jadi masalah, bukan masyarakat Kajang atau Borong Karrasa tak mampu menyediakan udara sejuk bagi segenap penghuninya, melainkan krisis iklim. Betul, sebagaimana teman yang menyimpulkan pertanyaanku kala itu. Aku mulai percaya, segala keluh tentang panas yang disampaikan oleh kawan-kawan di masing-masing tempat mereka mengabdi adalah benar gejala krisis iklim.
Jujur saja, krisis iklim mungkin terlampau jauh untuk dikira sebagai akibat dari panas jahannam di Tanah Kajang, namun bukan suatu yang mustahil apalagi omong kosong. Tidak diindahkannya hutan seperti yang terucap pada petuah Kajang merupakan langkah awal menuju krisis iklim. Apa mungkin ada faktor lain yang menyulut bencana panas yang tak jauh dari kawasan dan kehidupan masyarakat Kajang?
London Sumatera
Selepas isya adalah waktu yang paling tepat untuk melepas penat. Secangkir kopi dan kue ruhu-ruhu hasil bantu-bantu hajatan tetangga membuat suasana kami bertukar cerita dengan bapak posko. Seringkali sampai lepas larut malam menceritakan berbagai hal, mulai dari sejarah orang-orang kajang, ilmu hitam doti yang hanya dimiliki para orang-orang pintar di kawasan adat, hingga perilaku buruk tetangga-tetangganya, yang terakhir dia akan sedikit mendekat dan berbisik saat mengisahkannya. Namun malam itu, kami hanya membahas satu hal, dan dia juga setengah berbisik saat menceritakannya.
Percakapan berbisik bapak bermula kala kukeluhkan Perusahaan Karet yang tidak mengindahkan proposal yang kuajukan siang itu. Rencananya kami akan menjadikan perusahaan perkebunan itu untuk menyokong kegiatan festival anak saleh kegiatan yang telah kami canangkan saat seminar program kerja di balai desa. Kepala desa memberikan arahan agar mengusulkan proposal kegiatan di PT. London Sumatera, perusahaan karet seluas 5000 hektar yang tempo hari menyihirku dengan barisan rapi pohon-pohonnya.
Bapak posko menyuruhku mendekat saat kusebut nama perusahaan itu, dan sejurus ia mulai berkisah.
Konon kata bapak, perusahaan tersebut merupakan milik kompeni belanda sejak awal abad ke-19. Saat republik merdeka, perusahaan itu beralih ke tangan para tentara. Aku yakin, tentara yang di maksud bapak adalah pejabat orde baru. Konflik mulai terjadi kala perusahaan mencoba memperluas lahan seluas 250 hektar yang rupanya turut mencaplok kawasan adat suku kajang. Bentrokan tak terhindarkan.
Bapak menenggak kopinya, suaranya makin pelan.
Ternyata beberapa warga dusun adalah buronan dalam konflik itu, ada korban tewas dan banyak dari mereka yang luka tertembus timah panas. Suasana mencekam di pekan itu, tak ada yang berani keluar malam, sebab kampung dan kawasan adat tak ubahnya zona perang. Polisi berlalu-lalang dengan senjata laras panjang dan segera membubarkan kerumunan apapun yang mereka temui..
Selain desas-desus buronan yang diburu polisi, kabar soal orang-orang Kajang memiliki ilmu kebal tersebar seantero Bulukumba. Banyak polisi yang mengisahkan beberapa warga yang melawan tak bisa tertembus timah panas kendati diberondong dari jarak 50 meter. Setelah beberapa dekade, konflik sudah mulai terlupakan, tapi luka dan kengerian itu masih tersimpan di benak bapak.
“Seandainya itu perang terjadi sekarang pasti banyak polisi yang dipecat,”
Aku hanya mengagguk pelan mendengar cerita bapak, tak banyak bertanya seperti cerita-cerita sebelumnya. Sembari kutenggak kopi aku paham kalau di belahan dunia manapun industri yang membutuhkan banyak ruang dan sumber daya selalu menjadi musuh nyata bagi orang-orang kecil. Bahkan, berita dibukanya keran investasi untuk perkebunan sawit santer terdengar sejak Bupati baru dilantik pada awal 2021. Taipan perkebunan sawit dari keluarga Salim siap menyokong pembangunan areal perkebunan.
Melalui penuturan bapak dan kabar soal perkebunan baru di Bulukumba, aku hanya bisa menggerutu dalam hati. Kabupaten yang berbangga karena orang-orang Kajang terdaftar secara administratif di wilayahnya justru mendorong kembali investasi perkebunan sawit seluas lima ribu hektare. Tak terhitung berapa pohon, hutan dan manusia akan binasa karenanya. Orang-orang memang tak suka belajar sejarah. Bahkan aku mulai percaya sejak Pung Kahar berkisah soal hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat Kajang, bahwa hukum adat yang kuat dan dilindungi negara adalah satu-satunya aturan bijak yang dapat melindungi semuanya, bukan hanya masyarakat dan kebudayaannya atau lingkungan dan alam sekitar, tapi juga membendung sifat-sifat serakah para pemilik modal dan krooni pemerintahnya. Pada kasus masyarakat Kajang, Amma Toa selaku perwujudan Tu Ria ra Na adalah ratu adil yang transenden bagi mereka, titah Amma Toa adalah titah sang kuasa, dan tak ada yang berani menantang bala dengan melanggar aturan adat.
Membicarakan dampak hancurnya hutan adalah tuah yang akan dituai di masa depan. Tak usahlah jauh-jauh, mulai dari perkara tidur siang saja tak bisa lagi dirayakan karena panas yang makin menjadi kian hari. Aku khawatir nantinya masyarakat kajang juga tak bisa tidur di gelapnya malam karena panas yang kelak tak mengenal waktu. Yang paling buruk, pakaian hitam sehari-hari orang-orang kajang akan ditanggalkan karena warna hitam tak mampu melindungi kulit dari sengat panas atau bahkan mereka akan mulai memakai sandal, bukan karena takluk oleh modernisasi tapi karena telapak kaki tak bisa lagi berkawan dengan aspal yang mendidih. Apa yang lebih buruk dari kehilangan sebuah identitas dan kebudayaan?
Pulang;
Kendati matahari tenggelam, panas masih saja tak mau diajak berdamai. Senantiasa kubuka jendela kecil tepat di samping kasur, sekurang-kurangnya jendela kecil itu meniup angin-angin sepoi di waktu subuh. Namun, dini hari yang pekat itu. Aku terbangun. Tempias hujan membasahi kaki laksana mimpi di kemarau panjang selama ini. Kututup kembali jendela, dengan sedikit senyum kuucap pelan,
“Enyah kau panas sialan, sahabatku si hujan sudah datang,”.
Aku terbangun, napasku tersengal, keringat kembali banjir, panas itu datang lagi. Sepertinya hujan pagi itu hanya mimpi. Benar, panas tak pernah telat membangunkanku, dan aku segera bergegas sebab pagi itu adalah pagi ke 45, pagi terakhir kami di tanah Kajang.
Pukul 7.30, anak-anak SD yang saban hari kami temui di kelas sempit mereka, ibu-ibu yang kami bantu menimba air di sumur mushollah, dan bapak-bapak yang dengan senang hati memberi sedekah air kelapa, semuanya berkumpul di depan rumah bapak posko. Hari ini kami akan kembali ke dunia nyata perkuliahan, melepas tugas kuliah kerja nyata. Kami saling berangkulan, aku bahkan menangis sesenggukan mencium tangan pak dusun yang selalu tersenyum kendati matanya tak pernah bisa menyembunyikan haru. Ibu-ibu menyeruak memeluk kami dengan berbagai bungkusan berisi kue ruhu-ruhu khas Kajang. Seorang ibu-ibu menjabat tanganku memberi sebungkus ruhu-ruhu, seketika kubalas dengan senyum dan mencium tangannya.
“Kordes, saya itu mau bawakanko pisang nak sama pepaya, tapi we kodong itu mati semuai do, kering sekali kebun sekarang” ujarnya dengan logat kajang yang mendayu.
Aku hanya tersenyum dan berterima kasih, kehadiran mereka mengantar kami sudah sangat berarti. Dan lagi, panas tetap menjadi keluhan mereka, keluh yang menyambut dan mengantarku hingga pulang.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Menjelang Lenyapnya Kajang
Rabu, 24 Mei 2023 21:08 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan





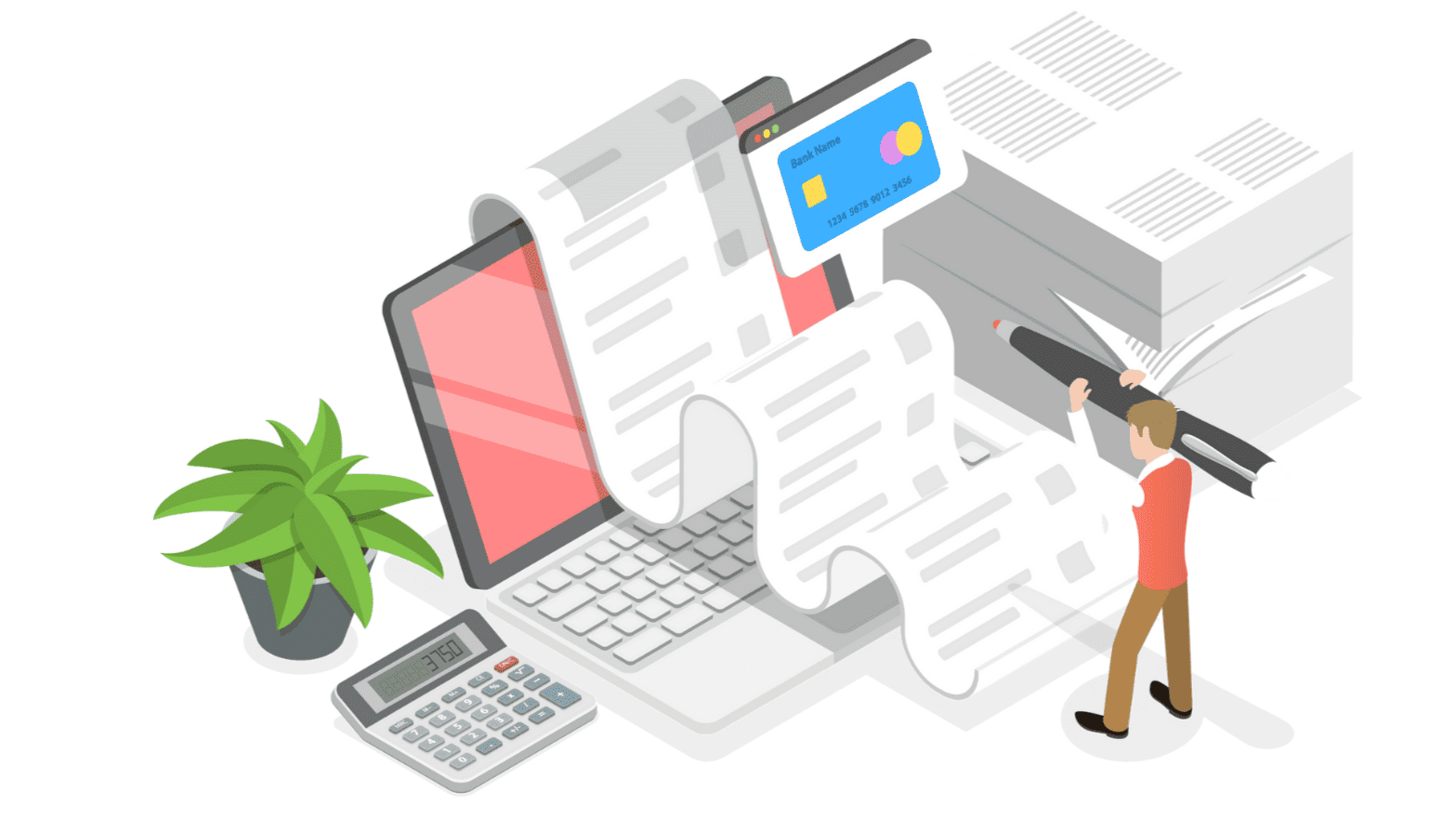

 98
98 0
0















