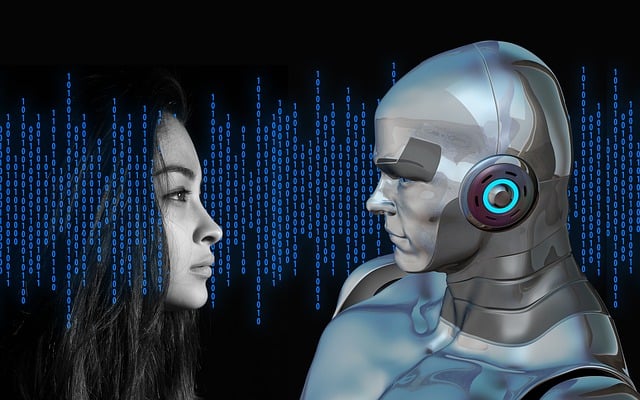Kasus Bacapres PDIP, Ganjar Pranowo tampil dalam tayangan adzan maghrib beberapa waktu lalu telah memicu reaksi publik dan mengundang pro-kontra di tengah masyarakat. Terlepas dari soal kontroversinya, kasus ini sebetulnya telah memberikan “hikmah” kepada kita perihal satu isu yang selama ini dicemaskan, yakni isu politik identitas.
Ganjar telah mengajak publik untuk “melawan lupa” perihal keterbelahan sosial yang pernah dialami bangsa ini sebagai dampak dari maraknya penggunaan politik identitas pada Pemilu-pemilu sebelumnya.
Tanpa bermaksud membuka luka lama, melainkan semata-mata untuk “melawan lupa” bahwa bangsa ini pernah nyaris terjerumus cukup dalam ke jurang bahaya, isu politik identitas dalam konteks perhelatan elektoral di Indonesia mengemuka pertama kali pada Pemilu 2014.
Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tajam pada Pilkada DKI 2017, dan menjadi residu yang merebak kembali dengan tensi yang tak kalah kuat pada Pemilu serentak 2019. Aspek identitas primordial yang menjadi titik tekan pada ketiga perhelatan elektoral itu adalah agama dan etnisitas.
Jika merujuk pada perspektif akademik, Agnes Heller dan Donald L Morowitz misalnya. Mereka melihat politik identitas sebetulnya hadir sebagai bentuk kesadaran individu untuk mengelaborasi identitas partikular (khas) dalam bentuk relasi identitas primordial, khususnya etnik dan agama. Dengan cara ini secara sosiologis suatu kelompok membangun soliditas internal, harmoni dan kesetiakawanan.
Instrumen Pemenangan
Akan tetapi dalam praktiknya kemudian, gagasan politik identitas mengalami transformasi menjadi instrumen politik untuk meraih kekuasaan dan/atau mempertahankan ststus quo oleh para aktor politik. Dalam posisi sebagai alat untuk memenangi kontestasi kekuasaan, politik identitas dikapitalisasi secara brutal dengan mengabaikan dampak sosiopolitik yang diakibatkannya.
Dalam kasus Pilkada DKI 2017 wajah politik identitas mengemuka melalui berbagai bentuk ekspresi dan artikulasi. Namun kesemua bentuk pengejewantahan itu bermuara pada identitas pembeda dua aspek primordial, yakni agama dan etnis yang melekat pada sosok calon gubernur, terutama Basuki Tjahya Purnama (Ahok, Kristen dan beretnik Tionghoa) dan Anies Rasyid Baswedan (Anis, Muslim dan beretnik Arab).
Kedua sosok populer itu mewakili dua kutub identitas yang secara diametral, bukan saja berbeda tetapi juga saling berhadapan dalam situasi kontestatif. Dan kedua kubu pendukungnya terjebak sama-sama menggunakan politik identitas.
Hanya saja, dalam situasi kontestatif itu kubu Anies lebih “diuntungkan” dengan terjadinya kasus penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok, yang sesungguhnya mungkin tidak pernah disengaja untuk menistakan agama Islam namun kemudian berkembang menjadi kasus blasphemy hingga memicu lahirnya aksi berjilid-jilid oleh eksponen 212.
Kubu Anies mengkapitalisasi kasus ini untuk kepentingan mobilisasi pemilih demi meraih kemenangan dalam Pilkada. Dan akhirnya memang terbukti : Anies yang kala itu berpasangan dengan Sandiaga Uno berhasil memenangi Pilkada di putara kedua.
Pengalaman Pemilu 2019
Fenomena politik identitas dalam Pilkada 2017 yang telah menorehkan luka kebangsaan karena efek daya sebarnya yang sangat luas itu kembali terjadi menjelang dan sepanjang perhelatan Pemilu 2019.
Tetapi agak berbeda dengan yang terjadi dalam Pilkada DKI, gejala politik identitas dalam Pemilu 2019 tidak secara vis-à-vis menghadapkan dua identitas primordial yang berbeda. Melainkan lebih ke pengidentifikasian dan stigmatisasi oleh masing-masing kubu terhadap kubu lawannya.
Kala itu kubu Jokowi-Ma’ruf distigmatisasi dengan beragam identitas buatan yang dikapitalisasi nyaris tanpa henti sepanjang, bahkan setelah Pemilu 2019 usai. Mulai dari tuduhan Jokowi keturunan PKI, antek asing-aseng, phobia Islam, penghayat aliran kepercayaan, pendukung dan pelindung LGBT dll. Sementara kepada kubu Prabowo-Sandiaga disematkan berbagai tudingan stigamtis yang sama buruknya, seperti Prabowo seorang ultra-nasionalis, Prabowo Natalan, pendukung Islam radikal dan penyokong ide khilafah, dst.
Melalui berbagai isu ini kedua kubu saling serang untuk meraih simpatik publik dan pemilih, meski keduanya menolak dituding sebagai telah memanfaatkan dan mengkapitalisasi isu-isu identitas untuk kepentingan pemenangan kontestasi (Puskapol UI, 2020).
Kubu Jokowi-Ma’ruf menuding kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan propaganda model Rusia dengan strategi firehose of falsehood, yakni menggunakan semburan kebohongan dalam kampanye untuk memengaruhi pemilih. Selain itu, kubu Jokowi-Ma’ruf juga menuding kubu Prabowo-Sandiaga menggunakan strategi politic of fear (politik ketakutan) dalam kampanye.
Sementara itu, sebaliknya kubu Prabowo-Sandiaga menuduh kubu Jokowi-Ma’ruf melakukan strategi playing fictim terkait isu identitas, yang justru kemudian mempraktikkan politik identitas dengan manuver memilih seorang Kyai sebagai Calon Wakil Presiden. Selain itu, kubu Prabowo-Sandiaga juga menuduh kubu Jokowi-Ma’ruf melakukan tudingan hoax untuk mengaburkan fakta-fakta terkait kegagalan pemerintah Jokowi sebelumnya dan melemahkan data serta argumen yang dikemukakan tim Prabowo-Sandiaga.
Sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai hasil riset dan fenomena praksisnya bahkan hingga saat ini, kapitalisasi isu-isu identitas sebagai salah satu faktor non-elektoral untuk meraih simpati dan memenangi kontestasi terbukti telah melahirkan kegaduhan dan pertengkaran di dalam masyarakat, baik di ruang-ruang digital maupun di dalam kehidupan nyata keseharian masyarakat.
Tidak sedikit dalam satu keluarga atau antar tetangga bertengkar lantaran beda dukungan dan pilihan. Lebih jauh dari sekedar gaduh dan bertengkar, tebaran isu-isu identitas yang dikapitalisasi dan kemudian memengaruhi persepsi dan perilaku elektoral para pemilih dari masing-masing kubu ini akhirnya mengarahkan masyarakat Indonesia pada situasi keterbelahan (polarisasi) sosial-politik di berbagai daerah.
Pemilu yang sejatinya memang merupakan ajang konflik politik untuk memperebutkan kekuasaan namun yang didesain demikian rupa pelaksanaannya hingga tetap berlangsung tertib dan damai, dengan pengerasan dan eskalasi isu-isu identitas yang terus berkembang secara masif konflik Pemilu menjadi tidak mudah dikelola dan dikendalikan.
Menolak Syahwat
Kita tentu berharap Pemilu 2024 berlangsung dalam suasan fair, kompetitif dan demokratis, namun sekaligus aman dan damai. Minus penggunaan politik identitas sebagai alat pemenangan. Biarlah identitas yang melekat secara natur dalam individu-individu dan kelompok-kelompok warga negara berhenti sebagai ciri khas, karakteristik dan kekayaan bangsa Indonesia saja. Jangan kemudian dikapitalisasi, dipolitisasi sebagai alat untuk memenangi kontestasi.
Untuk itu diperlukan komitmen, janji bersama para pihak terutama para elit dari setiap kubu yang bertarung di arena Pemilu, baik partai politik maupun para pasangan Capres-Cawapres beserta tim pemenangan dan massa pendukungnya. Janji untuk menolak syahwat politisasi identitas, janji tidak menggunakan lagi politik identitas dengan cara artikulasi dan bentuk ekspresi apapun, serta tekad kuat untuk meneguhi janji itu hingga hajat demokrasi nanti berakhir.
Ikuti tulisan menarik Agus Sutisna lainnya di sini.