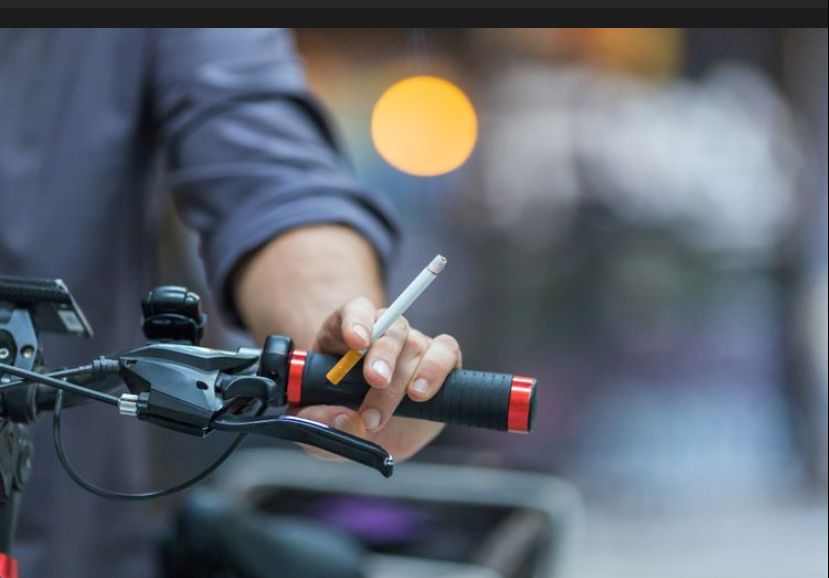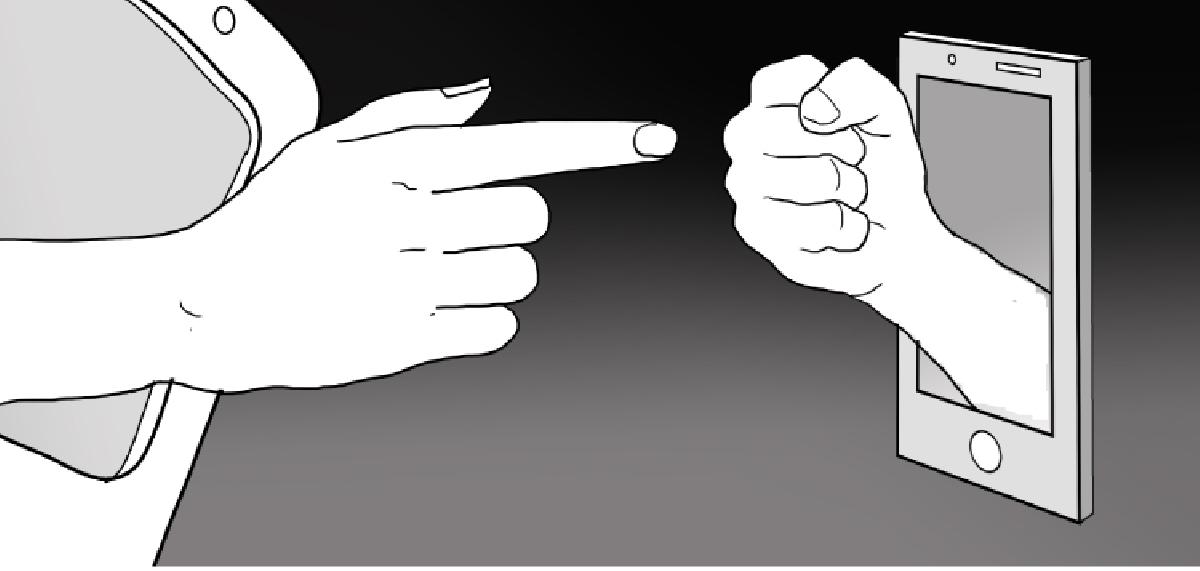Hari menjelang pagi, Hans Rudolf Springer—sipir malam di penjara Stammheim, Stuttgart, Jerman Barat—mulai merasa lega. Sebentar lagi, beberapa kawannya tiba untuk menggantikannya, dan ia bisa pulang ke rumah untuk tidur nyenyak.
Nyatanya tidak. Kepulangan Springer terhalang oleh kepanikan yang pecah pagi itu, saat rekan sipirnya membuka Sel 716 dan petugas lain mengantarkan roti dan telur rebus untuk sarapan pagi bagi para pesakitan. Keduanya mendapati tahanan Jan-Carl Raspe tidak berdiri di ruangnya seperti biasa, melainkan duduk di ranjang. Tubuhnya bersandar di dinding, kepalanya terkulai. Darah mengucur dari sisi kiri kepalanya. “Ada pistol di sini!” teriak petugas.
Raspe masih hidup ketika dibawa ke rumah sakit, tapi ajal menjemputnya di bangsal. Para sipir bergegas menuju Sel 719 dan mendapati keadaan serupa: Andreas Baader terbaring di lantai di atas genangan darah. Di Sel 720, Gudrun Ensslin tak menjawab panggilan petugas. Tubuhnya dingin menggantung. Di bawah selimut, Irmgard Moller tengah meregang nyawa di Sel 725.
Mereka, anak-anak muda di dalam penjara itu, telah melakukan apa yang ditulis oleh Ulrike Meinhof: “Bunuh diri adalah tindakan pemberontakan terakhir.” Ulrike sendiri setahun sebelumnya, 1976, ditemukan mati menggantung di dalam selnya.
Kira-kira baru 25 tahun Jerman meninggalkan Perang Dunia II ketika Andreas Baader, Gudrun Ensslin, bersama Ulrike mendirikan Faksi Tentara Merah (Rote Armee Fraktion--RAF, dalam Bahasa Jerman). Mereka menggambarkan diri sebagai kelompok “gerilya perkotaan” anti-imperialis yang melakukan perlawanan terhadap negara yang mereka anggap fasis.
Kaum muda Jerman marah atas apa yang mereka persepsikan sebagai kegagalan de-Nazi-fikasi pasca Perang Dunia II di Jerman Barat maupun Jerman Timur. Para mantan Nazi menempati posisi penting dalam pemerintahan dan kegiatan ekonomi. Di Jerman Barat, 1966, dua partai utama yang bersaing, SPD dan CDU, membentuk Koalisi Besar di bawah kepemimpinan Kanselir Kurt Georg Kiesinger, mantan anggota Nazi.
Para mahasiswa menentang Koalisi Besar yang mengendalikan 69 persen kursi Bundestag dengan mengusung aksi-aksi oposisi Ekstra-Parlementer. Banyak anak muda terasing dari orangtua mereka maupun institusi negara. Situasi serupa berlangsung di Italia, yang juga pernah diperintah oleh rezim Fasis, dan melahirkan Brigade Merah atau Brigate Rosse yang juga melakukan perlawanan keras.
Dalam buku RAF & The Baader Meinhof Complex, Stefan Aust menggambarkan kesukaran-kesukaran yang dihadapi oleh generasi sezamannya dalam menyikapi masa lampau bangsanya. Perang Vietnam yang melibatkan AS menyuburkan pergolakan sosial di negara-negara maju. Tulisan-tulisan Jurgen Habermas, Herbert Marcuse, juga Franz Fanon dan Antonio Gramsci memberikan pencerahan pada anak-anak muda ini tentang apa yang mesti mereka lakukan. “Hanya kelompok marjinal mahasiswa dan kaum miskin yang bergabung dengan kaum pekerja yang mampu melawan sistem secara efektif,” begitu tulis Herbert Marcuse.
Situasi Jerman memanas ketika protes damai atas kedatangan Shah Iran Reza Pahlevi di Berlin Barat berubah menjadi kerusuhan pada 2 Juni 1967. Tertembaknya mahasiswa Benno Ohnesorg memicu kemarahan dan menjadi titik tolak perjalanan Kiri Baru di Jerman Barat. Lahirlah Gerakan 2 Juni.
Musim semi 1968, Gudrun Ensslin dan Andreas Baader membakar dua toko serba ada di Frankfurt sebagai protes terhadap serangan AS ke Vietnam. Sempat mendekam di penjara, Baader dkk dibebaskan oleh Ulrike Meinhof yang saat itu masih berprofesi jurnalis. Mereka lari ke Jordania dan mengikuti latihan singkat tentang gerilya oleh Organisasi Pembebasan Palestina.
Sekembalinya ke Jerman Barat, mereka memulai apa yang disebut “perjuangan anti-imperialis”, dengan merampok bank dan menyerang fasilitas militer AS, kantor polisi Jerman, dan bangunan milik kerajaan pers Axel Springer. Di tahun itu pula, sebuah manifesto yang ditulis oleh Meinhof mengumumkan terbentuknya RAF.
Setelah serangkaian aksi yang mengguncang Jerman Barat, mereka tertangkap. Perlawanan terhadap penahanan dan proses peradilan berlangsung di ruang sidang, di sel-sel lewat aksi mogok makan, dan di luar penjara melalui aksi anggota RAF generasi kedua: menculik Peter Lorenz, calon walikota Berlin dari partai CDU, pengepungan kedutaan besar Jerman Barat di Stockholm yang diwarnai terbunuhnya dua orang sandera, dan pembunuhan Jaksa Agung Federal.
Saya tidak tahu, hingga kini, apakah Ulrike dan kawan-kawan telah membaca karya revolusioner Brasil, Carlos Marighella, dan mengambil inspirasi dari karya ini. Dalam Minimanual of the Urban Guerilla (1969), Marighella menggambarkan gerilya kota sebagai “seseorang yang melawan kediktatoran militer dengan senjata, menggunakan metoda-metoda tidak konvensional.. Gerilya kota mengikuti tujuan politik, dan hanya menyerang pemerintah, bisnis besar, dan imperialis asing..”
Memanfaatkan arsip, catatan yang masih dirahasiakan, materi yang sudah maupun belum diterbitkan, juga percakapannya dengan mereka yang terlibat, Stefan Aust merekonstruksi kisah pemberontakan kelompok Baader-Meinhof. Menampilkan kegelisahan yang dihadapi oleh anak-anak muda ini, pertentangan pendapat di antara mereka sendiri, Stefan—yang mengenal Ulrike Meinhof secara pribadi—mencoba memanusiawikan kelompok yang dikenal sangat keras ini.
Di mata Stefan Aust, Ulrike pribadi yang sangat mengesankan, berpendidikan baik dan jurnalis yang kritis sebelum bergabung dengan Baader. Ulrike juga menderita hidup di dunia yang tak adil. Ketika ia masih menjadi redaktur, Ulrike kerap menulis tentang kaum miskin, mereka yang diperas keringatnya, dan orang-orang yang dipenjara. Ia, akhirnya, tak bisa hidup di dunia dunia. “Saya pikir, keterlibatannya di RAF karena alasan pribadi dan psikologis,” ujar Stefan Aust.
Sebagai karya evolutif, buku ini diterbitkan pertama kali pada 1985 atau delapan tahun sesudah peristiwa bunuh diri di penjara Stammheim. Stefan merevisinya pada 1997 dengan melengkapi wawancara orang-orang yang terlibat. Setelah Jerman Barat dan Jerman Timur bersatu, mantan pemimpin redaksi Der Spiegel ini menulis ulang dan menerbitkannya kembali pada 2009. Karya ini kemudian difilmkan (2008) dengan judul yang sama di bawah pengarahan sutradara Jerman Uli Edel.
Aktivitas teroris, menurut Aust, selalu merupakan bagian dari gerakan radikal yang lebih besar. Sebuah kelompok teroris tumbuh dan berkembang hanya ketika gerakan radikal yang lebih besar ada, apapun jenisnya—kiri, kanan, nasionalis, atau keagamaan. RAF, dalam hal ini, adalah bagian dari kiri radikal di Jerman pada masa itu. Hanya dengan berada di dalam kerangka gerakan yang lebih besar, mereka dapat memperoleh cukup dukungan untuk dapat beroperasi dalam periode yang cukup lama.
Alih-alih memiliki karakter politik yang rasional, Stefan sejak awal risetnya tampak menyadari bahwa RAF memiliki karakter kuasi-relijius, seperti yang juga diucapkan oleh ayah Gudrun Ensslin, seorang teolog Protestan, saat ditanya tentang sepak terjang anak perempuannya itu. “Tindakannya merupakan realisasi diri yang sungguh suci,” ujar ayah Ensslin.
Mereka bertindak sebagai martir politik atau keagamaan, kata Stefan, untuk menunjukkan bahwa negara bertindak brutal sebagaimana mereka pikirkan. Bila demikian, benar belaka bahwa aksi mereka adalah eksperimen dengan kehidupan mereka sendiri maupun kehidupan orang lain sebagai bahannya. Mereka melakukan apa yang disebut dengan tepat oleh Heinrich Boll sebagai perjuangan 6 melawan 60 juta. Mengajak bangsanya untuk menumbangkan sistem kapitalis mungkin kenaifan anak muda belaka, tapi mereka telah sanggup mengguncang Jerman dan Eropa.
Dalam surat-suratnya, mereka kerap mengutip karya Bertolt Brecht, The Measures Taken. Drama yang berbicara tentang kehendak hati untuk mengubah dunia dengan pembunuhan, dan jika perlu dengan bunuh diri, yang kemudian menjadi kredo RAF. Ensslin menjuluki kawan-kawannya dengan nama-nama karakter dalam novel Moby Dick, karya Herman Melville. Di antara kekerasan yang mereka torehkan, Baader-Meinhof menjadi ikon dan gambar hitam-putih mereka menjelang kematian menghiasi Museum of Modern Art di New York.
Aksi-aksi sporadis dilakukan oleh RAF generasi ketiga sepanjang 1980an hingga 1990an hingga mereka kelelahan. Surat delapan halaman tiba di kantor berita Reuters pada 20 April 1998 berisi pengakuan bahwa “akhir proyek ini memperlihatkan bahwa kami tidak berhasil.” (Foto Andreas Baader dan Gudrun Ensslin; sumber telegraph.co.uk) ***
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.