Teologi Pilkada
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Mereka yakin benar bahwa seorang pemimpin non-muslim selamanya akan menghambat dakwah dan perkembangan Islam.
Sejak Nurcholish Madjid mencanangkan sekularisasi politik melalui pembebasan kaum muslim dari teologi pemilu dengan slogan "Islam Yes, Partai Islam No!" yang masyhur itu, boleh dikatakan para aktivis dan pemikir Islam tidak canggung lagi bergabung dengan partai-partai sekuler. Juga pada masa pasca-Orde Baru, yang memberi keleluasaan kepada partai-partai untuk berkompetisi. Bahkan, tidak sedikit aktivis muslim dari NU, Muhammadiyah, atau di luar keduanya, bergiat di partai yang bukan hanya sekuler, tapi juga didirikan oleh non-muslim. Keberhasilan Nurcholish membebaskan umat dari teologi pemilu juga tampak dari absennya ketegangan ideologis antara partai-partai yang berhaluan Islam dan partai-partai "sekuler".
Agaknya, bergabungnya para aktivis muslim ke partai-partai sekuler itu hanya menghilangkan rasa "berdosa" penganut Islam "kafah" untuk tidak memilih partai-partai Islam. Mereka memilih wakil-wakil mereka yang islamis di partai-partai sekuler. Penampakan boleh kuning, merah, atau biru, tapi di dalam tetap "hijau".
Inilah mengapa dalam pemilihan kepala daerah argumen-argumen teologis kerap bermunculan untuk menolak calon pemimpin non-muslim. Bagi mereka, bupati, wali kota, atau gubernur tidak hanya berurusan dengan keduniawian, tapi juga berdimensi ukhrawi. Para kepala daerah itu adalah ulul amri sekaligus imam. Dari perspektif ini, tidak mengherankan jika tidak sedikit ulama di Tanah Air yang mengharamkan kepemimpinan perempuan, misalnya, apalagi orang kafir.
Penganut Islam "kafah" umumnya yakin bahwa Islam bersifat holistik (menyeluruh) dan ada di mana-aman (omnipresent), yang tidak melulu mengatur perkara agama (din), tetapi juga urusan dunia (dunya) dan negara (daulah). Dari sinilah kemudian muncul pandangan integralistik mengenai bersatunya agama dan negara. Salah satu akibat hubungan yang campur aduk ini adalah politisasi agama.
Akibat lebih jauh dari pencampuradukan ini adalah penghilangan agama dari fungsinya yang hakiki, yaitu sebagai sumber moralitas. Ia hanya dijadikan sumber legitimasi untuk memobilisasi dukungan. Ukuran-ukuran obyektif dalam memilih pemimpin dikesampingkan oleh faktor subyektif yang teradministrasikan dalam "kolom agama". Dari sinilah muncul semacam fatwa dari sejumlah ulama, yang menyatakan bahwa pemimpin yang korup masih bisa diperbaiki, sedangkan yang kafir sulit untuk diubah karena menyangkut akidah dan hidayah Tuhan.
Mereka yakin benar bahwa seorang pemimpin non-muslim selamanya akan menghambat dakwah dan perkembangan Islam. Dalam memilih pemimpin mereka, antara lain, bersandar pada Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51 dan Al-Nisa ayat 144 tentang larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani serta kafir sebagai awliya, yang diterjemahkan sebagai pemimpin. Maka, tidak mengherankan jika dalam pilkada sekarang bertebaran kutipan di atas.
Jika kaum muslim hanya berpegang kepada argumen teologis semacam itu dalam menentukan kepemimpinan, Indonesia akan sulit menjadi sebuah negara yang demokratis. Islam, yang oleh sebagian aktivis dan pemikirnya dinyatakan kompatibel dengan demokrasi, dalam kenyataannya justru melawan praktek demokrasi itu sendiri.
Maraknya gerakan muslim antidemokrasi itu menunjukkan bahwa sekularisasi politik yang dicanangkan hampir setengah abad itu boleh dibilang tidak mengalami kemajuan yang berarti. Generasi penerus Nurcholish Madjid yang, antara lain, berhimpun di sekitar Yayasan Paramadina dan Jaringan Islam Liberal (JIL) kalah ofensif dibandingkan dengan gerakan seperti Hizbut Tahrir dan Front Pembela Islam. Gagasan-gagasan mengenai pluralisme dan liberalisme tampak kalah pamor dengan khilafah, yang dipropagandakan oleh Hizbut Tahrir sampai ke kampus-kampus itu.
Persepsi kaum muslim mengenai kafir pada umumnya lebih bersifat syari (syariat) ketimbang substantif. Secara administratif, mereka lazim disebut non-muslim, padahal dalam pandangan Allah belum tentu non-muslim itu kafir. Bahkan seorang muslim bisa disebut kafir jika berperilaku zalim, jahat, atau merusak. Maka, jika dalam Al-Quran disebutkan "harus bersikap keras kepada kafir", hal itu bukan menentang sesama kaum beriman yang berasal dari agama-agama, melainkan yang menolak kebenaran atas dasar kezaliman dan kecongkakan. Jika demikian, sejatinya tidak ada "hambatan teologis" bagi kaum muslim untuk memilih pemimpin non-muslim alias "kafir administratif".
Jadi, boleh-tidaknya non-muslim atau "kafir administratif" untuk dijadikan pemimpin, seperti kepala daerah, bukan sesuatu yang mutlak (qathi), misalnya hukumnya haram, melainkan merupakan tafsir atas ayat atau hadis tertentu. Padahal, tafsir selalu berkaitan dengan konteks waktu dan tempat.
Satu hal yang juga perlu diingat adalah sifat kepemimpinan. Kepemimpinan dalam negara demokrasi, termasuk di negara mayoritas berpenduduk Islam seperti Indonesia, adalah bersifat kelembagaan, bukan perorangan. Dalam kepemimpinan yang sifatnya munadhamah atau kelembagaan, kekuasaan tidak melekat kepada seseorang, melainkan pada lembaga yang juga memiliki batas-batasnya sendiri.
*) Tulisan ini terbit di Koran Tempo, Selasa, 10 Mei 2016
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Ruh Zakat
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Teologi Pilkada
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0






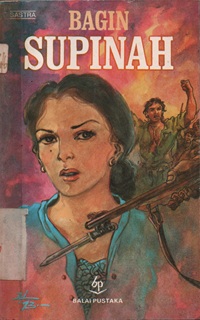

 97
97 0
0






 Berita Pilihan
Berita Pilihan






