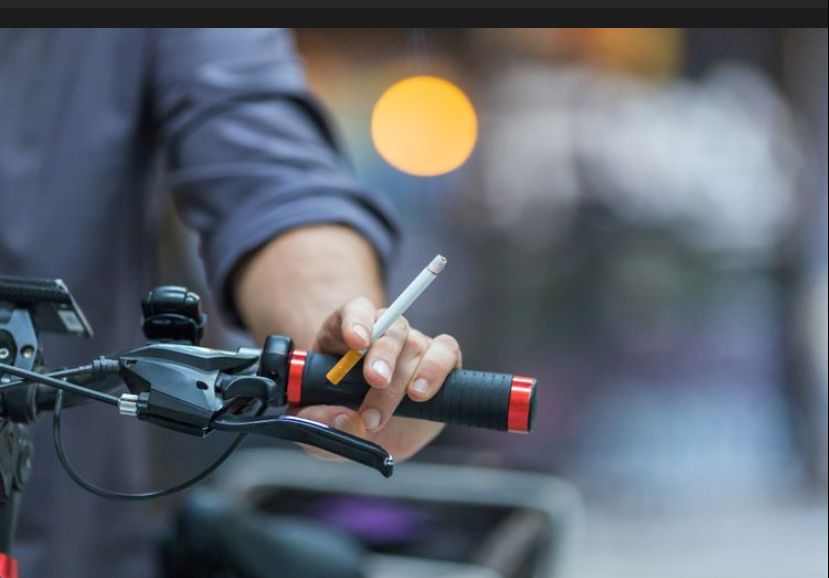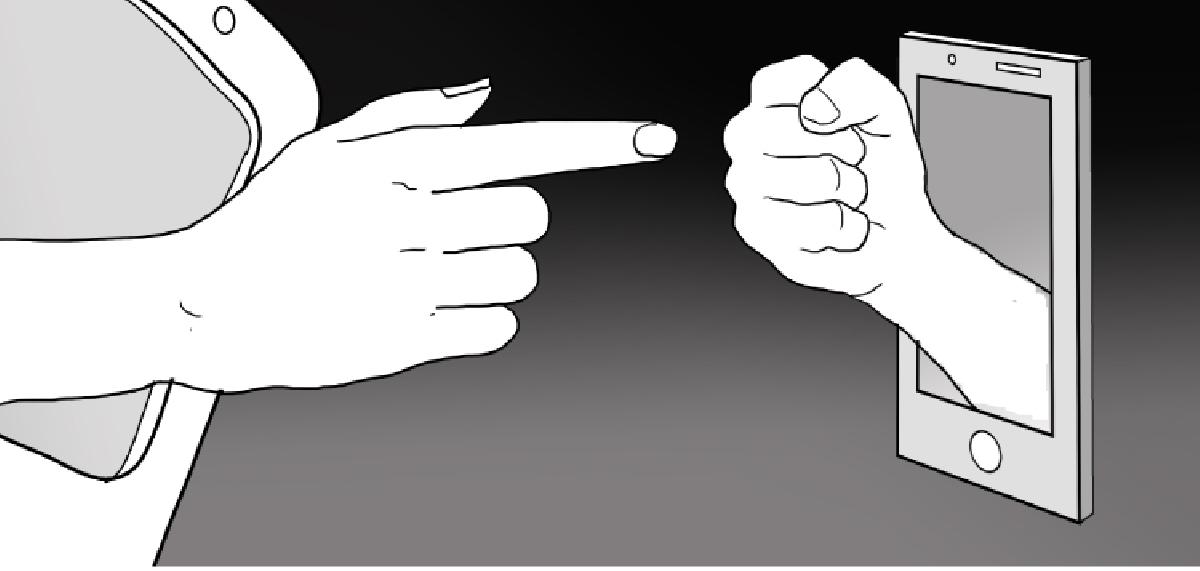Salah satu bahan pangan yang selalu menjadi isu nasional adalah daging sapi. Naiknya harga daging sapi akhir-akhir ini bisa menjadi indikator bahwa suplai daging sapi kita sangat terbatas dibandingkan dengan permintaan konsumen. Harga daging yang naik hingga rata-rata Rp 110- 120 ribu per kilogram di pasar tradisional membuat konsumen dan produsen pangan olahan berbasis daging berteriak. Kemudian Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar harga daging sapi bisa ditekan hingga Rp 80 ribu. Ini kebijakan yang cukup rasional dari sisi konsumen tapi kontroversial di sisi produsen.
Penelitian oleh Widiati (2016) menunjukkan bahwa harga sapi saat ini mencapai rata-rata Rp 45 ribu per kilogram, yang jika dikonversikan ke harga daging mencapai rata-rata Rp 95 ribu per kilogram pada saat keluar dari rumah potong hewan. Artinya, harga daging saat ini masih cukup layak dari sisi produsen. Itu sebabnya mengapa kebijakan Presiden menjadi kontroversial dari sisi produsen dan pedagang daging.
Mengapa harga daging sapi mahal? Kita perlu melihat proses produksinya. Secara umum, budi daya sapi potong di Indonesia adalah mixed farming atau peternakan terintegrasi dengan budi daya pertanian. Hal ini telah dipraktekkan oleh petani kita sejak awal abad ke-19 (Tanner, 2001).
Ini merupakan siasat petani untuk mengatasi keterbatasan lahannya. Para ahli juga menilai bahwa model budi daya ini diyakini menjadi salah satu solusi terhadap percepatan pertumbuh - an penduduk dan penyempitan lahan pertanian. Menurut BPS, pada 2013 terdapat 12 juta rumah tangga peternak dengan 12 juta ekor sapi potong. Ratarata setiap rumah tangga petani memiliki 1-2 ekor ternak. Jika disandingkan dengan kepemilikan lahan petani yang rata-rata 0,34 hektare, hal ini menunjukkan bahwa model peternakan terintegrasi masih menjadi tulang punggung produksi daging nasional.
Dengan lahan yang kecil, para peternak harus memaksimalkan pendapat - an dengan mengoptimalkan keterbatasan sumber dayanya. Lahan sempit itu harus ditanami tanaman pangan, rumput, dan bahkan komoditas lain. Dalam pemeliharaan sapi, kondisi ini memunculkan inefisiensi karena peternak harus mengeluarkan biaya pakan tambahan untuk menjamin ketersediaan pakan. Dengan biaya pakan yang mencapai 70-80 persen dari total biaya pemeliharaan, beban inefisiensi produksi pada akhirnya harus ditanggung oleh petani.
Penelitian FAO pada 1995 menyatakan, dengan keterbatasan itu, peternak harus berkolaborasi dengan unsur lain untuk mengakses konsumen. Di Indonesia, daging-daging sapi yang dipasok petani itu harus melewati rantai pemasar an yang cukup panjang untuk mencapai meja makan konsumen. Dalam kajian dari Kementerian Pertanian, daging sapi membutuhkan rata-rata sembilan titik di saluran pemasaran untuk mencapai konsumen. Jika pada setiap titik mendapatkan margin atau selisih 10 persen dari harga sebelumnya, bisa diprediksi bahwa harga di tingkat konsumen bisa mencapai hampir 140 persen dari harga di tingkat petani.
Harga daging yang mahal di tingkat konsumen menjadi indikator dari dua inefisiensi, yaitu pada saluran pemasaran dan proses budi daya. Jika melihat rata-rata konsumsi daging sapi per tahun yang mencapai 2,6 kg/kapita atau hampir 700 ribu ton atau setara dengan 4 juta ekor per tahun, tanpa adanya terobosan kebijakan dari pemerintah, masalah harga daging mahal, keterbatasan stok, isu impor daging, dan lain-lain akan selalu berulang.
Model pendekatan peternakan terintegrasi dengan skala usaha kecil seperti saat ini bukanlah solusi yang bijak untuk menghadapi tantangan masa depan. Perlu ada batasan minimal skala usaha dari pemerintah agar peternak bisa mengadopsi nilai-nilai efisiensi usaha peternakan. Negara tetangga, seperti Thailand dan Malaysia, sangat berhasil dengan menerapkan nilai-nilai efisiensi tersebut.
Pemerintah juga harus melakukan terobosan dalam mengefisienkan rantai pemasaran dengan merujuk pada efektivitas penyaluran barang dan jasa hingga ke tingkat konsumen (Kotler, 2009). Artinya, panjang- pendeknya rantai pemasaran tidak selalu berkorelasi dengan inefisiensi. Inefisiensi justru muncul ketika di antara titiktitik di rantai pemasaran justru berkompetisi tidak sehat dan menciptakan ketergantungan pasokan daging pada level selanjutnya. Tampaknya, praktek semacam kartel tersebut banyak terjadi di sini. Pemerintah dapat menjadi penyeimbang di pasar dengan peran-peran BUMN di pasar daging sapi untuk mengatasi praktek-praktek tidak fair di saluran pemasaran.
Ahmad Romadhoni Surya Putra, Dosen Fakultas Peternakan UGM
*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi Senin, 18 Juli 2016
Ikuti tulisan menarik Ahmad Romadhoni Surya Putra lainnya di sini.