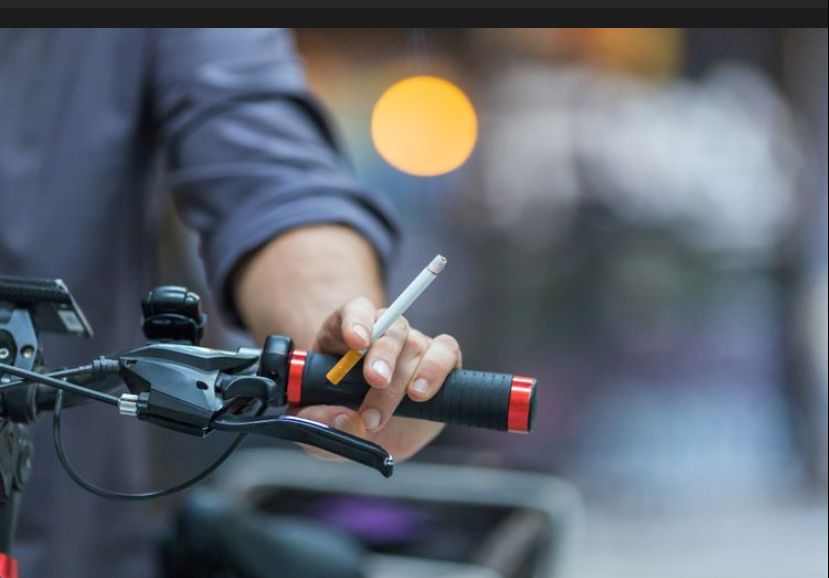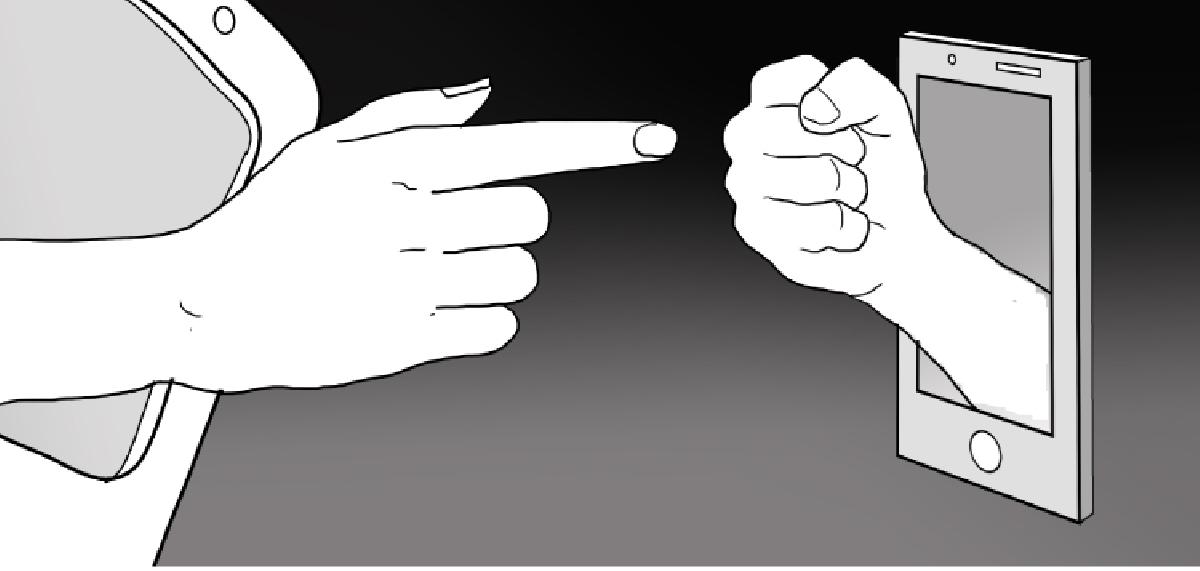Ditulis oleh Husnul Aqib, penggiat komunitas kajian budaya 'Indonesian Culture Academy' (INCA)
Peristiwa terbaru yang menunjukkan parno aneh tentang komunisme ditunjukkan oleh Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Riziq Shihab. Beliau mempersoalkan lambang rectoverso dalam uang keluaran terbaru Bank Indonesia, yang menurutnya memuat lambang Partai Komunis Indonesia (PKI). Meski telah dijelaskan oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini pejabat Bank Indonesia dan Menteri Keuangan, bahwa lambang dalam uang keluaran terbaru tersebut tidak memiliki kaitan dengan lambang PKI dan hanya sebagai pengaman pencetakan uang, Riziq Shihab tetap ngotot mempersoalkannya dengan mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga membawanya ke ranah hukum.
Sebenarnya saya tidak mau nyinyir dengan segala tingkah-polah Habib Riziq Shihab akhir-akhir ini, namun saya terpaksa nyinyir karena kengototan beliau mempersoalkan rectoverso dalam lembaran uang keluaran terbaru itu. Seolah-olah rectoverso tersebut menjadi lambang lahirnya gerakan baru komunisme atau simbol dalam ritual membangkitkan “hantu komunisme” di Indonesia.
Saya terpaksa nyinyir karena selain fobia berlebihan beliau hanya memancing keributan, yang mungkin memang tabiatnya, tingkah-polahnya selama ini membuat kita luput memperhatikan persoalan-persoalan yang jauh lebih substansial baik yang ada di tingkat lokal, nasional, maupun di tingkat global. Sangat disayangkan, energi besar umat Islam disia-siakan untuk merespon hal-hal yang sebenarnya remeh-temeh, sementara persoalan besar di depan kita masih numpuk-berjibun.
Saya juga terpaksa nyinyir terhadap kengototan Sang Imam Besar untuk melihat konteks yang lebih jauh mengenai kenapa komunisme tetap saja ditakuti bahkan setelah 19 tahun lengsernya Orde Baru, orde dimana komunisme dan gerakan-gerakannya dibabat-habis.
Negasi Total
Ketakutan masyarakat terhadap komunisme mirip dengan ketakutan terhadap sosok-sosok hantu. Entah sosok-sosok itu benar-benar ada atau sebaliknya hanya bagian dari mitos, legenda atau cerita rakyat, yang jelas, mereka punya fungsi laten sebagai teror mental, yakni menakut-nakuti.
Begitu pula dengan komunisme di Indonesia hari ini; bukan soal apakah mereka benar-benar masih eksis, namun yang pasti, dalam benak masyarakat sudah lekat suatu bayangan tertentu tentang komunisme. Bayangan itulah yang menanamkan efek teror di alam sadar atau bawah sadar masyarakat. Menyadari bahwa isu komunisme memiliki efek teror, banyak tokoh senang memanfaatkannya untuk meneror mental atau menakut-nakuti masyarakat. Sebab, tidak seperti cerita hantu, isu komunisme memiliki konsekuensi sosial-politik yang besar.
Meski sama-sama ditakuti, perlakuan terhadap sosok-sosok hantu dan komunisme seratus persen berbeda. Sosok-sosok hantu semisal Sundel Bolong, pocong, tuyul, arwah gentayangan, dan lain sebagainya diafirmasi dengan baik misalnya dengan diadaptasi dalam film atau reality show, pertunjukan kesenian - tari Sanghyang misalnya di Bali yang bertujuan untuk mengusir roh-roh jahat – seni gambar, lukis, ukir, hingga dalam sebuah boneka. Di sisi lain, apa yang dialami oleh komunisme dan gerakan-gerakannya adalah negasi total yang dilakukan mula-mula oleh negara lalu kemudian masyarakat.
Penegasian terhadap komunisme dan gerakan-gerakannya bersifat total karena berlangsung dalam semua aspek dan terwujud dalam berbagai bentuk dan cara. Instrumen yang pertama-tama tentu saja pelabelan atau stigma negatif seperti tidak bertuhan, kafir, dan melawan negara. Pelabelan atau stigma itu kemudian berlanjut dengan instrument paling keji, yakni penghilangan nyawa.
Dalam sejarah komunisme di Indonesia, pembantaian terhadap anggota atau simpatisan PKI dilakukan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat yang merasa memiliki legitimasi untuk melakukannya berdasarkan pelabelan atau stigma yang dilekatkan terhadap komunis. Berbagai pelabelan dan stigma buruk itu tetap melekat tidak hanya bagi para anggota dan simpatisan PKI, melainkan juga pada anggota keluarga dan keturunan mereka.
Penegasian total itu juga berlangsung di wilayah ide dan simbol. Misalnya dengan cara menyingkirkan para tokoh intelektual dan sastrawan yang dianggap pro-komunis serta memberangus karya-karya mereka seperti yang dialami oleh Pramoedya Ananta Toer. Nama Pramoedya dan karya-karyanya memang sudah terehabilitasi sehingga kini kita bisa menikmatinya dengan leluasa, namun tidak berlaku bagi palu-arit yang menjadi simbol PKI. Simbol itu tetap menjadi simbol terlarang dan bahkan begitu “ditakuti” oleh sebagian orang.
Walaupun sudah 19 tahun pasca Orde Baru, penegasian total ternyata tidak seratus persen menguap. Sebagaimana diperlihatkan oleh Habib Riziq dan tentu saja oleh orang-orang yang mempercayai beliau.
Yang menarik untuk dilihat dari sikap Habib Riziq itu adalah mengapa sentimen dan ideologi anti-komunis bertahan begitu alot hingga sekarang. Padahal semua orang tahu bahwa komunis telah dimusnahkan sejak permulaan hingga akhir kekuasaan Orde Baru Soeharto. Kalau pun ide-ide “kiri” masih tetap hidup, komunisme sebagai sebuah gerakan sosial-politik dapat dikatan nihil.
Kekerasan Budaya
Wijaya Herlambang (2013) melalui konsep kekerasan Johan Galtung melihat bahwa ada tiga jenis agresi yang dialami oleh komunisme dan gerakan-gerakannya di Indonesia, yakni aksi refresif negara, kekerasan struktural, dan kekerasan budaya.
Jenis kekerasan yang pertama tentu saja didominasi oleh aparatus-aparatus represif negara. Dan, kekerasan struktrural berlangsung dalam aparatus birokrasi dan struktur sosial. Sementara kedua jenis kekrasan tersebut relaif mudah diukur dan diidentifikasi, sebaliknya, hal serupa tidak berlaku terhadap kekerasan budaya meskipun pengaruhnya sangat mendalam dan laten di masyarakat.
Walaupun konsep kekerasan tersebut membagi kekerasan dalam tipologi yang berbeda, ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Dalam kontek agresi terhadap gerakan komunis di Indonesia agresi represif dan struktural negara itu terjadi bukan tanpa fondasi ideologis. Di situlah letak produk-produk kebudayaan yang dalam konsep kekerasan Galtung berfungsi sebagai legitimasi kekerasan langsung dan tidak-langsung negara.
Melalui produk-produk kebudayaan seperti ideologi resmi negara, museum, monument, penataran, hari-hari peringatan, buku-buku, sastra, hingga yang paling terkenal film Penghianatan G30S/PKI penguasa memonopoli narasi tunggal tentang komunis.
Produk-produk kebudayaan tersebut berperan selain sebagai legitimasi dan justifikasi kekerasan represif dan struktural negara, juga mengajarkan dan menceramahi sekaligus mengaburkan pandangan masyarakat untuk melihat represi dan eksploitasi sebagai tindakan yang lumrah atau wajar, bahkan untuk tidak melihatnya sebagai bentuk agresi sama sekali.
Jadi, sementara agresi refresif dan struktural negara berlangsung melalui kekerasan fisik, pengabaian, dan diskriminasi, kekerasan budaya bekerja secara hegemonik untuk mengkonstruksi sekaligus mengaburkan kenyataan melalui term-term agama, ideologi, bahasa, seni, dan ilmu pengetahuan. Cara kerja seperti itu menjelaskan kenapa efek kekerasan budaya bersifat laten. Sehingga, meskipun kekerasan represif dan struktural negara berakhir dengan lengsernya Orde Baru dan kebijakaran rehabilitasi, efek kekerasan budaya sudah terlanjur mengendap. Salah satu ekspresinya adalah comunisphobia.
Mengupayakan Pemahaman
Pola respon negatif terhadap isu-isu komunisme harus sudah diakhiri. Ketakutan berlebihan terhadap suatu fenomena biasanya terjadi karena kurangnya pemahaman dan konstruksi informasi yang salah atau sengaja dikaburkan. Oleh karena itu, apa yang harus diupayakan adalah menempatkan komunisme sebagai diskursus terbuka sehingga akan menumbuhkan pemahaman yang tepat dan adil.
Siapa pun harus berani meninjau kembali rentetan-rentetan sejarah dan harus berani untuk mengatakan apa yang benar sebagai benar, dan demikian juga sebaliknya. Apa yang selanjutnya kita harapkan adalah negara tidak boleh lagi melanggengkan alergi terhadap komunisme dan gerakan-gerakannya.
Bahkan, kalaupun negara tidak berani secara terbuka merehabilitasi sejarah kelam gerakan komunis di Indonesia karena konsekuensi politik, setidaknya negara dengan masukan semua kalangan mulai mengupayakan pembukaan kembali pengajaran diskursus komunisme di sekolah-sekolah dan universitas. Tujuannya tentu saja memberikan peluang bagi munculnya alternatif-alternatif lain atas stigma terhadap komunisme.
Mengupayakan pemahaman bukan hanya upaya penting untuk berlaku adil pada sejarah dan korban kekerasan negara, tapi juga bertujuan untuk menggeser berbagai stigma dan ideologi anti-komunis sehingga tidak perlu lagi muncul persoalan comunisphobia yang tak berdasar, seperti yang diperlihatkan oleh Imam Besar FPI Habib Riziq Shihab.
Pada dasarnya, komunisme memang tidak perlu lagi ditakuti, selayaknya ideologi dan diskursus-diskursus lain. Hanya orang-orang parno yang takut memahami fenomena yang mereka tidak tahu.
Ikuti tulisan menarik Wiranggaleng lainnya di sini.