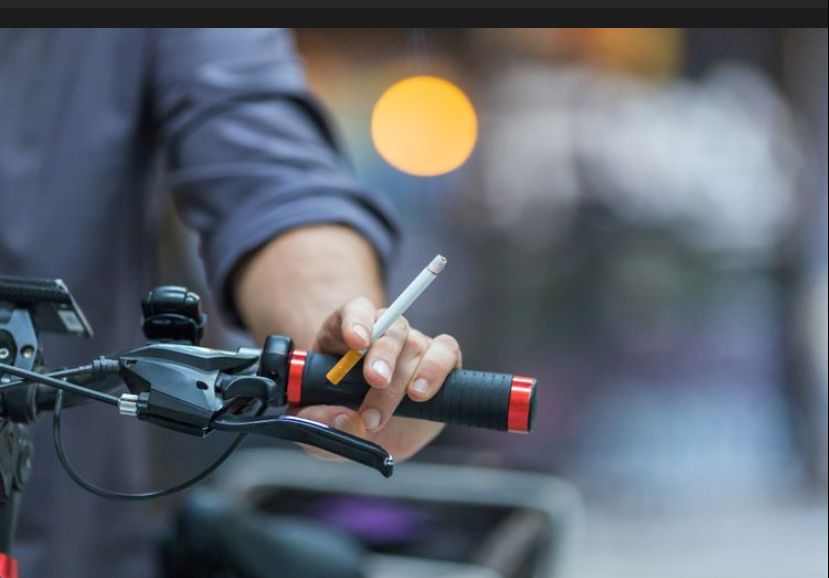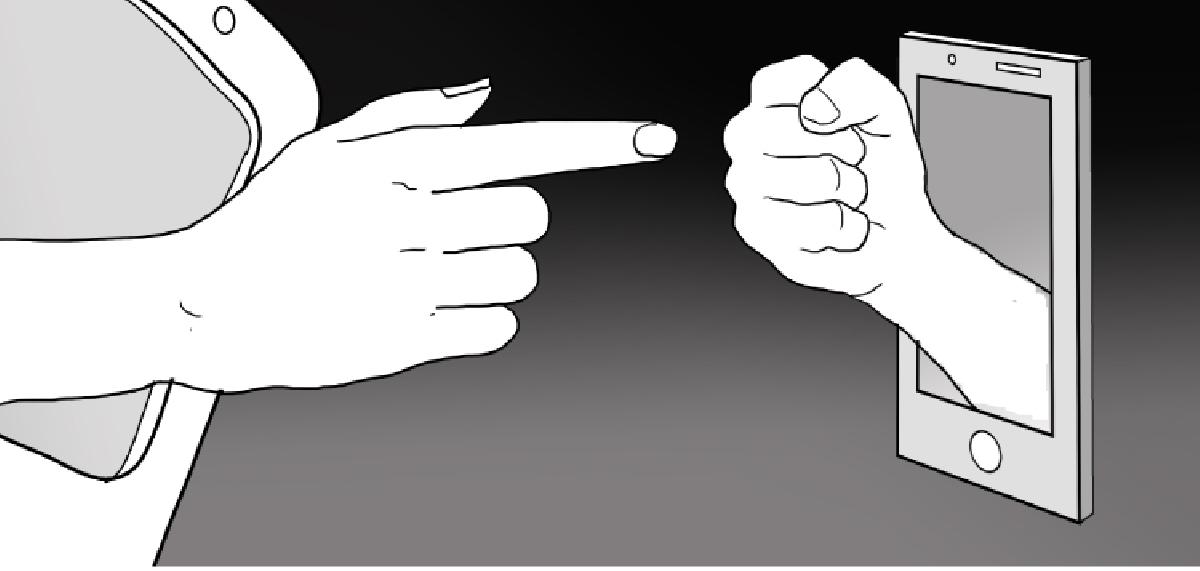Haryo Kuncoro
Direktur Riset Socio-Economic & Educational Business Institute Jakarta
Reformasi perpajakan terus bergulir. Setelah berakhirnya program amnesti pajak, pemerintah bergerak cepat dengan mengajukan rancangan peraturan pemerintah pengganti undang-undang mengenai keterbukaan informasi data keuangan (automatic exchange of information) untuk kepentingan perpajakan. Penerbitan peraturan itu nantinya akan menjadi dasar bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk langsung mengakses kerahasiaan data informasi nasabah yang berasal dari bank, pasar modal atau bursa efek, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya, baik untuk asing maupun domestik.
Konsekuensinya, harta yang selama ini masih "tersembunyi" di luar aset yang telah dideklarasikan melalui program amnesti pajak bisa terlacak Direktorat Jenderal Pajak atas nama pemilik, jumlah nominal, dan lokasi penyimpanannya. Pastinya, sanksi dengan tebusan dan penalti yang lebih berat akan menunggu.
Implementasi peraturan itu niscaya memiliki dampak yang signifikan bagi industri perbankan, terutama dalam upaya menghimpun dana pihak ketiga (DPK). Realisasi target pertumbuhan DPK perbankan yang mencapai 11,94 persen menjadi Rp 5.304 triliun tahun ini bisa jadi berantakan.
Pertumbuhan DPK sangat dibutuhkan untuk mengejar target penyaluran kredit. Mengikuti proyeksi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kredit dalam nominasi rupiah tumbuh 9-11 persen. Perkiraan Bank Indonesia (BI) sedikit lebih optimistis: 10-12 persen. Bahkan kompilasi data Rencana Bisnis Bank mematok pertumbuhan kredit 13 persen tahun ini.
Ketidakseimbangan antara pertumbuhan DPK dan kredit seakan membuka kembali cerita klasik soal kelangkaan likuiditas perbankan dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Fungsi intermediasi menjembatani antara pemilik dana berlebih dan pihak yang membutuhkan dana. Jika kebutuhan debitor lebih besar daripada dana yang terhimpun, bank menyertakan modal sendiri dan/atau mencari sumber pembiayaan lain. Faktanya, perbankan mulai melirik pasar modal lewat IPO dan right issue serta menerbitkan obligasi di lantai bursa untuk memenuhi kebutuhan dana jangka panjang.
Kecenderungan ini akan berimbas pada sektor korporasi. Alih-alih menarik kredit dari sektor perbankan, korporasi juga gencar mencari pendanaan ke pasar keuangan, baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah pun tidak kalah gesit menjual Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutup defisit APBN.
Agar tidak kehilangan DPK, perbankan bersiap-siap menaikkan suku bunga simpanan. Suku bunga kupon obligasi korporasi dan SBN pun tersundul naik karena itu. Akibatnya, terjadi jorjoran suku bunga sebagai imbas kompetisi memperebutkan dana publik antara perbankan, korporasi, dan pemerintah.
Efek lanjutannya adalah perputaran dana hanya terjadi antar-instrumen finansial. Dari sisi pemilik dana, mereka akan selektif dalam menempatkan dananya. Pemilik dana niscaya akan memindah-mindahkan dananya pada instrumen yang memberikan imbal hasil tertinggi dengan tingkat risiko paling rendah.
Hal yang sama juga berlaku pada investor luar negeri. Pasar keuangan domestik akan dipenuhi spekulator oportunis dari luar negeri. Dana "menganggur" asing yang menguasai 65 persen pasar finansial semata-mata mengejar tingkat bunga diferensial yang dengan cepat bisa terjadi pembalikan. Jelasnya, pasar finansial sangat rapuh.
Bank yang telah likuid pun merasa nyaman menyimpan dananya di instrumen portofolio ketimbang menyalurkannya sebagai kredit ke sektor riil. Konsekuensinya, proyeksi pertumbuhan kredit tidak terwujud sehingga target pertumbuhan ekonomi 5,1 persen tahun ini bisa jadi gagal tercapai.
Harus diakui, penyaluran kredit masih menopang 70-80 persen pendapatan industri perbankan nasional. Konsekuensinya, kalangan perbankan domestik senantiasa berupaya mempertahankan margin bunga bersih (net interest margin, NIM) pada level 5-6 persen agar tercapai laba yang optimal.
Dengan struktur semacam ini, biaya overhead lain harus ditutup dari pendapatan berbasis biaya. Ironisnya, jika pendapatan semacam ini dominan, bank lagi-lagi akan menjauh dari fungsi intermediasi. Alhasil, dorongan untuk mengejar NIM dikhawatirkan akan menurunkan kualitas kredit yang tersalur.
Dari sisi nasabah, probabilitas susutnya DPK perbankan kian membesar terkait dengan anggapan sementara anggota masyarakat bahwa harta yang disimpan di perbankan, kendati telah dideklarasikan lewat amnesti pajak, tetap akan dikenai pajak, alih-alih terhadap penghasilan dari aset (seperti bunga, return, atau yield).
Eksekusi peraturan itu berpotensi pula mengganjal minat bertransaksi melalui lembaga keuangan yang mensyaratkan kepemilikan rekening di bank. Boleh jadi masyarakat bersikap konservatif dengan balik lagi bertransaksi secara tunai. Padahal BI, OJK, dan pemerintah gencar mendukung transaksi nontunai.
Dengan berbagai skenario di atas, BI, OJK, Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Keuangan, dan perbankan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan dalam sosialisasi peraturan ini agar nantinya tidak kontraproduktif. Alhasil, dana perbankan di era transparansi data keuangan tetap memberikan sumbangsih bagi pembangunan nasional.
*) Artikel ini terbit di Koran Tempo edisi 17 Mei 2017.
Ikuti tulisan menarik Haryo Kuncoro lainnya di sini.