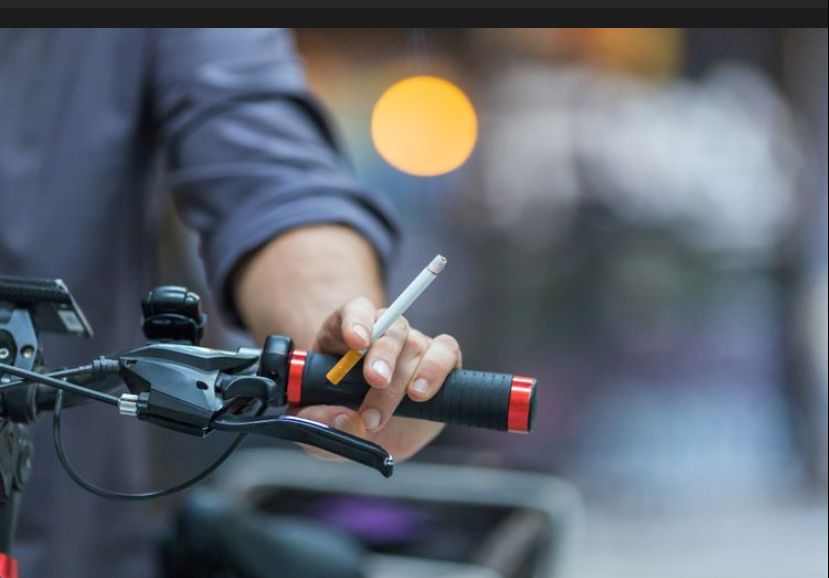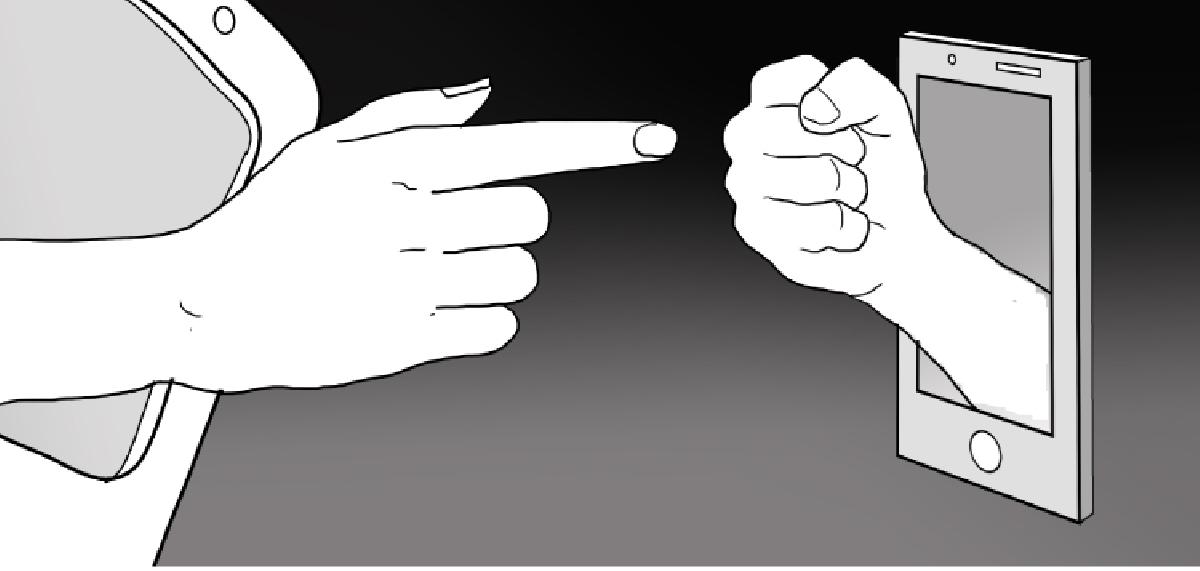Lontaran wacana Mendagri Tito Karnavian tentang perlunya evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah atau pilkada bukanlah hal baru. Pertanyaannya: kemana arah yang diinginkan Mendagri? Memperbaiki sistem pilkada atau mau mengubah sama sekali sistem dan mengembalikannya ke cara lama yaitu pemilihan kepala daerah oleh DPRD [provinsi untuk gubernur maupun kota/kabupaten untuk walikota/bupati].
Jika sistem pilkada diperbaiki lantaran alasan biaya besar yang mesti dikeluarkan, evaluasi tersebut memang perlu dilakukan. Namun, jika sudah diniatkan untuk mengembalikan cara lama pemilihan, maka evaluasi bisa jadi hanya sekedar menemukan alasan pembenaran. Tujuan akhirnyanya: merenggut kembali hak pilih yang sudah berada di tangan rakyat.
Gagasan untuk mengubah pilkada langsung pernah muncul pada masa pemerintahan SBY ketika partai-partai melalui wakilnya di DPR berhasil mensahkan undang-undang baru tentang Pilkada tidak langsung yang disahkan pada September 2014. Namun kemudian Presiden SBY segera menerbitkan Perppu No. 1 Tahun 2014 yang membatalkan undang-undang yang sudah disetujui DPR tersebut. Saat itu, upaya penghapusan pilkada langsung oleh para anggota DPR berhasil digagalkan karena keberpihakan Presiden kepada aspirasi rakyat akan pilkada langsung.
Kini, ide pilkada oleh partai politik sedang diramaikan kembali. Melalui Sekjen Hasto Kristiyanto, PDI-P dikutip oleh media menyatakan setuju dengan usulan Mendagri Tito untuk mengevaluasi pelaksanaan pilkada langsung. Alasannya, sistem pemilu langsung menyebabkan biaya tinggi dan memunculkan korupsi. PDI-P bahkan menyarankan pemilihan umum dikembalikan ke sistem musyawarah mufakat tanpa voting, yang berarti pemilihan kepala daerah dilakukan melalui forum DPRD.
Dapat diduga bahwa musyawarah yang dimaksud akan berlangsung di antara sedikit elite politik. Jikalaupun pembicaraan berlangsung di ruang-ruang sidang DPRD, para anggota DPRD hanyalah menjadi penyambung lidah para elite. Mereka akan cenderung menyuarakan kepentingan elite partai ketimbang suara rakyat. Anggota DPRD yang tidak mengikuti keputusan partai berpotensi untuk diganti. Jadi, siapa anggota DPRD yang berani menyuarakan figur kepala daerah yang dikehendaki rakyat banyak?
Jika pemilihan kepala daerah dikembalikan menjadi tidak langsung, maka para elite bisa sesuka hati menentukan siapa yang mereka kehendaki, sekalipun orang itu mungkin tidak dikehendaki rakyat. Bukankah praktik seperti ini mewakili karakter oligarki? Para elite politik yang menentukan semuanya. Para elite dapat ‘bermusyawarah’ untuk memilih seseorang yang sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan, dalam pemilihan langsung pun, para elite menentukan siapa yang boleh maju ke gelanggang pilkada. Rakyat hanya memilih dari sejumlah pilihan yang sudah disortir oleh partai.
Jika pilkada langsung hendak dikembalikan ke tidak langsung dengan alasan mahalnya biaya, bukankah bisa dilakukan efisiensi dengan cara membenahi komponen-komponen yang membuat biaya tersebut jadi besar. Apakah biaya tinggi itu disebabkan oleh ‘mahar’ seperti yang kerap disebut tapi jarang diungkap, praktik politik uang, maupun jor-joran anggaran kampanye? Jika ya, ini bisa diefisienkan. Alasan lain yang dikemukakan, pilkada langsung cenderung membuat kepala daerah melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang ditanam selama masa pemilihan. Apakah pilkada tidak langsung menjamin terpilihnya kepala daerah yang bersih?
Janganlah karena gubernur/walikota/bupati terpilih korup lantas sistem pilkada langsung yang dikorbankan. Janganlah karena alasan biaya tinggi, sistem pemilihan lama dikembalikan. Ini jelas wujud pikiran yang melompat. Tunjukkan lebih dulu biaya tinggi itu untuk pos apa saja, mengapa hal itu terjadi, dan apakah biaya itu bisa diefisienkan?
Begitu pula, jika alasannya pilkada langsung tidak selalu menghasilkan kepala daerah yang memiliki kapasitas dan kapabilitas, bukankah partai politik harus bertanggung jawab sebab partailah yang pertama-tama menyaring calon kepala daerah dan menentukan siapa yang boleh maju ke gelanggan pilkada. Sangat jarang calon kepala daerah yang maju ke pilkada langsung melalui jalur independen.
Pendeknya, janganlah karena alasan-alasan tadi hak demokrasi rakyat kemudian direnggut dan diserahkan kembali kepada para elite politik. Jika evaluasi dilakukan, lakukanlah secara komprehensif dan libatkan partisipasi rakyat. Jika pilkada langsung diganti dengan sistem lama yang tidak langsung, maka ini kemunduran demokrasi dan merenggut hak pilih rakyat yang telah puluhan tahun diperjuangkan agar terus tegak. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.