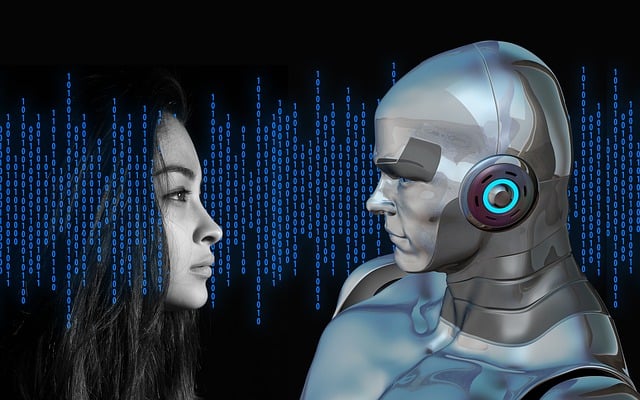Berdasarkan data pada laman MKRI (Putusan PUU), sejak tahun 2006 hingga sekarang, tercatat sebanyak 87 permohonan pengujian konstitusionalitas (constitutional review) atas sejumlah pasal (norma) dalam UU Pemilu. Terdiri dari dua kali atas UU No.23/2003; satu kali atas UU No.42/2008; dan 84 kali atas UU No.7/2017.
Dari seluruh permohonan tersebut, 30(34.5%) permohonan terkait dengan judicial review pasal (norma) “ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden” (presidential threshold) (pasal 9 UU 42/2008, dan pasal 222 UU 7/2017). Sangat mengejutkan, bahwa SEMUA permohonan untuk membatalkan presidential threshold, DITOLAK dan TAK DAPAT DITERIMA (niet ontvankelijk verklaard) sebagian atau seluruhnya oleh Mahkamah.
Permohonan yang ditolak dan tidak diterima oleh Mahkamah karena sejumlah alasan hukum. Pertama, dalil-dalil Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Kedua, substansi permohonan dianggap kabur dan tidak jelas (obscuur libel), serta tidak memenuhi syarat formal permohonan atau premature. Ketiga, Pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan.
Ada sejumlah dalil hukum yang diajukan oleh para pemohon terkait uji konstitusionalitas ketentuan presidential threshold. Bahwa presidential threshold: (1) bertentangan dan melanggar hak konstitusional rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan (memilih atau dipilih) sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat; (2) menciptakan politik oligarki yang menjadikan kekuasaan hanya dikuasai oleh segelintir kelompok elite masyarakat (berdasarkan royalti, kekayaan, ikatan keluarga, pendidikan, perusahaan, partai politik, dll.); (3) tidak dikenal dalam sistem presidensial murni yang diterapkan di Indonesia, dan hanya dikenal dalam sistem presidensial campuran; (4) mendiskriminasi parpol (baru), dan membedakan parpol berdasarkan perolehan kursi (parliamentary threshold). Sedangkan Konstitusi (pasal 6A ayat (2)) memberikan hak sama sama bagi parpol untuk mencalonkan bakal capres dan cawapres.
Dalil hukum lainnya yang diajukan oleh Pemohon adalah, bahwa presidential threshold: (5) menciptakan tawar menawar politik (politik transaksional, politik dagang sapi); (6) BUKAN “open legal policy” melainkan “closed legal policy”, karena syarat pengusulan calon Presiden oleh parpol sudah sangat lengkap diatur dalam UUD 1945 (pasal 6A ayat (3 & 4)); (7) irrasional, karena menggunakan hasil penghitungan Pemilu DPR sebelumnya; dan (8) bertentangan dengan logika keserentakan dimana rakyat bisa melakukan pemilihan Capres dan Cawapres secara “berbarengan/serentak” dengan pemilihan wakil-wakil rakyat (DPR, DPD, DPRD) (pasal 22E ayat (2)) (Putusan 52/PUU-XX/2022).
Semua dalil-dalil hukum yang diajukan pemohon dinyatakan oleh Mahkamah “tidak beralasan menurut hukum”, dan karenanya DITOLAK / TIDAK DITERIMA, walaupun ada di antaranya diwarnai oleh dissenting opinion dari beberapa hakim Mahkamah.
Berdasarkan dokumen putusan Mahkamah, ada 3(tiga) dasar pertimbangan hukum Mahkamah untuk menentukan konstitusionalitas penyelenggaraan Pilpres, yaitu: (1) kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, (2) original intent dari pembentuk UUD 1945, efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, serta (3) hak warga negara untuk memilih secara cerdas.
Atas dasar tiga pertimbangan tersebut, Mahkamah merumuskan 2(dua) pandangan hukum terkait dengan presidential threshold.
Presidential Threshold: Open Legal Policy
Berdasarkan pertimbangan kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan presidensial, Mahkamah berpandangan bahwa ketentuan presidential threshold merupakan bagian dari open legal policy (kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang). Bahwa ketentuan tersebut sebagai pendelegasian lebih jauh dari ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, karena pada pasal tersebut norma terkait persyaratan parpol tidak dirumuskan secara tegas (expressis verbis) dalam UUD 1945 oleh MPR.
Sepanjang pilihan kebijakan tersebut tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan tersebut tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah, dan konstitusional. Kecuali, kalau produk legal policy tersebut—yaitu norma presidential threshold—jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable (Putusan 53/PUU-XV/2017).
Presidential Threshold: Penguatan Sistem Presidensial
Berdasarkan pertimbangan kaitan antara sistem pemilihan dan pilihan sistem pemerintahan ala UUD 1945 serta hak warga negara untuk memilih secara cerdas, Mahkamah berpandangan bahwa desain ideal sistem ketatanegaraan dan pemerintahan ala UUD 1945 (pasca amandemen) adalah “sistem presidensial” (Putusan 53/PUU-XV/2017). Atas dasar itu, Mahkamah berpandangan bahwa Pilpres bukan semata-mata soal perwujudan kedaulatan rakyat (sovereignty of the people), tetapi juga soal rancang bangun sistem ketatanegaraan dan pemerintahan konstitusional, dan dalam konteks ini Pilpres harus memperkuat sistem presidensial.
Presiden sebagai kepala negara dan lambang pemersatu bangsa, tidak hanya ditentukan oleh mayoritas suara rakyat pemilih, akan tetapi juga syarat dukungan dari partai politik yang memiliki anggota di DPR (parliamentary threshold). Tujuannya adalah untuk rancang bangun sistem pemerintahan, serta kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bakal Capres & cawapres dipilih dan diajukan oleh parpol/gabungan, dan capres & cawapres usulan parpol dipilih oleh rakyat. Ada kesimbangan kekuatan dukungan antara rakyat dan DPR (mewakili parpol pendukung) kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Inilah yang menurut pandangan Mahkamah sebagai “rancang-bangun atau desain ideal” (constitutional design atau constitutional engineering) dari sistem ketatanegaraan dan pemerintahan presidensial ala UUD 1945.
Dengan kata lain, Pilpres BUKAN HANYA tentang hak dan kedaulatan rakyat, tetapi juga tentang imbangan, sinkronisasi, dan sinergitas kekuasaan antara “legisatif (DPR)” dan “eksekutif (Presiden)” agar jalannya pemerintahan eksekutif mendapat dukungan dari DPR. Pilpres secara konstitusional merupakan simbiosis-mutualisme antara “hak eksklusif” parpol/gabungan parpol dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, dan “hak sipil dan politik” (civil and political rights) rakyat dalam menentukan siapa yang terpilih menjadi Presiden dan legitimasi rakyat kepada seorang Presiden.
Pilpres juga adalah sangat terkait dengan hubungan antara DPR dan Presiden dan rancang bangun sistem pemerintahan presidensial. Dalam konteks ini maka posisi dan hubungan keduanya adalah sejajar atau setara berdasarkan prinsip hubungan yang saling mengawasi dan mengimbangi (checks and balances), sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.
Secara teoretik, pandangan dan sikap hukum Mahkamah tentang presidential threshold tersebut menganut pemikiran dan konsep keterwakilan dalam sistem representasi proporsional sebagaimana dikemukakan oleh Nohlen (1978). Konsep ini pula yang digunakan oleh Pemerintah (Kemdagri), dan DPR dalam Naskah Akademik RUU tentang Pemilu. Bahwa penetapan ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden (presidential threshold) merupakan bentuk penguatan parpol yang juga berarti memperkuat sistem pemerintahan presidensial. Karena, Presiden dan Wakil Presiden terpilih juga akan memiliki dukungan kekuatan politik di parlemen (Kemdagri, 2016; Komisi II DPR, 2020).
Presidential Threshold: Penyederhanaan Sistem Kepartaian
Berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum, termasuk Pilpres, Mahkamah berpandangan bahwa ketentuan presidential threshold juga berkaitan dengan sistem presidensial.
Menurut Mahkamah, pada umumnya diterima pendapat bahwa penerapan sistem pemerintahan Presidensial “idealnya” disertai dengan penyederhanaan sistem kepartaian. “Ideal” yang dimaksudkan adalah mengacu pada “efektivitas jalannya pemerintahan”. Kalaupun ada negara yang menerapkan sistem presidensial dengan sistem multipartai, tetapi dalam praktiknya tidak menjamin efektivitas pemerintahan. Lebih-lebih dalam masyarakat yang kultur demokrasinya masih pada “tahap menjadi” (in stage of becoming).
Dengan kata lain, dalam pertimbangan hukum Mahkamah, ketentuan presidential threshold dalam UU merupakan cara konstitusional yang bisa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan penyederhanaan jumlah parpol sebagai konsekuensi dianutnya sistem pemerintahan presidensial, “tanpa melalui paksaan norma Konstitusi.” Dalam konteks inilah, menurut Mahkaman, bisa dipahami mengapa MPR di dalam amandemen UUD 1945 tidak memasukkan norma “pembatasan/penyederhanaan jumlah parpol” secara tegas (Putusan 53/PUU-XV/2017).
Apapun hasil judicial review, dengan segala dissenting opinion dan kontroversi yang menyertai putusan Mahkamah, semoga hal ini tidak menyurutkan langkah para pejuang demokrasi untuk terus memperjuangkan demokrasi Indonesia yang menempatkan makna sejati pada kedaulatan rakyat. Semoga pula konstatasi sebagian orang yang menstigmasi Mahkamah tidak lagi menjadi “the guardian of the constitution”, dan telah berubah menjadi “the guardian of the oligarchy” (TribunNews, 08/07/2022) tidak terbukti. Sebab, jika hal ini yang terjadi dan terbukti, inilah awal dari keruntuhan demokrasi Indonesia.
Menarik menelisik studi Diskin, Diskin, dan Hazan (2005) tentang korelat-korelat runtuhnya demokrasi (democracies collapse). Mereka menemukan bahwa dari 4(empat) “variabel institusi” (institutional variables) yang berdampak pada keruntuhan demokrasi, “presidensialisme” (presidentialism) apakah itu sistem presidensial murni atau campuran (semi) “more prone to democratic collapse than parliamentary ones” (prediksi logis = 69.4%). Variabel presidensialisme ini nomor dua setelah variabel “kelemahan konstitusi” (constitutional weakness) (prediksi logis = 71.0%), tetapi jauh di atas dua variabel lainnya, yaitu “proporsionalisme” (proportionalism) (prediksi logis = 59.7%), dan “federalisme” (federalism) (prediksi logis = 51.6%) (p. 299).
Namun demikian, dalam kasus presidensialisme Indonesia diuntungkan oleh sejumlah variabel mediasi (mediating variables). Demokrasi dan stabilitas politik di Indonesia masih bisa terjaga, karena walaupun jumlah partai Parlemen dan partai Non-Parlemen banyak, tidak sampai terjadi fragmentasi yang tinggi (high level of fragmentation) (prediksi logis = 61.3%), dan polarisasi kekuatan politik (polarization) (prediksi logis = 66.1%) yang diprediksi bisa menciptakan ketakstabilan politik. Kondisi ini lebih diuntungkan lagi di Indonesia tidak terjadi ketidakstabilan pemerintahan (governmental instability) (prediksi logis = 75.8%) (p. 299).
Mengacu pada hasil studi tersebut, ada benarnya dasar pemikiran dan pertimbangan hukum Mahkamah bahwa presidential threshold adalah konstitusional, karena dimaksudkan untuk menguatkan sistem presidensial, disertai dengan penyederhanaan sistem kepartaian. Sehingga tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan stabil.
Wallahu a'lam.
Tangsel, 15 Juni 2022
Ikuti tulisan menarik Mohammad Imam Farisi lainnya di sini.