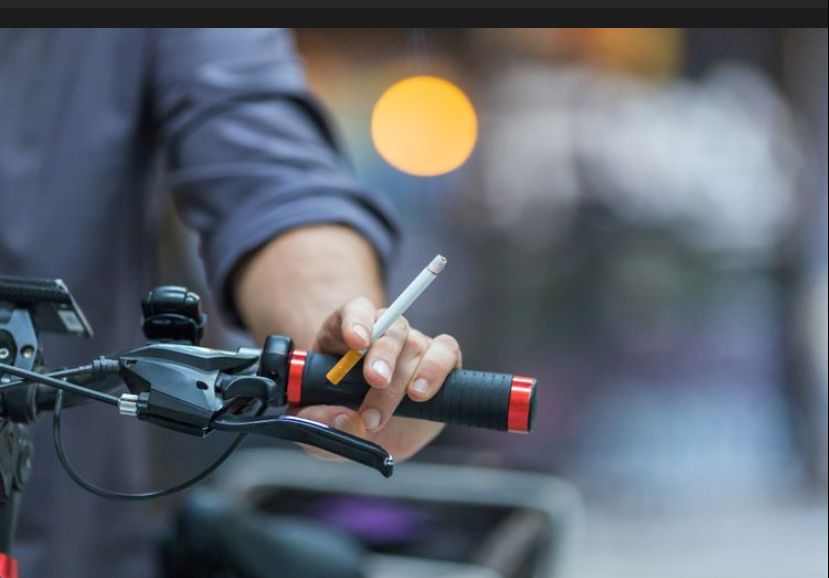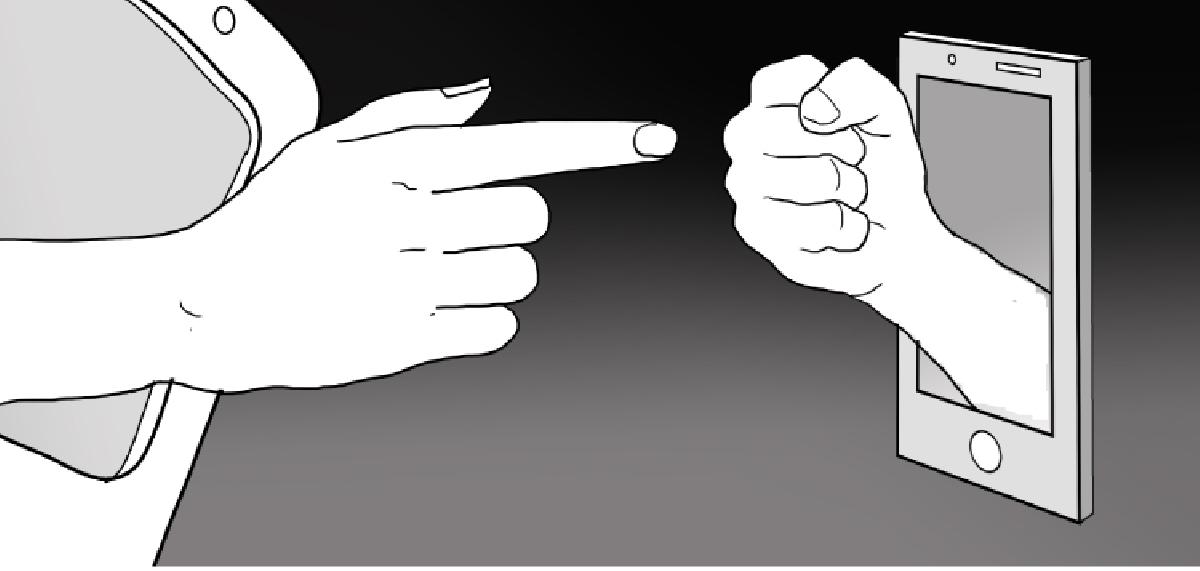Satu fenomena yang menghiasi pemandangan realitas di tanah air adalah semakin intensifnya kegiatan menulis buku biografi oleh para politisi tercinta kita. Tak perlu disebutkan satu persatu siapa dan apa yang ditulis, tetapi kenyataan di Indonesia lagi ada tren rame-rame (ramai-ramai) menulis buku biografi. Adalah satu langka positif ketika bangsa dan negara ini semakin giat menulis dan menghasilkan buku mengingat presentase jumlah buku yang dihasilkan di Indonesia, yakni 8.000 buku/pertahun, tidak sebanding dengan jumlah keberadaan masyarakat Indonesia yang kurang lebih 200 juta jiwa. Kenyataan ini berbanding terbalik dengan negara-negara tetangga kita seperti: Malaysia, Singapura, Jepang, dan lainnya, yang mampu menghasilkan buku melebihi jumlah penduduknya dalam rentang waktu tiap tahunnya.
Fenomena menulis buku sebenarnya telah ada sejak masa pra-kemerdekaan Indonesia. Umumnya, buku yang dihasilkan pada masa itu berisi sorotan dan kritik atas kondisi sosial-budaya bangsa Indonesia yang tengah berada di bawah pasungan kekuasaan penjajah. Hasilnya, buku-buku yang diterbitkan yang dihasilkan memiliki andil dalam membangun kesadaran dan mendorong perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia, di antaranya: Tanah Air (1922) dan Indonesia, Tumpah Darahku (1928) oleh Muhammad Yamin, Layar Terkembang (1936) oleh Sutan Takdir Alisjahbana, Di Dalam Lembah Kehidoepan (1940) oleh Hamka, dan lainnya. Walau buku-buku ini dihasilkan dalam warna sastra, tetapi sedikit banyak berperan dalam membentuk kesadaran masyarakat Indonesia atas realitas yang dialami sekitarnya secara halus melaui bahasa satranya. Di samping itu, ada beberapa tokoh politik dan intelektual yang diketahui menerbitkan bukunya, di antaranya: Tan Malaka dengan karya: Dasar Pendidikan (1921), Tunduk Pada Kekuasaan Tetapi Tidak Tunduk Pada Kebenaran (1924), Naar de Republiek-Menuju Indonesia baru (1924), Semangat Muda (1925), Soekarno dengan karyanya Indonesia Menggugat (1930), Marco Kartodikromo dengan karyanya Tudent Hidjo (1919) dan Rasa Merdeka (1924), Semaun dengan karyanya Hikayat Kadirun (1927), dan lainnya. Masa pasca kemerdekaan (Orde Lama) pun ditandai oleh kehadiran beberapa buku yang terutama ditulis oleh tokoh-tokoh politik dan intelektual seperti: Soekarno dengan karyanya Kepada Bangsaku (1947), Membangun Dunia Yang Baru (1960), Tan Malaka dengan karyanya Pandangan Hidup (1948) dan Madilog (1948), Bakrie Siregar dengan karyanya Jejak Langka (1954), dan lainnya. Demikian pun pada masa Orde Baru yang ditandai kehadiran pelbagai buku yang ditulis oleh tokoh politik maupun intelektual, seperti: Bumi Manusia (1981) dan Jejak Langkah (1985) oleh Pramodya Ananta Toer, Bertarung Demi Demokrasi (1989) oleh Mohamad Jumhur Hidayat, dkk, Bayang-bayang PKI (1996)oleh Studi Arus Informasi, dan lainnya.
Meskipun tiap periode perkembangan bangsa dan negara Indonesia ditandai oleh kehadiran begitu banyak hasil karya buku, namun kehadirannya ini sering kali diwarnai oleh sikap dan tindakan pelarangan terbit atau pemberendelan oleh pihak pemerintah yang berkuasa. Hal ini menjadi satu fenomena yang turut menyertai keberadaan buku-buku yang dihasilkan pada masanya, terhitung sejak zaman kolonial Belanda hingga menemui puncaknya yang paling signifikan pada era Orde Baru di bawa kepemimpinan Soeharto. Lantas pertanyaan Mengapa demikian?
Michael Foulcault dalam pembahasannya tentang “Diskursus” berpendapat bahwa “Kekuasaan dan pengetahuan saling menyatakan antara satu dengan yang lainnya. Tidak ada relasi kekuasaan tanpa dinyatakan dalam hubungannya dengan wilayah pengetahuan.” Artinya bahwa pengetahuan menjadi modal lahirnya sebuah relasi kekuasaan yang mana ada jenjang yang mengetahui menguasi yang tidak tahu. Dalam soal ini, kehadiran buku yang berisikan serangkaian pengetahuan tentunya akan mendistorsi relasi kekuasaan yang telah ada antara penguasa (Pemerintah) dan yang dikuasai (Masyarakat). Setidaknya hal ini memberikan satu pandangan penting tentang eksistensi kehadiran buku dalam arus kekuasaan. Sehingga tak heran pihak yang berkuasa senantiasa mengantisipasi hal-hal demikian, tak terkecuali mengontrol keberadaan buku-buku itu sendiri. Secara implisit hal ini sebagai klaim pengetahuan pihak yang berkuasa adalah kebenaran tunggal dan oleh karena itu ia dipandang layak, kredibel, kompeten, dan berwibawa. Sehingga munculnya pengetahuan-pengetahuan yang mengusung kebenaran lain melalui buku justru berpeluang mensejajarkan atau tahap ekstrimnya sampai membalikkan relasi kekuasaan yang telah ada. Yang layak menjadi tak layak, yang kredibel menjadi tak kredibel, yang berkompeten menjadi tak kompeten, dan berwibawa justru dipandang sebelah mata. Karenanya apakah masih layak berkuasa? Tidak bukan.
Kenyataannya, ketika buku-buku diberedel maka pengetahuan-pengetahuan yang mengandung kebenaran tertentu dibungkam. Muncul kecurigaan yang mendalam kenapa harus diberedel. Lantas hal ini kian memperkuat keyakinan bahwa yang dibungkam adalah satu kebenaran yang mutlak ditakutkan mendeskonstruksi kondisi laten yang telah mapan. Apalagi jika buku-buku tersebut ditulis dalam penderitaan penulis di bawah tekanan penguasa pemerintah kala itu, bukannya semakin memperkuat persepsi kita terhadap kebenaran yang dikandungnya? Tentunya ini menjadi satu bentuk pemikiran logis dan sederhana, tetapi justru menjadikan buku sebagai media penyampaian kebenaran. Poin penting mengenai esensi keberadaan buku pada masa-masa itu adalah kandungan kebenaran yang tertulis di dalamnya sehingga saking disegani.
Bagaimana dengan masa era reformasi?
Kita tentunya masih momen peralihan pemerintahan Orde Baru (1966-1998) di bawah kepimpinan Soeharto kepada masa pemerintahan reformasi yang tengah diperjuangkan kala itu. Demonstrasi, orasi, saling serang, pengrusakan, pelecehan seksual, penangkapan, dan bahkan pembunuhan mewarnai beberapa titik tempat utama, yaitu: Ibu Kota Jakarta, Surakarta, dan Medan. Segera setelah kejadian berlalu, maka munculnya upaya pengusutan dan penyelidikan dengan dalil adanya tindakan kriminalitas dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Lantas pihak militer menjadi sorotan utama sebagai pihak pengamanan situasi dan kondisi kekacuan. Memang akhirnya, ada tindak penegakan hukum berupa pengadilan militer. Tapi itu hanya secuil dari upaya penyingkapan dalang yang besar dan kompleks. Selanjutnya, opini publik mulai bergulir di antara masyarakat Indonesia. Sebagai upaya antisipasi, pelaku-pelaku sejarah pristiwa 5-15 mei 1998 punya versi tersendiri tentang apa yang terjadi. Terlepas kenyataan benar demikian atau sebaliknya, memang masing-masing pihak membangun upaya pencitraannya tersendiri dan itu salah satunya dilakukan melalui penulisan dan penerbitan buku. Di antaranya: Wiranto: Bersaksi di Tengah Badai (2004) oleh Taufik Abdullah dan Aidul Fatriciada Azhari, Detik-Detik Yang Menentukan : Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi (2006) oleh B. J. Habibie, Prabowo Sang Kontroversi : Kisah Penculikan, Isu Kudeta, dan Tumbangnya Seorang Bintang (2006) oleh Erros Djarot, Prabowo dari Cijantung ke Istana (2009) oleh Femi Adhi Soempeno, dan lainnya.
Masa pemerintahan selanjutnya, yakni Gus Dur dan Megawati kontroversi klaim kebenaran melalui penulisan buku tidak begitu nampak, namun bukan berarti tidak sama sekali. Di sini, bagaimana kita melihat kehadiran buku-buku bertemakan track record sejumlah figure public kita, terutama para politisi, sebagai satu klaim kebenaran atas realitas sosial yang dilakoni dan dialaminya, yang juga menyinggung satu perihal yang sama dengan versinya masing-masing. Kenyataannya sekarang, sejumlah politisi kita pun rame-rame menulis dan menerbitkan buku terutama buku biografinya, entah hasil tulisan sendiri maupun tulisan orang lain dengan tetap merujuk pada poin of view narasumber sendiri. Kisruh politik dalam tubuh partai demokrat melahirkan buku Tumbal Politik Cikeas (2013) oleh Ma’mun Murod Al-Barbasy dan Selalu Ada Pilihan (2014) oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Ada juga buku Indonesia di Jalan Restorasi: Politik Gagasan Surya Paloh (2013) oleh Willy Aditya, Jokowi: Politik Tanpa Pencitraan (2012) oleh Ajianto Dwi Nugroho dan Bimo Nugroho, dan masih banyak lainnya buku yang ditulis baik tentang kehidupan tokoh politisi tertentu, keberhasilannya, ide / gagasannya, dan sebagainya.
Sebagaimana yang diberitakan oleh media online BeritaJogja.co.id (4/11/2013), dosen sekaligus pengamat Politik UGM, Ari Dwipayana menyatakan bakal banyak buku yang menceritakan tentang partai politik atau figure di dalamnya. Menurutnya, akan banyak sekali tokoh partai politik yang akan membuat buku. Artinya, buku menjadi sarana pencitraan partai politik atau tokoh politik dengan tujuan tertentu. Terlepas dari benar-tidaknya kesan demikian, masyarakat Indonesia yang mampu berpikir secara kritis tentunya memiliki penilaiannya sendiri. Dibandingkan dengan masa-masa pemerintahan sebelumnya, kehadiran buku lebih mendapat ruang dengan alasan bahwa sebagai negara demokrasi, kita punya hak untuk aktif dan bebas berpendapat sejauh berdasarkan kenyataan dan tidak merugikan orang lain.
Hal yang paling ditakutkan adalah ketika kita lebih mendapatkan ruang berekspresi, lantas pengungkapan ide / gagasan / pendapat sungguh berlandaskan kebenaran? Dalam filsafat kebenaran terdapat beberapa kategori kebenaran dan dalam konteks ini, kita lebih cenderung mengamini kebenaran korespondensi, yaitu kebenaran yang diukur sejauh tingkat kesesuaiannya dengan realitas kehidupan. Oleh karena itu, muncul tanda tanya besar, apakah memang benar buku-buku terutama yang bertemakan biografi para politisi berdasarkan kenyataannya? Hal mau disoroti di sini adalah menyangkut track record atau sepak terjang para politisi kita.
Tak dapat dipungkiri bangsa dan negara kita tengah berada dalam situasi krisis kepercayaan dan aspek pengalaman menjadi satu-satunya ukuran kepercayaan kita dan bukan pemikiran idealis. Masyarakat Indonesia sudah capek dengan jajnji-janji politik. Berangkat dari aspek kebenaran maka setidaknya ada 2 poin penting menanggapi fenomena membuat buku oleh para politisi kita dewasa ini. Pertama, jika apa yang ditulis benar seturut kenyataan, maka tidak menjadi satu persoalan dan upaya mendapat penilaian positif karena dilihat sebagai satu keteladanan. Sebaliknya, jika menyimpang dari kenyataan sebenarnya, maka menjadi realitas kehidupan para politisi yang sungguh memprihatinkan dan memuakkan. Hal ini dikarenakan kebenaran oleh para politisi ibarat tanah liat yang sesuka hati diolah menjadi bentuk apapun. Lebih ironisnya lagi, jika pengetahuan umum masyarakat tentang kualitas para politisi kemudian dikonfrontasikan dengan apa yang dituliskan dalam buku mereka. Masyarakat selanjutnya dipaksa jadi penonton pasif walaupun sudah mengetahui dan memahami kebenaran sejatinya terkait apa yang disampaikan melalui buku mereka.
Masyarakat menjadi penonton pasif karena memang tak berdaya dan kuasa meluruskan kebenaran akibat tekanan kekuasaan penyelenggara negara ini. Analogi yang lebih jelasnya masyarakat seperti penonton bola kaki yang tak punya kuasa mengendalikan bola kebenaran di lapangan kehidupan sosial, kecuali para pemain politisinya yang mengendalikan bola kebenaran sesuka hati dengan cara dan strateginya. Salah sekalipun, masyarakat sebagai penonton tidak dapat berbuat banyak karena adanya aturan kewenagan dan relasi kekuasaan yang sedemikian kentalnya. Kedua, ketika masyarakat dalam kebimbangan, keragu-raguan, dan bahkan tidak tahu, maka buku oleh para politisi juga sangat berpeluang menjadi upaya membangun pengetahuan dan pemahaman demi tujuan dan kepentingan tertentu. Hal ini selanjutnya kita sebut dengan pencitraan.
Kekuasaan bagi politisi menjadi penting dalam statusnya. Kekuasaan itu lahir dari relasi antara aspek “know” dan “don’t know”, yang tidak berpengetahuan melegitimasi kekuasaan yang berpengetahuan untuk berkuasa-kontrak sosial. Hingga demikian karena pengetahuan itu dipersepsi mengandung kebenaran dan melahirkan kepercayaan. Mistisisme kehadiran buku ini juga dapat kita lihat / buktikan sepanjang sejarah kelahiran dan pembentukan negara Indonesia. Para tokoh-tokoh masa itu menggunakan buku sebagai sarana pengungkapan ide / gagasan / pendapat mereka tentang realitas di sekitarnya dan memang itu satu kebenaran nyata. Celakanya, asas pemikiran demikian selanjutnya diadopsi dan diterapkan oleh politisi kita dewasa ini pada masyarakat lewat buku yang berisi serangkaian pengetahuan yang entah benar atau tidak, guna melahirkan kepercayaan masyarakat agar melegitisimasi kekuasaan atau upaya pencapaian kekuasaan. Buku bagi politisi tentunya sangat berpeluang sebagai klaim kebenaran, guna memperoleh kepercayaan dan simpati masyarakat.
Maka dapat dikatakan, dengan menggunakan realitas tingginya kepercayaan masyarakat terhadap kebenaran yang terkandung di dalam buku, maka politisi kita mencoba mempengaruhi pemahaman masyarakat sekalipun yang disampaikan adalah suatu kebohongan, melalui buku-bukunya. Ini tentunya memperkosa mistisisme kehadiran buku di tengah-tengan masyarakat. Konsekuensi lain dari realitas ini, yaitu ketika para politisi kita rame-rame menulis untuk ramai-ramai mencitrakan diri dan kelompoknya, lantas masyarakat harus mempercayai yang mana jika ada satu tema yang sama, namun diceritakan menurut versi masing-masing. Ketika ada kebenaran berbeda tentang satu realitas yang sama, maka masyarakat akan lebih cenderung kritis melihat masing-masingnya sebagai klaim-klaim kebenaran.
Akhir kata, Yasraf Amir Piliang dalam bukunya Hantu-Hantu Politik dan Matinya Sosial (2003) menulis: “Secara substansial yang kita saksikan di dalam panorama kehidupan masyarakat kita adalah bercampurnya citra dan kebenaran, representasi dan realitas, tiruan dan asli. Semua ini menggiring kita untuk hidup dalam dunia bayang-bayang, fatamorgana, dan fantasmogaria.” Jika kita tidak belajar hidup dari kebenaran maka hidup kita akan selalu dalam fantasi sosial yang dangkal dan tidak substansial merubah kehidupan bangsa dan negara tercinta ini. Selama kebenaran itu dipermainkan layaknya bola yang digulir ke sana dan kemari, ibarat tanah liat yang mudah dibentuk sesuka hati, maka selama kita akan hidup dalam krisis kepercayaan. Kita mesti ingat bahwa sejuta problem di bangsa dan negara ini berpangkal dari krisis kepercayaan. Setidaknya para penyelengga pemerintahan ini mesti sadar bahwa mereka dipercayakan akan satu kekuasaan karena kebenaran yang mereka junjung tinggi. Jangan sampai kepercayaan itu hilang hanya karena kepentingan pribadi dan kelompok. Indonesia dibangun atas kebenaran penderitaan karena bangsa penjajah dan sebagai sesama manusia menuntu kemerdekaan sehingga lebih manusiawi. Sebagai generasi pengisi kemerdekaan itu, kita jangan lagi membuat kebenaran bahwa bangsa dan negara ini menderita oleh karena kebohongan penyelenggaranya. Meminjam ungkapan dalam film Senandung di Atas Awan “Ko Stop Tipu-Tipu ewww”.
Ikuti tulisan menarik Emanuel S Leuape Blonda lainnya di sini.