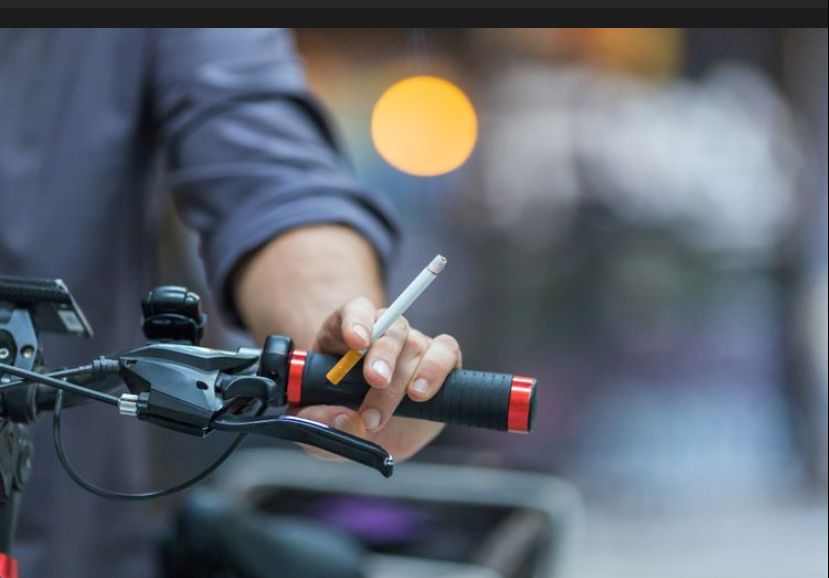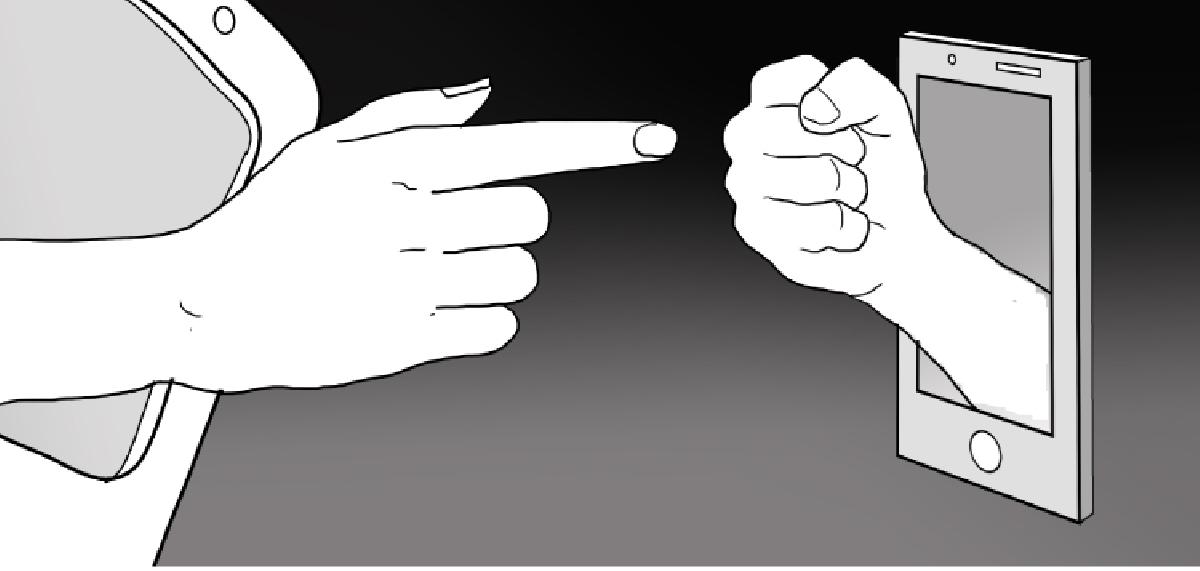Di suatu tempat yang tidak diketahui dengan pasti di mana lokasinya, hakim-hakim memutuskan perkara dari puncak bukit yang disebut 'tanah tinggi'. Perkara-perkara tersebut adalah masalah sosial yang terjadi di 'tanah lembah', area pemukiman penduduk di bawah lereng bukit. Meskipun tidak pernah turun ke tanah lembah, hakim-hakim itu meyakini bahwa segala keputusannya pasti benar. Sebabnya hanya merekalah yang dapat melihat tanah lembah secara utuh. Luasnya, posisinya di antara gunung-gunung, aktivitas masyarakatnya, serta sejarahnya. Dari kejauhan, hakim-hakim melihat segalanya.
Putusan hakim-hakim itu disebut sabdaraja. Diteriakkan melalui pengeras suara yang disebut 'corong langit'. Sebuah alat pengeras suara yang mengeluarkan bunyi gemuruh yang dahsyat, memekik, menyerupai teriakan yang dibacakan dengan lantang dari atas bukit. Vokal, kata, artikulasi dan intonasinya tegas. Lugas. Meskipun sampai ke tanah lembah, suara itu hanya terdengar sayup-sayup. Suara lirih yang terkesan tumpang tindih. Menyerupai sebuah gema. Atau gumaman yang tak jelas artinya. Berdengung. Seperti suara tawon yang rumahnya diusik beruang madu.
Kadang penduduk tanah lembah sampai tidak bisa membedakan apakah itu bunyi sabdaraja atau hanya dengungan suara tawon. Ngung-ngung nya mirip. Buzzing-nya sama-sama tidak jelas. Tiap corong langit berbunyi, yang terdengar di telinga penduduk tanah lembah hanyalah kebisingan yang lama-lama memudar. Pada siang hari beberapa kali terdengar potongan kata, "sejahtera", "demokrasi", "tuhan" dan deretan kata lainnya yang tidak begitu jelas.
Namun, bagi orang yang tidak tidur (di tanah lembah ada beberapa orang yang menghabiskan malamnya untuk bermunajat kepada tuhan) di malam harinya, kata-kata tersebut jika benar-benar didengarkan di kesunyian malam berbunyi "sejahatnya", "korporasi" dan "tuhan-tuhan". Orang-orang di tanah lembah sudah terbiasa mendengarkan sabdaraja yang berubah jika waktunya berbeda. Antara siang dan malam kata-kata tersebut berbalik 180 derajat. Biasanya kata sebenarnya, yang asli, sengaja dikumandangkan ketika orang-orang terlelap tidur.
Pernah suatu kali seorang pemuda dari tanah lembah protes naik ke atas bukit untuk menanyakan mengapa kata-kata tersebut tidak konsisten dan selalu berubah saat malam hari. Hakim-hakim menjawab bahwa kata-kata itu mengalami 'morfologi etimologi dan epistimologi leksikal-gramatikal dalam bingkai kebudayaan' yang lazim dialami juga oleh kata-kata lain dalam bahasa asing, di bangsa mana pun. Pemuda itu diyakinkan kalau perubahan arti dan makna kata adalah hal yang wajar terjadi di semua negara.
Hakim-hakim mengambil contoh kata 'langka' berubah menjadi 'terbatas', 'harga naik' jadi 'penyesuaian', 'utang' jadi 'pembiayaan', 'instan' jadi 'efektif-efisien' dan lain sebagainya. Namun pemuda itu bersekukuh bahwa kata, seharusnya mewakili arti dan arti mewakili makna yang tidak bisa disembarang-tukarkan. Ia bersikeras bahwa setiap kata harus sesuai dengan artinya. Ia sampai mengutip pendapat Zhuangzi, filsuf terkenal dari Cina, ketika ditanya apa yang pertama-tama akan dia lakukan kalau jadi penguasa dunia. Jawab Zhuangzi, "Membenahi kata-kata."
Sampai sekarang, tidak ada yang tahu apa itu yang dimaksud 'morfologi etimologi dan epistimologi leksikal-gramatikal dalam bingkai kebudayaan'. Karena pemuda itu tidak pernah kembali turun ke tanah lembah. Ada yang bilang bahwa pemuda itu sudah menjadi hakim. Ada juga yang bilang kalau pemuda itu sebenarnya tidak pernah naik ke tanah tinggi, tetapi melarikan diri. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, sabdaraja siang itu berbunyi, "Gugur, jadi pahlawan dalam suatu aksi." sedangkan di malam harinya, orang-orang yang tidak tidur mendengar suara, "Mati, jadi tahanan dan dieksekusi."
Pernah suatu kali, di suatu siang yang amat terik, terdengar bunyi, "Setiap pemberian harus dibalas terima kasih" dari atas bukit. Penduduk tanah lembah yang sudah terbiasa terhadap pembalikan kata-kata sengaja tidak mengindahkan suara tersebut. Mereka semua sepakat untuk menunggu sampai malam. Untuk bersama-sama mendengarkan kata apa yang muncul ketika matahari sudah terbenam. Pasalnya, para penduduk menduga kata-kata dari tanah tinggi akan berubah total ketika sudah tidak ada cahaya matahari. Di dalam gelapnya malam, akhirnya muncul suara dari corong langit, "Setiap pemberian harus dibalas terima kasih" yang diulang-ulang sampai beberapa kali. Di hari itu, untuk pertama kalinya sabdaraja berbunyi sama antara siang dan malam hari.
Di tengah keheranan, penduduk tanah lembah pun mulai ragu. Jangan-jangan selama ini mereka yang salah dengar. Selama ini antara siang dan malam sebenarnya sabdaraja itu sama. Dan orang-orang yang tidak tidur mulai disalahkan. Mereka dianggap pembohong dan dituduh menyesatkan pikiran penduduk agar tidak mempercayai hakim-hakim. Orang-orang yang tidak tidur dipojokkan, dihina, dan diusir dari tanah lembah.
Semenjak kepergian mereka, kepercayaan penduduk tanah lembah terhadap hakim-hakim mulai tumbuh. Setiap kata yang terdengar di siang hari mereka yakini berbunyi sama dengan kata di malam hari. Maka dari itu, sudah tidak perlu ada orang yang tidak tidur untuk mencari kebenaran kata di malam hari. Sejak mereka meyakini kata-kata di siang maupun malam itu sama, mereka tidur sebelum matahari terbenam. Karena bagi mereka, tidak tidur di waktu malam sudah tidak ada gunanya lagi.
Hingga suatu saat, tepat di tengah malam, tanah lembah diserbu oleh orang-orang barbar. Jangan dibayangkan bahwa kaum ini adalah kumpulan orang-orang primitif yang berperang menggunakan tongkat kayu dan batu. Tidak, orang-orang barbar ini adalah kaum berwajah elok nan rupawan, kata-katanya manis, dan tindak tanduknya tidak mencerminkan 'barbar' sama sekali.
Keesokan paginya, penduduk tanah lembah kaget bukan main melihat mereka, orang-orang berwajah malaikat ini menguasai area persawahan. Orang-orang barbar ini secara meyakinkan dapat menunjukkan bahwa penguasaan mereka atas sawah tanah lembah sudah disetujui hakim-hakim di atas bukit. Mereka tunjukkan selembar kertas yang telah ditandatangani oleh dua belas orang hakim. Kata-kata dalam kertas itu praktis tidak terbaca, banyak coretan sana-sini serta banyak istilah bahasa asing yang penduduk tanah lembah tidak mengerti artinya.
Baru belakangan ini diketahui kalau kertas itu memang ditulis dalam bahasa ketidakjelasan, bahasa orang-orang barbar. Dan lucunya, baru sejak saat itulah penduduk tanah lembah tahu kalau jumlah hakim di atas bukit adalah dua belas orang.
Karena hakim-hakim telah memutuskan bahwa tanah persawahan dikuasai oleh orang barbar, maka penduduk tanah lembah menerimanya. Hasil sawah diambil seluruhnya untuk kemakmuran orang barbar. Tidak ada sisa untuk penduduk tanah lembah. Untuk bertahan hidup, mereka harus mengemis dan mengais-ngais sisa makanan kaum barbar. Beberapa orang yang masih memiliki harga diri, memilih untuk memunguti butiran beras yang jatuh dari berjuta-juta ton hasil penen yang diangkut oleh kendaraan raksasa. Sebuah kendaraan yang sebenarnya didesain untuk memastikan tidak ada satu pun butir beras yang jatuh. Kali ini tidak ada protes. Tidak ada pemuda yang naik ke atas bukit untuk menggugat. Juga tidak ada lagi orang-orang yang tidak tidur untuk mendengarkan suara asli dari tanah tinggi.
Tujuh puluh delapan tahun kemudian. Demi asas kesejahteraan dan demokrasi yang berlaku secara global. Serta demi pengabdian kepada tuhan. Orang barbar dengan ijin hakim-hakim bersepakat untuk mengadakan bagi hasil dengan penduduk tanah lembah. Namun, agar harga tidak mengalami banyak penyesuaian, sehingga mengakibatkan stok beras menjadi terbatas maka diperlukan sebuah pembiayaan.
Pembiayaan ini adalah ongkos yang harus dibayar untuk operasional sistem bagi hasil agar efektif dan efisien. Pembiayaan ini atas nama tanah lembah dan dibebankan secara rata kepada tiap orang penduduk tanah lembah. Tidak lupa, orang barbar selalu mengingatkan bahwa pembiayaan ini semata-mata dilakukan demi terjaminnya asas kesejahteraan dan demokrasi yang disinggung di awal tadi.
Setelah tiap kepala dibebani beban pembiayaan di luar batas kemampuannya, sistem bagi hasilpun berjalan. Bukan main senangnya penduduk tanah lembah karena mereka, yang sebelumnya harus mengemis, mengais-ngais makanan dan memunguti butiran beras, kini telah demokratis dan sejahtera. Mereka mendapat segenggam beras gratis dari tiap satu ton beras yang dipanen oleh orang barbar di tanah lembah. Bahagia hati mereka mendapatkan makanan pokok dengan tidak perlu bekerja. Hanya perlu tanda tangan untuk bersedia menanggung pembiayaan.
Begitulah sistem bagi hasil yang mereka sepakati sebelumnya. Mereka bersorak-sorai tanda bahagia. Akhirnya mereka dapat memperoleh segenggam beras secara cuma-cuma. Mereka berterima kasih kepada orang barbar karena pemberiannya, sesuai sabdaraja terakhir, "Setiap pemberian harus dibalas terima kasih". Rencananya, mereka juga akan berterima kasih kepada hakim-hakim yang telah mewujudkan kesejahteraan dan demokrasi di tanah lembah.
Ramai-ramai mereka naik ke atas bukit sambil membawa sekantung beras yang mereka punya sebagai wujud rasa terima kasih. Sesampainya di atas, sebelum masuk ke tanah tinggi mereka menoleh ke belakang dan melihat luasnya tanah lembah yang tak terkira. Mereka ingin melihat betapa hijau hutan dan betapa biru lautannya, seperti yang diceritakan nenek moyang mereka.
Tetapi dari kejauhan, yang tampak hanyalah kerakusan dan keserakahan manusia. Dalam wujud eksploitasi sumber daya yang begitu masif. Mereka menyaksikan sendiri bagaimana alam tanah lembah telah dirusak. Ternyata tidak hanya ada persawahan, tetapi juga ada tambang-tambang. Tanah dikeruk, dihabisi, dan ditinggalkan begitu saja. Hewan-hewan telah berubah wujud menjadi bangkai. Hutan ditebang dan kayu diangkut ke negeri seberang menggunakan kapal-kapal raksasa yang menumpahkan limbah ke lautan. Hijau hutan dan birunya lautan tidak mereka temui. Hari itu, di atas bukit, hanya ada suara tangis dari penduduk tanah lembah.
Sambil menangis mereka memasuki tanah tinggi untuk menggugat hakim-hakim. Sesampainya di tanah tinggi, di puncak bukit itu hanya ada sebuah kursi kosong dan sebuah corong langit yang diselimuti debu, seolah-olah sejak semula tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka kebingungan mengapa hanya ada satu kursi. Bukankah hakim-hakim di tanah tinggi berjumlah dua belas? Ke mana perginya hakim-hakim?
Lalu yang tertua di antara mereka mencoba mengingat kembali. "Sudah tujuh puluh delapan tahun sabdaraja tidak berbunyi," begitu katanya. Suara dari atas bukit itu tidak pernah terdengar lagi semenjak kedatangan orang barbar di tanah lembah.
Dalam ingatannya yang telah samar dimakan usia, dia mengatakan bahwa malam itu, orang barbar yang menguasai sawah di tanah lembah berjumlah dua belas orang. Ia juga ingat kalau dulu, suara sabdaraja itu mirip dengan dialek orang barbar yang menguasai sawah mereka. Semakin terasa wajar jika sabdaraja itu hanya terdengar seperti dengungan atau gumaman tanpa arti, karena diucapkan dalam bahasa ketidakjelasan, bahasanya orang barbar yang tidak dapat penduduk tanah lembah pahami hingga saat ini.
Hari itu, di tanah tinggi, tidak ada hakim-hakim. Tidak ada sabdaraja. Hanya ada kesedihan.
Ikuti tulisan menarik Bryan Jati Pratama lainnya di sini.