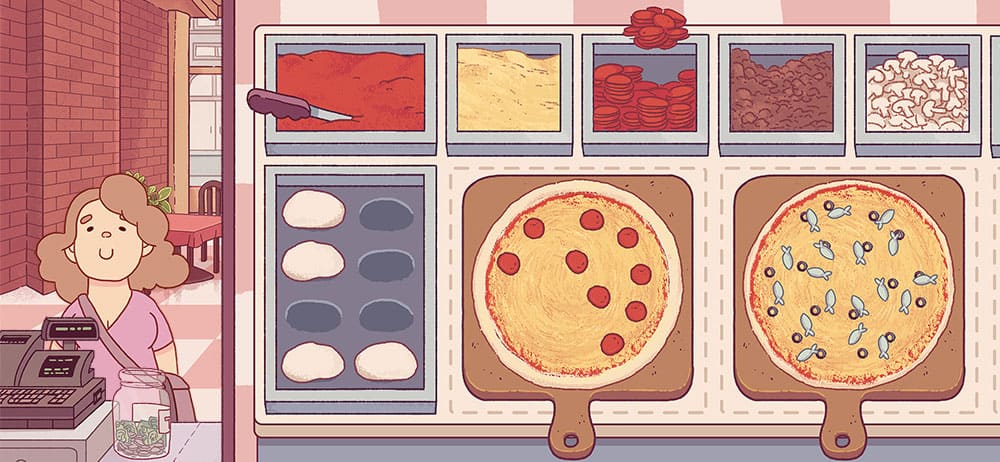Kenapa Pendeta Hindu Banyak Golput
Senin, 28 Agustus 2023 21:41 WIB
Pada setiap pemilu, para pendeta Hindu banyak yang golput. Penyebabnya bukan karena takut dianggap tak netral. Tetapi nama di daftar pemilih dan nama kependetaan tidak sama gara-gara kolom KTP tak bisa berubah.
Kenapa Pendeta Hindu Banyak Golput
Mpu Jaya Prema
Pemilihan umum dan pemilihan presiden secara serentak sudah dekat. Setiap hari ada saja berita soal hajatan demokrasi ini, terutama soal siapa yang menjadi calon presiden dan siapa wakilnya. Ributnya tak kepalang. Begitu pula para caleg (calon legislatif). Semua orang bisa melihat namanya. Seberapa banyak mantan narapidana koruptor, seberapa banyak caleg yang punya hubungan keluarga dengan petinggi partai. Bahkan ada satu keluarga yang semuanya menjadi caleg. Suami, istri, anak-anaknya.
Tapi ada yang enggan memilih, baik memilih caleg mau pun memilih capres dan cawapres. Istilah kerennya golput, singkatan dari golongan putih, sebagai simbol tidak mencoblos kertas suara. Orang yang mengaku bijak banyak mencemoh pelaku golput ini sebagai warga yang tidak bertanggung-jawab terhadap bangsa dan negara. Tapi dari sekian banyak yang golput, ada yang profesinya sebagai pendeta, khususnya lagi, pendeta Hindu. Apakah mereka tidak ikut bertanggung-jawab terhadap perjalanan bangsa ini?
Begini ceritanya. Memang selama ini berkembang pendapat, yang sengaja dipakai alasan untuk tidak berpanjang-panjang menjelaskannya. Yakni, pendeta Hindu itu harus netral dan mengayomi seluruh umat. Kalau ikut memilih berarti tidak netral. Lalu ditambah lagi penjelasan, yang seolah-olah begitu bijaknya, yakni seorang pendeta harus “sudah selesai” dengan kehidupan duniawi. Yang dilakoni hanyalah urusan non-duniawi. Tidak boleh bekerja mencari nafkah, tak boleh mencari hiburan, makanan harus dibatasi, tak boleh keluyuran dan seterusnya. Jadi, para pendeta itu hanya mengurusi masalah ritual.
Pendapat ini sempat dipercaya umat sebagai suatu kebenaran. Memang, ada yang benar, terutama dalam hal membatasi ruang gerak kebebasan seorang pendeta sehingga beliau tetap dianggap “manusia suci”. Karena itulah para pendeta Hindu di Bali disebut “sulinggih” (su berarti mulia, linggih berarti tempat) yang artinya seseorang yang harus dihormati.
Padahal dalam ajaran Hindu, seorang pendeta (disebut lain: sanyasin, bhkisuka) harus selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan menuntun umatnya. Mereka membawa teteken (tongkat) sebagai simbol dari menuntun dan memberi arahan kepada umat. Bagaimana mereka harus dipisahkan dari masyarakat? Mereka harus paham dan terlibat dalam urusan kemasyarakatan, tentu termasuk urusan negara dan bangsa.
Majelis umat Hindu, Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) pernah merumuskan bahwa semua orang wajib menerapkan konsep dharma agama dan dharma negara. Tak boleh dipisahkan. Dharma agama adalah kewajiban dalam melaksanakan ajaran agama. Baik ritual mau pun pengamalannya. Dharma negara adalah kewajiban sebagai warga negara, patuh dan terlibat dalam urusan kenegaraan. Dengan konsep ini, para pendeta tak boleh berada di menara gading, terpisah dengan masalah yang dihadapi umatnya, cuek dengan urusan bangsa dan negara. Justru pendeta dan ulama pada umumnya, siap menjadi penasehat pemerintah jika diminta. Di masa lalu, para pandita ada yang diangkat sebagai apa yang dulu disebut purohito, penasehat raja. Di Bali istilah purohito itu diganti bhagawanta. Sekarang pun, meski Bali bukan lagi kerajaan, Gubernur Bali memiliki bhagawanta.
Dengan konsep dharma agama dan dharma negara ini, tak ada alasan para pendeta Hindu ikut mencoblos saat pemilu. Tetapi dibatasi untuk tidak menjadi juru kampanye partai, apalagi menjadi buser politik. Tidak ada alasan pula untuk melarang para pendeta punya akun di medsos, yang sebagian orang menyebutnya tidak etis. Kini ada ratusan pendeta yang aktif di media sosial, terutama di Face Book dan Instagram. Mereka perlu komunikasi dengan umatnya. Dan justru lewat medsos itu mereka memberikan pencerahan dan tuntunan kepada umat. Jadi pendeta Hindu generasi kini adalah mereka yang aktif memanfaatkan kemajuan dunia. Barangkali ini juga pengaruh pendidikan, maklum pendeta masa kini rata-rata “orang sekolahan”, bahkan banyak yang doktor mau pun (pensiunan) professor.
Lalu apa urusannya dengan golput, kalau para pendeta itu umumnya orang yang sudah berpendidikan umum yang cukup? Kenapa tidak datang saja ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) dan ikut mencoblos? Apalagi dalam konsep dharma negara, itu termasuk kewajiban.
Mohon maaf, saya termasuk yang ikut golput. Sudah dua pemilu (2014 dan 2019) saya tidak ikut memilih. Pada pemilu 2024 pasti pula tetap golput. Bukan karena alasan para caleg banyak yang koruptor tapi masalah prinsip dan ini terkait dengan ajaran yang harus ditaati sebagai pendeta.
Begini ceritanya. Seorang pendeta itu selesai ritual upacara diksa atau di agama lain dibaptis, harus mengikuti perubahan dalam beberapa hal. Diksa itu di Bali disebut dwijati, artinya kelahiran yang kedua. Pertama ia lahir sebagai manusia biasa dari rahim sang ibu. Yang kedua menjadi manusia suci lahir dari “rahim guru nabe”. Ini bukan ritual sembarangan. Ada banten atau sesajen sebagaimana banten untuk orang yang meninggal dunia. Ketika “upacara kematian” itu calon pendeta ditutup tubuhnya dengan kain putih sebagaimana orang yang meninggal dunia, kalau dipadankan dengan umat Islam diberi kain kafan. Lalu digotong ke balai-balai dan kidung kematian berkumandang. Lalu hening sejenak dan guru nabe menghidupkan kembali. Nah, itulah kelahiran yang kedua.
Karena lahir kembali maka ada banyak perubahan dalam prilaku mau pun kebiasaan, tak boleh lagi memakai kebiasaan lama. Dari sekian banyak pantangan itu ada dua hal, yakni amari aran (berganti nama) dan amari busana (berganti pakaian). Ini penting disosialisasikan karena melibatkan orang lain.
Begini contohnya. Dulu nama saya Putu Setia. Setelah lahir kedua kali (dwijati) dan dinobatkan menjadi pendeta namanya menjadi Ida Pandita Mpu Jaya Prema Ananda. Nama yang panjang, tapi itu simbol karena yang benar-benar nama cuma satu kata. Ida Pandita artinya sang pendeta. Mpu adalah simbol dari pendeta trah tertentu, dalam hal ini pendeta yang leluhurnya dari Jawa. (Salah satu leluhur kami makamnya ada di Desa Kepasekan, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Setiap tahun saya ziarah di sana). Banyak sebutan pendeta di Bali dengan trah yang berbeda. Misalnya dengan sebutan Ida Pedanda, Ida Resi, Ida Bhagawan, Ida Dukuh dan sebagainya. Kata Jaya itu adalah identitas perguruan. Prema, nah itulah nama pemberian guru, yang konon didapatkan dari pewisik (bisikan) pada saat “ritual kematian”. Prema itu artinya kasih. Dan kata terakhir, Ananda, artinya anak. Ini adalah pertanda level di perguruan. Jadi kalau banyak pendeta yang sepintas namanya sama di Bali, itu karena berdasarkan trah, tapi pasti ada satu kata yang beda.
Nah, ketika ritual diksa itu selesai, diumumkan secara resmi nama kependetaan itu. Juga sejak saat itu amari busana berlaku. Busana ini selain masalah pakaian yang harus memakai kain dua lapis, memakai cincin simbol pengendalian diri, rambut harus digelung ke atas. Tak boleh lagi memakai celana panjang, misalnya. Atau berbaju batik.
Siapa pun sejak saat itu tak boleh menyebut nama saya yang lama. Yang belum tahu perubahan itu tentu harus dikasih tahu. Jika orang itu sudah dianggap tahu dan masih memanggil saya dengan Putu Setia, saya tak boleh menjawab. Itu pantang. Teman-teman saya di manapun termasuk di media sosial sudah terbiasa memanggil dengan nama kependetaan, minimal sebutan Mpu. Hanya tulisan di Koran Tempo yang terbit setiap hari Minggu secara online, nama Putu Setia masih dipakai. Itu saya anggap “ciri khas” atau semacam “hak paten” dan kebetulan diizinkan oleh perguruan. Di media lain saya pakai nama Mpu Jaya Prema.
Pertanyaan pokok, apa kaitannya dengan golput saat pemilu? Masalahnya, nama kependetaan itu tak serta merta bisa diganti di kolom KTP. Pernah ada usul ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), agar pergantian nama dikabulkan. Tapi ditolak dengan alasan: pergantian nama hanya bisa dilakukan setelah diputuskan oleh pengadilan. Ini kan tidak mungkin, seorang pendeta tak boleh ke pengadilan dalam urusan apa pun. Andai ada kasus pidana atau perdata yang melibatkan pendeta Hindu, status kependetaannya harus dicabut dulu. Ada ritualnya mencabut status kependetaan itu yang kasat mata dengan menggunting rambutnya yang menggelung ke atas. Dan itu dilakukan guru nabe.
Akhirnya nama kependetaan tak bisa diformalkan di kolom KTP. Padahal di daftar pemilih pemilu nama berdasarkan KTP. Kalau saya datang ke TPS, sudah pasti saya akan dipanggil Putu Setia oleh petugas pemilu. Jika saya bereaksi, lalu saya mengambil kertas suara dan mencoblos, berarti saya melanggar aturan kependetaan, menerima respon dengan nama lama. Saya bukan lagi pendeta.
Mungkin ini soal remeh. Tapi bagi seorang pendeta, ini pelanggaran yang prinsip. Sebenarnya ini bukan hanya soal pemilu, tetapi masalah keseharian juga. Saya pernah mengurus kartu ATM Bank yang diblokir dan harus datang sendiri ke kantor cabang. Saat mencari nomor antrean, saya sudah bilang, tolong nanti panggil nomor antrean. Entah lupa, petugas tetap panggil: Bapak Putu Setia…. Bukan hanya saya yang kaget, pengunjung lain juga heran, kok ada pendeta ke kantor bank. Akhirnya sekalian saya tutup rekening bank itu.
Ada kasus lain. Umat di Jayapura mengundang saya ritual. Tiket dibelikan online dari Jayapura. Pakai nama Mpu Jaya Prema, nama yang sudah akrab di mata umat. Untung saya cepat sadar, sehari sebelum berangkat saya urus ke kantor maskapai penerbangan itu. Rumit juga, saya harus menjelaskan apa kaitan Mpu Jaya Prema dengan Putu Setia.
Semoga pemilu dan pilpres 2024 nanti berhasil memilih presiden yang mendengar suara para pendeta Hindu ini. Lalu presiden memerintahkan Menteri Dalam Negeri agar Dukcapil membolehkan pendeta Hindu berganti nama di KTP, toh cuma sekitar seribu orang dan ada surat “kelahiran kedua” dari PHDI. Yang pasti saya tak bisa ikut memilihnya. (***)
Penulis Indonesiana
6 Pengikut

Ya Tuhan, Kami Bertobat
Minggu, 7 September 2025 19:34 WIB
Tunda Dulu Bepergian Ke Bali
Sabtu, 12 Juli 2025 15:13 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 98
98 0
0