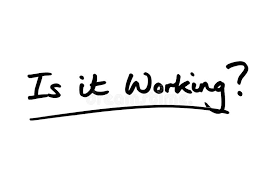Kurang Pas Jembatan Tol Jawa-Bali Ditolak dengan Alasan Mencederai Legenda
Kamis, 28 Maret 2024 13:45 WIB
Jembatan tol Banyuwangi-Gilimanuk kembali ramai mendapat penolakan di Bali, setelah Wikipedia Indonesia memuat datanya di web. Penolakannya masih mengacu kepada legenda terjadinya Selat Bali itu, suatu alasan yang kurang kuat karena keyakinan ini bukan bersumber dari ajaran agama. Harus ada alasan lain untuk menolaknya.
Oleh Mpu Jaya Prema, pemerhati budaya
Kontroversi rencana pembangunan jembatan laut yang menghubungkan Pulau Jawa dan Bali kembali ramai diperbincangkan. Perdebatan ini sudah berlangsung puluhan tahun. Penolakan jembatan laut itu oleh masyarakat Bali disuarakan permimpin Bali formal seperti gubernur dan bupati mau pun pemimpin Bali informal seperti pucuk lembaga adat dan keagamaan. Pemicu hebohnya kembali proyek itu disebabkan oleh munculnya data proyek di laman Wikipedia Indonesia belum lama ini.
Wikipedia Indonesia memang hanya memuat data soal jembatan laut yang disebut jembatan tol sebagai kelanjutan dari jalan tol Probolinggo – Jember – Banyuwangi yang akan disambungkan dengan jalan tol Gilimanuk – Mengwi – Tol Bali Mandara. Kedua ruas jalan tol di Jawa dan Bali itu memang sedang digarap. Tol Probolinggo – Banyuwangi yang berujung di Pelabuhan Ketapang sedang giat dikerjakan. Akan halnya tol Gilimanuk – Mengwi sedang direvisi anggarannya namun pembebasan tanah sudah mulai dilakukan. Tol Bali Mandara sendiri sudah rampung yang menghubungkan Denpasar dengan Nusa Dua lewat laut. Nah, jembatan tol Ketapang – Gilimanuk ini sesungguhnya belum jelas sampai di mana perencanaannya namun Wikipedia sudah memaparkan gambarnya. Bahkan panjang jembatan laut itu sudah dihitung sepanjang 39 km yang disebut lebih pendek dari jembatan Suramadu yang menyambungkan Jawa – Madura.
Kenapa jembatan tol Ketapang – Banyuwangi ditolak? Ada beberapa alasan menyangkut sosial ekonomi dan keyakinan orang Bali yang beragama Hindu. Alasan soal keyakinan ini yang mencuat besar karena itu tingkat emosionalnya menjadi tinggi. Kalau sudah masalah keyakinan dibawa-bawa maka persoalannya menjadi sulit untuk diperdebatkan. Bagaimana mendebat keyakinan. Padahal sesungguhnya apa yang disebut keyakinan itu adalah sebuah legenda, bukan terkait langsung dengan kaidah agama.
Legenda yang dipakai dalam kasus ini adalah tentang seorang brahmana di masa lalu – entah kurun waktu kapan – yang bernama Danghyang Sidhimantra. Beliau disebut tinggal di Jawa, tentu tidak diketahui siapa nama sebenarnya dan di mana tinggalnya. Nama-nama “leluhur orang Bali” yang berasal dari Jawa sudah pasti merupakan nama baru yang bersifat simbul ketika sudah di Bali. Danghyang itu sebutan orang suci (dang = orang, hyang = suci) sedang Sidhimantra dari kata sidhi yang artinya bertuah dan mantra yang diartikan puja doa. Danghyang Sidhimantra berarti orang suci yang doanya sangat bertuah atau sakti.
Beliau punya anak yang ternyata berbeda sifatnya dengan sang ayah. Anaknya ini suka berjudi sampai ke tanah Bali. Waktu itu Jawa dan Bali menjadi satu pulau dengan nama Pulo Dawa (artinya pulau yang panjang). Semua permintaan anaknya untuk berjudi dipenuhi sang ayah. Pada suatu ketika sang anak ini kehabisan uang di Bali, lalu mencuri harta berlian milik sahabat ayahnya yang tinggal di Goa Raja. Sahabat Sidhimantra ini disebutkan berwujud naga (ular besar) yang bernama Naga Basuki. Caranya adalah memotong ekor Naga Basuki yang penuh dengan perhiasan emas. Sayangnya Naga Basuki segera tahu hartanya dicuri lalu dengan kesaktiannya membunuh anak Sidhimantra itu.
Singkat cerita, Sidhimantra tahu anaknya dibunuh Naga Basuki. Lalu terjadi musyawarah. Sidhimantra sanggup menyambungkan ekor Naga Basuki kembali dengan imbalan Naga Basuki mau menghidupkan anak yang tewas itu. Kesepakatan tercapai, anak Sidhimantra hidup kembali dan sejak itu diperkenalkan dengan nama Manik Angkeran, artinya harta berlian (manik) yang keramat (angker) yang pernah dicuri. Manik Angkeran kemudian menjadi murid dari Naga Basuki.
Danghyang Sidhimantra selanjutnya kembali pulang ke tanah Jawa. Nah, di sebuah kawasan hutan lebat Sidhimantra merapalkan mantram suci dan dengan tongkatnya menggoreskan ke tanah. Tujuannya adalah anaknya, Manik Angkeran, tak bisa melewati goresan tanah itu sehingga Manik Angkeran tetap bisa belajar dengan tekun kepada Naga Basuki. Goresan tanah itu menjadi laut yang memisahkan Pulo Dawa menjadi dua, di timur disebut Bali dan di barat disebut Jawa. Itulah legenda yang memisahkan Jawa dengan Bali.
Kepiawaian tetua orang Bali dalam melanggengkan legenda sangatlah mumpuni. Tempat-tempat suci yang ada di Bali dilibatkan (seolah-olah ada) dalam legenda itu. Tempat tinggal Naga Basuki kini dijadikan tempat suci dengan nama Goa Raja. Tempat dihidupkannya kembali Manik Angkeran kini dikenal dengan nama Pura Bangun Sakti. Sidhimantra menggoreskan tanah di hutan lebat yang kemudian menjadi laut itu (kini Selat Bali) disebut menjadi lokasi Pura Segara Rupet. Lokasi ini memang paling dekat dengan Ketapang di Jawa. Lalu, entah dari mana didapat sumbernya, Sidhimantra ketika menggoreskan tanah itu berkata-kata: “Awya angatepaken Jawa muang Bali, yan atep Jawa muang Bali, rusak ikanang Bali pulina stananing hyang”. Artinya kurang lebih: Jangan sekali-sekali menyatukan Bali dengan Jawa, kalau disatukan Bali akan rusak sebagai tempat suci.
Ucapan Sidhimantra ini kemudian dikatagorikan bhisama, artinya “kata suci” yang harus ditaati umat Hindu. Padahal tetua orang Bali menyebut bhisama itu berarti catatan sesaat, bukan sesuatu yang harus dipatuhi sepanjang masa. Banyak ada bhisama yang dicatat dalam berbagai babad Bali, sejarah asal-usul warga Bali yang kini sudah berubah maknanya.
Nah, dari legenda Dhanghyang Sidhimantra dengan bhisama itu penolakan adanya jembatan laut Ketapang – Gilimanuk menjadi berkepanjangan. Apakah penolakan dengan dalih legenda ini bisa dianggap masuk akal oleh pemerintah pusat? Kita tahu, rencana jembatan laut Ketapang – Gilimanuk itu sudah diusulkan oleh mendiang Profesor Dr Ir Sedyatmo, guru besar ITB, pada tahun 1960-an. Ahli konstruksi cakar ayam ini menyebutkan sangat ideal menyatukan Pulau Sumatra, Jawa dan Bali yang diberinya nama Tri Nusa Bima Sakti. Pada 2012 silam, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggencarkan kembali pembangunan jembatan Selat Bali dengan tujuan memperlancar laju ekonomi masyarakat. Usulan tersebut langsung ditolak oleh ormas Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kabupaten Jembrana. Sejak itu penolakan juga digencarkan banyak tokoh.
Tapi, kenapa penolakan itu dengan menonjolkan sisi legenda Sidhimantra? Seberapa kuat hal itu didukung oleh generasi baru Bali? Bagaimana anak-anak Bali generasi milenial percaya ada seekor naga bermahkota emas berlian di sebuah goa? Lalu ada orang sakti membuat laut pemisah antara Jawa dan Bali hanya dengan menggoreskan tongkat? Kita seharusnya mencari alasan yang lebih bisa diterima oleh pemikiran masa kini yang tak dikaitkan dengan kepercayaan, apalagi basis agamanya tak ada sumber yang jelas.
Bagaimana kalau dicari alasan bahwa dengan adanya jembatan laut itu orang akan berbondong-bondong datang ke Bali dan pulau ini jadi sesak? Kelihatan menarik dan tepat. Tapi apa benar orang luar Bali saja yang diuntungkan? Bukankah orang Bali lebih banyak lagi yang ke Jawa dengan mudahnya? Entah itu tujuan bekerja, entah pula bersembahyang di berbagai pura yang bertebaran di Jawa. Jembatan itu hanya salah satu sarana yang kebetulan lebih cepat menyeberang. Dengan kapal laut saat ini sebenarnya tak masalah orang mondar-mandir ke Jawa atau Bali. Jadi, alasan ini tak begitu relefan pula, tanpa jembatan orang tetap bisa bebas datang ke Bali, seperti halnya orang Bali bebas pergi ke Jawa. Lalu lintas orang tak bisa dibatasi dengan sarana.
Ketergantungan Bali pada Jawa juga sangat besar, harus diakui hal itu. Untuk sarana upacara pun barang-barang mengalir dari Jawa. Kelapa, janur, pisang sangat tergantung pada Jawa. Setiap hari truck dari Jawa membongkar muatan pisang yang didatangkan dari Situbondo dan Jember. Lalu apa dong alasan untuk menolak jembatan laut di Selat Bali ini? Barangkali yang sederhana saja, biarkan Bali dan Jawa terpisahkan dengan sarana penghubung kapal laut. Alasannya agar Nusantara ini nyata terdiri dari gugusan pulau-pulau. Suasananya pasti beda jika mobil melintas di jembatan menyeberang laut, kesannya kok tidak ada laut. Jadi sederhana saja penolakannya, toh kita bisa menerima jalan tol Gilimanuk – Mengwi yang akan menghabisi sawah-sawah produktif dan banyak jalan layang dibangun. Bahwa jika penduduk pendatang dianggap akan membanjiri Bali, maka batasi itu dengan berbagai peraturan termasuk memperkuat lembaga adat. Namun itu pun dengan tetap dalam koridor berbangsa dan bernegara yang satu. Kalau kita terlalu ketat membatasi pendatang bagaimana kalau orang Bali yang berada di luar Bali, bukankah mereka juga pendatang di komunitas yang lain?
Ingat kita satu negara, Indonesia. Mari kita tolak jembatan laut di Selat Bali itu dengan alasan melestarikan angkutan laut sambil menjaga kelestarian alam Bali yang nantinya pasti rusak oleh jalan tol.
Penulis Indonesiana
6 Pengikut

Ya Tuhan, Kami Bertobat
7 jam lalu
Tunda Dulu Bepergian Ke Bali
Sabtu, 12 Juli 2025 15:13 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0