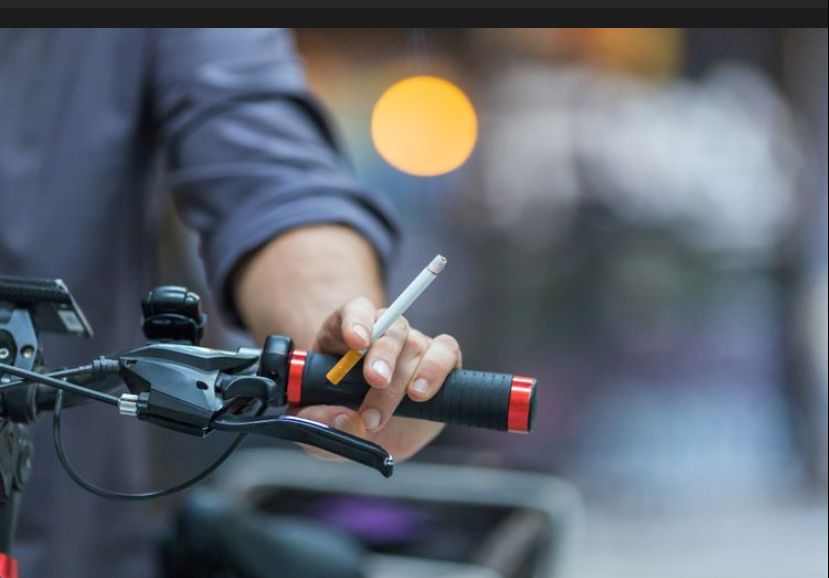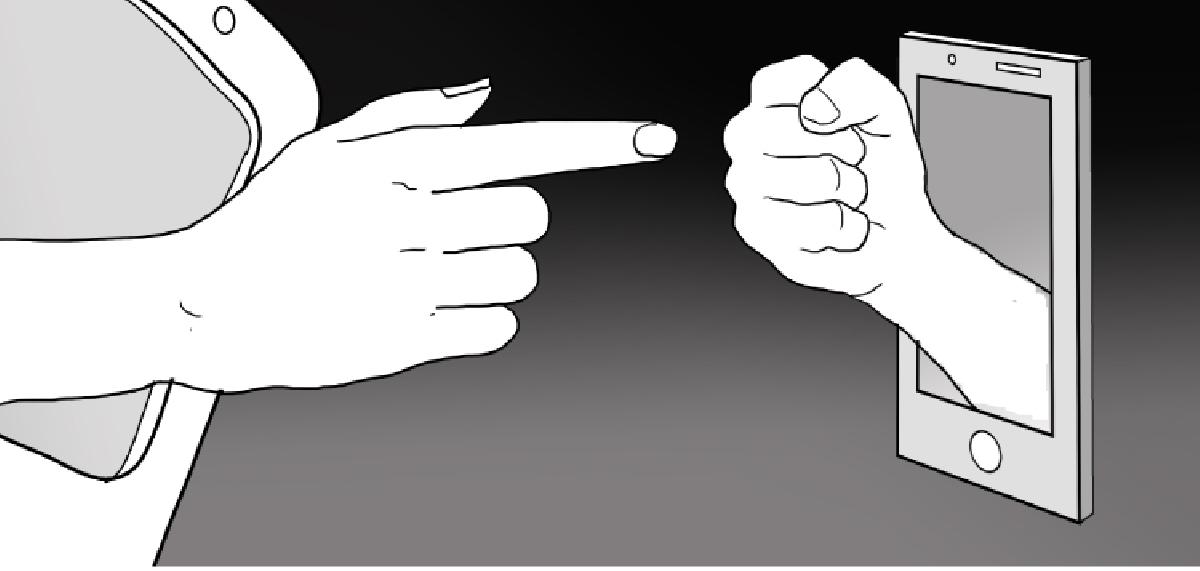Di Indonesia, bulan September digambarkan sebagai bulan yang penuh kekelaman, khususnya dalam perjuangan hak asasi manusia. Ada banyak rentetan peristiwa kelam dalam perjalanan sejarah bangsa yang pernah terjadi di bawah kekuasaan rezim otoriter Orde Baru. Oleh karena itu, masyarakat sipil atau kalangan aktivis sering menggaungkan kampanye “September Hitam” setiap tahunnya sebagai rangka merawat ingatan dan menyuarakan suara-suara dari keluarga korban penculikan atau penghilangan paksa masa lalu.
Berbicara soal penghilangan paksa, ada satu novel yang mampu menggambarkan peristiwa tersebut, yakni novel Laut Bercerita karya Leila S. Chudori. Novel tersebut merupakan salah satu novel yang berlatarkan situasi sosial-politik dan pergerakan mahasiswa pada masa Orde Baru.
Sepanjang membaca novel tersebut, ada banyak perasaan yang menyelimuti diri saya. Ada perasaan marah, sedih, putus asa, hingga kepahitan akan kehilangan orang yang dicinta. Namun, di satu sisi yang lain, novel tersebut juga ingin mengatakan bahwa kita harus tetap menjaga harapan dan konsisten pada perjuangan dalam membela kelompok yang lemah dan berani melawan penguasa yang sewenang-wenang.
Sementara itu, salah satu hal yang saya suka dalam novel tersebut ialah mampu membuat karakter di dalamnya menjadi “hidup” dan membuat saya penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya. Selain itu, saat membaca novel tersebut, saya merasa sedang ikut berada di dalam dimensi cerita tersebut. Novel ini wajib dibaca oleh orang-orang yang ingin mendapatkan gambaran bagaimana perjuangan melawan penguasa tiran.
Rezim Otoriter Yang Anti-Kebebasan
Layaknya seperti rezim otoriter dibelahan dunia lainnya, rezim Orde Baru memiliki ketakutan terhadap kebebasan. Apapun bentuk kebebasannya. Dari kebebasan berpikir hingga kebebasan pers. Semuanya ingin dikendalikan oleh mereka karena takut dapat mengancam stabilitas politik nasional. Kelompok penguasa memang memiliki obsesi yang begitu besar untuk mengontrol atau mengendalikan sektor-sektor kehidupan masyarakat sipil.
Misalnya, dalam soal baca-membaca saja mereka mencoba untuk mengaturnya. Pemerintah melarang masyarakat untuk membaca buku-buku “kiri” karena dianggap berbahaya dan orang-orang yang nekat untuk membacanya maka akan dicap sebagai pengkhianat bangsa. Mengerikan, bukan? Selain itu, kampus-kampus juga dilarang untuk membicarakan isu-isu politik yang bersentuhan langsung dengan kepentingan kelompok penguasa.
Rasa-rasanya kelompok penguasa ingin membodohi warga negaranya dan tidak ingin warga negaranya memiliki pikiran yang kritis dan kesadaran terhadap isu sosial-politik. Selain itu, pemerintah juga melarang pelaksanaan diskusi-diskusi publik. Tak jarang, diskusi publik dihadiri atau disusupi oleh intel yang mengaku sebagai aktivis. Seperti yang disampaikan oleh bapaknya Biru Laut, bahwa sering kali banyak intel yang keluar-masuk ke acara diskusi berpura-pura menjadi bagian dari kelompok pergerakan mahasiswa.
Sementara itu, pada masa itu juga tidak ada yang namanya kebebasan pers. Pada masa itu terdapat suatu departemen yang mengatur dan mengontrol kerja-kerja media. Bahkan, dalam suatu bagian dijelaskan para mahasiswa membuat sebuah manifesto yang di dalamnya terdapat pengecaman terhadap pembredelan tiga media di Indonesia. Setiap kali membaca dari satu halaman dan berlanjut ke halaman lainnya, saya terkadang melakukan perenungan terhadap situasi masa lalu dengan situasi saat ini.
Terkadang, saya merasa bersyukur dengan kondisi saat ini, terlepas dari segala kekurangannya. Sekarang, tidak ada lagi media yang takut dibredel atau informasi yang disensor oleh kelompok penguasa. Walaupun, memang masih banyak kekerasan atau penyerangan kepada para jurnalis di Indonesia.
Di samping itu, kita bisa membaca buku apapun yang kita inginkan sekaligus bisa mendiskusikan isinya tanpa ada rasa takut atau was-was. Tidak seperti yang dirasakan oleh Biru Laut dan kawan-kawannya yang di mana jika ingin mendiskusikan suatu bacaan harus diam-diam. Begitu buruknya ketika suatu negara dipimpin oleh orang-orang bertangan besi dan korup.
Pahitnya Merasakan Ketidakpastian & Kehilangan
Tidak ada satu orang pun yang siap merasakan kehilangan. Dan, tidak ada satu orang pun yang menyukai ketidakpastian. Setidaknya, itulah yang dirasakan oleh keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa pada masa Orde Baru. Setiap detik ke detik, menit ke menit, hari ke hari, bahkan tahun ke tahun, mereka selalu diselimuti pertanyaan dalam diri mereka tentang keberadaan orang-orang yang mereka cintai. Pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak ada ujungnya.
Sulit membayangkan rasanya ketika kita sudah terbiasa menghabiskan waktu atau menjalankan suatu aktivitas dengan orang-orang yang kita cintai selama bertahun-tahun, lalu mereka lenyap begitu saja, tanpa kita tahu keberadaannya. Kemudian, kita harus terbiasa, atau lebih tepatnya terpaksa untuk melewati dan menjalani hari-hari seperti biasa. Rasanya seperti ada kepingan yang hilang atau kehampaan dalam diri kita. Lagi-lagi, itulah yang dirasakan oleh keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa.
Terdapat bagian yang menyayat hati saya mengenai gambaran bagaimana kedua orang tua yang selalu menunggu dan menanti anaknya kembali ke rumah. Gambaran itu diceritakan melalui point of view Asmara Jati, adik dari Biru Laut. Setiap hari Minggu pada momen makan malam bersama, ayahnya selalu mengambil 4 buah piring dan meletakannya satu per satu di atas meja.
Dari keempat piring hanya satu piring saja yang tidak digunakan. Satu-satunya piring yang selalu menanti kedatangan pemiliknya. Piring yang selalu disediakan dengan perasaan cinta dan kasih sayang orang tua kepada anaknya yang dihilangkan secara paksa dan tak tahu secara pasti apa yang telah terjadi kepada anaknya di luar sana. Dalam waktu yang sangat panjang, keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa selalu hidup dalam penyangkalan.
Mereka (baca : keluarga korban) selalu menyangkal bahwa anaknya atau orang-orang yang mereka cintai telah diculik, dihilangkan, atau mungkin telah dibunuh. Bahkan, untuk menghilangkan rasa rindunya, tak jarang dari mereka memegang barang-barang milik anaknya atau sekadar membersihkan atau menjamah buku-buku koleksi anaknya. Semua upaya itu dilakukan untuk mengusir rasa rindunya kepada orang tercinta.
Mereka selalu menyisakan atau memberikan “ruang ilusi” dalam kepala mereka tentang dunia yang di mana mereka masih memiliki keluarga yang utuh, hangat, dan bisa berbagi tawa. Sulit memang bagi orang tua yang kehilangan anaknya untuk mengatakan bahwa anaknya telah meninggal, sedangkan mereka sendiri tidak tahu lokasi makam atau kuburan anaknya. Para keluarga korban saling menguatkan dan saling memberikan semangat satu sama lain bahwa akan selalu ada harapan atau kemungkinan dari mereka yang hilang akan kembali ke rumah masing-masing. Sementara itu, penderitaan yang sama membuat mereka harus melakukan aksi untuk menyadarkan pemerintah.
Aksi itu terjadi setiap hari Kamis di depan Istana Negara. Aksi yang dihadiri oleh keluarga korban, kawan, saudara, simpatisan, serta wartawan dengan atribut serba hitam dan payung hitam sebagai simbol sekaligus mempertanyakan ke mana para aktivis yang hilang itu. Aksi Kamisan merupakan aksi merawat ingatan bahwa orang-orang keji yang memiliki kuasa masih berkeliaran dan mereka harus segera diadli dan dimintai pertanggungjawabannya. Aksi itu telah berlangsung bertahun-tahun, tanpa membawa jawaban dan tindakan yang berarti dari Negara.
Tulisan ini akan saya tutup dengan salah satu kutipan yang termuat dalam novel Laut Bercerita. Sejujurnya, sulit bagi saya untuk memilih kutipan mana yang akan saya gunakan karena terlalu banyak kutipan yang relevan dengan kondisi Indonesia saat ini dan juga kutipan yang mampu mengguncang hati nurani dan rasa kemanusiaan kita. Pada akhirnya, saya memilih untuk memasukan Aksi Kamisan atau Aksi Payung Hitam.
“Mungkin Aksi Payung Hitam setiap hari Kamis bukan sekadar sebuah gugatan, tetapi sekaligus sebuah terapi bagi kami dan warga negeri ini ; sebuah peringatan bahwa kami tak akan membiarkan sebuah tindakan kekejian dibiarkan lewat tanpa hukuman. Payung Hitam akan terus-menerus berdiri di depan Istana Negara. Jika bukan presiden yang kini menjabat yang memberi perhatian, mungkin yang berikutnya, atau yang berikutnya…”
Sebuah harapan di tengah keputusasaan.
Ikuti tulisan menarik Arman Ramadhan lainnya di sini.