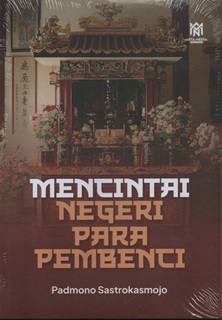Pemula yang menyulam hal-hal sepele menjadi jalinan kisah, cerita, tuturan, dan narasi, agar lahir pencerahan di setiap simpulnya.
Jejak Sunyi Teh Mumun
Kamis, 28 Agustus 2025 07:05 WIB
Disebut pahlawan devisa, namun pulang dalam peti kayu. Ini kisah Teh Mumun dan mereka yang tak boleh hilang dalam sunyi.
***
Aku pernah mengenal seorang perempuan bernama Maemunah—sering kupanggil Teh Mumun. Perjumpaan kami singkat, hanya beberapa kali di swalayan dekat apartemenku, di kota asing yang menelan wajah-wajah pendatang tanpa peduli asal-usulnya. Namun ada sesuatu dari dirinya yang menempel di ingatan: senyum ramah khas mojang Sunda, mata letih yang tetap jernih, dan cara ia menyebut kata kampung dengan nada yang terdengar seperti doa.
Teh Mumun berasal dari sebuah kampung pelosok di Jawa Barat. Sawah yang dulu menjadi sumber hidup keluarganya perlahan menyempit, satu demi satu berganti menjadi deretan pabrik. Bekerja di pabrik sekitar pun tak mungkin, karena ia hanya lulusan SD. Sementara ayahnya sudah renta, ibunya sakit-sakitan, dan adik-adiknya masih sekolah. Maka ia memilih merantau jauh ke negeri asing ini, dengan satu harapan sederhana: memperbaiki kehidupan keluarganya.
“Kalau aku tinggal, kami tak bisa bertahan,” katanya lirih. “Kalau aku pergi, setidaknya ada harapan.”
Dan ia pun pergi. Menyebrangi laut dengan perjanjian kerja yang ditulis dalam bahasa yang nyaris tak ia mengerti. “Kontrak dua tahun,” ucapnya sambil tersenyum. Tapi di balik senyum itu, aku tahu ada getar takut yang tak pernah ia ucapkan.
Hari-harinya di negeri asing ini seperti garis lurus tanpa jeda. Dari fajar sebelum matahari bangun hingga larut malam ketika kota sudah terlelap, tubuhnya terus bergerak: menyapu, mengepel, mencuci pakaian, mengasuh anak, membersihkan kaca jendela yang menjulang, lalu kembali ke dapur dengan tangan yang pecah-pecah digerogoti sabun.
Bahasa dan budaya menjadi jarak asing yang membatasi dirinya. Kata-kata pertama yang ia kuasai hanya empat atau lima: kul (كُل, makanlah), nām (نام, tidurlah), na‘am (نعم, iya), dan āsif (آسِف, maaf). Sisanya ia isi dengan bahasa tubuh, senyum, dan diam. Kadang ia dimarahi karena salah paham, kadang disalahkan untuk sesuatu yang bukan kesalahannya.
Tapi ia bertahan.
“Aku kuat,” katanya suatu sore ketika kami duduk di taman apartemen, saat ia mengasuh anak majikannya. “Kalau aku pulang sekarang, siapa yang akan bayar biaya sekolah adik-adikku?”
Aku menatapnya waktu itu. Tubuhnya kecil, tangannya kasar, tetapi di matanya ada sesuatu yang besar: tekad. Seperti api kecil yang tak mudah dipadamkan meski ditiup angin keras.
Hari-harinya berlalu begitu saja: sunyi, namun dipenuhi kerja tanpa henti. Diam, tapi menyimpan makna yang dalam. Aku jarang menemuinya, namun setiap kali berpapasan selalu ada senyum simpul yang ia sisipkan—seolah cukup untuk menyembunyikan rindu yang panjang.
Suatu sore, ketika kami duduk sebentar di kursi taman, ia menatapku dengan mata berbinar yang jarang kulihat sebelumnya.
“Salah satu adikku sekarang masuk madrasah aliyah,” katanya pelan. Lalu ia menghela napas panjang. “Aku hanya lulusan SD. Tapi kalau adik-adikku bisa sekolah lebih tinggi dariku, dan suatu hari aku bisa membeli kembali sawah untuk keluarga, rasanya semua letih ini tidak sia-sia.” lanjutnya sambil tersenyum sumringah. Aku hanya mengangguk, ikut senang.
Hingga kabar itu datang.
Teh Mumun sakit. Mula-mula demam ringan yang tak kunjung turun, disertai batuk panjang yang membuat napasnya berat. Majikan hanya memberinya obat seadanya. Klinik terlalu mahal untuk seorang pekerja yang tak punya asuransi. Beberapa hari ia masih mencoba bekerja, tapi tubuhnya kalah cepat.
“Bronkitis,” kata orang. Infeksi yang mungkin diperparah udara gurun yang kering, atau terlalu sering menghirup uap bahan kimia pembersih. Tubuhnya akhirnya menyerah sebelum sempat mendapat pertolongan.
Aku tak sempat menemuinya di hari-hari terakhir. Yang kudengar hanya kabar lirih: Teh Mumun sudah tiada.
Namanya muncul di selembar berita kecil koran lokal: “Maemunah, seorang pekerja migran asal Indonesia, meninggal di apartemen majikannya.”
Hanya begitu saja. Tanpa wajah. Tanpa kisah. Namun bagi keluarganya di kampung, Teh Mumun adalah segalanya.
Dia adalah anak yang mereka besarkan dengan susah payah. Dia adalah kakak yang rela menanggung beban agar adik-adiknya bisa sekolah. Dia adalah perempuan yang menyeberangi lautan, bukan untuk mengejar mimpi besar, melainkan untuk memenuhi kebutuhan paling mendasar: makan dan bertahan hidup .
Dan setiap kali aku mengingatnya, ia selalu kembali: sosok yang menyimpan harapan yang sangat besar di balik tubuh kecilnya.
Sore ini, di kursi taman tempat kami beberapa kali berjumpa, aku mencoba mengenang setiap detail kecil tentangnya. Senyum simpulnya di kasir. Caranya bercerita tentang sawah yang kini tinggal kenangan. Nada suaranya ketika menyebut rindu pulang ke kampung halamannya. Juga matanya yang berbinar ketika mengatakan bahwa ia ingin adik-adiknya terus bersekolah, dan membeli sawah untuk keluarganya—dua impian sederhana yang seolah membayar semua lelahnya.
Dan aku merasa bersalah. Karena aku tak pernah benar-benar mendengarkannya.
Yang tersisa kini hanyalah namanya. Sebaris nama di paspor, yang mungkin sudah dicap berkali-kali di perbatasan, tetapi tak pernah tercatat dalam ingatan negeri asing tempat ia bekerja. Nama yang mungkin segera dilupakan di kota ini, tetapi akan selalu hidup di kampung yang menunggunya pulang.
Dan aku bertanya dalam diam: mengapa negeriku memanggil mereka “pahlawan devisa” tetapi membiarkan mereka pulang dalam peti kayu? Mengapa tubuh-tubuh rapuh itu dibiarkan bekerja tanpa perlindungan yang layak, seolah pengorbanan mereka hanya seperti angka di laporan keuangan? Dan yang lebih perih, mengapa aku pun bagian dari kebisuan itu—tak sempat menggenggam tangannya dan mengatakan, “Teh... kau sudah cukup berjuang.”
Teh Mumun, seperti banyak pekerja migran lain, adalah wajah dari keberanian yang tak terucap. Ia pergi bukan untuk berpetualang, melainkan untuk menyelamatkan keluarganya. Ia rela menanggung sepi, caci, sakit, bahkan kehilangan dirinya sendiri, agar ada yang bisa makan, agar adik-adiknya bisa terus bersekolah, dan agar suatu hari keluarganya kembali memiliki sawah.
Teh Mumun lebih dari sekadar nama di paspor. Di mata keluarganya ialah pahlawan sesungguhnya, yang membuat rumah mereka tetap berdiri meski ia sendiri tak punya apa-apa.
Di senyum ramah khas mojang Sundanya, aku melihat jejak tanah Parahyangan- tenang diluar, tabah menahan luka di dalam. Kini senyuman itu tinggal kenangan.
Dan aku, yang hanya mengenalnya sebentar, perlu menuliskan kisahnya agar senyum itu tak lenyap bersama tubuh yang pergi terlalu cepat. Sebab Teh Mumun adalah potret ribuan perempuan yang disebut pahlawan devisa—perempuan yang berjuang dengan tabah dalam diam, namun sering terabaikan oleh negerinya sendiri.
Mengingatnya berarti menjaga agar mereka tak hilang tanpa jejak dan menuliskan namanya adalah cara kecilku untuk menjaga agar kisah ini tetap dikenang, bukan ditelan sunyi.
Pemula
0 Pengikut

Doa Hering Tua
3 hari lalu
Karpet Terakhir
Rabu, 8 Oktober 2025 17:19 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0









 Berita Pilihan
Berita Pilihan 98
98 0
0