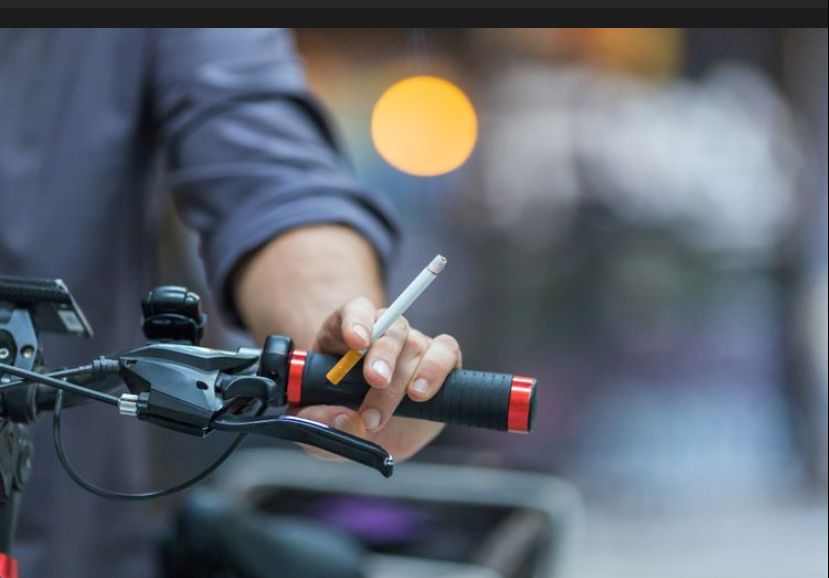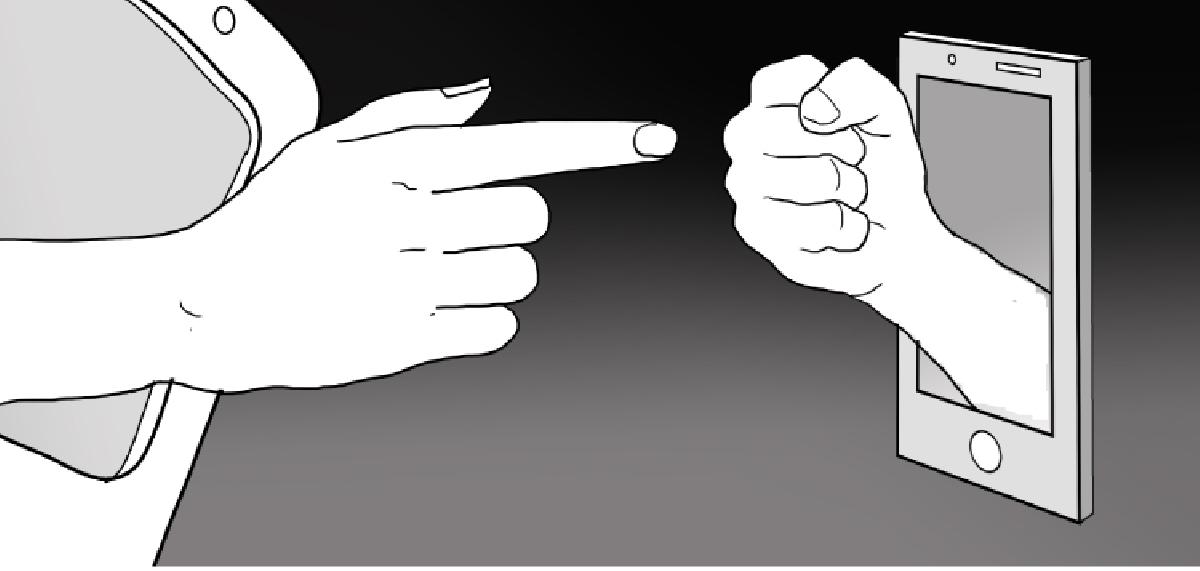MEMBACA PEREMPUAN PELAKU BOM
Lies Marcoes
aktivis perempuan, peneliti perempuan dalam kelompok radikal
Di antara komentar atas tragedi bom di Surabaya 13-14 Mei 2018 lalu, ungkapan keterkejutan atas fakta bahwa salah satu pelakunya perempuan dengan membawa serta anak-anaknya begitu menonjol. Meski tak selalu eksplisit, tekanan nadanya penuh penghakiman. Implikasi lain dari absurdnya fakta itu memunculkan spekulasi bahkan tuduhan bahwa ini merupakan rekayasa yang sempurna.
Tak kalah tingkah, awak media pun kerap bertanya soal kenormalan atau keabnormalan pelaku. Media pun cenderung menggiring pada jawaban yang seolah memberi rasionalitas atas tindakan yang tak masuk akal itu. Misalnya soal isyarat gangguan psikologis, atau penanda adanya gangguan kejiwaan atau hal-hal lain yang intinya menjelaskan tentang prilaku abnormal itu. Namun sebegitu jauh, perangkat studi tentang konstruksi sosial atas peran gender yang menjelaskan perempuan bisa menjadi pelaku bom bunuh diri jarang diperhitungkan.
Perempuan, sebagaimana lelaki, dibentuk, dicita-citakan, diharapakan untuk bertingkah laku sesuai harapan masyarakatnya. Meskipun rentang harapan itu tidak ajek, secara umum perempuan diharapkan berwatak halus, lembut, baik, pengasih, penyayang dan seterusnya. Harapan ini dibentuk karena perempuan dianugerahi kemampuan fungsional reproduksi, sehingga melalui rahimnya ia sanggup melahirkan anak. Atas kesanggupan itu, perempuan dikonstruksi secara sosial politik (harus) melanjutan fungsi reproduksi biologisnya ke fungsi reproduksi sosial. Kemampuan kedua itu antara lain menjalani peran perawatan, pemeliharaan, pemberian kasih sayang, melindungi, mengurus dan seterusnya. Karenanya mereka dicitrakan dan dipantas-pantaskan memiliki sifat kelembutan, keibuan, penuh kasih, cinta dan kasih sayang. Mereka juga diharapkan sedia berkorban sebagai perwujudan lain dari watak feminin itu. Rentang pengorbanan yang dituntut bisa memuai tak terbatas dari keluarga hingga dunia global. Pengorbanan perempuan demi keluarga, demi kehidupan, demi perjuangan seringkali diglorifikasikan dalam beragam bentuk ekspresi dari puisi hingga petisi, dari ayat suci sampai ayat konstitusi. Narasinya adalah perempuan pemilik mutlak kelembutan, welas asih, rasa kasih sayang dan sederet ekspresi lain yang meneguhkan kepemilikan sifat feminin dan karenanya mustahil melakukan hal yang sebaliknya.
Harapan yang bersifat gender (konstuksi sosal atas jenis kelamin) itu sedemikian rupa dikukuhkan hingga muncul keyakinan tanpa kesangsian bahwa sifat kelembutan, kesediaan untuk berkorban, kasih sayang yang dimiliki perempuan adalah alamiah dan otomatis adanya. Karenanya tatkala terjadi hal yang tak sesuai dengan harapan, ia dianggap menyimpang atau anomali. Kepadanya kemudian menempel label- label yang menggugurkan femininitasnya bahkan dianggap sebagai orang yang meny impang dari karakter yang seharusnya.
Padahal dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada karakteristik feminin yang permanen dan statis merasuk kepada perempuan, demikian sebaliknya pada lelaki. Karakter itu lentur dan pragmatis menyesuaikan pada keadaan dan kebutuhannya. Banyak lelaki yang mengambil peran dan fungsi feminin meskipun diharapkan berlaku hanya kepada perempuan, demikian juga sebaliknya pada perempuan. Namun dalam struktur masyarakat biner ini, pemujaan kepada karakter maskulin teramat tinggi dibandingkan feminin akibatnya penghormatan atas peran, posisi, status yang dipadankan kepada maskulinitas juga begitu tinggi.
Pada kenyataanya karakteristik feminin-maskulin itu cair dan timbal balik. Namun manusia membutuhkan stabilitas keajegan. Karenanya elemen-elemen pembentuk karakter seperti budaya, politik, agama dan bahkan ekonomi sedemikian rupa berupaya mematri karakter itu menjadi permanen pada etitas biner lelaki maskulin- perempuan feminin. Rekayasa sosial yang dilakukan itu sesungguhnya beradaptasi juga kepada kebutuhan. Sebab kebudayaan, tafsir keagamaan, politik dan ekonomi juga lentur terhadap perubahan peran di antara perempuan dan lelaki itu. Namun pelabelan, pencitraannya atau “ stereotyping” -nya, tetap kokoh membentuk oposisi biner feminin-maskulin sebagai milik mutral perempuan- lelaki seolah-olah merupakan kodrat Ilahiah.
Karenanya ketika perempuan keluar dari pakem pencitraannya, orang terkejut. Terlebih untuk tindakan yang begitu ektrim melibatkan anak dalam pilihan kematiannya. Sebaliknya hampir tak ada pernyataan yang mengutuki bapaknya meskipun ia melakukan hal yang juga keji. Ini artinya ada permakluman kepada lelaki sebagai menyandang watak maskulin dalam melakukan tindakan bom bunuh diri itu. Tidak adanya pertanyaan yang menghubungkan tindakan bunuh diri dengan bapaknya dalam kasus di Surabaya itu selaras belaka dengan konstruksi dan pencitraan atas lelaki dengan karakter maskulinitasnya. Orang tetap bisa “menerima” untuk perbuatan yang paling ektrim sekalipun. Melalui citra itu, orang telah memberi ruang “permakluman” bahwa lelaki bisa dan sanggup melakukan tindakan kejam membawa anak istrinya meledakkan diri dengan bom, tapi tidak bagi perempuan.
Pada kenyataannya, kekejaman tak berjenis kelamin, tak berkelas dan tak berwarna kulit. Artinya tindakan itu bisa dilakukan oleh siapapun. Demikian halnya karakter mengasihi, merawat bukan pula secara mutlak domain perempuan. Dalam kehidupan, tindakan kekerasan bisa (sangat mungkin) dilakukan oleh keduanya secara timbal balik.
Dengan memahami bahwa karakter feminin atau maskulin tak terhubung langsung dan permanen dengan jenis kelamin biologis, maka mencari jawaban mengapa perempuan tega berbuat aniaya kepada anaknya sendiri bisa terjawabkan.
Pertanyaannya mengapa mereka sanggup? Ada yang berteori, letaknya ada pada kerentanan relasi antara perempuan dan lelaki. Lelaki dengan karakter maskulin dianggap sebagai pemimpin, perempuan dipimpin; lelaki imam perempuan makmum: lelaki penentu perempuan ditentukan; lelaki berkehendak perempuan mengikuti kehendak dan seterusnya. Relasi timpang ini memudahkan penundukkan kepada perempuan karena lelaki memiliki kuasa yang dengan kuasanya dapat menuntut kepatuhan perempuan atau anak yang ada dalam kuasanya.
Teori lain menegaskan bahwa karena karakteristik maskulin secara kultural politik senantiasa menjadi patokan dan karenanya mendapatkan keuntungan dan keutamaan secara sosial politik, padahal karakter itu bersifat bentukan, pada kasus ekstrim perempuan telah meniru dan mengadopsinya untuk menunjukkan bahwa perempuan pun sanggup. Dalam isu kekerasan ekstrim perempuan kemudian menjadi pelaku utama seperti bom bunuh diri.
Tuntutan sosial untuk senantiasa berkorban telah cukup untuk melakukan hal-hal yang diterima sebagai kepantasan seorang perempuan sesuai dengan harapan masyarakatnya. Apalagi jika dorongan itu bersumber dari ideologi yang diindoktrinasikan sedemikian rupa sampai tersedia lagi ruang tanya atau kritis. Ideologi itu bukan hanya memberi penghormatan atas keberaniannya tetapi juga janji kemuliaan yang teramat tinggi yang hanya bisa diraih oleh sang pemberani untuk berkorban. Ketika telah teryakinkan dapat meraih surga dan kemuliaan sebagai istri dan ibu, maka betapapun kejamnya di mata awam, perempuan niscaya sanggup melakukannya. Sedang sehari-hari saja telah begitu banyak pengorbanan apa lagi yang hendak dinanti untuk meraih kemuliaan yang dijanjikan dan diidamkannya. []
Ikuti tulisan menarik Lies Marcoes lainnya di sini.