Sipil dan Militer di Era Demokrasi Oligarki
Sabtu, 24 Agustus 2019 10:04 WIB
Artikel ini mengkaji tentang aksi pihak sipil dan militer dalam sejarah membangun republik di Indonesia. Dengan kajian itu, diharapkan dapat membantu untuk merumuskan peran dari masing-masing pihak, khususnya seusai Pemilu 2019 lalu, di era demokrasi oligarki.
Seusai Pemilu 17 April 2019 tampak bahwa ada perbedaan yang cukup jelas antara calon pemimpin berlatar belakang sipil dan militer. Perbedaannya terletak pada bagaimana cara memandang suatu persoalan dan mengambil tindakan yang diperlukannya. Maka tak heran jika sipil cenderung bergaya diplomatik, sedangkan militer berpola, sesuai dengan keahliannya, yaitu angkat senjata. Benarkah demikian?
Dalam sejarah, pimpinan sipil, seperti Bung Karno, Bung Hatta, dan Sjahrir, berpendidikan cukup tinggi. Karena itu, mereka bersikap sangat terbuka dan punya ide-ide yang amat cemerlang. Itulah mengapa mereka sudah terbiasa bertukar, bahkan bertarung, ide satu sama lain. Jadi, masuk akal jika mereka berkemanusiaan. Artinya, meski bisa tidak setuju antara yang satu dengan yang lain, namun mereka tidak mau saling menjatuhkan, apalagi sampai membunuh.
Sementara pimpinan militer, semisal A.H. Nasution, Alex Kawilarang, dan Gatot Subroto, yang tampak lebih muda dibanding para pimpinan sipil memang tidak terlalu berpendidikan tinggi. Namun, mereka justru berpandangan bahwa pimpinan sipil tidak bisa apa-apa alias tidak bisa memimpin dengan disiplin dan tegas. Buktinya, di tengah berbagai kekacauan pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang dapat dengan cepat dan tepat memadamkan api pemberontakan adalah militer. DI/TII atau PRRI/Permesta adalah sejumlah pemberontakan yang amat jelas mengarah pada perpecahan dan hanya mungkin diselesaikan dengan angkat senjata. Karena itulah, persatuan yang ditegakkan dengan senjata hanya dapat dikerjakan dengan aksi-aksi yang militeristik.
Dua wajah pimpinan yang secara historis telah membentuk Indonesia menjadi sebuah republik memberi pelajaran bahwa tidak mudah untuk mengontrol lembaga-lembaga, baik sipil maupun militer (Daniel S. Lev, 2017). Keduanya seperti punya tujuan dan kepentingan politiknya masing-masing, meski sama-sama selalu mengaku sedang melayani kepentingan masyarakat. Sementara bagi masyarakat kebanyakan, kepentingan yang menjadi tanggungjawab lembaga-lembaga untuk menyuarakannya justu malah sering terabaikan.
Maka, sebagaimana dicatat George McT. Kahin, bukan soal siapa/apa yang lebih berperan dalam membangun republik di Indonesia, apakah melalui “perjuangan” (militer) atau “diplomasi” (sipil). Tetapi justru yang penting untuk digarisbawahi adalah kuatnya rasa kebangkitan nasional atau nasionalisme sebagai prasyarat dari keduanya. Sebab hal itu menjadi penanda utama dari lahirnya kesadaran politis kerakyatan, khususnya selama Revolusi Kemerdekaan (1945-1949). Berkat kesadaran itulah, perjuangan untuk memerdekakan diri menjadi tak bisa dibendung lagi, bahkan oleh strategi dan persenjataan perang modern sekalipun.
Benedict Anderson menggambarkan dahsyatnya perjuangan itu dalam diri para pemoeda yang bukan hanya rela mati syahid, tetapi juga yang dengan nekadnya menghadapi tentara modern hanya dengan bambu runcing. Bayangkan, betapa tingginya semangat perlawanan dari anak-anak muda yang baru berumur belasan tahun dan mampu membuat tentara seperti Sekutu menjadi bengong melihat bagaimana rakyat bisa bangkit melawan mereka.
Tentu menjadi pertanyaan yang penting untuk direnungkan seusai Pemilu 2019 ini: apakah semangat itu masih ada? Ataukah, sudah lama menghilang dari diri, khususnya para pemuda masa kini? Penting untuk dicatat bahwa para pelopor nasionalisme di masa lalu tidak peduli Islam atau Kristen, mereka berjuang bersama-sama dengan satu tujuan Indonesia merdeka. Sedangkan para orang tua justru masih sibuk dengan agama masing-masing yang membuat mereka kebanyakan tidak diperhitungkan dalam perjuangan kemerdekaan.
Dan hal yang menarik lagi, “pemuda-pemuda nggak usah bersumpah lagi. Tapi bisa bergerak. Bisa berevolusi. Bisa melawan Belanda. Bisa mendongkel bupati.” Sebuah tantangan yang masih relevan untuk diwujudkan oleh anak-anak muda masa kini yang akan menjadi para pemimpin di masa depan.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Yang Tidak Biasa
Selasa, 9 Agustus 2022 15:56 WIB
Impian Arimbi
Jumat, 19 November 2021 06:25 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0





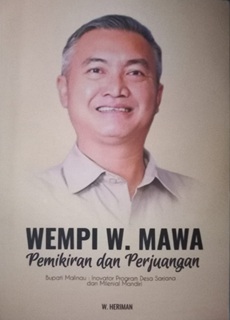

 Berita Pilihan
Berita Pilihan

 97
97 0
0

















