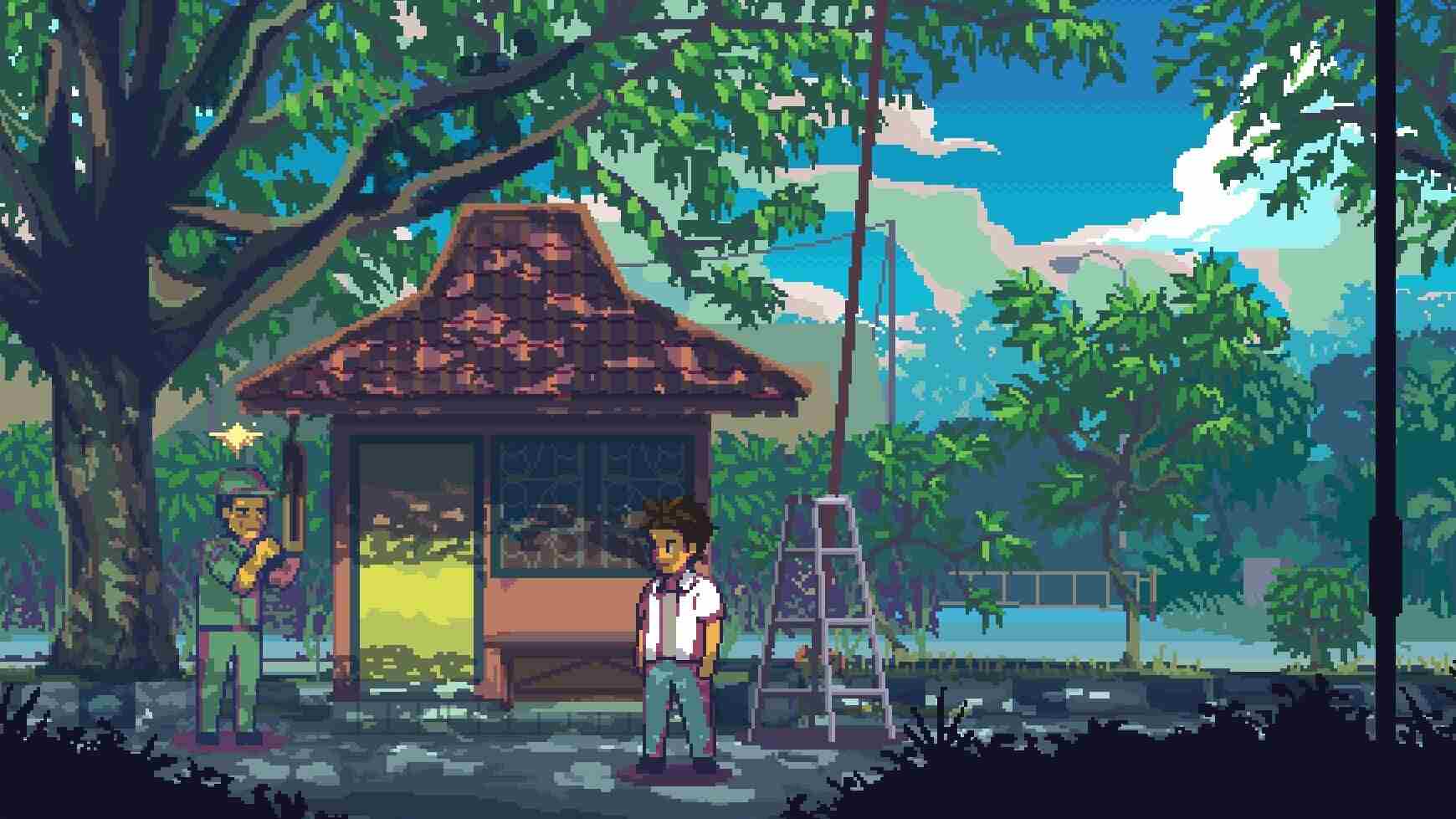20 Cerpen Indonesia Terbaik 2008
Senin, 1 Juni 2020 17:28 WIB
20 cerpen yang dimuat di surat khabar yang dipilih oleh panitia Anuegrah Sastra Pena Kencana untuk diterbitkan oleh Gramedia dan dilombakan melalui pooling SMS.
Judul: 20 Cerpen Indonesia Terbaik 2008
Penulis: Agus Noor, dkk
Tahun Terbit: 2008
Penerbit: Gramedia Pustaka Utama
Tebal: xxii + 204
ISBN: 978-979-22-3449-7
Saya baru saja mendapatkan buku ini. Di tahun 2020. Baru. Masih terbungkus plastik. Saya membelinya dengan harga yang lebih murah dari semangkok bakso. Artinya saya mendapatkan buku ini 12 tahun setelah terbit. Padahal buku ini adalah tentang karya sastra pada genre cerpen yang dianggap terbaik di tahun 2008. Kok bisa? Apakah orang Indonesia memang tak lagi menyukai sastra?
Budi Darma dalam pengantar di buku ini menengarai bahwa sejak tahun 1950, sastra Indonesia didominasi oleh produk cerita pendek. Perlahan tetapi pasti, karya-karya cerpen ini kemudian eksis di terbitan surat khabar. Baik itu surat khabar nasional, seperti Kompas, Republika, Koran Tempo dan Media Indonesia, serta koran-koran lokal seperti Suara Merdeka, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, Jawa Pos dan anak-anak korannya di berbagai kota. Kita harus berterima kasih kepada koran-koran ini yang masih memberi ruang untuk berkarya di tengah sempitnya ruang untuk menerbitkan karya dalam bentuk buku.
Buku yang berisi 20 cerpen yang dimuat di koran atau surat kabar yang dianggap terbaik tersebut diterbitkan dengan maksud untuk melibatkan masyarakat memberikan penilaian terhadap cerita pendek yang termuat di surat kabar. Tidak sekadar ikut menilai, masyarakat pun dijanjikan untuk mendapatkan hadiah yang wah.
Sedemikian burukkah kondisi sastra kita?
Ceita Pendek yang dulu mempunyai rumah yang sangat bergengsi, yaitu majalah sastra, kini terpaksa hanya menghuni tak lebih dari seperempat halaman koran. Para penulis cerpen rela saja karyanya dijuluki sastra koran. Mau apa lagi? Memang demikianlah kondisinya. Untunglah bukan hanya koran ibukota yang menyediakan tempat untuk memajang karya. Kosan-koran daerah pun membuka ruang bagi para cerpenis untuk mengunggah cerita.
Karena tempat memuatnya di koran, maka panjang cerpen pun dibatasi. Cerpen yang panjang otomatis disingkirkan. Bahkan sebelum cerpen tersebut dinilai kelayakannya dari segi sastra. Terpaksa para penulis cerpen harus menyesuaikan diri dengan ruang terbatas tersebut. Maka tema-tema aktual menjadi pilihan utama para penulisnya. Itu pun para penulis harus berhati-hati dengan detail narasi, supaya tak melewati jumlah kata yang diperkenankan oleh redaksi. Apakah keterbatasan tersebut membuat cerpenis tak mampu mencipta karya indah? Tentu saja tidak. Sastrawan, dalam hal ini cerpenis adalah orang-orang brilian yang gelisah terhadap diri dan sekitarnya. Keterampilannya merangkai kata membuat tema aktual dijabarkan dengan narasi yang pejal, tetapi tidak berjejal.
Entah disengaja atau tidak oleh tim yang menyeleksi, cerpen-cerpen yang termuat di buku ini memang bertema aktual dan kebanyakan lokal. Meski ada juga tema yang sedikit nakal. Tema anak sekolah yang dijejali pengetahuan, sehingga setiap hari harus menggendong ransel penuh buku, hampir seluruh hidupnya dipakai untuk mengerjakan PR adalah salah satu tema aktual. Kerisauan Gus tf Sakai membawa tema tersebut dirangkai dalam cerpen berjudul “Kami Lepas Anak Kami” di koran Suara Merdeka. Gus tf Sakai begitu riau dengan sistem pendidikan yang membuat anak seperti tong untuk menampung pengetahuan yang seragam, seperti baju yang dipakainya setiap ke sekolah. Apakah pendidikan adalah proses penyeragaman? Apakah ke sekolah hanya untuk menghafalkan segala ilmu?
Puthut EA mengemas tema korupsi di tengah bencana dengan menampilkan pemuda yang suka protes kepada penguasa dalam cerpennya berjudul “Di Sini Dingin Sekali.”
“Bukan Yem” karya Etik Juwita, “Turmaida” karya Hasan Al Banna dan “Saleha di Tengah Badai Salju” berkisah tentang perjuangan perempuan sebagai penopang ekonomi keluarga adalah contoh tema aktual lainnya. Ketiga cerpenis ini mengisahkan betapa perempuan tak dihargai. Padahal mereka telah bekerja sangat keras untuk mencukup kehidupan keluarganya.
Dan Triyanti Tiwikromo membahas perilaku para lansia di Panti Wreda yang sangat sulit dipahami oleh mereka yang muda. Uniknya, cerpen berjudul “Cahaya Sunyi Ibu” ini dihubungkan dengan Serangan Umum Satu Maret di Jogjakarta.
Memang tidak semua tema aktual yang dipilih oleh para pencerita. Agus Noor, Eka Kurniawan dan Lan Fang misalnya. Mereka memilih tema yang sedikit nakal untuk dijahit menjadi cerita. Agus Noor memilih tema tentang kematian. Betapa nikmatnya jika kita bisa memilih cara mati yang elegan dan penuh damai. Sang tokoh dalam cerpen ini adalah orang yang tahu kapan ia akan mati. Hari, tanggal, jam dan detiknya. Maka tokoh dalam cerpen ini menyiapkan diri cara mati yang tidak menakutkan. Ia mandi, berhias dan tidur dengan senyum untuk menanti detik terakhir nyawanya menghilang.
Eka Kurniawan membawa Marto yang menjadi Marni saat di Jakarta dan kemudian Martha saat di Los Angeles. Nah ketika akhirnya ia berganti kelamin supaya benar-benar menjadi Martha, Kemala - teman kencannya malah merasa ada jarak yang terlalu jauh untuk ditempuh. Sedangkan Lan Fang mengisahkan dua perempuan yang sama-sama menjadi istri kedua tetapi bernasip berbeda.
Marilah kembali membahas pertanyaan di awal tulisan tadi. Apakah orang Indonesia memang tak lagi menyukai sastra?
Upaya “Anugerah Sastra Pena Kencana” ini adalah salah satu tindakan dari kegelisahan sastrawan akan kurangpedulinya masyarakat terhadap sastra. Setelah penerbitan karya melalui buku menjadi semakin pengap, karya sastra koranlah sasaran para sastrawan untuk berkarya. Untunglah cerpen minggu (dan juga weekend, karena beberapa terbit di hari Sabtu) direspon cukup baik oleh pembacanya. Sebagai sebuah harapan yang masih tersisa, maka ceruk kecil saluran sastra yang masih dibaca oleh masyarakat umum ini kemudian diuri-uri sedemikian rupa.
“Anugerah Sastra Pena Kencana” adalah upaya dari para sastrawan untuk memberi penghargaan kepada anggotanya. Memang menyedihkan bahwa pemerintah dan masyarakat umum kurang peduli dengan karya sastra, sehingga sastrawan sendirilah yang mesti peduli kepada anggotanya.
Seandainya saat itu saya ikut memilih, cerpen mana yang harus saya pilih sebagai cerpen terbaik? Sebagai seorang penikmat sastra saya tentu menggunakan pertimbangan yang sangat subyektif. Sebab saya tidak mengakumulasi pengetahuan tentang kriteria karya cerpen yang baik. Saya hanya menikmati saya cerpen-cerpen yang saya baca. Jika temanya dan cara bertuturnya mengena pada rasa, maka saya akan menikmati cerpen tersebut. Jika tidak, ya tidak habis saya baca. Saya tinggalkan begitu saja. Jadi, lebih baik saya tidak memilih salah satu dari 20 cerpen yang sudah diseleksi oleh para Begawan sastra ini.
Memang berbahaya menggunakan metode pengumpulan SMS masyarakat. Sebab, seperti yang saya ungkapkan di atas, para penikmat satra akan memilih karya berdasarkan rasa. Itu kalau semua yang berkirim SMS adalah mereka yang memang suka menikmati sastra. Bisa saja para pengirim SMS ini hanya tergiur pada hadiah yang disediakan saja. Sebenarnya mereka bahkan tak pernah membaca satu cerpen pun dalam hidupnya. Atau mereka digerakkan oleh kepentingan tertentu untuk memilih salah satu cerpen. Semacam penggiringan masa begitu.
Penulis Indonesiana
3 Pengikut
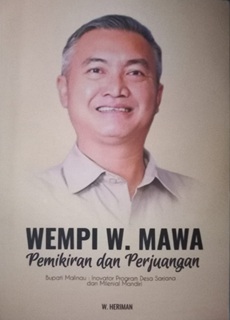
Wempi W. Mawa – Pemikiran dan Perjuangan
1 hari lalu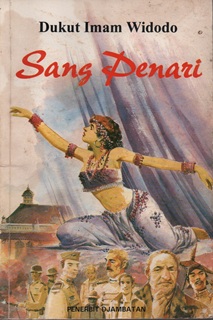
Sang Penari - Riwayat Mata-Mata Jerman Dari Jawa
3 hari laluBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0









 Berita Pilihan
Berita Pilihan 99
99 0
0