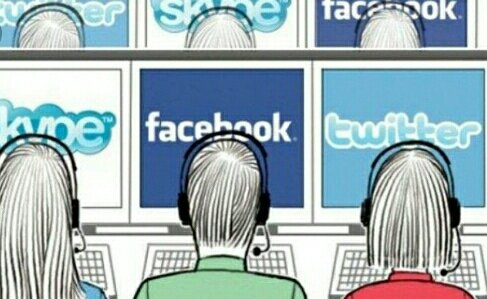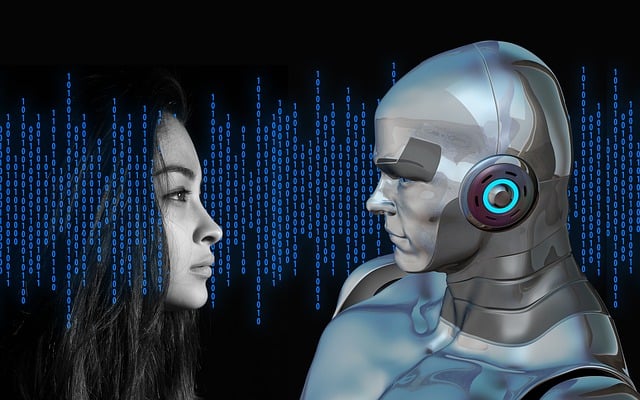Publikasi hasil penelitian Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bersama Universitas Diponegoro, KITLV Leiden, Universitas Amsterdam, Universitas Islam Indonesia, dan Drone Emprit mengenai fenomena buzzer tidaklah 100% mengejutkan, sebab cukup banyak informasi mengenai peran buzzer yang telah terungkap ke masyarakat. Namun, penelitian ini mengonfirmasi apa yang sudah beredar secara lebih akurat, menyediakan kedalaman pengetahuan, dan meluaskan wawasan apa yang telah diketahui publik tentang buzzer—mengenai cara kerja, struktur, afiliasi, hingga bayaran.
Walaupun para buzzer tidak tergabung dalam organisasi, bukan berarti mereka tidak terorganisasi. Hasil penelitian tersebut menyebutkan: ada jejaring yang melibatkan buzzer, kreator konten, koordinator, hingga influencer. Kreator bertugas membuat konten, sedangkan buzzer menyebarluaskannya di media sosial. Mereka bekerja di bawah komando koordinator. Begitu konten mengenai suatu isu telah disusun, buzzer bergerak menyebarkan konten ke berbagai media sosial melalui akun-akun mereka.
Buzzerizazi merupakan fenomena media sosial karena adanya faktor kecepatan dan keluasan distribusi pesan, konten, atau informasi, lalu viralisasi yang memungkinkan pesan direplikasi ke berbagai jejaring pengguna, serta volume pesan yang nyaris tak terhingga digelontorkan ke ruang publik dari waktu ke waktu. Penggelontoran pesan media sosial berpotensi menimbulkan kekacauan orientasi warga mengenai mana informasi yang dapat dipegang kebenarannya dan mana yang menyesatkan.
Mengapa buzzer menjadi fenomenal di tengah upaya mewujudkan iklim demokrasi yang sehat sebagaimana diinginkan rakyat banyak? Tak lain karena adanya kelompok kepentingan yang tidak menyukai adanya perbedaan pendapat—apa lagi penolakan—di tengah masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan yang menguntungkan kelompok kepentingan. Mereka ini bukan hanya pebisnis, tapi juga pejabat publik yang memiliki bisnis maupun yang memperoleh advantage dari dunia bisnis.
Para buzzer bekerja untuk memengaruhi opini publik agar menerima apa yang menjadi keputusan dan kebijakan pemerintah. Kita tidak akan lupa bagaimana buzzer demikian gencar menyuarakan dukungan pada revisi UU KPK dan omnibus law—UU Cipta Kerja. Sejumlah influencer yang dikenal publik pun dibayar agar mau menyuarakan dukungan. Ketika konten mengenai suatu isu menjadi trending topic di media sosial dan penerimaan masyarakat meningkat, maka inilah salah satu tolok ukur keberhasilan kinerja buzzer.
Siapakah pengguna buzzer? Karena buzzer bekerja atas dasar bayaran, maka hanya pihak yang memiliki sumber dana serta mempunyai kepentingan tertentu yang merasa perlu menyewa buzzer. Masyarakat luas jelas tidak membutuhkan buzzer, karena masyarakat bertumpu pada suara mereka sendiri—betapapun lemahnya dibandingkan dengan pengguna jasa buzzer, karena DPR pun dalam realitasnya bukanlah pelantang aspirasi rakyat.
Penelitian LP3ES dan institusi lain itu memperlihatkan bahwa praktik buzzerisasi media sosial telah mencemari ruang publik karena menciptakan semacam toxic environment, di mana informasi palsu dan menyesatkan, kabar bohong, serta pembalikan fakta menjadi bagian dari upaya mengubah opini publik. Masyarakat dipaksa meninggalkan pandangan lamanya dan memercayai informasi yang terus-menerus digelontorkan ke ruang publik.
Upaya itu dilakukan berkelanjutan, karena elite politik berkepentingan agar agenda mereka dapat berjalan tanpa gangguan yang tak bisa diatasi. Penggunaan buzzer merupakan wujud ketidakmampuan elite politik untuk meyakinkan masyarakat luas perihal agenda tersebut. Elite membutuhkan bantuan buzzer untuk memengaruhi masyarakat luas dengan cara membanjiri ruang publik dengan pendapat, informasi, hingga kabar yang membingungkan. Bahkan, mungkin saja penggelontoran pesan dan informasi itu dilakukan dengan memanfaatkan mesin bot yang bekerja tanpa tahu apa yang ia kerjakan.
Laporan The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation, yang ditulis oleh Professor Philip Howard, Direktur Oxford Internet Institute (OII) bersama Samantha Bradshaw, peneliti di OII, menyebutkan bahwa manipulasi oleh media sosial yang terorganisasi telah meningkat jadi dua kali lipat sejak 2017 hingga 2019. Di negara demokratis sekalipun, politisi dan partai politik menggunakan alat-alat propaganda untuk menyebarluaskan informasi yang sudah dimanipulasi. Pemerintah menggunakan alat-alat propaganda untuk mengendalikan opini publik maupun pers, serta mendiskreditkan para pengritik maupun suara oposisi.
Yang terjadi di ruang publik bukanlah perdebatan argumentatif, melainkan pembanjiran pesan dan informasi yang terus-menerus untuk memanipulasi opini masyarakat, mengacaukan pandangan yang berbeda, serta mendeskreditan warga yang bersikap kritis. Laporan Howard memaparkan bagaimana berbagai alat dan teknik propaganda digunakan, termasuk akun-akun palsu—bot, manusia, cyborg, serta akun yang diretas—untuk menyebarluaskan disinformasi.
Dari seluruh negara yang dikaji, Laporan Global menyebutkan penggunaan akun bot berlangsung di 80% negara, akun manusia di 87% negara, akun cyborg di 11% negara, serta akun yang diretas atau dicuri terjadi di 7% negara. Cybertroop menggunakan strategi komunikasi berbeda untuk memanipulasi opini publik, seperti menciptakan disinformasi, mass-reporting content ataupun mass-reporting accounts, dan strategi trolling, doxing, maupun harassment. Sebanyak 52 negara menggunakan disinformasi serta memanipulasi media untuk menyesatkan warga. Menurut Laporan ini, jumlah negara yang mensponsori troll untuk menyerang oposisi maupun aktivis sosial meningkat dari 27 negara (2018) menjadi 47 negara (2019).
Manipulasi opini publik melalui media sosial jelas merupakan ancaman terhadap upaya membangun demokrasi yang sehat dan adil. Seperti dikatakan Howard, demokrasi yang kuat membutuhkan akses kepada informasi berkualitas tinggi serta kemampuan warga untuk bergabung dalam debat publik yang mencerahkan, berempati, serta menemukan kesepakatan dengan cara yang sehat, jujur, dan adil. >>
Ikuti tulisan menarik dian basuki lainnya di sini.