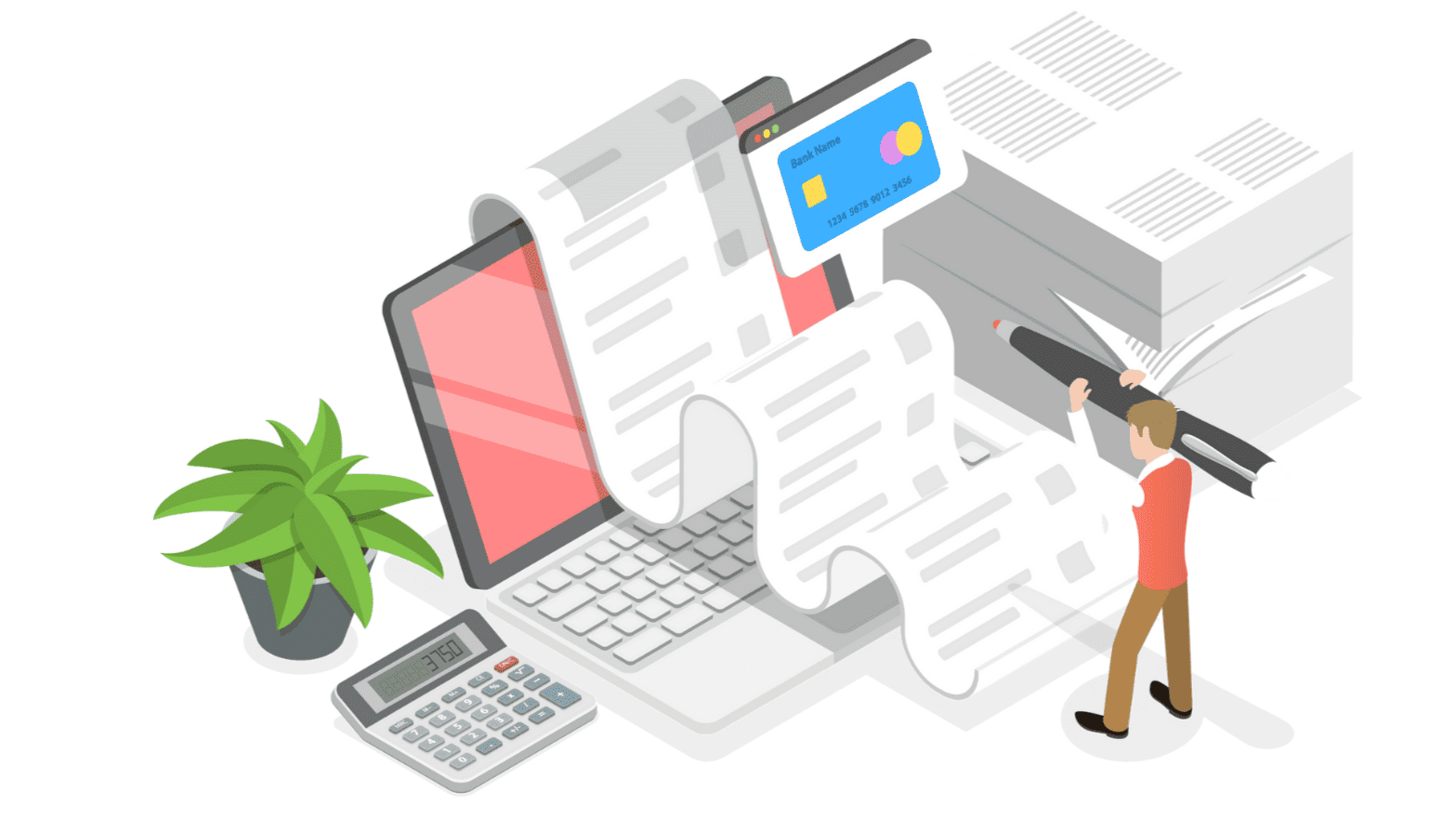Bermula dari Kaset Telanjang
Selasa, 18 Juli 2023 06:56 WIB
Sebuah kaset tanpa identitas apa pun mengarahkan Paul Simon ke Afrika Selatan. Perjalanan pencarian ini membuahkan album yang menjadi salah satu karya terbaiknya.
Oleh Purwanto Setiadi
Beberapa hari belakangan saya menyimak kembali lagu lawas karya Paul Simon berjudul The Boy In the Bubble. Saya mendengarkannya berulang-ulang. Dan saya jadi teringat cerita tentang asal usul album yang memuatnya, yang merupakan buah dari satu perjalanan panjang yang bermula dari sebuah kaset telanjang.
Di mobilnya, pada musim panas 1984, Simon mendapati kaset tanpa identitas—tak ada judul, tak ada nama artis, tak ada apa-apa—pemberian Heidi Berg, gitaris sekaligus temannya itu. Dia memutarnya, dan memperoleh surprise: musik yang keluar dari pengeras suara serta-merta menjernihkan pikirannya. Kala itu dia memang sedang tak punya rencana, dan malah absen memikirkan apa pun, setelah gonjang-ganjing tur reuninya dengan Art Garfunkel, pasangan duetnya; perceraiannya dengan istri keduanya; dan apalagi albumnya yang berjudul Hearts and Bones jeblok di pasar.
Setelah berulang kali mendengarkan musik yang digambarkannya beritme riang, menyemangati, dan pepat dengan permainan akordeon yang ganjil tapi penuh penjiwaan dia membuhulkan tekad: dia ingin tahu dari mana musik itu berasal dan siapa yang memainkannya. Untuk mendapatkan jawaban, dia melakukan perjalanan yang kemudian mengarahkannya ke Afrika Selatan. Bukan saja menjumpai seniman atau musikus yang dicarinya, dia akhirnya bahkan memutuskan untuk merekam album di negara itu, yang kala itu masih diboikot karena politik apartheid-nya. Judul album yang digarap antara 1985-1986 ini Graceland.

“Saya tak bakal pernah melalui semua hal ini kalau saya tak ngotot mencari tahu asal usul sebuah kopi dari sebuah kopi dari sebuah kaset,” kata Simon kepada Davic Fricke dari majalah Rolling Stone pada 1986.
Simon bukan musikus pertama yang jatuh hati kepada musik Afrika dan lalu mengambil unsur-unsurnya untuk menghasilkan album. Pada 1980-an itu, bisa dibilang, musikus Barat sedang dalam euforia menemukan kembali musik folk Afrika.
Elemen musik Afrika sebetulnya sudah mulai menyusup di Eropa karena emigrasi musikus-musikus dari benua itu sejak 1950-an, misalnya dari Kongo segera setelah pemerintahan dikuasai para diktator. Selain Kongo, negara-negara di Afrika yang ikut menyebarkan pengaruh musik Afrika ke lanskap internasional di antaranya adalah Nigeria, Ghana, Mali, Zimbabwe, Kamerun, Senegal, dan Afrika Selatan. Di samping menyemaikan elemen-elemen musik Afrika, para musikus diaspora ini pun “meminjam” anasir-anasir musik Barat.
Yang juga patut disebut sehubungan dengan hal itu adalah musikus-musikus kelahiran Afrika yang kebetulan sedang bermukim di Eropa. Pada 1970-an, merekalah yang memperkenalkan apa yang disebut afro-rock. Misalnya Osibisa, yang Indonesia dikenal berkat Sunshine Day. Dibentuk pada 1969 di London oleh empat ekspatriat Afrika serta tiga musikus dari kawasan Karibia, dan hingga kini masih aktif meski sudah bongkar pasang personel, Osibisa dianggap band “Afrika” paling sukses.
Mungkin asosiasi orang cenderung ke blues bila disebut pengaruh musik Afrika—yang menurunkan rock’n’roll dan musik pop pada umumnya. Tapi, di luar musik yang lahir dari penderitaan kaum kulit hitam di ladang-ladang kapas di Mississippi, Amerika Serikat, itu, ragam musik Afrika sesungguhnya sangat kaya. Malah yang lebih berakar sebagai musik tradisi atau folk adalah yang lazim dimainkan di acara-acara sosial, pesta dansa, atau di peristiwa-peristiwa penting yang menghimpun banyak orang. Ciri khasnya: sangat ritmis; biasanya pola iramanya kompleks, tak jarang terdiri atas satu irama yang “dibenturkan” dengan irama lain sehingga jadilah poliritme.
Yang membuat Simon tergugah di mobilnya adalah ragam musik semacam itu. Dia bukan musikus yang tak “gaul”, yang belum mengenal sama sekali musik Afrika. Tapi di kupingnya lagu-lagu yang terdengar dari kaset itu mirip dengan rock’n’roll di masa awal, yang dibawakan musikus kulit hitam di tempat-tempat hiburan perkotaan. “Iramanya cenderung cepat, rasanya dalam 2/4,” katanya.
Belakangan, berkat upayanya melacak, diketahui kaset tersebut berjudul Gumboots: Accordion Jive Hits, Volume II. Setelah tiba di Afrika Selatan, Simon pun berjumpa dengan musikus-musikus yang ikut berkontribusi di dalamnya, di antaranya The Boyoyo Boys, Tao Ea Matsekha, dan Ladysmith Black Mambazo, kelompok vokal yang terdiri atas sepuluh personel. Dengan merekalah, antara lain, dia menggarap sejumlah lagu di studio di Johannesburg. Selain dari proses produksi ini, sisa materi dari Graceland dirampungkan di New York City.
Dirilis pada Agustus 1986, Graceland memuat kandungan gado-gado yang eklektik. Ada pop, rock, a capella, zydeco yang meramu blues, R&B, musik lokal dan sangat dikenal di barat daya Louisiana, dan entah apa lagi. Seperti jenis musiknya, liriknya pun meliputi macam-macam topik. Simon mengaku dia menulis syair yang umumnya ringan, mengikuti irama dan not lagu-lagunya yang uptempo, setidaknya bila dibandingkan apa yang dilakukannya di album-albumnya terdahulu. Meski demikian, dia masih menyisipkan refleksi dan kritik, berdasarkan apa yang dia rasakan saat berada di Afrika Selatan.
Misalnya, ya, The Boy In the Bubble itu. Digubah bersama dengan Forere Motloheloa, pemain akordeon dari Lesotho, lirik lagu ini mengeksplorasi problem kelaparan dan terorisme, membenturkannya dengan kearifan dan optimisme. Menurut Simon, kesan bahwa pesan di dalamnya merupakan campuran antara perasaan-perasaan takut dan harapan adalah caranya melihat dunia: ada keseimbangan di antara kedua hal itu, “tapi cenderung berpihak ke sisi harapan”. Peter Gabriel, mantan vokalis Genesis yang memasukkan banyak unsur musik dunia dalam album-album solonya, termasuk Afrika, mengambil lagu ini, mengaransemennya dengan orkestra, untuk dia bawakan di satu proyek solonya pada 2010 (Simon membalasnya dengan membawakan Biko, karya Gabriel, di proyek yang sama).
Simon bercerita bagaimana dia mendapatkan idenya. Suatu malam, saat masih di Afrika Selatan, dia tertidur; di suatu titik saat kesadarannya mulai surut tebersit dalam benaknya kalimat ini: the way the camera follows him in slo-mo, the way he smiled at us all. “Saya mendapat bayangan dalam pikiran tentang film pembunuhan Kennedy, gerakan lambat itu, manakala kau menyaksikannya panel demi panel.... Entah bagaimana saya mendapatkan bayangan itu--mungkin karena ada terlalu banyak kekerasan yang terjadi di negara itu yang tak dibicarakan,” katanya.
Sebagai lagu pembuka, The Boy In the Bubble boleh dibilang mewakili dengan pas seluruh kandungan album yang memuatnya. Perjalanan panjang Simon tak sia-sia. Album ini berhasil di pasar, menjadi salah satu karya terbaik Simon, memenangi penghargaan Grammy pada 1987, dan pada 2006 dimasukkan ke daftar National Recording Registry karena memenuhi kriteria-kriteria “penting secara kultural, historis, dan estetis”.
Buat Simon, boleh jadi sukses itu bukan hal istimewa. Tapi jadi lain ceritanya jika direnungkan kembali betapa semua itu bermula dari sebuah kaset telanjang.
(*)
...wartawan, penggemar musik, dan pengguna sepeda yang telah ke sana kemari tapi belum ke semua tempat.
5 Pengikut

Stop Mengubur Karbon, Mulailah Mengubur Kebohongan
Senin, 29 September 2025 06:44 WIB
Tiada Pemerataan Tanpa Demokrasi di Tempat Kerja
Kamis, 18 September 2025 06:52 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
 Berita Pilihan
Berita Pilihan

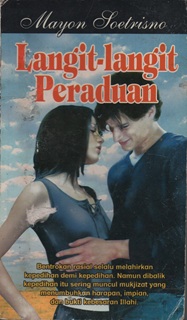






 97
97 0
0