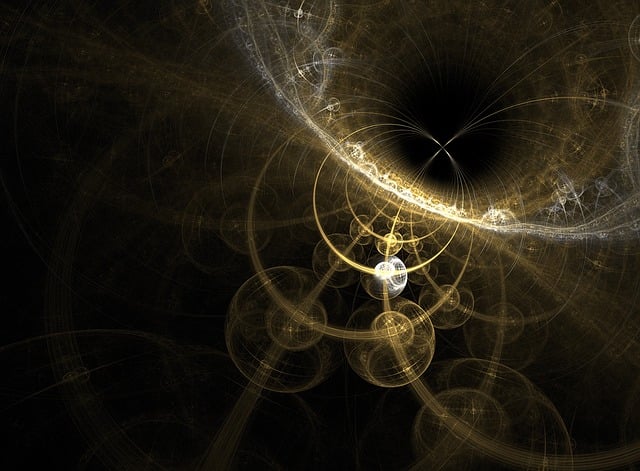Kita sebetulnya punya warisan berlimpah pitutur dan tradisi yang mementingkan dan menjunjung tinggi etika, juga moral. Tapi, sejak entah kapan dan memuncak pada hari-hari ini, sebagian dari kita secara sadar memilih untuk menormalkan hal yang sebaliknya: bahwa etika, juga moral sebagai kompas dari perilaku dan tindakan-tindakan kita, adalah perintang yang harus ditabrak.
Sebagian itu tidak sedikit; jumlahnya banyak. Mereka seakan-akan menganut prinsip “dua hal yang salah akan jadi benar”--padahal sebaliknyalah yang berlaku. Dan yang memasygulkan, lebih dari sekadar menyangkut penyimpangan, adalah sikap tersebut berkenaan dengan adanya upaya mempermainkan, menekuk-nekuk, hukum demi permainan kekuasaan belaka.
Tentu saja, dalam sejarah kita, seperti halnya sejarah bangsa lain, ada juga yang mengabaikan prinsip-prinsip yang jadi panduan untuk menilai mana yang baik dan mana yang buruk, juga mana yang benar dan mana yang salah, itu. Tapi yang demikian ini umumnya terjadi pada tataran terbatas. Ia tidak menjadi semacam penyakit menular, tidak mengundang dukungan yang masif.
Saya jadi teringat, suatu kali, pada satu artikel saya membaca kutipan ini di bagian awal: “Dalam kehidupan yang beradab, hukum mengapung di lautan etika.”
Kutipan itu disebutkan berasal dari Earl Warren, pengacara dan politikus yang pada 1953-1969 menjadi Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat. Asal usul ini mungkin tak teramat penting. Yang substansial adalah kandungannya, maknanya, juga implikasinya secara praktis.
Kata-kata Warren itu sesungguhnya menerangkan bahwa hukum dibangun dengan fondasi nilai-nilai etika. Maka, bisa dikatakan, dalam praktiknya, setiap kali kita menjalankan kewajiban legal kita, pada saat itulah pula kita memenuhi kewajiban etika kita. Kalau dalam masyarakat tak beradab justifikasi bagi tirani atau barbarisme bisa “memotivasi” kewajiban untuk mematuhi hukum, dalam masyarakat beradab kewajiban untuk bertindak etis bukan semata-mata merupakan hasil dari kewajiban untuk mematuhi etika, melainkan juga buah dari nilai-nilai etika yang bersifat mengikat yang telah memberitahukan kandungan hukum.
Tetapi hal itu sebetulnya “norma” di atas kertas. Dengan kata lain, ia masih berupa harapan, atau aspirasi.
Dalam realitasnya, bukan rahasia bahwa negara-negara yang dianggap beradab dan dengan baik dibatasi aturan hukum mungkin saja diperintah dengan hukum yang tak beradab--yakni tidak benar secara etika. Perbudakan, apartheid, dan penculikan/penyiksaan telah dipraktikkan menurut hukum di negara-negara yang dianggap beradab. Selain itu, dalam rezim liberal Barat ada doktrin dan prinsip tentang hak milik, kontrak, serta perbuatan melawan hukum yang penerapannya justru menimbulkan penderitaan bagi kaum miskin dan rentan. Padahal, jelas, hukum yang membolehkan perusakan lingkungan, eksekusi mati bagi orang yang tak bersalah, dan korupsi politik sama sekali bukan hal-hal yang etis.
Sebetulnya, sebagai aspirasi, aturan hukum yang didasari moral dan etika yang kukuh punya daya tarik. Kaum konservatif dan mereka yang merasa paling religius mungkin menumpukan pandangannya tentang hal ini pada kepercayaan bahwa hukum harus menjadi alat bagi penentuan moral--keyakinan etikanya, nilai-nilainya, dan prinsip-prinsipnya. Ia harus menjadikan kita berbudi. Kaum progresif dan mereka yang cenderung sekuler, di sisi lain, mungkin percaya bahwa hukum harus terus memperluas kebebasan, persamaan, dan toleransi. Masalahnya, kita tidak selalu melihatnya diekspresikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam perilaku dan tindakan.
Dalam praktik hukum kita sejauh ini, paling tidak, kita juga belum melihat adanya kemajuan yang substansial. Hukum sekadar ada, tidak ditegakkan. Atau, hukum dipermainkan--dipelintir, dimanipulasi--demi tujuan-tujuan yang tak berdimensi kemaslahatan publik. Misalnya, itu tadi, untuk melayani hasrat agar bisa terus berkuasa.
Kalau inteligensi, atau bahkan suara hati, kita tidak tersinggung oleh regresi semacam itu, yang terang-terangan dan nirmalu menafikan etika dan moral, mungkin kita memang sudah tak memilikinya lagi.
Ikuti tulisan menarik purwanto setiadi lainnya di sini.