Hilangnya Sejumlah Tanah Adat di Bali
Selasa, 28 Mei 2024 16:48 WIB
Tanah adat di Bali nyaris lenyap. Padahal di masa lalu setiap pembangunan rumah ibadah pasti ditopang tanah adat. Begitu pula untuk nafkah aparat desa adat, semuanya berupa tanah adat. Termasuk pemukiman warga. Kini alih fungsi dan alih kepemilikan terjadi. Betulkah penyebabnya karena harus ada sertifikat tanah?
Oleh Mpu Jaya Prema
Tanah adat nampaknya menjadi masalah klasik di seluruh Nusantara. Sedikit demi sedikit lenyap. Beralih fungsi menjadi tanah milik perorangan atau sebuah lembaga atau bahkan milik pemerintah daerah. Uniknya alih fungsi dan alih kepemilikan ini tanpa ada suatu keributan. Sepertinya mulus-mulus saja.
Di Bali baru belakangan ini orang tiba-tiba sadar kehilangan tanah adat ini. Sesuatu yang dinilai ganjil karena dalam berbagai dokumen tradisional yang berupa lontar -- tertulis dengan aksara Bali di daun rontal – disebutkan semua pura suci di masa lalu pasti punya tanah adat sebagai pendukungnya. Pura dan tanah adat menjadi satu kesatuan. Segala pembiayaan untuk pura itu, baik pembangunannya mau pun ritualnya, diambilkan dari hasil tanah adat ini. Kenapa lenyap begitu saja?
Saya harus merinci dulu bermacam-macam tanah adat yang dikenal masyarakat Bali tempo dulu sesuai yang ditulis dalam lontar. Setidaknya ada tujuh jenis tanah adat yang berawal dari pembukaan hutan yang dilakukan warga desa.
Yang pertama disebut “tanah bukti”. Lahan ini berupa tanah sawah atau tanah ladang yang dikuasai oleh desa adat yang diberikan kepada perangkat atau pejabat desa adat sebagai nafkah selama yang bersangkutan dalam masa jabatannya.
Yang kedua disebut “tanah pecatu”. Lahan ini adalah kawasan yang dikuasai oleh desa adat yang dibagikan kepada warga desa sebagai pembagian dari gotong royong dalam pembukaan hutan pada saat pembentukan desa. Di lahan inilah warga adat hidup sebagai petani.
Yang ketiga “tanah pecatu dalem”. Lahan ini adalah tanah sawah atau ladang yang diberikan oleh dalem (sebutan raja-raja kecil di masa lalu) kepada seseorang dengan melaksanakan kewajiban memberi upeti kepada dalem. Kepada siapa tanah itu diberikan adalah hak dalem.
Yang keempat disebut “tanah pelaba pura”. Adalah tanah yang dikuasai oleh desa adat yang dipergunakan untuk keperluan pura baik untuk lokasi di mana pura itu dibangun maupun berupa sawah atau ladang yang hasilnya diperuntukkan untuk kepentingan pura.
Yang kelima disebut “tanah ayahan desa”. Ini adalah tanah sawah atau ladang yang dikuasai oleh desa adat yang penggarapannya diberikan kepada warga desa dengan hak untuk dinikmati hasilnya, dengan catatan warga tersebut melaksanakan kewajiban (ayahan) berupa tenaga atau materi kepada desa adat saat diperlukan. Ini hampir sama dengan “tanah bukti”. Bedanya, jika “tanah bukti” berdasarkan masa jabatan perangkat desa, sedang “tanah ayahan desa” bisa dialihkan kapan saja.
Yang keenam disebut “tanah druwe desa”. Ini adalah kawasan yang disediakan oleh desa untuk kepentingan umum seperti misalnya untuk tanah lapang, balai desa, membangun sekolah dan lainnya.
Yang ketujuh disebut “tanah pekarangan desa”. Ini adalah tanah yang dikuasai oleh desa adat yang diberikan kepada warga desa untuk tempat mendirikan perumahan yang luasnya hampir sama bagi setiap warga desa. Tanah ini bisa diwariskan kepada keturunannya tetapi tidak bisa dialihkan kepemilikannya kepada warga di luar desa adat itu.
Demikianlah jenis-jenis tanah adat di masa lalu usai masyarakat bergotong-royong membangun desa dengan membuka hutan. Setelah desa itu terbentuk maka penerapan keharmonisan antar warga mulai dirumuskan dengan mengacu kepada ajaran leluhur yang disebut Tri Hita Karana – tiga keharmonisasn mulia. Harmonis dalam memuja Tuhan bersama-sama yang disebut parahyangan, harmonis sesama warga yang disebut pawongan, dan harmonis menjaga alam (terutama tanah adat) yang disebut palemahan.
Apa yang terjadi saat ini? Sesuatu yang sangat mengkhawatirkan. Palemahan sudah tidak harmonis lagi. Bukan karena tanah Bali menyempit, tetapi sudah terjadi alih fungsi dan alih kepemilikan pada palemahan. Tanah yang berada dalam lingkungan desa adat di Bali sudah dimiliki oleh orang luar yang tidak berkaitan dengan kegiatan adat di wilayah itu. Secara sederhana disebut bahwa palemahan di Bali sudah dihunii oleh penduduk yang bukan penduduk asli pada saat pembukaan hutan itu.
Cobalah berjalan-jalan di kawasan wisata Bali Selatan seperti Nusa Dua, Kuta, Canggu. Sudah sangat banyak wilayah desa adat yang dimasuki “warga pendatang”. Sawah dan tegalan sudah beralih fungsi menjadi bangunan beton, entah itu hotel, restoran, villa dan seterusnya. Bahkan baru saja terungkap ada kawasan yang diberi nama New Moscow. Di sana disinyalir ada sejumlah wisatawan dari Rusia yang sudah berhari-hari tinggal dan bekerja, lalu seolah-olah membentuk perkampungan tersendiri.
Apakah pemerintah kecolongan, kenapa ada wisatawan sampai melakukan pekerjaan tak semestinya di Bali? Kenapa sampai menguasai masalah palemahan, di mana pula pengawasan dari lembaga adat? Jika palemahan menyempit, baik karena lahannya sudah dijual ke orang asing atau beralih fungsi menjadi bangunan, gerak kegiatan ritual orang Bali sudah pasti terganggu.
Saya kembali mengajak nostalgia ke masa lalu. Aturan keberadaan tanah adat itu tatkala hutan baru saja dibuka berdasarkan saran atau ajaran yang tertulis dalam lontar yang dibuat Mpu Kuturan. Mpu Kuturan adalah pendeta Hindu asal Jawa yang datang ke Bali untuk menata kehidupan masyarakat Bali dan beliau pula yang membuat aturan soal desa adat, yang dulu disebut desa pekraman. Dalam lontar yang berjudul Panugrahan Mpu Kuturan (lontar ini sekarang jadi koleksi di Museum Lontar Gedong Kirtya di Singaraja) disebutkan, jika kita membangun pura wajib membuka sawah ladang untuk dukungan kebutuhan biayanya. Itu dikenal sebagai “tanah pelaba”, bisa berupa carik (sawah) atau abian (kebun).
“Tanah pelaba” ini sekarang mulai hilang, meski tidak di semua desa adat. Di kampung saya, Desa Adat Pujungan, “tanah pelaba” itu masih ada berupa kebun kopi yang luasnya sekitar 15 hektar. Konon, di masa lalu lebih luas lagi. Jadi, kalau ada upacara besar di pura desa, tak ada warga yang dipungut iuran untuk pembiayaan ritual. Semua biaya dari hasil tanah itu.
Lalu dari ke tujuh jenis tanah adat yang sudah diuraikan, apa saja yang masih ada di kampung saya? Selain “tanah pelaba pura” masih ada “tanah druwe desa” dan “tanah pekarangan desa”. Namun “tanah druwe desa” sudah habis dipakai untuk bangunan sekolah, ada enam buah Sekolah Dasar, satu SMP, satu SMA, satu pasar, satu balai budaya dan satu balai desa. Sedangkan “tanah pekarangan desa” tetap ada dengan bangunan rumah yang mulai mengikuti selera masa kini. Lahan perumahan ini tetap tak boleh diperjual-belikan secara formal. Bahwa di antara keluarga besar itu ada yang saling bertransaksi, itu secara non-formal. Masalahnya adalah tanah adat itu tidak memiliki sertifikat, seperti halnya “tanah pelaba pura” dan “tanah druwe desa”.
Sertifikat hak milik, nah itulah biang keladi dari lenyapnya sejumlah tanah adat di Bali. Program nasional agraria mewajibkan setiap tanah harus ada sertifikatnya. Jika sulit mendapatkan sertifikat maka pemerintah siap membantu. Jika perlu gratis. Bahkan kini ada kampanye sertifikat digital. Presiden Joko Widodo pun termasuk sangat aktif membagikan sertifikat tanah ke berbagai daerah. Di Bali imbauan agar semua tanah disertifikatkan itu sudah ada sebelum Presiden Joko Widodo, meski tidak segencar saat ini.
Tanah-tanah adat pun disertifikatkan. Atas nama siapa sertifikat itu? Tentu atas nama perorangan, yakni siapa yang secara nyata di lapangan mengerjakan tanah adat itu. Kalau itu berkaitan dengan pura (tempat ibadah) maka ada yang disebut pemangku di pura itu. Tanah adat di luar peruntukan tempat ibadah, pemegang sertifikat adalah siapa yang bekerja di tanah itu. Sertifikat bisa dimiliki oleh perorangan dan bisa dimiliki oleh lembaga berbadan hukum. Nah, persoalannya adalah lembaga adat bukan berbadah hukum.
Di sinilah awal dari hilangnya tanah adat di Bali. Karena sertifikat harus dimiliki perorangan atau badan hukum, maka tanah adat kemudian berangsur-angsur menjadi kabur kepemilikannya. Ditambah dengan cueknya masyarakat dan adanya alih generasi, status sertifikat itu pun menjadi rancu, pindah tangan antar generasi. Akhirnya pindah tangan antar warga, termasuk warga pendatang. Satu-satunya yang aman adalah “tanah pekarangan desa”. Penyebabnya, kalau beralih tangan ke pihak luar para tetangga pasti curiga dan melaporkan ke adat. Ini pun hanya terjadi di desa-desa pedalaman, desa tua istilah orang Bali, seperti di desa saya. Kalau desa di perkotaan yang bukan dari “pembukaan hutan” sudah nyaris tak ada lagi tanah adat.
Andai pun, misalnya, ada yang menggugat tanah adat itu, pastilah pemenangnya adalah siapa yang tercantum di sertifikat itu. Para tetua yang tahu sejarah tanah adat itu sudah pada tiada, bagaimana bisa dijadikan saksi.
Adakah yang masih peduli dengan tanah adat dalam kasus di Bali ini? Jika ada yang ingin menyelamatkan warisan leluhur yang masih tersisa, meski cuma sebagian kecil, hentikan pensertifikatan tanah adat. Atau lembaga desa adat dibuatkan badah hukum khusus sehingga berhak atas kepemilikan tanah. Mari hormati hak-hak masyarakat adat. ***
Penulis Indonesiana
6 Pengikut

Ya Tuhan, Kami Bertobat
1 hari lalu
Tunda Dulu Bepergian Ke Bali
Sabtu, 12 Juli 2025 15:13 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0
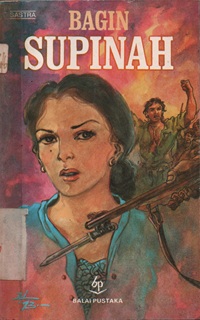






 99
99 0
0




 Berita Pilihan
Berita Pilihan










