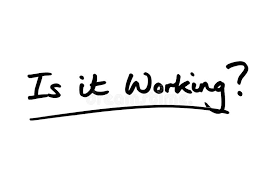Gunoto Saparie lahir di Kendal, Jawa Tengah, 22 Desember 1955. Aktif dalam dunia literasi, menulis cerita pendek, puisi, novel, dan esai. Kumpulan puisi tunggalnya yang telah terbit adalah Melancholia (Damad, Semarang, 1979), Solitaire (Indragiri, Semarang, 1981), Malam Pertama (Mimbar, Semarang, 1996), Penyair Kamar (Forum Komunikasi Wartawan Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah, Semarang, 2018), dan Mendung, Kabut, dan Lain-lain (Cerah Budaya Indonesia, Jakarta, 2019), dan Lirik (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2020). Kumpulan esai tunggalnya Islam dalam Kesusastraan Indonesia (Yayasan Arus, Jakarta, 1986) dan Kiri Islam dan Lain-Lain (Satupena, Jakarta, 2023). Kumpulan cerita rakyatnya Ki Ageng Pandanaran: Dongeng Terpilih Jawa Tengah (Pusat Bahasa, Jakarta, 2004). Novelnya Selamat Siang, Kekasih dimuat secara bersambung di Mingguan Bahari, Semarang (1978) dan Bau (Pelataran Sastra Kaliwungu, Kendal, 2019) yang menjadi nomine Penghargaan Prasidatama 2020 dari Balai Bahasa Jawa Tengah.\xd\xd Ia juga pernah menerbitkan antologi puisi bersama Korrie Layun Rampan berjudul Putih! Putih! Putih! (Yogyakarta, 1976) dan Suara Sendawar Kendal (Karawang, 2015). Sejumlah puisi, cerita pendek, dan esainya termuat dalam antologi bersama para penulis lain. Puisinya juga masuk dalam buku Manuel D\x27Indonesien Volume I terbitan L\x27asiatheque, Paris, Prancis, Januari 2012. Selain menjabat sebagai Ketua Umum Satupena Jawa Tengah juga sebagai Ketua Umum Dewan Kesenian Jawa Tengah, Ketua Komunitas Puisi Esai Jawa Tengah, dan Ketua Umum Forum Kreator Era AI Jawa Tengah. Ia juga aktif di kepengurusan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Jawa Tengah, Majelis Kiai Santri Pancasila, dan Forum Komunikasi Keluarga Purnawirawan Baret Merah Jawa Tengah. Pernah menjadi wartawan, guru, dosen, konsultan perpajakan, dan penyuluh agama madya. Alumni Akademi Uang dan Bank Yogyakarta dan Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Semarang.
Membayar Pajak Bukan Hanya Perkara Teknis, tapi Juga Imajinasi
Jumat, 22 Agustus 2025 17:15 WIB
Membayar pajak adalah ikut serta membangun sesuatu yang tak kasatmata: negara sebagai ruang bersama.
Oleh Gunoto Saparie

Optimisme Reformasi Perpajakan
Keadilan, barangkali, selalu terasa jauh. Orang membayangkannya sebagai sesuatu yang rapuh: seperti garis tipis di atas pasir pantai yang segera dihapus ombak. Maka ketika negara bicara tentang reformasi pajak, yang terngiang adalah sebuah usaha untuk menegakkan garis itu. Direktorat Jenderal Pajak menyebutnya Core Tax Administration System. Sebuah sistem baru, mesin birokrasi yang lebih rapi, lebih cepat. Ia diberi nama yang teknokratis, Coretax, seolah-olah yang inti dari hubungan antara negara dan warga hanyalah perangkat lunak.
Kita percaya, mesin itu bisa mendamaikan sesuatu yang lama mengganjal: jurang antara fiskus dan wajib pajak, antara kecurigaan dan keterbukaan. Tetapi mungkin yang sesungguhnya sedang dicari bukanlah sekadar teknologi. Di balik layar situs pajak.go.id yang berkilau dengan visualisasi data, ada suara lain: suara tentang partisipasi, tentang kesediaan orang untuk rela menaruh sebagian penghasilannya ke kas negara.
Pajak, pada akhirnya, bukan hanya kewajiban administratif. Ia adalah cerita tentang kepercayaan. Pemerintah bicara tentang keadilan. Tentang beban yang lebih ringan bagi mereka yang kecil, dan lebih berat bagi mereka yang besar. Tentang progresivitas. Tetapi seperti kata seorang filsuf, keadilan tidak pernah selesai dihitung, hanya bisa dirasakan. Apakah sistem baru ini kelak bisa membuat orang percaya bahwa uang yang diambil darinya benar-benar kembali dalam bentuk sekolah, jalan, atau rumah sakit?
Ada yang menganggap reformasi perpajakan hanyalah perkara teknis. Tetapi ia juga perkara imajinasi. Membayar pajak adalah ikut serta membangun sesuatu yang tak kasatmata: negara sebagai ruang bersama. Tanpa itu, pajak hanya dipandang sebagai beban, dan negara sekadar pemungut. Maka kita sampai pada pertanyaan yang lebih tua dari semua peraturan perpajakan: Apakah arti kebersamaan? Coretax bisa saja berjalan lancar, situs pajak bisa saja tampil canggih, tetapi yang menentukan tetaplah rasa percaya itu, sesuatu yang tak bisa diprogram.
Reformasi perpajakan, kata pemerintah, adalah perekat. Pemersatu. Mungkin benar. Tapi ia hanya akan benar bila orang merasa dirinya tidak sendirian ketika membayar. Bila mereka melihat yang lain pun, tanpa terkecuali, ikut serta. Bila garis tipis di atas pasir itu, untuk sesaat, tak mudah dihapus ombak.
Memang, ada yang menarik setiap kali kita berbicara tentang reformasi perpajakan. Ia penuh dengan optimisme. Tentang Coretax yang akan jadi tulang punggung digitalisasi. Tentang rasio pajak yang akan naik. Tentang restitusi yang lebih cepat. Tentang pemeriksaan yang lebih ringkas.
Semacam sebuah janji: sebuah negara yang makin dewasa dalam memungut pajak dari rakyatnya. Tetapi di balik janji, kita teringat bahwa pajak selalu punya wajah ganda. Ia bisa jadi alat pemerataan, tetapi juga bisa terasa sebagai penagihan yang dingin, tanpa wajah.
Kenaikan PPN, misalnya. Angka 12 persen memang terdengar kecil, hanya satu digit lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, pajak konsumsi selalu memukul rata: tak peduli orang miskin membeli beras atau orang kaya membeli tas bermerek. Negara lalu bergegas menambal ketidakadilan itu dengan insentif: rumah tapak, kendaraan listrik, PPh 21 DTP. Tetapi, kita tahu, insentif semacam itu sering lebih banyak dinikmati oleh mereka yang sudah relatif mapan. Maka, adakah reformasi itu menjawab sesuatu yang lebih dalam: rasa adil?
Coretax, dengan segala keunggulan digitalnya, mungkin memang akan membuat lebih sedikit celah bagi manipulasi. Tapi, bukankah teknologi juga bisa menciptakan jarak? Mesin yang dingin, sistem yang kaku, algoritma yang tak bisa bernegosiasi. Pada saat yang sama, masih ada jutaan wajib pajak kecil, pedagang pasar, nelayan, buruh, yang bahkan belum sepenuhnya terbiasa dengan ponsel pintar.
Barangkali inilah paradoks reformasi: semakin modern sistem dibangun, semakin rawan pula ia meninggalkan mereka yang paling sederhana. Dan tetap saja, yang utama dalam pajak bukan sekadar efisiensi. Ia adalah persoalan etis. Seberapa besar negara boleh masuk ke kantong warganya. Seberapa adil beban itu dibagi. Seberapa jujur pemerintah mengembalikan pungutan itu menjadi jalan, sekolah, atau rumah sakit.
Memang benar, kemandirian fiskal merupakan tujuan. Tetapi, di ujungnya, mungkin yang lebih penting bukan soal mandiri atau tidaknya negara. Melainkan apakah setiap rupiah yang diambil benar-benar kembali dalam wujud yang bisa disentuh warga: air bersih di desa, bus kota yang terjangkau, udara yang tak sesak oleh polusi.
Di titik itulah, pajak bukan lagi hanya angka di atas kertas. Ia bisa hadir sebagai rasa: rasa percaya, atau justru rasa dikhianati. Mungkin di sanalah inti dari reformasi itu akan diuji. Bukan di ruang-ruang konferensi pers, bukan pula di pasal-pasal Peraturan Menteri Keuangan. Melainkan di meja dapur keluarga sederhana yang menghitung belanja harian, dan bertanya dalam hati: “Pajak ini apakah sungguh akan kembali kepada kami?”
*Gunoto Saparie adalah Ketua Umum Satupena Jawa Tengah.Tinggal di Jalan Taman Karonsih 654, Ngaliyan
Penulis Indonesiana
2 Pengikut
Baca Juga
Artikel Terpopuler



 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0