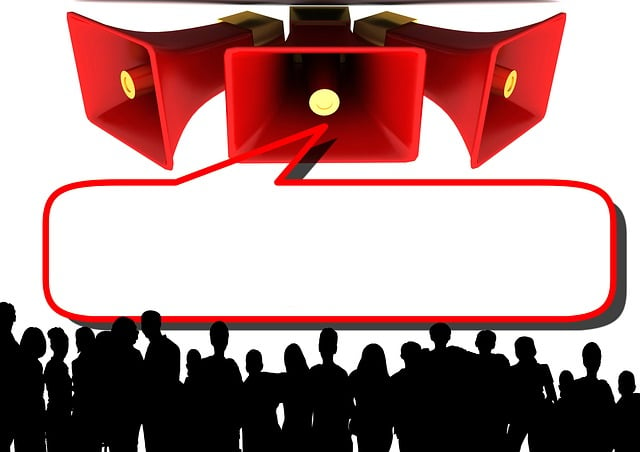Oleh: Mpu Jaya Prema
Keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2023 yang ditujukan kepada kepala pengadilan negeri dan kepala pengadilan banding, mengundang polemik panjang. SEMA itu berisi tentang “Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan” dikeluarkan pada 17 Juli 2023 lalu. SEMA ini tentu saja berlaku interen, namun karena menyangkut orang banyak, maka heboh tak terhindarkan. Apalagi ini masalah pencatatan perkawinan yang dianggap masyarakat sebagai bentuk pelayanan administrasi negara kepada warganya.
Kawin adalah urusan pribadi masing-masing penduduk. Cinta tak bisa dibatasi oleh agama, apalagi di sebuah negara besar dengan banyak agama dan budaya yang berbeda. Keberagaman Indonesia tak bisa dibatasi dengan sekat-sekat agama sehingga seharusnya perkawinan bisa dilakukan secara bebas sebagai hak asasi manusia. Nah, urusan HAM pun dibawa dalam kasus ini.
Masalahnya adalah negeri ini mengatur perkawinan dengan undang-undang. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu mengatur bagaimana syarat sebuah perkawinan yang dianggap sah sehingga bisa didaftarkan ke negara. Pasal 2 ayat (1) undang-undang ini jelas menyebutkan: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”
Bagaimana ajaran agama mensyaratkan bahwa perkawinan itu sah? Semua agama yang diakui di negeri ini punya pedoman yang mengatur bahwa perkawinan beda agama dianggap tidak sah, karena perkawinan itu adalah sarral dalam ritual keagamaan. Sakral di setiap agama bisa berbeda-beda.
Ajaran Islam jelas memerintahkan umatnya melangsungkan perkawinan dengan sesama Islam sebagaimana termaktub dalam kitab sucinya. Hal ini diperjelas lagi dengan Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tanggal 28 Juli 2005 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 (c) dan Pasal 44 yang menetapkan bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
Agama Kristen juga melarang perkawinan beda agama sebagaimana tertera dalam kitab sucinya. Begitu pula dengan pemeluk agama Katholik yang menyebutkan perkawinan adalah sebuah sakramen atau sesuatu yang kudus dan suci.
Bagaimana dengan umat Hindu? Karena perkawinan adalah sesuatu yang sakral maka perkawinan dalam Hindu (wiwaha samkara) adalah penuh dengan ritual keagamaan. Maka sangatlah tidak mungkin mereka yang menjalankan ritual itu ada yang bukan beragama Hindu dalam arti pasangan ini berbeda agama.
Kawin Sah Juga Secara Adat
Tidak usahlah kita rinci bagaimana ritual perkawinan dalam Hindu itu. Kita cukup menelusuri bagaimana perkawinan itu dicatat oleh negara. Perkawinan umat Hindu mendapatkan akte pengesahan (pencatatan) dari Kantor Catatan Sipil, karena umat Hindu tidak punya Kantor Urusan Agama (KUA) sebagaimana umat Muslim. Pengajuan akte ke Catatan Sipil menggunakan formulir dengan lampiran ada pengesahan perkawinan secara adat dan agama. Jadi kalau dalam UU hanya disebut sah secara agama, untruk umat Hindu di Bali malah lebih berat lagi, sah juga secara adat. Karena setiap warga di Bali harus masuk dalam strata adat. Dalam surat lampiran ini juga disebutkan, siapa pendeta Hindu yang memimpin ritualnya di mana alamat pendetanya, di mana ritual perkawinan dilangsungkan, dan seterusnya.
Pendeta membubuhkan tanda tangan di formular itu lalu ada saksi dari ketua adat, baik ketua adat tempat tinggal mempelai pria, maupun ketua adat asal mempelai putri, jika pasangan ini berdomisili di desa adat yang berbeda. Dan memang upacara ritual perkawinan yang sakral dipimpin pendeta ini baru berlangsung setelah kepala adat masing-masing mempelai mengadakan pertemuan dan menandatangani formulir yang diperlukan. Kantor Catatan Sipil tak akan memberikan pengesahan kalau lampiran surat-surat itu tak ada. Lalu, bagaimana seorang pendeta pada saat memimpin ritual perkawinan? Pasangan pengantin itu haruslah satu agama dan agama itu mutlak Hindu. Namanya saja perkawinan Hindu dengan pendeta Hindu, pastilah semuanya beragama Hindu.
Tidak mungkin terjadi pasangan pengantin itu beda agama. Misalnya, yang lelaki Hindu yang perempuan Islam atau Katolik atau Buddha. Pendeta memimpin ritual dengan penuh kesakralan, bukan akting atau main-main untuk dokumentasi atau konten. Bagaimana mungkin pendeta menjalankan upacara ini kalau salah satunya bukan Hindu? Tak ada doa atau mantram yang bisa dilantunkan pendeta jika pengantin itu beda agama. Semua doa atau mantram dengan bahasa Sansekertha, bahasanya kitab Weda. Andai satu orang mempelai bukan Hindu, apa mau dia larut dalam ritual itu?
Pendeta Hindu pun tak perlu menanyakan apa agama kedua pengantin sebelum memimpin upacara. Ya, sudah pasti Hindu, karena sebelumnya ketua masing-masing adat yang memprosesnya. Bagaimana kalau salah satu pasangan itu bukan beragama Hindu? Harus dihindukan dulu sebelum melangsungkan ritual perkawinan. Upacara masuk Hindu ini disebut Sudhiwadani. Boleh dipimpin oleh pendeta tetapi cukup sah jika dilakukan oleh tetua adat. Sudhiwadani itu dilangsungkan menjelang ritual pernikahan. Prosesnya sederhana saja dan surat pengesahan masuk Hindu itu cukup diketahui Parisada Hindu Dharma Indonesia tingkat desa atau kecamatan. Tak perlu sampai mengubah statusnya di KTP yang memerlukan proses lama. Intinya adalah kedua mempelai harus satu agama, yakni Hindu.
Bisakah ritual ini disiasati dengan main akal-akalan? Artinya upacara masuk Hindu atau Sudhiwadani itu hanya pura-pura saja? Ada banyak rumor hal itu sering terjadi dan banyak orang melakukannya. Bahkan orang-orang yang berpendidikan tinggi – maklum saja, orang desa yang lugu mana berani main akal-akalan itu. Ceritanya begini. Ada lelaki Hindu akan kawin dengan pacarnya yang beragama bukan Hindu. Supaya perkawinan itu sah, sang pacar melakukan ritual Sudhiwadani dulu untuk masuk Hindu. Setelah ritual pernikahan selesai, pencatatan perkawinannya disahkan Catatan Sipil. Selang beberapa hari atau minggu, sang pacar yang sudah jadi istri ini kembali ke agamanya semula.
Bahwa ini akal-akalan atau memang “berubah pikiran” bukan urusan para pendeta yang tadinya memimpin ritual perkawinan. Juga bukan urusan ketua adat. Ini adalah orang yang pindah agama, hal yang tak bisa dicampuri karena memeluk agama adalah hak asasi manusia tanpa paksaan. Bagaimana mungkin orang dilarang pindah agama? Memeluk agama dan keyakinan itu urusan pribadi dan dilindungi hak asasi. Begitu pula sebaliknya, calon istri yang kembali ke agama asal mengajak calon suaminya untuk ikut agamanya dan melangsungkan perkawinan ulang dengan agama yang baru itu. Semuanya tergantung mereka, mau pindah agama atau tetap dengan agama masing-masing.
Sering sekali kita mendengar bahwa pasangan yang beda agama tetap bisa rukun sampai punya anak. Mereka konon bahagia. Entah mereka melakukan perkawinan dengan sistem “akal-akalan” itu atau melangsungkan perkawinan di luar negeri yang kemudian bisa dicatatkan di Indonesia. (Ini sebenarnya kasus aneh juga dan diskriminatif, sudah jelas beda agama kok bisa dicatatkan asal kawin di luar negeri).
Ada pula cerita yang lebih serem. Atau mengasyikkan? Kawin akal-akalannya lebih serius lagi. Pasangan mempelai beda agama, yang satu Hindu dan yang satu Islam. Mereka melangsungkan perkawinan dua kali. Pertama di Bali dengan salah satu mempelai ikut ritual Sudhiwadani, lalu kawin secara Hindu. Beberapa hari kemudian, yang baru masuk Hindu itu kembali masuk agama Islam, dan proses perkawinannya kembali dilakukan di KUA. Tentu ada yang mualaf terlebih dahulu. Ini untuk menyenangkan masing-masing keluarga. Keluarga yang Hindu senang, lalu keluarga yang muslim juga senang. Urusan selanjutnya terserah bagaimana keluarga baru ini, apa tetap ke agama aslinya atau salah satu mengalah. Konon banyak yang melakukan hal ini, tapi ini sebatas konon, karena agak rishi mempersoalkan urusan pribadi orang lain.
Yang perlu dipertanyakan, bagaimana mengasuh anak-anaknya, apakah tidak mengalami kesulitan? Lalu bagaimana kalau suami istri itu kelak meninggal dunia, apakah tidak ada ribut-ribut masalah penguburannya? Nah, ini lagi-lagi ada cerita yang heboh sekaligus memprihatinkan.
Kawin Dua Kali
Ada pasangan suami istri beda agama, yang lelaki Hindu dan yang perempuan Islam. Proses perkawinannya sepertinya mendua dengan teknik “menyenangkan masing-masing keluarga”. Namun masing-masing keluarga tidak tahu kalau menjelang perkawinan itu ada yang pindah agama secara akal-akalan. Bertahun-tahun tak ada keluarga masing-masing yang tahu masalah ini. Kedua pasangan itu agaknya menyimpan rahasia dengan bagus. Keluarga itu pun terkesan sangat bahagia. Tiba waktunya lelaki itu meninggal dunia. Tentu saja dikuburkan secara Islam di Jawa, di mana mereka menetap. Mendengar ini keluarga di Bali marah besar, mau membongkar kembali kuburannya supaya bisa diaben di Bali. Tak bisa, padahal berbagai upaya sudah dilakukan. Karena faktanya surat nikah keluarga itu berdasar perkawinan yang kedua, secara Islam.
Keluarga di Jawa punya bukti otentik akte nikah mereka di KUA. Lalu berkembanglah cerita sampingan, konon keluarga lelaki di Bali dapat bisikan dari dukun (istilah di Bali balian) bahwa lelaki itu rohnya terombang-ambing karena minta diaben. Ya permintaan itu dipenuhi dengan ngaben tanpa jenazah (disebut sawa pranawa) dan roh lelaki itu “dipanggil” dalam ritual.
Itulah resiko kawin beda agama dengan cara “akal-akalan”. Untuk calon pengantin yang masih beda agama, kalau memang tak ada kesepakatan soal “menyatukan agama” lebih baik batal kawin. Kalau “kumpul kebo” juga resikonya besar jika merujuk ajaran agama disebut berzina, tanpa ada akte nikah (pencatatan perkawinan) tanpa ada perlindungan hukum, baik untuk pasangan itu maupun anak-anaknya. Ini umumnya nasehat dari pemuka agama.
Revisi Undang-Undang Perkawinan
Begitu banyak kisah atau catatan yang pernah ada di sekitar perkawinan beda agama. Meski kita punya UU Tentang Perkawinan yang tidak menganggap sah perkawinan tanpa hukum agama, toh banyak orang melakukan hal itu. Berbagai jalan ditempuh untuk mencatatkan perkawinannya, antara lain, lewat penetapan pengadilan negeri. Juga lewat uji materi UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Paling tidak sudah dua kali MK menolak uji materi ini. Namun pengadilan negeri sudah berulang kali justru mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama itu. Sampai kemudian MA mengeluarkan edaran lewat SEMA No. 2 Tahun 2923. Surat edaran ini memang terkesan MA telah melakukan tekanan terhadap para hakim dan seolah-olah hakim tak boleh punya tafsiran lain soal ini.
Pro kontra muncul. Banyak yang mendukung MA dengan surat edaran ini. Umumnya pemuka agama mendukung surat edaran ini dengan alasan ajaran agama memang melarang perkawinan beda agama. Setidaknya perkawinan itu tidak sah secara agama. Konsekwensinya tidak bisa dicatatkan oleh negara, sesuai undang-undang.
Yang menolak surat edaran MA dan tetap ingin ada celah untuk mencatatkan perkawinan beda agama dasarnya adalah hak asasi manusia. Perbedaan agama, termasuk beda suku, tak seharusnya menghambat orang untuk bersekutu dalam cinta di negeri yang majemuk ini. Kelompok ini kemudian sampai pada usulan untuk merevisi UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu.
Andai UU ini direvisi maka tentu akan banyak sekali pasal yang akan ditambahkan. Apalagi revisi itu dimaksudkan untuk membolehkan perkawinan beda agama. Di beberapa budaya seperti Bali, misalnya, agama berkaitan erat dengan adat. Jika pasangan keluarga itu berbeda agama, bagaimana kedudukan keluarga itu dalam adat? Lalu yang masih bertahan dengan agama Hindu, sementara pasangannya beragama lain, kemana mereka bergabung dalam persembahyangan di pura? Belum lagi kalau ada kematian, tidak ada kuburan untuk umum di Bali. Yang ada kuburan adat (untuk Hindu), kuburan Muslim, kuburan Katolik dan seterusnya. Memang belakangan ini berkembang adanya krematorium, tempat kremasi jenazah yang banyak dipergunakan oleh mereka yang bermasalah dengan adat. Namun harap dimaklumi, tidak semua jenazah orang Hindu di Bali harus dikremasi.
Belum lagi masalah ahli waris dan urusan-urusan duniawi, seperti perceraian, mengangkat anak dan seterusnya. Memang bisa saja diupayakan jalan tengahnya dan kebayang betapa ribetnya undang-undang itu. Lalu yang sangat krusial adalah apakah perkawinan bisa dilepaskan dari faktor agama atau yang lebih luas lagi, kehidupan bergama bisa berubah pengamalannya hanya karena perkawinan? Ini bisa jadi renungan bersama dan betapa peliknya urusan ini di negeri yang dasar negaranya mencantumkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama. ***
Ikuti tulisan menarik Mpu Jaya Prema lainnya di sini.