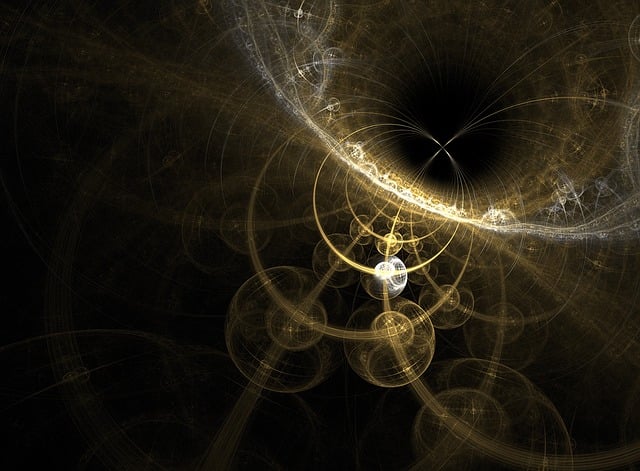Pada 1966, Soekarno yang telah memerintah enam tahun dengan Demokrasi Terpimpin-nya yang gegap-gempita itu digantikan seorang tentara pendiam. Ia tampan, banyak tersenyum, di tangannya ada selembar surat mandat berkuasa: Supersemar.
Sejak itu, bahkan berpuluh-puluh tahun setelah jenazahnya dikebumikan di Astana Giribangun, Solo, pada 2008, mayor jenderal pendiam itu terus mengharu biru bangsa ini. Ya, Soeharto (1921-2008) tak berhenti di situ.
Ada nostalgia yang selalu membuat orang rindu akan stabilitas yang dibangunnya dulu, manakala demokrasi menimbulkan riak-riak ketidakpastian: kebebasan berekspresi yang berisik, unjuk rasa yang sewaktu-waktu bisa berubah menjadi anarki, dan para oportunis yang senantiasa mendominasi panggung-panggung kekuasaan. Sikapnya yang tak pernah beringsut dari doktrin NKRI dan tidak toleran terhadap aspirasi daerah juga sekonyong-konyong jadi alternatif ketika potensi separatisme mulai muncul.
Tiga puluh dua tahun berkuasa, Soeharto tentu saja mempunyai banyak kesempatan untuk berbuat baik maupun buruk. Namun ada proses yang terus-menerus berlangsung di masa pemerintahan yang panjangnya hanya bisa ditandingi oleh pemimpin Kuba yang telah tiada, Fidel Castro, itu. Yaitu sentralisasi, bahkan kemudian personalisasi, dengan sosok Soeharto sebagai nukleus dari segenap perkembangan di negeri ini.
Proses sentralisasi bisa tercium sejak dini. Tepatnya tatkala ia menyederhanakan partai-partai--kantong-kantong kekuasaan di luar pemerintah--peninggalan demokrasi liberal yang dibikin lumpuh Demokrasi Terpimpin-nya Soekarno. Pada Pemilu 1971, seperti ditulis Herbert Feith dalam “The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia”, partai yang jumlahnya puluhan itu disederhanakan menjadi 10 partai, dan segenap aturan pemilu digiring ke satu tujuan: kemenangan Golkar.
Pengikisan kekuasaan di luar nukleus pemerintahan Orde Baru ternyata tidak berhenti. Sebuah kejadian pada pertengahan 1970-an mengantar pengikisan selanjutnya: sepuluh partai diringkas menjadi PDI, PPP dan Golkar. Sementara itu, sentralisasi kekuasaan yang berjalan selama satu periode itu pun mencapai tahap yang cukup mencengangkan: nukleus itu melebar. Putra-putri Presiden Soeharto yang sudah mulai besar itu menjadi bagian dari inti sel dan terjun ke dunia bisnis berbekal ”hak-hak istimewa” sebagai anak presiden. Majalah Forbes memberitakan, betapa setelah krisis moneter 1997, kekayaan Soeharto dan keluarganya mencapai US$ 16 miliar.
Dalam memoarnya yang tebal, From Third World to First, mendiang Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew mengatakan, “Saya tidak mengerti mengapa anak-anaknya perlu menjadi begitu kaya.” Dalam buku yang sama, Lee menyayangkan Soeharto telah mengabaikan nasihat mantan Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal Benny Moerdani pada akhir 1980-an supaya ia mengekang gairah anak-anaknya untuk mendapatkan aneka privilese bisnis.
Puncak sentralisasi yang sangat nepotistis itu akhirnya tampil dalam bentuk yang begitu transparan pada 1997: ia terpilih untuk ketujuh kalinya, dan itu berarti hampir separuh dari usianya dihabiskan sebagai presiden negeri ini. Dalam Kabinet Pembangunan VII, Siti Hardijanti Rukmana, putri sulungnya, diangkat menjadi Menteri Sosial. Dan manakala jangkauan wewenang yang diberikan kepada seorang Menteri Sosial kemudian terlihat begitu luas, orang pun mulai membayangkan sebuah suksesi yang tidak berbeda dengan peristiwa keluarga: sang putri sulung mengambil alih peran ayahnya.
Syukurlah, drama politik dinasti yang sangat dikhawatirkan di atas ternyata tidak pernah menjadi kenyataan. Pada 1997 Krisis Moneter menghadang bangsa ini, dan gelombang demonstrasi yang dipicu oleh melonjaknya harga BBM dan sembilan bahan pokok itu kemudian cepat menjelma jadi tuntutan agar presiden yang telah puluhan tahun ditakuti itu segera turun takhta.
Mei 1998, ia meletakkan jabatan. Ironisnya, hingga 25 tahun berselang, politik dinasti bukan saja tak ikut berhenti, tapi kian menjadi-jadi, baik di dataran eksekutif maupun legislatif. Sayangnya, terpukau pada dunia eksekutif, kita seperti melupakan dinasti politik yang tak kalah seru --alias mengerikan-- di dunia legislatif.
Kurang lebih, demikianlah ceritanya mengapa faktor keluarga sangat menentukan dalam pengambilan keputusan di negeri ini.
Ikuti tulisan menarik idrus f shahab lainnya di sini.