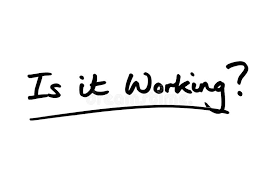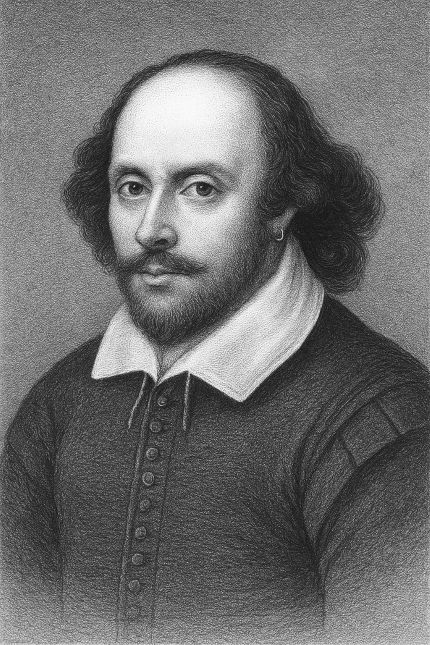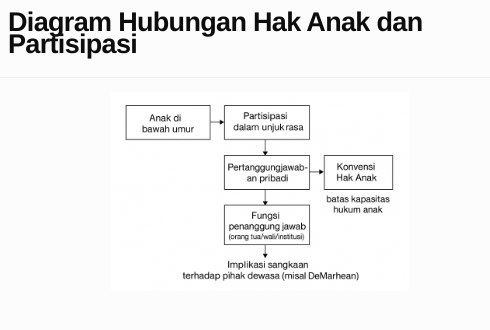Pandu: Pemandu Literasi yang Syahdu
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Ini tentang sastrawan yang berjuang di dunia sunyi. Menemani para pemuda meresapi laku kreatif literasi yang penuh substansi.
Langit kebudayaan Cirebon kini tengah mendung pekat dan gelap gulita. Setelah presiden penyair Ahmad Syubbanuddin Alwy memejamkan mata pasca seminar kebudayaan akhir tahun lalu, kini Chaerul Salam, pemerhati kebudayaan dan pejabat yang ramah itu, juga pergi untuk selamanya. Meninggalnya dua penulis cum budayawan Cirebon di atas jauh lebih menyayat dada ketimbang wafatnya dua penulis dunia, Umberto Eco dan Harper Lee, yang kini tengah jadi gincu di linimasa twitter maupun facebook. Gajah di pelupuk mata tak teraba, semut nun jauh di sana begitu kentara. Itulah kira-kira kredo jemaat sosial media.
Di sekujur pantura Jawa Barat, semua publik kesenian mengakui bahwa Alwy adalah penyair yang sepanjang hayatnya mengabdi pada literasi, pada puisi. Apapun yang ia lakukan semata hendak menegakkan marwah kebudayaan kembali ke puncak tertingginya. Kendati ia lahir dari tradisi Islam tradisional yang patuh, bukan majlis-majlis pengajian warisan ayahnya yang ia bina, melainkan anak-anak muda di tubir modernitas yang gelisah karena mencari. Bai’atnya pada susastra sudah mantap. Sebab baginya susastra adalah senyawa-kimia dari sufisme dalam bentuknya yang lain. Perkataan terakhirnya perlu saya kutip: “Jangan lagi arah mata angin kebudayaan kita didikte oleh mereka yang tak mengerti kebudayaan!” Itu beberapa patah kata yang dengan susah payah ia eja satu hari sebelum kita semua berduka karena kehilangannya.
Kendati saya tak mengenal Chaerul Salam sedalam perkenalan saya dengan Alwy, rasa kehilangan itu tetap dalam tak terperi. Perbincangan-perbincangan singkat dengannya, senantiasa menumbuhkan kesan impresif: bahwa ia pecinta tangguh literasi dan kebudayaan yang lahir dari lokus lain. Di tengah sakit yang menelikungnya, satu bulan yang lalu di sebuah acara di Hotel Zamrud Cirebon, ia masih sempat berujar: “Insya Allah saya akan ikut menulis obituari untuk mengenang Alwy”. Tapi Tuhan menggariskan lain. Kini mereka berdua sudah pergi ke nirwana meninggalkan segantang idea dan cita akan kota literasi yang diimpikan sekian lama.
Awalnya, rasa kehilangan itu benar-benar merasuk kalbu. Tapi, entah kenapa, saya percaya adagium mati satu tumbuh seribu. Dan di antara yang seribu itu adalah Pandu. Ya, Pandu Abdurrahman Hamzah, atau lazim dikenal Pandu Hamzah. Sastrawan muda yang satu ini tak hanya inspiratif, tapi juga selalu membuat kita iri pada semua “laku kreatifnya” selama ini. Di saat sindrom menjadi arkhe dan logos begitu menggebu menimpa para sastrawan di daerah saya, Pandu justru tak pernah lelah mendekonstruksi kediriannya dalam bumi asketisme yang acuh pada dunia selebral. Di saat semua pseudo-seniman-sastrawan berlomba-lomba tampil ingin mengambil peran, Pandu justru menepi dari hiruk-pikuk. Ia begitu curiga pada panggung, mikrofon, dan sorot kamera. Apalagi mentalitas romo yang selalu ingin dikelilingi para pengikut setia.
Padahal, ia sastrawan yang jam terbangnya sudah bertaraf nasional. Ketika umurnya baru 21 tahun, cerpen pertamanya, Kurusetra (1998), sudah mejeng di harian Kompas. Novel perdananya, Tanah Biru, sanggup menggedor-gedor kesadaran keberagama(a)n kita yang membuat juri Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) mengganjarnya sebagai roman terbaik harapan II di tahun 2003. Novel terbarunya, Sebuah Wilayah yang Tidak Ada di Google Earth (2015) berhasil membuka katup kesadaran kita bagaimana perselingkuhan negara dan kapitalisme industri ekstraktif dalam menggerus tradisi dan kekayaan aneka ragam hayati.
Tapi itu semua tak membuatnya harus berbesar kepala dan merasa sebagai segalanya. Ia justru kian meringkuk di sudut kota kecil Kuningan, Jawa Barat. Pandu tak ubahnya sastrawan yang benar-benar memilih jalan sunyi untuk segala laku kreatifnya. Seperti Umbu Landu Paranggi di satu sudut di Bali, Ahmad Tohari di pinggiran Banyumas, Gus tf Sakai di kota kecil Payakumbuh, dan semua pejuang kebudayaan lainnya. Mengutip Umbu, Pandu tak hanya mengajarkan pada anak-anak muda di sekitarnya bagaimana cara membuat puisi, tapi lebih dari itu: bagaimana menyelami dan melakoni kehidupan puisi. Kehidupan puisi itu ia torehkan dengan pelbagai strategi-strategi literasi yang sangat substansial. Nyaris dalam seluruh perikehidupannya. Pandu adalah Umbu bagi orang Kuningan dan sekitarya.
Ia, yang hanya dosen tak tetap itu, nekad membuat semacam “jariyah literasi” bagi anak-anak muda yang ingin mengakrabi dunia ide dan aksara. Lewat penerbitan bernama Silalatu, ia mendorong anak-anak muda untuk menerbitkan karyanya tanpa biaya dan regulasi secuilpun yang mencekik. Setiap penulis ia “subsidi” biaya percetakan senilai 5 juta rupiah. Syaratnya hanya satu: penulis yang sudah disubsidi harus mau menyisihkan sekian persen dari 100% royalti haknya untuk (calon) penulis lain. Tujuannya agar uang itu bisa terus bergulir melahirkan embrio karya-karya penulis (pemula) lain yang kerap dilecehkan penerbit major atau kesulitan bea dalam mencetak karyanya. Dan itu ia lakukan sejak tahun 2008.
Tak sedikit penulis “lahir” dari tangan dinginnya. Dari dalam Cirebon (Kuningan) bisa kita eja misalnya, Lien Aulia Rachmah (Pinangan Cahaya), Nana Mulyana (Jurig Citamiang), Ira Rahayu (Kepada Nohesca). Di luar Cirebon: Afrilia Utami (Halte Biru/Tasikmalaya), Epon (Aku Masih Ada/Garut), dan banyak lagi. Rata-rata buku yang ia subsidi berupa kumpulan puisi. Pasalnya, buku bergenre puisilah yang kerap mendapatkan kesulitan serius ketika hendak mencari inang untuk mencetaknya. Bahkan, khusus untuk mengenang sahabat sekaligus gurunya, Ahmad Syubbanuddin Alwy, Pandu menginisiasi lahirnya buku obituari apik yang berjudul: Ketika Alwy Pergi (Esai dan Puisi).
Suatu ketika Pandu berujar pada anak-anak muda yang tengah tekun menjalani laku sunyi literasi: “Para pendaki yang paling cepat mencapai puncak adalah pendaki yang khusyuk tak banyak bicara. Bukan pendaki yang selalu meributkan sesuatu tiap kali menemukan fenomena berkelebat di depannya”. Ini adalah tamsil, bahwa terkadang (mereka yang mengaku) sastrawan itu banyak mempersoalkan persoalan yang sebenarnya bukan persoalan. Hasil reformasi baru berhasil melahirkan orang-orang berisik yang selalu ingin bicara, tapi belum sanggup menciptakan manusia-manusia pencumbu sunyi demi mengakrabi karya.
Begitulah Pandu Hamzah. Banyak hal lain yang membuat kami, para petani literasi pemula, diam-diam menjadikannya sebagai referensi. Mengutip Joko Pinurbo dalam puisi Durrahman: dalam diri Pandu ada seorang pujangga yang tak binasa. Hatinya suaka bagi segala pecinta literasi yang ingin membangun kembali puing-puing ide dan aksara, ibukota bagi pecinta sastra pemula. Ketika kami semua ingin jadi sastrawan, baju kesastrawanannya sudah lebih dulu ia tanggalkan. Jangan pergi dulu ya Mas? Kepala dan dada kami masih butuh nutrisi untuk mengerti akan arti kebudayaan yang sebenarnya. Arti puisi yang sesungguhnya.
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Pandu: Pemandu Literasi yang Syahdu
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0