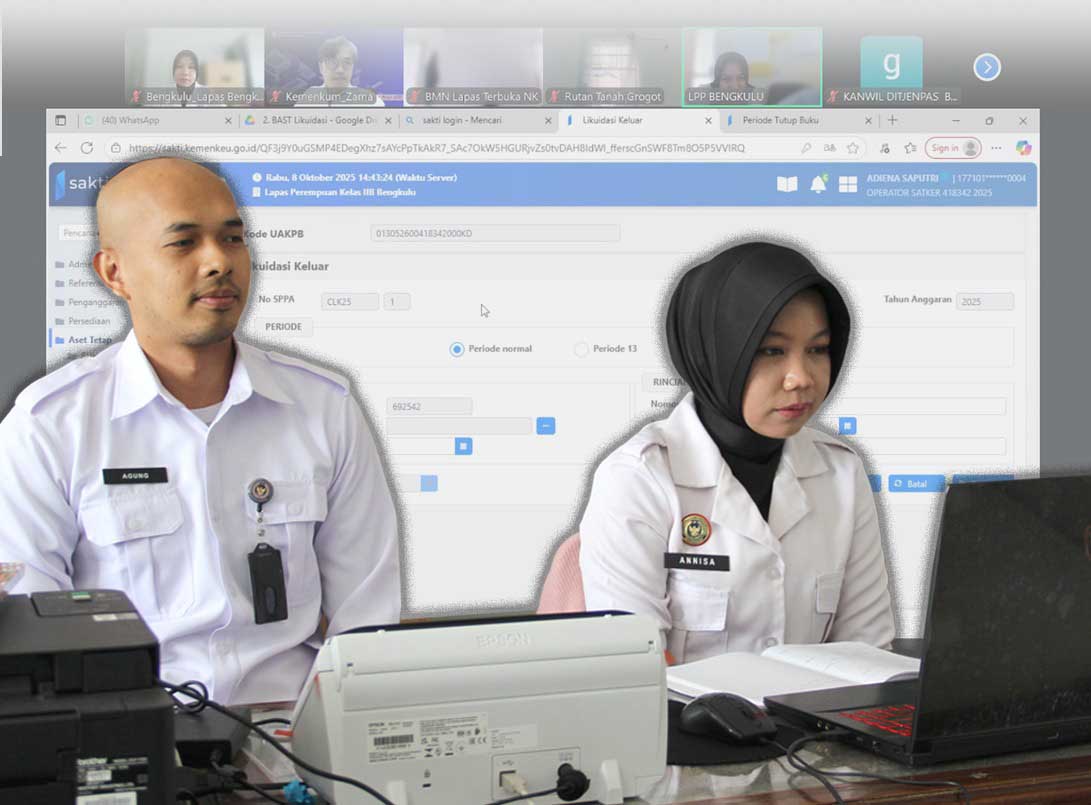Ibuisme (Pedagogis) Kartini
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Di sinilah perubahan besar terjadi: Kartini muda yang bergelora, kritis, emansipatif, dan penuh daya reflektif menjadi perempuan dewasa, keibu-ibuan.
R.A. Kartini hanya beberapa hari saja menjadi ibu. Ia mati muda pada 1904, saat berusia 25 tahun. Anak yang dilahirkannya, Singgih (R.M. Soesalit), tak sempat memanggilnya "ibu" di hadapannya langsung. Saat Kartini masih hidup, tak ada yang memanggil dia dengan sebutan "ibu". Namun, secara resmi dan aklamasi, "Ibu Kartini" menjadi nama panggilan resmi Kartini di Indonesia masa kini. Kita tak bisa lagi, sebagaimana permintaan Kartini kepada sahabat penanya, Stella Zeehandelaar, "Panggil aku Kartini saja-itu namaku." Tak cukup menyebut dan memanggilnya "Kartini" saja, harus menjadi "Ibu Kartini", sebagaimana dipopulerkan dan diajarkan di sekolah dasar.
Panggilan Ibu Kartini banyak dipengaruhi oleh lagu komponis nasionalis Wage Rudolf Supratman, yang termasyhur sejak zaman pemerintahan Belanda di kalangan kaum pergerakan nasional dan tiap kelompok pandu. Judul dan lirik lagu itu hanya Lagu Raden Ajeng Kartini, tanpa sebutan "Ibu". Namun, setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, frasa "Raden Ajeng Kartini" diganti menjadi "Ibu Kita Kartini", kata Sitisoemandari Soeroto (1983:471), meski surat pengangkatan kepahlawanannya hanya disebut "Sdr. Raden Adjeng Kartini". Di sinilah perubahan besar terjadi: Kartini muda yang bergelora, kritis, emansipatif, dan penuh daya reflektif menjadi perempuan dewasa, keibu-ibuan yang kalem.
Setidaknya, ada dua alasan perihal perubahan ini. Pertama, di Jawa pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, "ibu" adalah sebentuk penghormatan terhadap tindakan dan peran perempuan dalam keluarga, kelompok, kelas, perusahaan, atau bahkan negara yang dilakukan "tanpa menuntut kekuasaan atau prestise sebagai imbalan"-sesuatu yang sangat berbeda dengan hasil penelitian sejarawan Peter Carey dan Vincent Houben (2016) perihal kekuasaan dan keperkasaan perempuan Jawa sebelum abad ke-19. "Wewenang ibu tecermin pada sebutan kehormatan 'ibu bangsa' yang diberikan kepada Kartini, seorang tokoh nasional emansipasi kaum perempuan yang didukung negara," kata Julia Suryakusuma (2011:3). Rezim Orde Baru secara ideologis justru mengibukan perempuan Indonesia dalam bentuk "pengiburumahtanggaan" dan "domestikasi" menjadi "ibu [kepunyaan] negara" demi kepentingan kekuasaan penguasa (Suryakusuma, 2011).
Kedua, perubahan ini tidak terlepas dari pemikiran pendidikan-pengajaran Taman Siswa. Konseptor undang-undang pendidikan-pengajaran nasional pertama di Indonesia, sekaligus pendiri Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara, mengatakan, "Sebelum perang Djepang-Rusia (1904-1905), sebetulnya sudah mulai ada bukti2 kesadaran, lepas dari peristiwa2 di luar negeri. Timbulnja tjita2 baru dalam djiwa Kartini, segala usaha Dr. Wahidin Sudirohusodo (sebelum "Budi Utomo" lahir), dan lain2 sebagainja, adalah bukti2 kebangunan, meskipun waktu itu masih individueel."
Pada April 1903, nota Kartini yang kedua, setelah Geef den Javaan Opvoeding!, beredar di berbagai surat kabar. Kutipan yang termasyhur dari Kartini (dalam Arbaningsih, 2005:187), "Di pangkuannya [ibu] si anak untuk pertama kali belajar merasakan, berpikir, berkata-kata... Dan pendidikan yang mula-mula ini pasti bukan tidak besar pengaruhnya bagi kehidupannya di kemudian hari."
Pemikiran pedagogis Kartini ini sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dalam buku diktat pengajaran Taman Siswa, Soal Wanita, Ki Hajar (1961:16) menulis tentang sistem among yang dianggap sesuai dengan perempuan, "Nampak djelas sikap orang wanita (sesuai dengan kedudukannja sebagai 'Ibu') terhadap anak-anak jang mereka 'emong', penuh perhatian jang berdasarkan rasa tjinta-kasih memberi kebebasan seperlunja terhadap anak-anak (selama tak ada antjaman bahaja), menuntun perkembangan hidup anak-anak dari sifat kodrati kearah sifat abadinja; demikian seterusnja."
Menjadi wanita adalah menjadi guru, yang tak harus berdiri di ruang kelas. Inilah penerapan tut wuri handayani yang menjadi peran dan tugas wanita dalam pemikiran pedagogis Ki Hajar. Dan pemikiran ini semakin kuat relevansinya pada Zaman Malaise, yang membuat pemerintah Belanda mengurangi anggaran pendidikan. Maka, pada 1935, Ki Hajar membuat propaganda, "Tiap-tiap rumah djadi Perguruan! Tiap-tiap orang djadi Pengadjar!" Banyak sekali wanita yang menjadi "ibu guru", baik sudah bersuami ataupun belum punya anak. Dan kita ingat, sebutan "ibu guru" atau "(ba)pak guru" dipopulerkan ke seluruh Indonesia melalui Taman Siswa.
Pemikiran wanita sebagai ibu guru ini barangkali bisa dituduh dan divonis sebagai domestikasi, terutama pada masa Orde Baru dengan ideologi bapakisme otoriter Soeharto. Perempuan seakan dimuliakan, tapi dikerdilkan kekuasaannya demi melayani kepentingan penguasa, negara, dan sistem kapitalisme. Namun, ilmu pengetahuan dalam praksis pendidikan-pengajaran bisa membebaskan dan memuliakan perempuan, juga manusia secara universal. Dan inilah yang dicita-citakan dan diamalkan Kartini.
*) Artikel ini terbit di Koran Tempo, Jumat, 22 April 2016
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Verenginging Bibliotheek
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIB
Maha Saudagar Buku
Sabtu, 27 April 2019 20:06 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan







 99
99 0
0