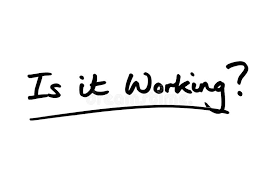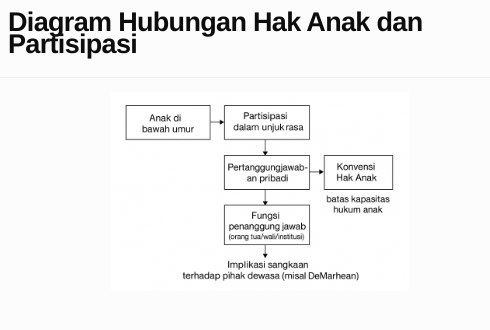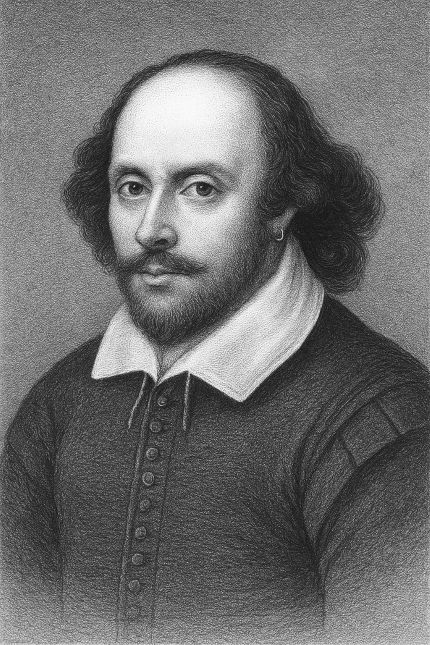Apakah Penemuan Terbesar Steve Jobs (1955-2011)?
Jumat, 9 Agustus 2019 20:51 WIB
Tentang Steve Jobs yang tak pernah habis sebagai bahan untuk dibicarakan.
SUNGGUH tidak enak menjadi seorang Steve Jobs (1955-2011), pada mulanya begitu. Dan sungguh membanggakan menjadi seorang Steve Jobs, pada akhirnya begitu.
Sejak awal ia adalah manusia yang tidak diharapkan lahir ke dunia. Beberapa lama dia juga tak tahu hendak menjadi apa. Kelahirannya tidak dikehendaki. Ibu dan ayah biologisnya masih mahasiswa di University of Wisconsin ketika janinnya berkembang.
Orangtua si mahasiswi, tidak ingin anaknya menikah dengan lelaki keturunan Suriah bernama Abdulfattah Jandali, yang hingga si anak meninggal tak pernah saling bertemu. Jandali kini masih hidup dan bekerja di sebuah kasino.
Pilihannya hanya satu: aborsi! Si mahasiswi - Joanne Schieble memilih melahirkan bayinya. Diam-diam ia tinggalkan Wisconsin dan pergi ke San Francisco dan melahirkan di sana, lalu menyerahkan anak yang tak sempat ia beri nama itu pada pasangan Paul dan Clara Jobs - sebuah keluarga kelas pekerja yang dalam struktur ekonomi-sosial Amerika mungkin berada di level paling bawah.
Paul tak tamat SMA. Ia bekerja macam-macam: jadi penagih utang, tukang sita barang, dan masinis. Sementara Clara bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan teknologi canggih pertama di Lembah Silikon.
Meski dalam kontrak adopsi ada kesepakatan bahwa si orangtua angkat itu harus mengurus pendidikan si anak hingga selesai kuliah, nyatanya Steve Jobs hanya sempat duduk satu semester di kursi perguruan tinggi.
Paul dan Clara Jobs sempat ingin mengembalikan Steve Jobs, anak angkatnya yang ternyata sangat merepotkan. Steve kecil tumbuh sebagai anak yang galgal, temperamental.
Tangannya pernah terbakar karena memasukkan jepitan rambut ke colokan listrik. Ia pernah minum racun semut, dan nyawanya selamat setelah isi perutnya dipompa.
“Dia anak yang menyusahkan,” kata Clara Jobs.
Keluarga Jobs lalu pindah ke Mountain View dengan tekad mengubah nasib yang tak kunjung baik. Saat itu Steve kecil berusia tiga tahun. Paul menjajal usaha properti dan memperbaiki mobil.
Ketika kelas empat Steve yang tidak pintar – dan dengan putus asa pernah menjawab gurunya, Imogen Hill, begini: “Saya tak paham kenapa kami tiba-tiba begitu melarat.”
Saat itu gurunya bertanya kepada setiap murid, “Apa yang kamu tidak pahami di alam semesta ini?”
Sampai di situ, riwayat hidup Jobs tidak menjanjikan apa-apa. Di kelas ia usil, terlalu banyak bicara, dan kurang memperhatikan pelajaran.
Belakangan Steve mengaku diselamatkan oleh guru Hill yang membayarnya lima dollar agar mau mengerjakan pekerjaan rumah dan membaca.
Hill, guru yang jeli itu, melihat potensi besar di balik kenakalan anak didiknya itu. “Dia adalah salah satu penyelamat hidup saya,” kata Jobs, seperti ditulis Norman Seeff di majalah Rolling Stone (November, 2011).
Ketika SMA, tanpa merasa bersalah dan menutup-nutupi pada ayahnya, Steve menjadi pengguna mariyuana, pergi dari rumah dan hidup serumah dengan pacarnya. Sampai di titik itu, ia juga belum tahu hendak hidup sebagai apa, dan ia belum menemukan dirinya sendiri.
Steve lalu masuk kuliah di perguruan tinggi swasta Reed College, di Oregon. Itu hanya ia jalani selama enam bulan dan setelah itu ia merasa kuliah tak ada gunanya.
Ia merasa bersalah karena kuliah itu hanya akan menghabiskan tabungan orangtua angkatnya. Ia memilih berhenti. Lagipula sebagai mahasiswa Steve amat miskin, ia tak bisa menyewa kamar asrama, dan tidur menumpang di lantai kamar kawan-kawannya, bergantian.
Putus kuliah, Steve secara iseng saja belajar kaligrafi. Diakuinya kelak, bekas pelajaran kaligrafi itulah yang membuat produk Apple sangat kuat secara desain, dan komputer Mac menyediakan jenis-jenis font yang indah.
Saat kosong kuliah itulah, ia juga berkenalan dengan ajaran spiritual Neem Karoli Baba, hingga melakukan perjalanan ke India untuk menemui sang guru spiritual itu. Pertemuan itu tak pernah terjadi karena sang guru meninggal sebelum Steve tiba.
Ia lalu menggunduli kepala dan berkelana di pegunungan Himalaya. Di sana ia menyaksikan betapa menyiksanya kemiskinan, sesuatu yang sudah sangat akrab dengan dirinya.
Di sanalah, dan di saat-saat itulah Steve tercerahkan.
Jiwanya yang gelisah dan mencari ketenangan (atau pelarian?) spiritual, pelan-pelan bergeser ke dunia praktis, ke solusi teknologi.
Ia akui, saat itulah ia berpikir bahwa Thomas Alva Edison lebih banyak jasanya dalam memperbaiki dunia daripada Karl Marx dan sosok yang menginspirasi dia Neem Karoli Baba.
Kisah Steve Jobs kemudian membenarkan satu adagium yang menyebutkan bahwa dunia hanya akan menyerahkan diri kepada orang-orang yang berani menjelajah, orang-orang yang tak pernah berhenti mencari dan tidak lekas mengikatkan diri pada satu pendapat sempit. Steve adalah penjelajah.
Ia pelahap lagu-lagu Bob Dylan. Pada suatu masa Steve adalah perombak lirik-lirik lagu milik idolanya itu, dan menuliskan ulang menjadi puisi-puisinya sendiri.
Ia dan teman-teman awalnya pendiri Apple pernah bekerja memerankan tokoh-tokoh Alice in Wonderland demi mendapatkan uang.
Kisah selanjutnya adalah sejarah seorang sosok besar yang mengubah dunia dari kemungkinannya yang paling membosankan. Steve Jobs dengan produk-produk jenial Apple membuat hidup manusia bergairah.
“Steve Jobs adalah Bob Dylan-nya mesin,” kata Bono, vokalis U2, “Dia adalah Elvis Presley-nya dialektika perangkat keras – perangkat lunak.”
Kira-kira apa yang dimaksudkan oleh Bono adalah: sebagai Bob Dylan, Steve Jobs begitu teguh menempuh jalannya. Ia dipuja dan jadi panutan banyak orang. Sebagai Elvis, ia mencapai puncak popularitas, kadang dengan sensasi yang terkesan dicari-cari.
Tapi, itulah Steve Jobs.
“Dia menciptakan banyak perangkat keras hebat, tapi selama bertahun-tahun, dia juga menciptakan diri sendiri!” kata John Perry Barlow, seorang perintis industry digital dan penulis lirik-lirik lagu untuk kelompok Grateful Dead. Itulah penemuan terhebatnya: Ia berhasil menemukan diri sendiri.
Sebagai manusia, tentu Steve Jobs jauh dari sempurna. Sikap kasarnya yang tumbuh sejak kecil, terbawa hingga ia dewasa. Ia, seperti dalam kesaksian mantan karyawan Apple, punya sisi terbaik dan terburuk seorang manusia. Yang pasti ia seorang visioner.
“Kami di Apple tidak menciptakan barang untuk memenuhi kebutuhan orang. Kami membuat barang yang akan dibutuhkan orang,” katanya, sebagai mana diakuinya dalam biografinya yang baru saja terbit. Ini adalah pernyataan seorang visioner sejati.
Jika kebanyakan seorang visioner hanya berpikir besar, Jobs menyatukan kejelian seorang desainer dalam dirinya. Ia sangat peduli pada detail desain. Itu yang membedakan dan memberi karakter pada produk-produk Apple. Di Apple, kata Jobs, mereka membuat produk-produk yang hebat, bukan mencari uang. Tentu saja uang diperlukan untuk riset menghasilkan barang yang bagus.
“Tapi, kalau uang yang menjadi tujuan, maka segalanya selesai!” kata Jobs. Ia dengan pernyataan itu menohokkan kritik keras pada John Scully, CEO Pepsi yang dia sendiri yang merekrut, tapi kemudian membuat Steve dipecat oleh dewan direksi Apple pada usia ke-30.
Pemecatan itu terlihat masuk akal, soalnya pilihannya adalah Scully yang tenang dan matang dan Steve Jobs yang perangainya berangasan. Keduanya ternyata tak bisa disatukan. Scully dipertahankan.
Tapi, saat itu, tanpa Steve Jobs Apple kehilangan rohnya, kehilangan gairah berinovasi dan semata mengejar laba. Itu yang justru membuat perusahan itu terjun bebas ke tubir jurang kebangkrutan, sebelum Jobs direkrut kembali.
Sekuat apa produk-produk Apple? Ada lelucon begini: hanya ada dua jenis pengguna komputer. Pertama, pemakai Mac. Kedua, mereka yang ingin menjadi pemakai Mac.
Ya, ini memang cuma lelucon, tapi setidaknya itu bisa memberi gambaran betapa kuatnya produk yang lahir dari visi seorang Steve Jobs.
“Seperti penjara,” kata kawan saya, “sekali kita memakai Mac, kita tak bisa lagi memakai produk lain. Tapi, kita betah di dalam penjara ini.” Sekarang, saya ada dalam penjara itu. Kolom ini saya tulis di MacBook Air, notebook paling tipis pertama di dunia.
Terima kasih, Steve Jobs.[]
Penulis Indonesiana
0 Pengikut

Metode Pengambilan Keputusan yang Rasional dalam Memilih Presiden
Selasa, 9 Maret 2021 06:46 WIB
Pembajakan Partai Demokrat dan Pendidikan Politik
Senin, 8 Maret 2021 06:51 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 99
99 0
0