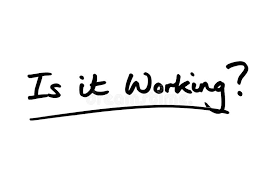Dua Cinta di Puncak Jaya (Bab 1)
Jumat, 22 Juli 2022 10:04 WIB
Ini kisah tentang laki-laki yang tanpa sengaja terlibat dalam sayap perempuan gerakan papua merdeka. Ia ingin kembali menemui keluarganya di pulau jawa
1
Danau Sentani. Danau alam menghampar, sungguh amat memesona. Orang-orang mengatakan danau Sentani memiliki keluasan sekitar 110 kilo meter persegi atau 9,360 hektar dengan ketinggian di sekitar 75 meter di atas permukaan air laut.
Air bening biru mempongahkan kedalamannya, memanjakan sekitar 21 pulau kecil di tengah-tengahnya. Tertidur nyaman dalam ayunan punggung puluhan bukit-bukit yang saling bergandeng, mengelilinginya. Seakan menjaga agar air tak tertumpah ruah dan menjadi bencana bagi penduduk di sekitarnya.
Dalam rahim Sentani ikan-ikan begitu banyak ragam, berenang ke sana ke mari, bercumbu rayu melestarikan spesiesnya. Beragam ikan air tawar, tak terhitung jenis dan jumlahnya. Jenis ikan paling mengagumkan, menurut cerita penduduk, ikan Hiu Sentani, orang juga menyebutnya Largetooth Jawfish. Ikan ini memiliki gigi-gigi sangat tajam. Dengan keberaniannya, Hiu Sentani mengembara ke berbagai negara tetangga, seperti Australia, Thailand, dan tentu saja negara terdekat PNG melalui sungai-sungai, danau besar, dan rawa-rawa.
Waktu sudah Senja. Rio masih berdiri gelisah di tepi danau. Kawasan wisata alam Kathloke. Festival Danau Sentani, peristiwa budaya yang dilakukan setiap tahun sekali, dipusatkan di tempat ini. Sebuah festival yang menunjukkan keunggulan tradisi adat di Papua, dan karya-karya budaya yang menakjubkan dan tak tertandingi.
Wajahnya muram tak bersemangat. Sesekali kakinya menendangi batu-batu kerikil, dengan lenguhan geram, seakan-akan sedang mengusir beban berat dari rongga dadanya yang semakin terasa menyesak. Kerikil itu berserakan di permukaan tanah yang tak rata di sepanjang tepi danau, berlubang di sana-sini, dengan rumput kecil yang tumbuh hijau, dan sebagiannya lagi berduri.
Sejenis burung bangau berwarna putih, dengan paruh panjang tajam menyepuh kemuning, terbang melayang-layang tenang di atas danau. Paruhnya mengarah ke air dengan pandangan mata yang terus menajam. Mengincari mangsa, ikan-ikan kecil yang berenang riang dan tidak waspada. Di atas sang pemangsa bisa kapan saja mengakhiri hidup mereka. Hukum alam yang kejam atau memang harus begitu untuk atas nama keseimbangan.
Sementara burung-burung cucuk urang yang berparuh indah, berlompatan dari satu dahan ke dahan lain dengan luncuran yang begitu cepat. Ketika mangsa berada dalam jangkauannya ia menangkap dengan gesit, dan terbang kembali ke dahan yang lain. Kadang hinggap di atas keramba-keramba yang berjajar-jajar.
Petani-petani ikan terus berjaga-jaga dengan memegang tongkat atau tali-tali bergrombyangan dengan kaleng-kaleng bekas, plastik, kain dan sebagainya. Keramba-keramba yang baru saja diisi nener itu harus diawasi, kalau masih ingin panen dengan hasil yang lumayan.
Sayangnya, Rio, laki-laki berusia 50 tahun itu, tak bisa menikmati keindahannya, kegalauan menguasai pikirannya. Sepanjang usianya, ia mengalami berbagai persoalan hidup, menjadi relawan di wilayah konflik dan daerah-daerah bencana dengan tingkat kejahatan dan penjarahan amat tinggi. Semuanya bisa dilalui dengan tenang, pikiran jernih dan optimis. Menggunakan cara pandang positif dan menghindari prasangka sejauh bisa dilakukan, dan selalu ia mengusahakannya.
Di tanah Papua, kenapa semuanya menjadi berbeda. Kegalauan tiba-tiba muncul, menyelusup dalam hati, lembut dan terus menyakit. Rasa itu menghentak-hentak seakan menuntut jawab. Namun, ia tak bisa merangkai satu kalimat pun untuk mengurai. Kecuali gumam lirih, panjang, dan samar, kemudian menghilang di antara riak air danau saat bersapa dengan angin bukit.
Hujan turun dengan derasnya, tanpa aba-aba, dan tiada tanda-tanda. Puluhan orang yang masih menikmati keindahan danau berlarian mencari tempat berteduh. Petani keramba masuk ke rumah, dan tak lagi berjaga-jaga.
Rio berlari ke arah gubuk kosong di bawah pohon sagu yang berdiri kokoh. Daun mudanya tegak lurus seakan menusuk langit mengabarkan kedukaan. Ada satu pelepah kering masih menggantung di batang pohon yang mulai membasah. Tetes-tetes bulir air meluncur melalui sela daun yang mengering, cokelat tua. Baju Rio mulai basah. Atap gubuk dari daun sagu yang mulai rapuh tak mampu menahan air hujan di petang itu.
Rasa dingin menusuk-tusuk tulang belulang, menerobos masuk melalui pori-pori kulit. Ya, kulit yang mulai renta, dan berkeriput di makan usia.
Rio menghadapi kenyataan hidup orang-orang Papua, tentang kepahitan, kesedihan, dan penderitaan. Selama ini ia hanya mendengar melalui seminar, dan diskusi, membaca hasil-hasil riset, dan menonton berita, program talkshow televisi, dan video-video dokumenter. Semuanya kini menari-nari di pelupuk matanya. Begitu nyata, menyengat tajam bagaikan lebah hutan liar yang beterbangan kian kemari di sela pohon-pohon besar dan tua di hutan Papua.
Terlebih setelah melihat berpuluh-puluh dokumen milik David. Nama lengkapnya David Wompere, bagi orang-orang Papua, sudah dapat ditebak dari mana asal daerahnya, nama fam dari suku asli Papua yang hidup di Teluk Cenderawasih. Sekarang berganti nama menjadi Kabupaten Biak Numfor.
Rio mengenal David saat sama-sama makan nasi kuning di Abepura, dekat gedung Perpustakaan Daerah Papua. Pertemuan malam itu memang singkat, tetapi hari-hari selanjutnya terus berkomunikasi dengan obrolan-obrolan lepas, kadang sangat berat, tetapi kadang-kadang sangat remeh temeh. Dan tidak jarang hanya tertawa-tawa sampai pagi, mengulang-ulang kembali berbagai humor yang dikeluarkan Gus Dur [Abdurahman Wahid] semasa hidupnya. Mereka rupanya sama-sama pengagum Gus Dur. Pertemanan itu menjadi cepat akrabnya, bahkan serasa sudah mengenal sejak masa kecil.
Dalam dokumen risetnya, David menceritakan mengenai orang-orang Papua yang hidup dalam ketidakpastian, kewaspadaan, kehati-hatian, dan pelan namun pasti, menjelma menjadi ketakutan. Menghunjam dan berurat akar di bawah alam sadarnya. Seperti lengan-lengan gurita yang mencengkeram mangsanya.
Kapan saja bisa terdengar jerit kesakitan, rintihan kehilangan dan lolongan panjang kematian yang hadir sesukanya. Pohon-pohon besar, rimbun, menjulang, menyeringai sinis, menawarkan getah kematian, dan tak perlu harus menunggu adanya alasan. Dari batang-batangnya, akar-akarnya, dan ranting-rantingnya.
“Hukum sebab akibat, di Papua tak memiliki makna,” kata David.
“Lalu...?”
“Entahlah..., diam seakan menjadi pilihan yang bijak,” sahut David, seorang peneliti sosial yang amat tekun.
Semua informasi tercatat dan tersimpan dengan baik. Tidak hanya tulisan, tetapi juga dokumen dalam bentuk foto dan video. Namun, jangan berpikir video rekamannya berbobot. Rio sudah menyaksikan sendiri lebih dari dua pertiga rekaman video yang tersimpan di ruang kerja pribadi David.
Sebagian besarnya bahkan sangat konyol, dan bikin jantung hendak meledak karena jengkel. Sebaiknya, mereka yang menderita serangan jantung, tidak perlu memiliki keinginan menonton rekaman video ini. Coba bayangkan, video berdurasi satu jam, ternyata gambarnya hanya anjing sedang kawin. Meskipun suara-suara obrolan tetap terdengar dengan jelas karena menggunakan clip on yang sangat sensitif, tetapi bercampur aduk dengan hiruk pikuk anak-anak, berteriak-teriak, sorak sorai, merayakan kemenangan.
“Siapa yang merekam video seperti ini?”
Masih dengan santai dan tanpa beban, David menjawab, “Anak-anak Papua, mereka camera person yang amat berbakat, bukan?”
“Sudahlah, tidak usah dipikirkan terlalu serius rekaman itu. Saya tidak pernah bercita-cita mau menjadi produser atau youtuber,” lanjutnya.
“Tapi ini keterlaluan,” ujar Rio masih tidak bisa menerima dokumen video itu.
“Minum dulu kopinya, untuk meredakan kekecewaanmu.”
Tetapi itulah kecerdikan David. Dengan menyerahkan kamera ke anak-anak tak ada rasa curiga dari orang-orang yang sedang berdiskusi tentang gerakan di tanah Papua. Mereka tak tahu suaranya terekam dalam video anak-anak itu.
David banyak menulis mengenai suku dan adat di tanah Papua. Pemikiran dan pandangan masyarakat kebanyakan terhadap berbagai persoalan, termasuk penolakan terhadap masuknya zending ke tanah Papua.
Semuanya sangat serius, dan terkadang tampak subversif. Tetapi dengan santainya pula, ia memberi judul transkrip riset itu dengan sekenanya, ada yang berjudul ‘tentara kehilangan celana dalam’, ‘mama kehabisan pinang’, ‘mabuk kok tahu kalau mabuk', dan ada juga judul berbentuk pisuhan, ‘cuki ma, jempol kakiku keinjak, Pak Dhe.” Semuanya benar-benar seenaknya sendiri.
Meskipun begitu kaya informasinya, David tak pernah ingin menerbitkannya, membuat buku digital, apalagi memproduksi video dokumenter. Alasannya sederhana, khawatir berbeda dengan apa yang selama ini selalu menjadi pelajaran di sekolah-sekolah.
“Nanti jadi membingungkan anak-anak,” katanya sambil tersenyum renyah. Wajahnya sumringah tanpa beban, dan tanpa keinginan yang berat-berat. Setiap memikirkan masalah tak pernah lepas dari selera humornya, dan terkadang tak terduga, nyleneh.
Apa akal sehat bisa menerima, mengabaikan data yang amat penting dari riset aksinya bersama suku-suku di Papua, hanya dengan alasan agar tidak membingungkan anak sekolah. Argumentasi apa pula ini?
“Banyak pihak penting mengetahui data itu, terutama orang-orang Papua sendiri,” kata Rio tidak terima dengan argumentasi kacangan David. Tetapi yang mendapat diprotes malah tertawa terbaha-bahak, sampai air matanya menetes keluar dari kelopak matanya.
“Baik-baik, untuk menghiburmu bulan depan kuajak kau ke Puncak Jaya,” katanya sambil memasukkan pinang ke mulutnya, menyusul bunga sirih, kapur.
Setelah mengunyah berpuluh kali, air ludahnya mulai berubah warna. Bibir tebal hitam itu, tampak memerah. Menjaga agar dirinya tidak terkena ludah merah itu, Rio mengambil sebuah kaleng biskuit kosong, “nah, meludah di sini,” katanya.
“Hahaha, terima kasih. Ini asbakmu,” kata David sambil menyerahkan asbak beling cukup besar pula.
David menceritakan pengalamannya mendaki empat puncak pegunungan Soedirman dan Jayawijaya, “yang terpendek namanya puncak Carstensz Pyramid tingginya sekitar 4.884 meter di atas permukaan air laut.”
Puncak yang lain namanya puncak Yamin dengan tinggi 5.100 meter, puncak Trikora 5.160 meter, dan puncak Jaya dengan ketinggian mencapai 5.500 meter di atas permukaan air laut.
Puncak yang selalu kesepian, dan menahan rasa dingin yang menusuk. Salju-salju abadi yang mengerak. Lalu meleleh membasahi sungai Memberamo, dengan gletser dari puncak-puncak tanpa interupsi, berkilau ketika matahari mencium aroma surga tanah Papua.
“Tetapi orang-orang Papua tidak bisa menikmati keindahannya,” lanjut David dengan nada suara menurun dan pelan.
Benar agaknya. Di sana hanya terukir kepedihan dan tapak kaki gugup menjejak di lambung gunung yang menggembung, luka. Kesakitan, dan kematian yang selalu mengintai. Siapa saja bisa mengalaminya. Ketentuannya, siapa dahulu yang akan menembak atau meluncurkan anak panah. Itu saja.
Lalu, kicau burung dan keributan koloni kera akan terdiam seketika. Berganti dengan salakan senjata atau desah angin mengikuti luncuran anak panah yang kehausan. Peluru panas mencari lembutnya kulit manusia, mengisap anyir darah yang mengalir membasahi gembur tanah hutan, berhumus dengan kesuburan luar biasa. Setelah itu, burung-burung, koloni kera, dan hewan-hewan hutan akan ribut kembali, tetapi terdengar samar dan menjauh.
“Kisah nestapa dari dua ratus lima puluh lima suku di Papua,” kata Rio.
“Benar...!” kata David sambil mengacungkan dua ibu jari tangannya tinggi-tinggi. Tetapi karena terlalu bersemangat, pinang yang sudah nyaris luluh itu, terlontar begitu saja dari mulutnya. “Byuhhhh.” Rio berteriak, terlonjak reflek dari kursinya menghindari muntahan dahsyat itu. Buntalan pinang yang bisa berakibat kerja ekstra untuk menghilangkan nodanya di baju, apalagi jika kebetulan berwarna putih.
Orang-orang Papua yang bernaung dalam petak-petak ruang dan pulau terpenggal-penggal. Mereka sedang berada dalam ambang batas ketidakpastian budaya, menghadapi amuk badai infiltrasi dari kebudayaan berbeda.
Rio membayangkan, bagaimana orang-orang yang membutuhkan waktu tidak kurang dari enam puluh ribu tahun untuk sampai di Tanah Papua dari daerah asalnya di daratan asalnya, berada berganti-gantian dalam cengkeraman kekuasaan Jerman, Belanda, Jepang, dan sekarang dari wilayah Barat Indonesia, Jakarta. David menuliskan situasi ini dengan sangat indah, dan Rio membacanya dengan keras, “Menyublim sudah, membumbung tinggi bersama awan. Rapuh dan hilang tradisi asli para leluhur. Roh-roh sesembahan mereka."
"Ajaran-ajaran tentang hidup yang menyatu dengan alam, saling membantu, menguatkan, dan melindungi di antara warga suku yang menderita."
"Tata aturan moral dan pergaulan keseharian yang kadang-kadang menjadi mencengangkan, karena sering kali tak pernah kita dengar, tak pernah disebarkan. Termasuk oleh David.”
“Hahahaha, jangan kau tambahi catatan itu. Katamu itu dokumen penting,” teriak David meledek, Rio menyambut dengan tawa lepas. Mereka tertawa tergelak-gelak.
Dalam catatan Rio, jejak dan kidung leluhur menghilang, berantakan sebagian besarnya, dan tak tersentuh sebagian kecilnya, bermula ketika pulau yang muncul akibat mendangkalnya samudra Pasifik, patahnya lempengan di daratan Australia, menjadi ajang pamer kekuasaan dan ruang perebutan imajinasi tak terbayangkan.
Zending dengan menyebarkan sekte ajaran Protestan memasuki Manokwari, diperkirakan tanggal 5 Februari 1855, dan terus melebarkan pengaruhnya di bagian pantai utara Papua. Perebutan ruang imajinasi semakin ramai dengan masuknya Belanda, dengan membangun pusat kekuasaan pertamanya di Manokwari tahun 1898, dan Merauke tahun 1902. Dengan membonceng ekspansi politik dan ekonomi Belanda, misi Katolik menyebar di bagian pantai selatan Papua. Misi ini meminggirkan spiritualitas suku asli Papua.
Kini, imajinasi suku-suku Papua mengenai kekuatan yang mengontrol kehidupan tersingkirkan. Kekuatan dahsyat dari mistisisme suku-suku asli Papua, berganti dengan keyakinan baru tentang Tuhan yang tak terjamah. Lebih tepatnya, terpaksa berpindah imajinasi.
Sebagaimana menjadi watak dasar agama samawi, ekspansif, merebut sebanyak-banyaknya pengikut sebagai bagian utama dari misi keagamaan. Untuk mendapatkan surga sebagaimana janji dalam kitab-kitab suci.
Rio masih ingat benar cerita David mengenai kepercayaan suku-suku Papua. Misalnya, suku Yali di Yahukimo masuk dalam wilayah pegunungan tengah Papua memiliki tradisi penyembahan ular dengan menyajikan darah babi. Suku Dani mempercayai kekuatan sakti para nenek moyang yang akan menurun kepada anak laki-laki di antara anggota suku. Laki-laki yang terpilih. Kekuatan menyembuhkan penyakit, menyuburkan tanah, dan menjaga ladang.
Mereka membuat Kaneka untuk menghormati para leluhur. Lambang penghormatan para leluhur. Melalui Kaneka Hagasir, lantunan doa-doa mengalir deras kepada roh-roh nenek moyang untuk meminta kesejahteraan keluarga, dan memohon kemenangan dalam perang.
Dalam tumpukan persoalan itu Rio merasa dirinya seperti sampah-sampah plastik yang beterbangan bersama tiupan angin kering. Tak berguna sama sekali, kecuali hanya mencemari tanah. Ujung sepatunya membentuk garis-garis tak beraturan di permukaan tanah. Beberapa batang rumput yang terinjak mulai tampak layu, dan terdengar mengeluh.
Seperti rumput-rumput itulah kelak, tradisi suku-suku di Papua akan hilang, musnah, dan orang-orang kehilangan citra spiritualitasnya. Segera akan bisa terasakan ketika manusia terpisahkan dari alam. Alam terpisahkan dari kekuatan Tuhan.
“Saya sangat memahami semua yang terjadi di tanah ini,” bisik Rio sambil berlari menuju mobil sewaannya setiap kali melakukan perjalanan.
“George, tolong pesankan tiket ke Merauke, untuk lusa,” katanya membuka perbincangan, setelah beberapa kilometer kendaraan yang ditumpanginya meninggalkan danau Sentani. Melalui jalan tanah yang tidak terlalu lebar, sebelum akhirnya sampai ke jalan utama.
“Baik, Pak,” kata George sambil tetap memegang kemudi, dan menjaga kecepatan kendaraannya tetap stabil.
Hujan di luar masih amat derasnya, mengguyur jalanan aspal yang bersemu warna kelam. Papua mulai menggelap, memasuki malam, segera tidur dalam ketidaktenangan. Gelap akan semakin menggulati, karena tak lama kemudian, biasanya akan disusul dengan listrik yang padam, dan tidak ada kepastian kapan akan menyala kembali.***
Nantikan BAB 2 yang terus semakin menarik
Pekerja sosial, jurnalis, fasilitator pendidikan kritis
0 Pengikut

Vinri Panggoa, Bergerak untuk Pemenuhan Air Bersih di Jayapura
Rabu, 9 Agustus 2023 19:49 WIB
Cempluk Goes to School, Pendampingan Pasien Autoimun Lupus
Selasa, 8 Agustus 2023 17:02 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0