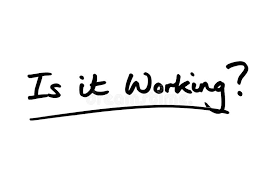Dua Cinta di Puncak Jaya (Bagian 2)
Senin, 25 Juli 2022 05:54 WIB
Ini kisah tentang laki-laki yang tanpa sengaja terlibat dalam sayap perempuan dari Gerakan Papua Merdeka. Ia ingin kembali di Pulau Jawa menemui keluarganya, istri dan 2 anaknya.
Malam terus merangkak tinggi, menelusuri batas-batas kesadaran manusia. Wilayah perbatasan Papua dengan Papua Nugini mulai tampak melamun. Warga yang sejak siang menikmati suasana di daerah perbatasan telah kembali dalam pelukan keluarga.
Jalanan di pedalaman Merauke teramat sepi. Tugu perbatasan berbentuk kubus diam membisu. Taman Nasional Wasur membeku memeluk pohon-pohon besar, rahimnya berbentuk rawa-rawa, dan mengemban keindahan Danau Rawa Biru. Suku Marind, menjadi satu dari empat suku Papua yang memiliki hak tanah ulayat dalam Taman Nasional ini.
Rio dan David malam itu mengurungkan niat mengurungkan niat bertamu ke rumah Oliga Mawaranu dan akan mengikuti acara pelepasan arwah esok harinya. Rio mendengar kabar Oliga mengalami duka, anak perempuan dan menantunya menjadi korban peluru nyasar di hutan dua hari lalu.
Malam itu, Oliga Mawarune, seorang Ondoafi yang makin melemah fisiknya, berusaha keras menahan kantuk. Ribuan kubik kayu seakan membebani kelopak mata keriput, berkedip-kedip di antara suara nyamuk yang tak pernah berdamai, mendengung-dengung, lalu menghilang sesaat setelah menghisap darah yang tinggal sedikit tersisa dalam tubuh Oliga.
Kesedihan merayapinya, menggigit-gigit seluruh jiwa rentanya. Cucu perempuannya yang berumur 7 tahun masih terus menangis. Dengan suara yang semakin menghilang, masih memanggil mama dan bapaknya yang belum pulang juga hingga menjelang larut.
Ingin ia mengatakan sejujurnya kepada bocah kecil itu, tak usah lagi menunggu kedua orang tuanya. Darahnya telah tertumpah, membasahi akar-akar pohon hutan sekitar 12 kilometer arah barat daya perkampungan. Tak ada kesalahan yang mereka buat, ketika tiba-tiba terdengar suara menggema, “pengkhianat, pengkhianat...”, “tembak saja, habisi nyawanya ...”, “beri pelajaran, biar tahu mereka, betapa kuatnya NKRI.”
Oliga hanya mendengar teriakan begitu banyak orang tentang anak perempuan yang sangat dikasihi dan menantu laki-lakinya. Selebihnya, tak lagi mendapatkan cerita. Ia berlari lintang pukang menghindari tembakan dari kelompok orang itu. Meski berat rasanya meninggalkan anaknya yang bersimbah darah, tetapi mengurus cucunya yang masih akan menghadapi masa depan jauh lebih penting baginya.
Oliga merasa tidak akan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan cucunya, ketika harus bercerita soal kematian itu. Cucunya akan menyalahkan, menuduh tak memiliki kasih sayang kepada anak sendiri, menyongsong nyawa melepas badan, mungkin perlahan atau mungkin melesat cepat bersama malaikat.
Membayangkan itu, menggigil tubuhnya. Namun, ia harus menemukan cara untuk menceritakan yang sebenarnya. Oliga tak ingin dirinya terus menerus berdusta. Kebohongan yang akan menghancurkan diri pada waktunya, entah kapan, esok, lusa, atau mungkin waktu itu tak pernah akan ia temui. Nyawa rak betah lagi membersamai tubuh.
“Cobalah, lihat wajah Kakek,” katanya, ketika tangis cucunya tak juga mereda. Suara yang menyayat puncak-puncak gunung, membedah hutan-hutan, dan menghantam batas-batas pantai pemecah ombak.
Tangisan bocah perempuan kecil yang kehilangan ruang, kesirnaan tempat berteduh dan mengadu ketika teman-teman sebaya merebut mainannya. Tempat mendapatkan kehangatan ketika kantuk menyerang dalam gelap yang terus memekat. Canda tawa di waktu senggang saat angin sepoi menciumi daun-daun sagu di depan rumah.
Oliga merasa bergembira, jiwanya terlonjak. Tangannya menari, dan kaki rentanya melangkah, ketika kepala yang sejak senja tadi menunduk, perlahan bergerak mendongak ke arahnya. Ia melangkah lebih dekat lagi, duduk di samping cucunya, lalu mengelus rambut hitam berombak dengan ikatan karet ikat berwarna-warni.
“Kau anak perempuan yang pintar. Cahaya matamu menunjukkan kekuatan itu,” kata Oliga dengan suara teramat lembut, sengau angin saja mampu menimpanya.
Anak perempuan itu tetap terdiam, membatu. Mungkin ia sedang mencoba memahami kata-kata kakeknya yang tiba-tiba begitu terdengar tenang dan dalam. Suara yang sangat akrab di telinganya, karena sejak kecil ia memang berada dalam asuhannya.
“Saya mau mama,” kata bocah itu, seperti tak menghiraukan kata-kata kakeknya atau memang enggak pernah paham tentang kalimat itu. Tentu saja si kakek mengerti benar apa yang menjadi keinginan cucunya. Namun, kemauannya tidak akan pernah terpenuhi, mewujud menjadi kenyataan. Meskipun tangis itu juga tak akan pernah berhenti, siang menjelang malam, malam menjelang siang. Dan sampai entah berapa ribu kali lagi akan bertukar, berputar dan berganti. Bahkan ketika air berubah menjadi darah, dan mata cekung ke dalam seperti danau-danau lepas tanpa tuan.
“Setiap anak pasti merindukan orang tua mereka. Namun, setiap anak kelak akan sendiri, dan harus melepaskan dirinya dari bayang-bayang orang tuanya,” kata Oliga. Kalimat itu mengalir begitu saja, tanpa menghiraukan cucunya itu belum bisa memahami makna-makna mendalam tentang kehidupan.
“Setiap yang hidup akan menjalani kematian, masuk dalam keabadian, dan berbahagia bersama para leluhur yang terus menuntun di jalan keabadian,” lanjutnya.
“Kakek juga akan mati?”
Pertanyaan itu menghenyakkannya. Kalimat polos dan murni seorang bocah, tetapi tak pernah ia menduganya. Meski selalu berbicara kematian sebagai sebuah kewajaran, tetapi laki-laki tua itu tidak pernah terpikirkan tentang kematian untuk dirinya sendiri. Nafasnya agak sedikit tersengal, dan batuk susul menyusul untuk beberapa saat lamanya.
“Ya, Kakek akan mati, kamu akan mati. Semua yang bernyawa, berjiwa akan menemui ujung kehidupan,” jawabnya dengan suara terdengar parau.
“Kalau saya kan masih kecil, Kek.”
“Kematian tidak memandang usia, seseorang memiliki garis ketentuannya sendiri-sendiri. Bisa saja kematian datang ketika ia masih bayi, bisa saja ketika seseorang sudah tua renta seperti Kakek.”
“Siapa yang begitu jahat menjadikan orang tak lagi bernafas? Mereka nakal, ya, Kek.”
“Tidak cucuku, ini bukan soal jahat dan baik. Memang begitulah takdir kehidupan manusia. Kehidupan adalah pemberian, dan pemilik kehidupan akan memintanya kembali.”
“Sesembahan kita, Chaimbo, yang mengatur seluruh kehidupan ini, yang menghamparkan langit di angkasa, menumbuhkan pohon-pohon, yang membesarkan hewan-hewan, dan menciptakan udara untuk kita bernafas.”
Oliga terus bercerita dengan sepenuh hati sambil mengelus kepala cucunya yang kini telah yatim piatu, telah patah kedua sayapnya.
Chaimbo itulah yang menjelma menjadi air, hutan dan gunung-gunung. Ia memberikan kesejahteraan dan keselamatan bagi semua warga di kampung ini. Tak ada yang terlewatkan, semua mendapat perhatian dan kasih sayangnya.
Jika Chaimbo sudah menginginkan kematian, Ia akan mengutus Yonggoway untuk mencabut nyawa manusia. Keinginannya adalah hukum, dan tanpa bisa ditawar lagi. Maka kematian yang begitu cepat menjemput tak perlu menjadi sesal, kehidupan yang lebih panjang tak perlu menjadi sombong, membanggakan ke sana ke mari.”
“Mama dan Bapak juga akan mati?”
“Ya, dan kita tidak pernah tahu kapan mereka mati, seperti Kakek juga tidak pernah tahu kapan mati.”
“Akhir kehidupan harus kita sambut dengan suka cita, karena yang mati akan meninggalkan penderitaan, dan akan menyambut kebahagiaan abadi.”
“Kedukaan dan air mata hanya akan membuat mereka yang mati bersedih, dan turut pula menangis. Kita yang hidup tak elok membuat yang mati menangis,” kata Oliga.
Oliga mengatakan mereka yang meninggal dunia mengalami kebahagiaan abadi. Roh mereka tetap melingkupi keluarganya, bersama semua saudara-saudaranya. Para roh mengetahui kedukaan seluruh keluarga, dan mereka turut bersedih hati. Para roh mengerti kebahagiaan yang sedang melingkupi keluarga, dan mereka bersuka cita melihatnya.
“Cucuku, apakah kamu akan bersedih jika Mama dan Bapakmu mati?” tanya Oliga setelah merasa memberikan pijakan kuat bagi cucunya untuk menghadapi kabar duka, berita tentang kematian kedua orang tuanya, ketiadaan anak dan menantunya sendiri. Kabar yang tak pernah sama sekali ia inginkan sepanjang jalan hidupnya.
“Saya akan membuat Mama dan Bapak gembira. Saya akan bergembira.”
“Begitulah anak berbakti, cucuku. Dan itulah anak yang sungguh-sungguh pintar."
"Jika Mama dan Bapakmu sampai tiga hari ini tak juga kembali, mungkin saja mereka sudah mati,” lanjut Oliga.
Batu gunung yang terasa di kepalanya itu terasa sirna saat ia bisa mengatakan kepada cucunya tentang kemungkinan Mama dan Bapaknya telah meninggal dunia. Tak akan menemuinya lagi selamanya.
“Mama dan Bapak akan terus melihatku, dan berbahagia jika melihat saya senang. Bukan begitu, Kek?”
“Benar, maka sekarang berilah Kakek senyummu, agar Mama dan Bapakmu juga melihatnya dan mereka tersenyum bahagia. Mereka ada di sekitar hit, dan akan selalu menjaga dirimu, seperti Kakek akan menjagamu, sebelum Kakek nanti juga akan mati.”
Bocah perempuan kecil itu memandang wajah kakeknya, seulas senyum mengembang begitu amat manisnya. Oliga merengkuh tubuh cucunya. Terbayang melintas cepat wajah-wajah yang sama manisnya dengan cucunya, wajah istrinya yang tersenyum, wajah anak perempuannya yang tertawa menampakkan gigi serapi biji mentimun.
Air matanya mengalir perlahan, meski bibirnya tetap menjaga senyum. Ia memandang wajah cucunya sekali lagi, matanya sudah terpejam, nafasnya mengalir begitu teratur, dan senyum tetap mengembang di bibirnya yang mungil.
Waktu berjalan terasa begitu cepat. Tiga hari telah berlalu. Hari-hari yang berat membebani pundaknya yang sudah sering mengeluh. Oliga mengajak cucunya ke tengah hutan, membawa satu mangkuk darah babi, merah segar.
Tepat di bawah pohon tua yang amat besar kira-kira sebesar dua ekor kerbau lingkarannya, mereka berhenti dan duduk bersimpuh. Warga kampung mengikuti Kepala Suku mereka untuk memberikan persembahan kepada leluhur.
Tangan mungil bocah kecil itu menumpahkan darah merah segar di akar-akar pohon, mengalir perlahan mengikuti akar-akar yang kokoh berlekuk masuk ke bumi. Darah itu terus meresap perlahan, dan tak tampak lagi warna merahnya, meninggalkan sisa basah yang mengental.
“Saya tersenyum agar Mama dan Bapak berbahagia, dan selalu menjaga saya dan Kakek,” ucap cucu Oliga.
“Lihatlah anak perempuanku, cucuku tersenyum, menyegarkan pohon-pohon yang kering, daun-daun sagu yang melengkung, menggemburkan tanah-tanah yang subur, dan mewangikan bunga-bunga” kata Oliga.
"Lihatlah, betapa mereka telah bersabar dalam duka, berdiam dalam nestapa, dan menunduk saat dihina-hina."
“Maka berbahagialah kalian bersama para leluhur, tetap jagalah anakmu, sehingga ia terbebas dari segala kejahatan yang keji, dari segala keculasan manusiawi, dari rasa dengki dan iri hati,” lanjutnya.
Tak ada satu pun warga yang tidak meneteskan air mata, setidak-tidaknya berkaca-kaca. Mata yang mengerjap dan memerah. Membening.
Angin berhembus sepoi, dan makin lama mengencang, lalu terdiam membentur batu di tepian gunung. Daun-daun kering luruh, melayang-layang, dan jatuh ke tanah tanpa suara, tanpa keluhan. Warga kampung semuanya diam, wajah khusyuk, dan sebagiannya menegang. Mereka mengerti, roh anak dan menantu Kepala Suku mereka sedang menuju ke pohon itu, memohon agar roh sesembahan bisa menerima kehadiran mereka.
Menyadari situasi yang ditunggu telah tiba, Kepala Suku bergetar tubuhnya. Sekarang tiba saat terpenting dan paling bermakna bagi sang roh untuk mendapatkan bantuan dari yang hidup, agar para leluhur bisa menerima roh mereka.
“Wahai para leluhur, selamat dan bahagia,” kata Oliga sambil mengangkat tangan tinggi-tinggi. Tubuh kurusnya bergerak-gerak, bergetar kadang melambat dan kadang begitu cepat, seperti tak lagi mampu kaki kurus kering itu menyangga tubuhnya sendiri.
“Karuniakan keselamatan kepada anak dan menantuku, kepada semua warga kampung ini,” lanjutnya.
Tarian pemujaan terus berjalan, pemuda dan pemudi menabuh tifa, tombak-tombak mengacung menusuk langit, merobek-robek angkasa, mengalir darah putih tanda duka. Mantra-mantra, dan nyanyian sambung menyambung.
Angin berputar-putar membumbungkan daun kering, dan debu-debu telah menghilang. Suasana menjadi hening dan senyap. Tarikan nafas pun seakan tak terdengar sama sekali. Semua berharap, leluhur menerima roh putri dan menantu Kepala Suku.
Orang-orang itu membuat kesaksian, meneriakkan pernyataan, selama hidupnya pasangan suami istri itu sungguh sangat baik kepada tetangga. Kalau toh pernah melakukan kesalahan itu manusiawi belaka, semua warga menyatakan maafnya.
Upacara pelepasan roh selesai, warga bubar meninggalkan tempat pemujaan, semua kembali ke rumah masing-masing. Memang begitulah ajarannya. Setiap usai melakukan doa-doa, tak ada warga yang boleh bekerja di ladang. Semuanya harus tinggal di rumah bersama keluarga.
Rio dan David mengikuti upacara pelepasan roh dengan diam, seperti juga warga yang lain. Rio belajar tentang keteguhan, tentang ketabahan seorang Ondoafi yang sudah berusia lebih dari seratus tahun. Laki-laki yang begitu teguh terhadap nilai-nilai sukunya, dan terus memelihara tradisi-tradisi sukunya.
Rio memang belum mengenal Oliga Mawarune dengan baik, Kepala Suku yang sudah merenta itu. Namun, Rio tahu pasti, Oliga masih melanjutkan tradisinya, menuntun tangan mungil cucunya, melangkah pelan dan tertatih, menuju ke arah barat daya perkampungan. Membawa cucunya melihat wajah Mama dan Bapaknya untuk yang terakhir kali, kemudian akan menguburkannya di tanah miliknya, di samping kuburan istrinya.
Lima puluh tahun lamanya Oliga telah memegang jabatan Kepala Suku. Seperti juga para penggagas perubahan tradisi di dunia, Oliga banyak mendapatkan perlawanan, ketika mengubah tradisi ritual kematian di sukunya, pembakaran warga suku yang meninggal, tetapi ketika yang meninggal memiliki anak kecil ritual dengan pemakaman.***
Dua Cinta di Puncak Jaya Bab 1:
https://www.indonesiana.id/read/156544/dua-cinta-di-puncak-jaya-bab-1
Pekerja sosial, jurnalis, fasilitator pendidikan kritis
0 Pengikut

Vinri Panggoa, Bergerak untuk Pemenuhan Air Bersih di Jayapura
Rabu, 9 Agustus 2023 19:49 WIB
Cempluk Goes to School, Pendampingan Pasien Autoimun Lupus
Selasa, 8 Agustus 2023 17:02 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 Berita Pilihan
Berita Pilihan 0
0









 98
98 0
0