‘Lubang Kelinci’ dari ‘Fandom’ Politik
Senin, 16 Oktober 2023 12:15 WIB
Berlebihan memuja-muji bisa memerosokkan orang ke dalam “lubang kelinci”. Dalam politik, fenomena semacam ini bisa disaksikan berlangsung berkepanjangan sejak pemilihan presiden pada 2014.
Oleh Purwanto Setiadi
Sebagai kiasan, yang berasal dari cerita anak-anak berjudul Alice‘s in Wonderland, istilah lubang kelinci bisa bermakna ranah yang bagaikan labirin, yang betapapun melawan akal sehat, orang bakal terus melaluinya karena memang sulit keluar begitu sudah terperosok ke dalamnya. Memuja-muji seseorang secara berlebihan, seperti yang bisa diamati terjadi sejak sembilan tahun yang lalu itu, jadi memaksakan pembelaan yang kelewat lewah, begitu seterusnya.
Pengalaman tersebut mengatakan kepada kita
bahwa, dalam pemilu, kebanyakan pemilih terlibat bukan sekadar untuk menyumbangkan suara, buat politikus yang mengincar kursi legislatif (yang ini jarang, sih) maupun, terutama, jabatan eksekutif (bukan hal yang asing, ‘kan?)--apalagi dalam sistem atau kondisi yang memungkinkan opini terbelah menjadi ini atau itu. Pemilih juga, sesungguhnya, tampil sebagai penggemar; mereka bahkan pemuja. Mereka mengingatkan orang kepada banyak penggemar dalam musik atau olahraga. Mereka bagian dari fandom politik.
Fenomena itu bukan hal baru, sebetulnya. Dulu Silvio Berlusconi, misalnya, punya penggemar/pemuja; dia sengaja mendirikan partai, Forza Italia, untuk mewadahi mereka. Sukarno, presiden pertama negara kita, juga punya penggemar. Di era media sosial, pada zaman pasca-kebenaran ini, “kepenggemaran” atau fandom itu menemukan medan permainan baru. Sayangnya, itulah pula yang sekaligus menjadi sumber masalah, yang malah berpotensi merusak demokrasi.
Media sosial memungkinkan penggemar/pemuja politikus bukan saja berekspresi, menyatakan pendapat, secara bebas. Penggemar/pemuja politikus jadi bisa pula berkumpul di satu “ruang” untuk mengelu-elukan pujaannya, bersorak dan melakukan apa saja seakan-akan berada di stadion menyaksikan pertandingan…gulat, misalnya; seakan-akan persaingan atau kampanye politik, atau menjual ide tentang suatu kebijakan publik, adalah cabang olahraga baru, malah semacam kepentingan bersama untuk menjelek-jelekkan--membunuh karakter--pesaing atau pengritik politikus pujaannya.
Prof. Cornel Sandvoss dari University of Surrey, Inggris, menyatakan fandom menyematkan identitas dan memunculkan rasa memiliki. Perihal identitas, penulis buku Fans: the Mirror of Consumption ini menyebutnya sebagai hal penting sebab sumber identitas “tradisional” semakin memudar: karena menikah bukan lagi pilihan bagi makin banyak orang, karena orang tak terhubung sepenuh hati dengan pekerjaannya, karena orang tak punya atau tak bisa mengasosiasikan diri dengan kelas ekonomi, kelompok agama, atau serikat pekerja yang jelas. Banyak orang mengisi kehampaan itu dengan menjadi penggemar/pemuja.
Ada yang mengemukakan pandangan D.W. Winnicott, seorang psikoanalis dari Inggris, tentang fungsi boneka beruang--atau mainan pada umumnya--bagi anak sebagai pembanding dalam melihat perilaku penggemar/pemuja dalam politik. Boneka itu adalah obyek atau ruang peralihan antara kesadaran di dalam diri dan kesadaran terhadap dunia luar yang semakin jelas di satu titik dalam fase pertumbuhan. Penggemar/pemuja politik menjadikan politikus yang didukungnya sebagai boneka itu, untuk menautkannya dengan dunia. Prof. Sandvoss punya istilah untuk hal ini: libidinal-narsisistik.
Masalahnya, ada yang hilang dari gegap-gempita “kepenggemaran”, yakni perhatian terhadap isu, ideologi, dan kebijakan. Padahal hal-hal inilah yang seharusnya mengemuka dalam politik--dan demokrasi secara umum.
Sebagian memang bisa saja merasa harus menyetujui kebijakan tertentu, misalnya pelonggaran investasi, pembangunan infrastruktur. Tapi kebanyakan penggemar/pemuja mengabaikan isu, ideologi, dan kebijakan, tak memandangnya sebagai prioritas, bahkan kalaupun ada kengawuran atau pelanggaran hukum menyangkut kebijakan. Mereka acuh tak acuh bila yang terjadi kemudian, di antara elite politik, adalah bagi-bagi kekuasaan, potong-potong “kue” kedudukan, bukan saja antar-“kawan”, tapi juga dengan oposan. Mereka hanya ikut berbaris sebagai pendukung karena, ya, semata-mata suka saja kepada seorang politikus. Seperti teman saya yang menggemari Liverpool, umpamanya, bukan karena secara teknis kini mereka tim yang membaik, tapi, ya, suka saja.
Wajar, meski tak selalu bisa masuk dalam akal sehat, bila retorika yang berlaku dalam fandom adalah loyalitas abadi. Di era media sosial, politikus yang dipuja-puja, yang memahami “psikologi” ini, bisa memanfaatkan pendengung atau buzzer untuk terus menggemakan “kepenggemaran” kepada dirinya dan bahkan menggiring pemujanya ke mana pun, seperti gerombolan tikus dalam dongeng The Pied Piper of Hamelin, jika punya niat dan alasan.
Saya tak ingin jadi seperti tikus-tikus itu. Sebagai penggemar musik, tapi bukan pemuja musikus, yang mudah saya ingat dan bisa saya elu-elukan selamanya adalah The Piper at the Gates of Dawn--satu album ikonik dari era psikedelia.
(*)
...wartawan, penggemar musik, dan pengguna sepeda yang telah ke sana kemari tapi belum ke semua tempat.
5 Pengikut

Stop Mengubur Karbon, Mulailah Mengubur Kebohongan
Senin, 29 September 2025 06:44 WIB
Tiada Pemerataan Tanpa Demokrasi di Tempat Kerja
Kamis, 18 September 2025 06:52 WIBBaca Juga
Artikel Terpopuler

 0
0

 Berita Pilihan
Berita Pilihan





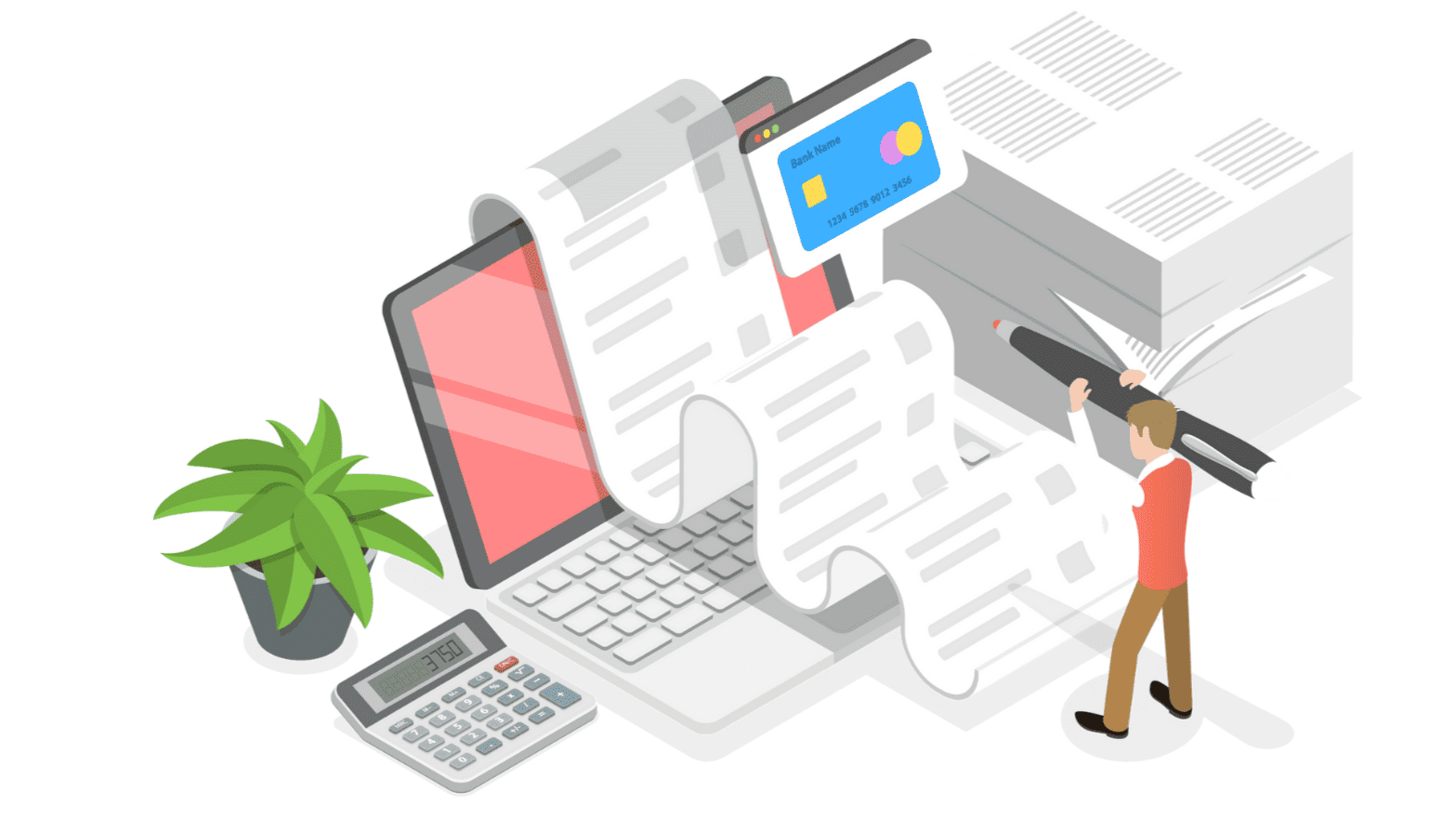

 98
98 0
0













