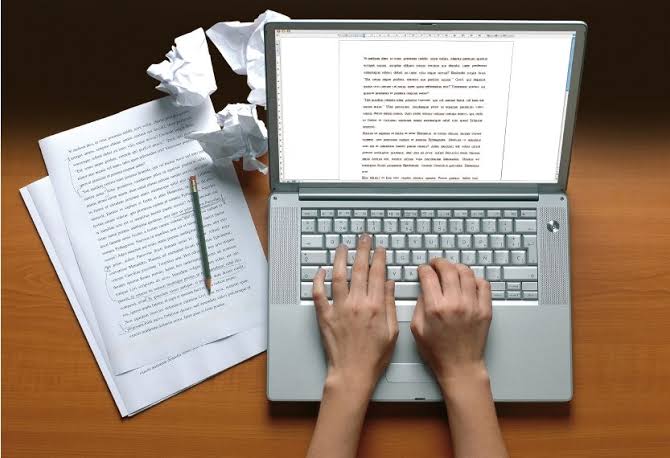21 Juni, 29 tahun yang lalu: Catatan dari Yogyakarta.
Ditulis Oleh: Rustam Fachri Mandayun ( Kepala Biro Majalah Berita Mingguan Tempo Daerah Istimewa Yogyakarta: 1992 – 1994)
Beberapa waktu yang lalu, seorang teman, wartawan, cukup senior sih, malah resminya sudah pensiun sebagai wartawan dari sebuah perusahaan pers, agak mengerenyitkan dahi ketika saya mengatakan, “Sebentar lagi 21 Juni, ya.” Lantas teman tadi bertanya , “Ada apa dengan tanggal itu?” Agak sedikit heran, saya jawab, itu tanggal pembredelan Tempo, Detik dan Editor pada 1994. Barulah pembicaraan kami nyambung.
Memang bagi sebagian orang, sekalipun dia sudah menjadi wartawan pada saat kejadian pembredelan –asal kata breidel, dari bahasa Belanda yang artinya: pemberangusan, peristiwa yang terjadi pada tanggal tersebut, mungkin tidak terlalu penting untuk diingat-ingat. Tapi tidak buat saya. Pembredelan; penghentian terbit media atau pers oleh pemerintah itu ibarat “kiamat kecil” buat mereka yang bekerja di ketiga media tersebut. Baik wartawannya, maupun karyawannya.

Karyawan TEMPO saat mengadukan kasus pembredelan ke DPR tahun 1994. Dok. TEMPO/Gatot Sriwidodo.
Buat saya, khabar pemberedelan, pada hari Selasa Legi tersebut, merupakan salah satu titik penting dalam time line kehidupan. Di usia awal 30 an, memimpin sebuah kantor Biro Majalah Berita Mingguan (MBM) Tempo wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah, tentu menantang sebagai jurnalis. Tapi, tiba-tiba semangat itu dijeda.
Dari sisi kredibilitas profesional dan bisnis, Tempo, termasuk salah satu perusahaan pers yang dihormati dan sehat. Kompeten jurnalisnya, dan sehat entitas bisnis. Tentu karyawannya sejahtera – juga wartawannya.
Kabar pemberhentian (baca: pemberangusan) ketiga media oleh Pemerintah melalui Departemen Penenerangan (Deppen) –nah ini, Deppen sesuatu yang sekarang “purba”-- itu adalah majalah Tempo, tabloid Detik dan majalah Editor dicabut Surat Izin Usaha Penerbitan Pers nya atau SIUPP (istilah langka lagi nih SIUPP), yang berarti ketiganya tidak boleh melakukan kegiatannya sebagai pers atau media.
Memang perintah pembredelan tersebut, bukan yang pertama dialami MBM Tempo. Tahun 1994 itu adalah yang ke dua kalinya.Tahun 1982, Tempo pernah dibredel juga, bedanya, saat itu, berupa pembredelan sementara waktu. Setelah menandatangi kesepakatan, beberapa waktu kemudian, Tempo boleh terbit kembali. Nah, yang 21 Juni 1994 ini, Tempo dan kedua media lain, dinyatakan harus tutup selamanya!
Tempo dibredel untuk kali kedua, karena pemberitaan dugaan kasus korupsi impor 39 kapal perang bekas Jerman Timur yang diprakarsai Menteri Riset dan Teknologi saat itu, B.J. Habibie. Menurut pemerintahan Orde Baru saat itu, dengan presidennya Soeharto, pemberitaan Tempo tersebut dapat mengganggu stabilitas nasional.
Kembali ke riak-riak kecil di Yogyakarta. Tentu kami di biro DIY & Jateng terkejut dengan kabar tersebut. Sedih sembari marah sudah pasti. Saya ingat betul, hari itu ibarat hari berkabung buat kami, wartawan dan karyawan Tempo Biro DIY dan Jateng. Mungkin juga buat sebagian masyarakat Indonesia–-mudah-mudahan bukan asal klaim, ya .
Satu persatu sahabat Tempo, atau kalau sekarang kita sebut saja anggota komunitas Tempo di Yogyakarta, berdatangan ke kantor Biro Tempo yang terletak di Jalan Kaliurang KM 5 Yogyakarta. Teman-teman ini, seakan–akan takziah, layat ke kantor Tempo. Silih berganti.
Sebelum ini, sesuai dengan keinginan mas Goen ( Goenawan Muhamad- GM, Pemimpin Redaksi Tempo, yang kemudian digantikan Fikri Jufri saat pembredelan), agar kantor biro dijadikan center of exellence atau pusat kegiatan yang bermanfaat sesuai dengan lingkungannya. Karena kami berada di Yogyakarta, pusat orang orang pintar –Yogya dikenal sebagai kota pendidikan- dan kota tempat seniman berhimpun, maka kegiatan rutin yang dilakukan saat itu adalah diskusi-diskusi dengan menghadirkan pembicara-pembicara dari dunia akademis maupun praktisi dengan undangan kaum intelektual baik dosen maupun mahasiswa yang ada di Yogyakarta. Dosen tamu dari Belanda, antropolog orientalis, Martin van Bruinessen pernah diundang berdiskusi di kantor Tempo di Yogyakarta. Wartawan Tempo. M. Faried Cahyono jadi koordinator kegiatan diskusi.
Pameran karya seni bagi seniman-seniman muda berbakat baik dari kampus maupun masyarakat umum, juga digelar di kantor Tempo secara reguler. Termasuk pameran lukisan kaca dari pengrajin seni lukis kaca sekitar candi Borobudur, Jawa Tengah. Wartawan Tempo, R. Fadjri jadi kordinator kegiatan seni ini.
Dengan adanya acara acara seperti di atas, maka terbentuklah semacam “komunitas Tempo” Yogya. Mereka terdiri dari para akademisi, mahasiswa, aktivis pers mahasiswa, seniman dan juga para demonstran. Komunitas semacam ini juga terbentuk di kota kota lain, tempat kantor Biro Tempo berada, sesuai dengan lingkungannya.
Mendengar khabar pembredelan, sejumlah tokoh kampus berdatangan ke kantor Tempo seakan menyatakan ikut berduka atas apa yang menimpa Tempo. Mereka, antara lain, Dr. Affan Gaffar, dosen politik di Universitas Gadjah Mada, sekaligus kolumnis Tempo. Tentu ada juga pak Kayam (Dr. Umar Kayam), budayawan serta kolumnis Tempo. Pak Kayam ini juga sahabat mas Goen. Keduanya sudah mendahului kita. Tidak ketinggalan, Cak Nun – Emha Ainun Najib, budayawan dan kolumnis Tempo- menyempatkan datang ke kantor kami.
Mahasiswa penyuka diskusi, mahasiswa pegiat pers mahasiswa dan mahasiswa demonstran jalanan juga datang ke kantor Tempo. Suasana layat - kesripahan, kematian, kata orang Jawa, benar benar terasa. Meski tetap diselingi dengan sendagurau. Kami, wartawan dan karyawan Tempo di Yogya tentu merasa terhibur dengan adanya simpati semacam itu.
Bahkan dalam gelombang-gelombang demonstrasi menentang pembredelan – di hari hari kemudian, seorang mahasiwa UGM, saat itu, bernama Anies Baswedan, yang kelak menjadi Gubernur DKI, datang ke kantor Tempo menyatakan simpati dan mepersiapakan materi demo yang akan diikutinya keesokan hari. Ya, beberapa lembar kertas ukuran poster warna putih dan sepidol ukuran besar kami sediakan. Ilmuwan politik internasional, Dr. Amien Rais pun, motor reformasi, pada masanya , ikut turun ke jalan menentang pembredelan.
Nah, saya mau tidak mau menjadi demonstran dadakan. Mosok yang dibela gak turun ke jalan. Maka beberapa kali saya bergabung dengan tokoh kampus, budayawan, seniman dan mahasiswa demontrasi menenatang pembredelan. Utamanya yang diadakan di bundaran di depan Balairung UGM. Saya yang demonstran amatiran ini dengan penuh rasa was-was ikut teriak teriak dalam cuaca panas menentang pembredelan. Di hadapan kami berjajar pasukan anti huru hara (PHH) berada di hadapan demonstran. Intel militer berkeliaran berpakaian sipil, berdandan ala wartawan, atau wartawan yang juga intel, gak jelas, berkeliaran di antara para demonstrans. Saya sempat didorong dan diplototin satu di antaranya. Ya, jiper juga lah.
Yang menarik, demonstran yang saat itu terlihat beringas dan pemberani, dengan tanpa konteks, antara lain meneriakan kata-kata; “Kalian PKI, kalian PKI” – mungkin untuk memancing provokasi, ke arah para polisi PHH. Tentu aparat terpancing dan demo berakhir ricuh. (Menyimpang sedikit, di zaman SBY jadi Presiden, beberapa dari demonstran yang galak-galak itu jadi komisaris di beberapa BUMN. SBY memang pernah jadi Komandan Korem di Yogya meski sebentar di tahun 1995). Saya kok gak diajak?)
Peristiwa pembredelan, menurut saya salah satu amunisi penyemangat gerakan reformasi. Di lingkungan wartawan sendiri, ya jurnalis, kemudian muncul gerakan anti wadah tunggal. Semua organisasi profesi di zaman Orde Baru – baca: pemerintahan Soeharto, harus hanya ada satu. Termasuk di kalangan pers. Saat itu hanya ada satu wadah organisasi profesi untuk para pewarta, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Maka di beberapa daerah muncul bibit bibit organisasi tandingan untuk jurnalis. Di Yogya ada Forum Diskusi Wartawan Yogyakarta (FDWY, kebetulan saya ketua untuk priode pertama). Di Jakarta ada Solidaritas Jurnalis Independen (SJI), di Surabaya ada Surabaya Pers Club (SPS) dan di Bandung didirikan Forum Wartawan Independen (FOWI). Dari sini kemudian pada 7 Agustus 1994, keempat organisasi tadi berhimpun di Aliansi Jurnalis Independen (AJI).
Tahun 1998 Soeharto dan rezimnya tumbang. Reformasi tak terbendung. Lalu lahirlah Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers). Undang undang ini lahir dari semangat reformasi. Undang Undang sebelumnya, Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pokok Pers, diganti dengan UU Nomor 40. Undang undang yang baru lebih menjamin kemerdekaan pers. Antara lain, untuk menerbitkan pers / media tidak diperlukan lagi Surat Izin Penerbitan Pers (SIUPP) yang dulu menjadi monopoli penguasa. SIUPP saat itu ibarat stick and carrot. Jika media manut dikasih, media gak manut, SIUPP cabut.!
Imbas undang-undang pers yang baru itu pun berdampak pada idenpendensi lembaga Dewan Pers. Dewan Pers (DP) masa Orde Baru adalah kepanjangan tangan penguasa. Kenapa begitu? Karena ketuanya ex officio Menteri Penerangan yang menjabat saat itu. Siapa berani lawan? Berharap apa pers dan wartawan untuk menjalankan fungsinya, di antaranya melakukan kontrol sosial dari pejabat semacam itu?
Di UU Pers, disebutkan bahwa Dewan Pers adalah lembaga independen. Anggota Dewan Pers, baik ketua maupun anggotanya dipilih oleh masyarakat pers sendiri. Masyarakat pers yang mengatur dirinya sendiri.
Akibat reformasi pula, Presiden Abdurahman Wahid (yang pernah menjadi salah satu kolumnis Tempo) membubarkan kementerian dengan nama Departemen Penerangan pada 2000. Dengan demikian aturan bahwa menterinya secara langsung adalah ketua Dewan Pers, pun raib.
Lho, katanya catatan dari Yogyakarta, kok kebablasan sampai ke pusat kekuasaan, Jakarta? Ya anggap saja tulisan ini tagline nya; catatan dari Yogya untuk Indonesia. Ups!
Ikuti tulisan menarik Rustam F Mandayun lainnya di sini.